 Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Terdapat perbedaan antara apa yang disebut sebagai kebijakan publik (public policy) dengan kebijakan sosial (social policy). Kebijakan publik membahas mengenai proses formulasi dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan otoritas dalam hal ini pemerintah/otoritas formal dan proses politik. Jadi jika kita berbicara tentang penggodokan UU atau peraturan, maka kita berbicara mengenai kebijakan publik terlepas dari apakah kebijakan itu menyangkut persoalan sosial, ekonomi, politik, olahraga atau transportasi, sejauh ia menyangkut pengaturan dan tata kelola hal-hal yang akan memengaruhi kehidupan publik, maka ia disebut sebagai kebijakan publik. Sementara jika kita berbicara tentang kebijakan sosial, maka kita membicarakan kebijakan sebagai upaya pengelolaan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan. Paparan ini disampaikan Atnike Nova Sigiro, Program Manajer Asian Advokasi pada Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) dalam kelas Kaffe (Kajian Filsafat dan Feminisme) yang diselenggarakan Jurnal Perempuan dengan tema Kebijakan Publik, Etika Publik dan Konsep Keadilan pada Kamis (26/8) di kantor JP. Lebih lanjut Atnike menjelaskan bahwa kebijakan publik membicarakan soal prosedur dan legitimasi. Sedang kebijakan sosial membincangkan kesejahteraan dan kehidupan sosial. Kesejahteraan ini menurut Atnike dibedakan menjadi dua, yakni wellbeing dan welfare. Idealnya menurut Atnike kesejahteraan bukan semata-mata welfare yang lebih pada konotasi fisik (ekonomi, infrastruktur, hal-hal yang bisa dilihat secara fisik), tetapi lebih jauh dari itu, kesejahteraan seharusnya mencakup wellbeing yang artinya sejahtera lahir batin. Lebih jauh Atnike mengemukakan berbicara mengenai perempuan atau feminisme maka dalam isu kesejahteraan sosial, perempuan adalah salah satu objek yang selalu lekat dengan isu kesejahteraan, tetapi seringkali ia dilekatkan secara negatif. Karena peran sosialnya maka perempuan dalam isu kesejahteraan seringkali mengandung banyak stigma, misalnya perempuan sebagai sosok dependen atau bergantung pada suami, perempuan dengan kemampuan atau kapasitas yang lebih rendah. Di Barat misalnya berkembang istilah welfare mother dan welfare queen yang mengandung stigma terhadap perempuan dalam isu kesejahteraan. Welfare mother adalah istilah yang diberikan kepada perempuan atau ibu yang memiliki anak tetapi secara ekonomi tidak mampu, sehingga ia bergantung kepada bantuan sosial, entah dari pemerintah atau lembaga amal. Sedang welfare queen cenderung lebih negatif yakni istilah yang berkembang di Amerika untuk perempuan-perempuan atau ibu yang mendapatkan bantuan sosial tetapi mereka dianggap menyalahgunakan bantuan tersebut. Itu semua adalah stigma yang berkembang khususnya di negara-negara kapitalistik liberal yang menganggap orang yang menerima bantuan sosial adalah orang-orang pemalas, orang-orang yang tidak serius mencari nafkah, tidak serius berjuang memenuhi kebutuhannya sendiri. Atnike mengungkapkan Indonesia juga memiliki stigma terkait perempuan dan kesejahteraan meskipun tidak secara vulgar seperti di Barat. Misalnya pada masa pemerintahan SBY terdapat program keluarga harapan, dan pemegang kartu keluarga harapan adalah perempuan karena dianggap perempuan lebih bertanggung jawab dan akan menggunakan uang yang diberikan untuk kebutuhan keluarga seperti yang diinginkan. Perempuan diberi peran lebih untuk memastikan bantuan itu sampai kepada keluarga. Begitu juga dengan program yang sekarang, kartu yang sekarang ada sebetulnya kelanjutan saja dari program bantuan di masa lalu, hanya namanya saja yang diubah. Bantuan-bantuan sosial tersebut selalu mensyaratkan yang berhak mendapat bantuan adalah ibu dan ana. Posisi perempuan yang dianggap lemah terefleksi dari syarat-syarat pemberian kebijakan, seperti ibu dan anak atau ibu yang hamil. Menurut Atnike, pada satu sisi situasi tersebut memperlihatkan perempuan didahulukan tetapi di balik itu dia sebenarnya mengandung stigma bahwa perempuan selalu dependen terhadap bantuan. Padahal dalam kenyataannya peran ekonomi perempuan dalam konteks Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan laki-laki atau kepala keluarga laki-laki yang umumnya dikenal. Lebih lanjut Atnike mengungkapkan terdapat perdebatan yang selalu muncul ketika kita bicara tentang feminisme dan kebijakan sosial. Pertama soal keluarga dan individu. Jika kita berbicara kebijakan sosial, pertanyaannya adalah kepada siapa kebijakan sosial itu akan diberikan, individu atau keluarga. Misalnya BPJS, apakah ketika membuat kebijakan ini pemerintah berpikir bahwa yang akan mendapatkan manfaat adalah keluarga atau individu. Tradisi yang melihat unit kehidupan merupakan keluarga, sebetulnya merupakan tradisi tempo dulu, orang hidup dalam keluarga inti merupakan tradisi atau kondisi masyarakat tahun 60-an sampai 80-an. Sehingga kalau BPJS diberikan kepada keluarga, maka akan ada banyak orang yang tidak memenuhi syarat. Di Indonesia syarat-syarat untuk mengklaim kebijakan atau bantuan sebagai individu masih sangat sulit. Kedua perdebatan mengenai pasar tenaga kerja dan negara. Dalam kehidupan sosial khususnya dalam sistem kapitalisme diasumsikan pada satu titik manusia harus masuk dalam lapangan tenaga kerja karena dia harus hidup dari pendapatan yang diperoleh dari lapangan tenaga kerja. Sementara terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa pasar tenaga kerja tidak selalu mampu menyerap individu. Sehingga ketika tidak ada penyerapan di pasar tenaga kerja maka negara harus mengambil peran untuk memastikan kesejahteraan individu atau keluarga. Ketiga soal equal opportunity versus differences. Misalnya dalam soal pasar tenaga kerja, equal opportunity artinya semua orang, entah laki-laki atau perempuan mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan mereka harus berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi equal opportunity ternyata tidak cukup, karena equal opportunity tanpa memperhitungkan perbedaan kebutuhan justru akan menimbulkan diskriminasi. (Anita Dhewy)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Banyak kebijakan berangkat dari asumsi bahwa seakan-akan semua warga negara adalah laki-laki. Hal ini tercermin dari bahasa yang digunakan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan yang ini kemudian menimbulkan masalah. Untuk itu etika publik membantu untuk keluar dari satu arah dalam kebijakan. Demikian pengantar yang disampaikan Haryatmoko saat mengajar di kelas Kaffe (Kajian Filsafat dan Feminisme) yang diadakan Jurnal Perempuan pada Kamis (19/8) di kantor JP dengan tema Kebijakan Publik, Etika Publik dan Konsep Keadilan. Lebih lanjut Haryatmoko mengemukakan bahwa istilah etika publik baru populer sekitar tahun 80-an di Amerika setelah muncul skandal Watergate. Sebelumnya digunakan istilah etika pemerintahan. Etika pemerintahan berorientasi pada kekuasaan sedang etika publik orientasinya pelayanan publik. Di Indonesia etika publik dipopulerkan Sri Mulyani pada awal ketika beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan. Haryatmoko menjelaskan menurut definisinya etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik fokusnya pada pelayanan publik yang berkualitas, responsif dan relevan. Realitasnya seringkali kebijakan publik tidak relevan, sebatas menguntungkan pembuat kebijakan namun tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah modalitas etika yakni semua yang menjembatani dari norma ke tindakan. Hal ini menjadi penting karena banyak dari kita mengira jika sudah tahu maka berarti sudah menjalankan, sementara antara tahu dan melakukan terdapat jarak yang jauh. Tekanan etika publik terutama pada menjembatani antara norma atau yang seharusnya dengan tindakan nyata atau yang faktual. Modalitas berbentuk aturan dan sistem, serta tidak bisa hanya disandarkan pada niat baik. Jadi fokus etika publik adalah menyediakan fasilitas, sarana, membuat sistem yang baru supaya ada perubahan. Lebih lanjut Haryatmoko mengungkapkan bahwa etika publik masuk pada etika sosial bukan hanya etika individual sehingga tidak tergantung pada oknum. Bahwa oknum juga berpengaruh tetapi juga terdapat sistem di sana. Perbedaannya etika individual hanya berkaitan dengan perilaku individu dalam masyarakat sedang etika publik berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam bermasyarakat. Jadi objeknya hukum, politik, strategi, praktik kelompok dan komunitas serta institusi sosial. Sedang validitasnya pada etika individual tergantung pada kesahihan premisnya, artinya sejauh dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, maka tidak menjadi masalah. Sementara etika publik tidak cukup hanya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, tetapi harus disetujui sebanyak mungkin anggota masyarakat. Karena itu dibutuhkan mediasi dalam etika sosial atau etika publik. Profesi ikut berperan, misalnya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dalam bidang kedokteran. (Anita Dhewy) 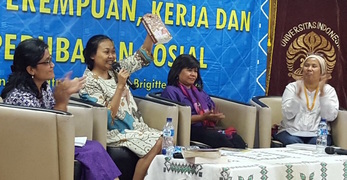 Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Senin, 22 Agustus 2016, buku Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial cetakan kedua yang diterbitkan oleh Yayasan Kalyanamitra diluncurkan sekaligus diduskusikan di Gedung IASTH Salemba UI dengan kerjasama Yayasan Jurnal Perempuan dan Program Studi Kajian Gender UI. Buku karya Ratna Saptari dan Brigitte Holzner terbit pertama kali pada 1997 dan menjadi salah satu buku rujukan untuk perkuliahan di Program Studi Kajian Gender. Ratna Saptari dalam memberikan pidato kunci dalam acara ini, ia mengungkapkan bahwa buku ini telah ditulis pada sejak awal 90-an, jadi sudah lebih dari 2 dakade. “Buku ini sudah sangat lama sekali, dan saya harap buku ini menyumbang pemikiran kritis serta penelitian-penelitian terkini”, ungkap Ratna. Ia melanjutkan bahwa penting bagi studi perempuan untuk terintegrasi dengan gerakan perempuan menyoal isu-isu perempuan terkini, sehingga studi perempuan dan gerakan perempuan dapat bekerja bersama-sama dan saling melengkapi. Setelah paparan kunci dari Ratna Saptari, acara dilanjutkan dengan diskusi tentang buku Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial yang dipandu oleh Dewi Candraningrum, Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan. Diskusi buku ini menghadirkan Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan), Mia Siscawati (Ketua Program Studi Kajian Gender UI), Siti Maimunah (Sajogyo Institute) sebagai pembicara. “Buku ini, mengingatkan saya pada pemikiran McRobbie, bahwa ada disartikulasi pada gerakan perempuan, meski buku ini sudah 2 dekade saya rasa ini tidak kita jadikan sebagai penghambat untuk melahirkan sebuah pengetahuan. Saya rasa hari ini kita sedang merayakannya”, ungkap Dewi. Lebih lanjut Dewi menyilakan Yuniyanti Chuzaifah untuk memberikan paparannya. “Buku ini mengoneksikan dunia akademis dan aktivisme”, tutur Yuniyanti. Ia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa kemajuan setelah buku ini diterbitkan, misalnya tentang buruh yang sebelumnya sangat sulit sekali berorganisasi, setelah 19 tahun kemudian buruh sudah bisa berorganisasi dan bisa menyuarakan hak-haknya. Sekarang isu migran sidah menjadi isu politis, gerakan perempuan pekerja di grass root juga banyak seperti perempuan petani, perempuan penambang, perempuan adat dan lainnya. Menurutnya buku ini adalah karya penting yang harus dilanjutkan dengan melihat konteks gerakan perempuan di Indonesia sekarang. “Membangun pengetahuan perempuan bersama menjadi penting karena gerakan perempuan dan ruang akademisi adalah hal yang saling melengkapi”, ungkap Yuniyanti. Kemudian diskusi disambung dengan paparan Mia Siscawati, Ketua Program Studi Kajian Gender UI. “Gerakan perempuan menyumbang besar terhadap perkembangan studi perempuan”, tutur Mia Siscawati. Ia melanjutkan bahwa buku ini telah menjadi salah satu buku bacaan wajib untuk mahasiswa kajian gender dan menjadi sangat penting karena ada kajian interseksionalitas. Mia menyebutkan bahwa dalam buku ini penulis tidak hanya memerhatikan jenis kelamin namun juga persinggungan antar kelas, dan disanalah letak kajian interseksionalitas yang sangat penting. Menurutnya bukan hanya kajian interseksionalitas, buku ini juga menyumbang metodologi penelitian yang berbasis gender. “Ratna Saptari menggunakan metodologi penelitian PAR, Participatory Action Research, yang pada waktu itu banyak mengatakan ini tidak ilmiah, namun Ratna bisa membuktikannya dalam buku ini”, ungkap Ketua Program Studi Kajian Gender UI. Selanjutnya moderator menyilakan Siti Maimunah untuk memberikan paparannya terkait buku Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial. Mai Jebing mengungkapkan ada hal penting dalam buku ini yang bisa kita tangkap ialah bahwa kita tidak bisa meletakan pengetahuan dan pengalaman perempuan sebagai suatu yang umum atau sama dengan yang lain. “Pengetahuan dan pengelaman perempuan adalah sesuatu yang berbeda satu sama lain dan bisa berubah dari waktu ke waktu, tidak statis. Saya rasa penting untuk mendengar pengalaman perempuan Indonesia karena sangat kaya”, Ungkap Mai. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa untuk isu kerja sendiri perempuan memiliki tantangan yang berat karena harus bernegosiasi untuk keluar dari ruang domestik, stigma dan beban ganda ruang publik dan domestik. Mai menjelaskan hasil penelitiannya bahwa berdasarkan data KHL tahun 2008 menunjukan bahwa 75% dari 9000 dokumen Amdal yang disetujui dokumennya buruk dan sekitar 50% Komisi Amdal Daerah tidak berjalan sesuati tugas dan fungsinya. Inilah yang menurut Mai pembangunan tidak berperspektif terhadap keadilan lingkungan yang akhirnya memiliki dampak langsung terhadap kerja-kerja perempuan di ruang domestik maupun publik. Setelah paparan dari ketiga pembicara, moderator membuka sesi pertanyaan dengan mempersilakan para penanya pertama. Pinky Saptandari, Dosen Antropologi Universitas Airlangga memberikan tanggapan bahwa buku Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial juga menjadi bacaan wajib mahasiswanya di kampus, sehingga ia sangat senang dan juga menunggu cetakan kedua buku ini. Diskusi berlangsung interaktif, peserta sangat antusias. (Andi Misbahul Pratiwi) Rilis Pers Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) “Dirgahayu Indonesia,Lestari Kendengku”  Dok. JMPPK Dok. JMPPK Hari ini, 17 Agustus 2016, tepat 71 tahun yang lalu saat Founding Father memproklamasikan kemerdekaan Negara Indonesia, terbebas dari belenggu penjajahan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi perayaan istimewa bagi kami para petani Kendeng. Ingar-bingar dari Sabang sampai Merauke dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan juga kami rasakan di Pegunungan Kendeng, tempat kami lahir dan dibesarkan, tempat kami mengabdikan diri mengisi kemerdekaan ini menjadi PETANI, dimana bertani menjadi panggilan suci hidup kami. Tempat kami terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga kelestariannya sebagai wujud rasa syukur atas semua nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Sang Semesta. Banyaknya rintangan mengadang tidak menyurutkan kami untuk terus menghidupi panggilan kami sebagai petani. Karena kami sadar bahwa bertani adalah saka guru bangsa. Bertani adalah wujud bakti kami pada ibu bumi yang telah merawat kita sejak lahir hingga hari ini, dan bertani adalah jati diri bangsa Indonesia. Rencana ekspansi pabrik semen di Pegunungan Kendeng yang berada di beberapa kabupaten, mulai dari Rembang, Pati, Grobogan, Blora sungguh mengoyak nurani kami sebagai petani. Terancam hilangnya kelestarian Pegunungan Kendeng sebagai sumber penghidupan dan eksistensi kami sebagai bangsa yang merdeka, di depan mata. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sungguh mencintai negeri ini, kami terpanggil untuk mencegah perusakan Pegunungan Kendeng dari berbagai upaya sistematis yang dilakukan oleh korporasi. Perlawanan yang bermartabat, mengedepankan budaya rembugan dengan berbagai pihak menjadi pilihan utama bagi kami. Hukum sebagai pilar keadilan utama telah kami tempuh, walaupun hasilnya belum sesuai dengan nurani dan kebenaran, tidak membuat kami berputus asa. Upaya kasasi dan peninjauan kembali kami lakukan. Kami masih memercayai bahwa pemimpin tertinggi kami, Presiden Republik Indonesia, masih setia mengemban amanat rakyat. Keputusan Pak Jokowi untuk menghentikan semua izin pertambangan di wilayah Pegunungan Kendeng (5 kabupaten) selama proses KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) menjadi bukti bahwa Pak Jokowi masih bersama petani, masih bersama rakyat Kendeng. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 yang dilakukan oleh 2000 petani Kendeng, menjadi tonggak sejarah bagi kami untuk menancapkan kuat-kuat semangat penyelamatan dan kelestarian Pegunungan Kendeng. Bertempat di Kali Kedung Jurug, desa Karangngawen, Kecamatan Tambakromo, Pati, yang rencananya akan ditambang dan dijadikan tapak pabrik semen, menjadi pilihan kami. Upacara penuh hikmat yang diadakan di atas sumber mata air ini, menjadi simbol semangat kami yang terus mengalir tiada henti untuk menyelamatkannya sekaligus menjadi saksi bahwa daerah kami yang sangat subur dan produktif ini SANGAT TIDAK LAYAK UNTUK PERTAMBANGAN. Kekhidmatan upacara yang dilanjutkan dengan brokohan dan sedekah bumi dalah wujud rasa syukur kami atas nikmat kemerdekaan ini. Lantunan doa kami panjatkan semoga “kemerdekaan sejati” bisa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagaimana telah diamanatkan oleh Founding Father dalam UUD 45 dan Pancasila. Merdeka untuk menjadi jati diri masing-masing: petani tetaplah tidak “kehilangan” lahan untuk bercocok tanam, nelayan tetap bisa melaut dengan gagah dan gembira, ilmuwan bisa mengabdikan keilmuannya untuk kebaikan kehidupan, pemimpin baik pusat maupun daerah setia mengemban amanat rakyat dengan mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya yang membawa kepada kehidupan yang semakin baik, pengusaha teruslah berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia dengan tetap memerhatikan kaidah-kaidah hukum dan sosial budaya masyarakat, penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya yang selalu berkiblatkan pada KEBENARAN. Dengan demikian semua anak negeri mewujudkan panggilan hidupnya masing-masing secara bertanggung jawab. “Dirgahayu Negeriku, Dirgahayu Indonesiaku, Sentosa dan makmurlah bangsaku, Lestari Kendengku, Lestari Indonesiaku” Salam Kendeng Lestari....!!! Narahubung Gunretno: 081391285242 Bambang: 085290140807 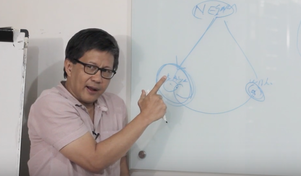 Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Seluruh bukti tentang efektivitas kebijakan publik dapat dilihat dari output-nya, misalnya kepekaan negara terhadap orientasi seksual manusia atau perhitungan upah minimum berdasarkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika kita periksa secara cepat, intuisi kita mengatakan bahwa kebijakan publik kita defisit dalam dua hal, pertama ia tidak paham pada apa yang disebut sebagai ketidakadilan (injustice) dan kedua ia secara sengaja menggelapkan sejarah perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pernyataan ini dilontarkan Rocky Gerung saat mengajar di kelas KAFFE (Kajian Filsafat dan Feminisme) yang pada bulan Agustus ini mengambil tema Kebijakan Publik, Etika Publik dan konsep Keadilan di kantor Yayasan Jurnal Perempuan, Kamis (4/8). Rocky melanjutkan bahwa persoalan yang kerap terjadi adalah kebijakan publik seringkali diselenggarakan tidak dengan posisi teori yang kritis. Sehingga ketidakadilan tumbuh dan kita baru bisa melihat akibatnya setelah satu atau dua periode ke depan. Selain itu kebijakan publik juga tidak bisa membedakan antara ketidakadilan pada laki-laki dan ketidakadilan pada perempuan. Jika seorang laki-laki mengalami ketidakadilan, dia mungkin hanya mengalami kemalangan (misfortune), tapi bagi perempuan, ketidakadilan adalah penderitaan (misery), satu konsep yang tidak mungkin dipahami oleh laki-laki. Penderitaan pada laki-laki adalah penderitaan karena kekurangan hak, sedang penderitaan pada perempuan adalah kulminasi dari semua jenis penderitaan, termasuk penderitaan terhadap harapan akan masa depan. Jadi dari awal kita bisa melihat bahwa distingsi antara ethic of rights dan ethic of care tidak dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik. Jadi kebijakan publik selalu hanya bertumpu pada satu konsep dalam teori keadilan yaitu ethic of rights. Dengan kata lain teori keadilan selalu bertumpu pada basis etika hak, transaksi hak, jumlah hak yang diperlukan, dan bukan pada ethic of care. Lebih jauh Rocky mengungkapkan terdapat beberapa posisi teori yang dominan dijadikan basis kebijakan publik. Prinsip-prinsip itu bisa ditemukan dalam dua gugus teori filosofi yakni utilitarianisme dan libertarianisme. Utilitarianisme digagas oleh Jeremy Bentham pada abad XVII untuk memperlihatkan bahwa kebahagiaan hanya bisa disebut adil bila memuaskan mayoritas. Atau dikenal dengan prinsip “the greatest happiness of the greatest number”, suatu masyarakat disebut adil bila sebagian besar mayoritas memperoleh kebahagiaan terbanyak dari produk nasional atau produk masyarakat. Masalahnya kemudian adalah keadilan bagi siapa? Ide tentang mayoritas menganggap semua manusia setara di dalam kebutuhannya. Feminisme memberi kritik bahwa sejatinya tidak setara. Kita bisa melihat misalnya pada masa Orde Baru ukuran untuk menghitung utilitas manusia untuk membuat formula kebutuhan pokok, disebutkan bahwa kebutuhan manusia diukur berdasarkan kebutuhan laki-laki, karena itu uang rokok dimasukkan sebagai kebutuhan pokok, sementara pembalut perempuan tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jadi gaji dialokasikan berdasarkan kebutuhan fisik laki-laki, karena dianggap buruh adalah laki-laki. Sehingga dari awal kita bisa melihat ada bias dalam teori keadilan dan bias itu menyelundup dalam kebijakan publik. Tetapi prinsip utilitarianisme cukup egaliter pada masanya karena pada masa itu keadilan hanya ditentukan berdasarkan belas kasihan seorang aristokrat atau ditentukan oleh hukum yang diatur dalam teologi. Pada masa itu hak hanya ada pada seorang raja, kaum feodal, atau para pendeta. Pada masa sekarang teori ini menjadi tidak demokratis karena tidak memerhatikan jenis ketidakadilan yang bekerja pada tubuh perempuan. Akan tetapi praktik-praktik kebijakan publik saat ini masih menggunakan prinsip-prinsip utilitarianisme sebagaimana terjadi dalam proses penyusunan APBN atau APBD. Sementara gugus teori lain yang juga mendominasi pembuatan kebijakan publik adalah libertarianisme. Jika utilitarianisme memandang keadilan berdasarkan jumlah kebahagiaan terbanyak yang bisa dinikmati oleh suatu masyarakat, pada libertarianisme keadilan didasarkan pada hak setiap individu untuk menghasilkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Libertarian memandang setiap orang memiliki preferensi sendiri tentang kebahagiaan, jadi tidak mungkin kebahagiaan diakumulasi dan dihitung secara agregat. Menurut Immanuel Kant manusia adalah subjek yang utuh, jadi ia harus dihormati termasuk jika ia memilih untuk miskin. Moralitas kita tidak bisa digunakan pada orang lain. Di luar kedua teori tersebut, feminisme muncul sebagai reaksi teoretis terhadap teori keadilan yang mainstream. Rocky menjelaskan seringkali istilah gender dan feminisme tidak kompatibel. Jika kita mengatakan gender equality, ini bisa terjadi karena praktik utilitarian, sehingga kesetaraan gender ada tetapi tidak ada pemutusan hubungan ideologis dengan patriarki. Patriarkisme masih dapat bekerja di dalam fasilitas gender equality karena ada kesalahan perspektif. Di dalam gender equality orang ingin menyetarakan hak melalui kebijakan, sedang pada feminisme kritiknya bukan sekadar kesetaraan hak tetapi perubahan logika di dalam kebijakan. Jadi feminisme lebih tajam karena ia menginginkan segala jenis patriarki berakhir. Karena itu dalil filosofinya lebih radikal dibandingkan gender equality. Rocky mengungkapkan Indonesia masih pada tahap gender equality. (Anita Dhewy)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Kamis, 11 Agustus 2016, kelas Kajian FIlsafat dan Feminisme (Kaffe) dibuka dengan cuplikan film Les Miserables, Kaffe pada pertemuak ini mengangkat tema tentang Republikanisme dengan pengajar Robertus Robert, dosen Sosiologi UNJ. “Disini ada yang tahu tentang republikanisme? Ada yang pernah dengar republikanisme sebagai suatu konsep atau istilah?” Robertus Robert mengawali kelas Kaffe dengan mengutarakan pertanyaan tersebut. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kita sering mendengar kata republikanisme, bahkan bentuk Negara Indonesia adalah republik, tapi kita tidak pernah diajarkan tentang apa arti republik, apa artinya menjadi warga Negara sebuah republik. Robertus Robert melanjutkan bahwa pada rapat BUPKI (Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Moh. Yamin berkata bahwa penting untuk merumuskan bentuk Negara segera, sebelum kemerdekaan. Pada saat sidang BUPKI ada banyak usulan, seperti bentuk negara kerajaan, termasuk usulan republik. Bentuk Negara republik terpilih berdasarkan vote, suara terbanyak memilih republik. Alasannya sederhana karena republik adalah bentuk Negara yang berbeda karakteristiknya dengan Kolonial yaitu feodalistik. Maka republik dipilih dengan argumen yang sanagt sederhana yaitu dengan memilih republik maka kita tidak memilih bentuk kerajaan. Kemudian Robertus menjelaskan tentang pandangan republikanisme Aristoteles, ia memulai dengan pemikiran Aristoteles tentang perbedaan manusia dan binatang yaitu phone dan logos, binatang hanya memiliki kemampuan phone, kemampuan menyuarakan sakit dengan bunyi tapi binatang tidak memiliki kemampuan logos yaitu membaca simbol dan komunikasi linguistik, maka binatang tidak bisa membahasakan keadilan. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa yang menurut Aristoteles yang memiliki logos hanya laki-laki, perempuan hanya memiliki phone, perempuan hanya bisa menyuarakan rasa sakit, demikian juga budak. Logos sebagai cara, ekspresi, deliberative untuk mengupayakan apa yang adil hanya ada di satu tempat yaitu polis (politik). Jadi polis dalam konsep Aristoteles adalah satu wahana tindakan dimana manusia (laki-laki) mengekspresikan secara deliberative apa yang adil bagi society. Sedangkan perempuan tidak boleh berada dalam polis, perempuan memiliki tempat sendiri yaitu oikos (rumah tangga). Pandangan Aristoteles tersebut mengawali suatu pemilahan antara polis dan oikos, kemudian dalam pandangan Cicero, polis adalah res publica dan oikos adalah res privata. Ini awal pembelahan antara yang publik dan privat dalam filsafat dan gagasan awal republikanisme. Polis bukan entitas geografi, polis adalah wahana tindakan. Pandangan Cicero dalam tradisi Romawi Kuno bahwa res publica adalah sebuah cara pemerintahan dimana orang memperjuangkan keadilan untuk tujuan bersama. Res publica ini yang kemudian menjadi kata republik, selanjutnya republikanisme sebagai sebuah filsafat politik bergeser menjadi sebuah pandangan hukum ketatanegaraan. Lebih jauh Robertus menjelaskan bahwa Indonesia sebagai sebuah bentuk negara republik yang memisahkan antara yang publik dan privat tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik. Misalnya, agama adalah suatu yang privat namun dijadikan elemen dalam penentuan kebijakan publik. Contoh lain adalah tentang tes keperawanan yang merupakan sesuatu hal privat namun dibawa ke ranah publik. Robertus mengungkapkan bahwa dalam pemikiran Aristoteles ini pun masih memiliki inkonsistensi, karena pemisahan ini masih berdasarkan relasi kuasa, dimana perempuan sebagai manusia ditempatkan di oikos karena tidak memiliki logos, namun disaat yang sama hal privat masuk ke dalam ruang publik karena relasi kuasa yang sama. Kebijakan publik seharusnya adalah wahana tindakan untuk mencapai kepentingan bersama, namun kultur patriarki masih kental di masyarakat Indonesia. Republikanisme adalah gagasan generik, dia punya cacat bawaan, republikanisme sebagai gagasan membutuhkan feminisme untuk mengikis patriarki, ia juga butuh liberalisme untuk memperjuangkan hak asasi. (Andi Misbahul Pratiwi)  Selasa, 9 Agustus 2016, pameran karya instalasi “Kitab Visual Ianfu” dengan Kurator Dolorosa Sinaga digelar di Cemara 6 Galeri-Museum. Pameran karya instalasi yang melibatkan 12 perupa perempuan dari lintas generasi ini digagas oleh Komite Ianfu Indonesia dalam rangka sosialisasi Hari Peringatan Internasional untuk Ianfu atau International Memorial Day for 'Comfort Women'. Pameran ini merupakan bentuk kepedulian serta pengungkapan sejarah untuk Ianfu, perempuan korban perbudakan seksual oleh militer Jepang. Pameran ini akan digelar pada 9-23 Agustus 2016. Perempuan perupa yang berpartisipasi dalam pameran instalasi ini adalah Ade Artie Tjakra, AP Bestari, Putri Ayu Lestari, Ayu Maulani, Bibiana Lee, Dyah Ayu, Gadis Fitriana, Ida Ahmad, Indah Arsyad, Indira Natalia, Indyra, Nia Laughlin. Acara pembukaan pameran instalasi dilaksanakan pada hari pertama pameran ini, pukul 19.00 WIB di tempat yang sama. Terlihat lebih dari 30 tamu undangan yang hadir dari berbagai latar belakang yang menunjukan bahwa mereka peduli terhadap Ianfu. Acara ini diawali oleh sambutan Inda Noerhadi selaku sambutan direktur Cemara 6 Galeri. Dalam sambutannya Inda mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi acara pameran instalasi Ianfu ini. Selanjutnya acara disambung dengan sambutan dari Toeti Heraty. Ia mengungkapkan bahwa lama waktu penjajahan Jepang telah diramalkan, yaitu seumur tahun jagung. “Jagung itu kan matang ketika 3,5 bulan, tapi ramalan berkata seumur tahun jagung, jadi benar 3,5 tahun, meskipun waktunya singkat, tapi penjajahan Jepang sangat kejam”, tutur pemilik Galeri Cemara 6 Museum ini. Ia juga mengungkapkan pada waktu penjajahan Jepang, ia masih sangat muda dan pada saat itu ia hanya berbicara dalam bahasa Belanda dan Jawa pada orang tuanya, “ketika Jepang datang, kami semua tidak boleh bicara dengan bahasa Belanda”, ungkapnya. Lebih jauh ia menceritakan bahwa pada saat itu banyak anak remaja yang keluar rumah dengan mengenakan pakaian laki-laki, bertopi, memakai celana, agar terlihat seperti laki-laki, ia mengungkapkan bahwa remaja tersebut takut menjadi korban tentara Jepang. Toeti mengungkapkan bahwa pada waktu itu ia tidak pernah mendengar tentang Jugun Ianfu, yang ia hanya dengar Romusa, sama apa yang kita ketahui sekarang hanya Romusa. Dengan begitu ia menyimpulkan bahwa sebenarnya kita sangat jauh dengan sejarah perempuan, dimana perempuan ditindas dan tidak mendapatkan keadilan. “Saya berharap dengan adanya pameran karya instalasi ini, pengetahuan kita tentang sejarah perempuan dapat terbuka, bahwa sebenarnya Jugun Ianfu adalah perempuan korban perbudakan seks”, tutur Toeti di akhir sambutannya.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Setelah itu acara dilanjutkan dengan sambutan dari Dolorosa Sinaga. Ia sangat berterima kasih kepada para undangan yang hadir, “Ruangan yang penuh ini menunjukkan bahwa masih banyak yang peduli terhadap sejarah perempuan, kita semua peduli terhadap Ianfu”, ungkap Kurator pameran instalasi “Kitab Visual Ianfu”. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa pameran ini merupakan karya kolaborasi yang melibatkan 12 perupa lintas generasi. “Kami mengambil judul kitab visual Ianfu, karena kita tahu bahwa kitab adalah pengetahuan, maka diharapkan pameran ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang Ianfu setelah sekian lama terbungkam”, tutur Dolorosa. Melibatkan perupa muda menurut Dolorosa juga sangat menarik, karena pameran ini adalah percakapan dengan waktu, sehingga perupa lintas generasi akan menampilkan karya yang beragam bahkan ada yang melibatkan teknologi. Setelah Kurator, Eka Hindra, peneliti independen Ianfu Indonesia, memberikan sambutannya. Eka Hindra sangat terharu mengenang perjalanan panjangnya meneliti Ianfu. Menurutnya ini adalah penelitian sekaligus perjalanan yang 'menyakitkan' ketika mendengar eyang-eyang bercerita tentang pengalamannya. “Mereka hidup dalam kesepian karena sejarah yang salah, neagra yang absen dan stigma yang melekat, Ianfu bukanlah pelacur”, tutur Eka. Ia bercerita bahwa ada Ianfu asal Solo, yaitu Tuminah, yang pada tahun 1992 berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, atas motivasi yang diberikan oleh orang-orang terdekat akhirnya Tuminah memutuskan untuk bercerita. Berkat keberanian dan pernyataan Tuminah, maka kita semua bisa melihat lebih dekat, dan membuka pengetahuan lebih dalam. “Setidaknya dengan pameran ini, kita bisa memberikan keadilan bagi Ianfu ketika negara abai”, tutur Eka dengan penuh haru. Setelah rangkaian sambutan, Azriana Rambe Manalu, Ketua Komnas Perempuan dipersilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka pameran karya instalasi “Kitab Visual Ianfu”. Azriana sangat berterima kasih kepada penyelenggara, kurator, perupa yang telah memungkinkan pameran instalasi Ianfu ini terjadi. “Apa yang terjadi pada Ianfu membuktikan bahwa perempuan sangat rentan dalam kondisi perang atau konflik, Negara harus tahu dan peduli terhadap kasus kekerasan masa lalu dan tidak membiarkan impunitas terjadi”, ungkap Azriana. Ia juga mengungkapkan bahwa perbudakan seksual masuk dalam kategori kekerasan seksual dan Komnas Perempuan sedang mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar dapat disahkan segera. Menurutnya, sisitem hukum Indonesia harus mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual bukan hanya saat konflik tapi juga di ruang-ruang domestik, sehingga UU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan agar kekerasan tidak berulang di masa yang akan datang. Azriana mengakhiri sambutannya dengan membuka secara resmi pameran ini. Setelah rangkaian sambutan, acara dilanjutkan dengan dengan melemparkan kupu-kupu kertas berwarna kuning oleh seluruh tamu undangan. Kupu-kupu kuning menjadi simbol internasional untuk Ianfu. Pameran ini merupakan ruang untuk berinteraksi terhadap kepedihan-kepedihan, pada waktu, pada Ianfu. Karya yang ditampilkan sangat beragam, mulai dari lukisan, instalasi ruangan, instalasi pakaian kebaya transparan, topi-topi tentara Jepang hingga hologram. Pengetahuan tentang sejarah Ianfu perlu disosialisasikan dalam beragam bentuk dan media, karena Ianfu berhak mendapatkan pengakuan dan keadilan setelah sekian lama terpinggirkan dan hidup dalam kesunyian. (Andi Misbahul Pratiwi)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Jakarta, 3 Agustus 2016, Komnas Perempuan mengeluarkan laporan hasil pemantauan tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kelompok penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Laporan yang diluncurkan di Aula Mahkamah Konstitusi ini diharapkan mendapatkan tanggapan dari Kementerian/Lembaga. Hadir wakil Menteri Dalam Negeri, wakil Menteri Hukum dan HAM, wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wakil Menteri Agama, dan 4 perwakilan kepala daerah (NTT, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Tengah). Serta dihadiri oleh sekitar 80 perwakilan organisasi dari masyarakat sipil dan organisasi keagamaan, serta 15 perwakilan dari masyarakat penganut penghayat kepercayaan/ Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat. Peluncuran ini ditujukan terutama kepada para penyelenggara negara, para penegak hukum, lembaga-lembaga agama, tokoh agama dan masyarakat luas, agar dapat menyimak berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan penghayat kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat. Laporan pemantauan ini menggambarkan kekerasan dan diskriminasi atas dasar keyakinan/kepercayaan, terhadap perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat yang menyebabkan kesengsaraan fisik, psikis, dan juga gangguan reproduksi pada korban, serta dampak ekonomi, sosial dan hukum yang ditanggung oleh korban dalam waktu yang panjang. Seluruh pengalaman itu menyebabkan mereka mengalami penderitaan yang hebat akibat merasa digerus rasa kemanusiaannya, menderita karena kehilangan perlindungan atas kehormatan dan martabatnya. Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Andy Yentriyani, perwakilan dari Kemeterian Agama mengungkapkan bahwa Kementerian Agama sedang menyiapkan RUU Perlindungan Umat Beragama. RUU ini diharapkan dapat melindungi para penghayat kepercayaan maupun umat beragama diluar 6 agama yang disahkan pemerintah. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi berbasis agama dan gender. Andy Yentriyani mengungkapkan penting bagi kita semua untuk berdiskusi serta menyamakan persepsi. Negara berkewajiban memfasilitasi warga negaranya dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan keyakinan dan agama. Diskusi ini juga menghadirkan para penghayat dari berbagai daerah. Salah satu penghayat Sunda Wiwitan, Juwita, mengungkapkan kebingungannya terhadap kebijakan pemerintah yang mengharuskan penghayat kepercayaan untuk diorganisasikan. Menurutnya jika kepercayaan diorganisasikan maka akan timbul yang mayoritas dan minoritas. Menanggapi pertanyaan tersebut perwakilan dari Kementerian Agama mengatakan bahwa penting untuk melakukan pendataan termasuk pengorganisasian agar kedepannya tidak ada konflik horizontal antar umat beragama. Meski sudah 71 tahun Indonesia merdeka, banyak kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati hak-hak konstitutionalnya. Hal tersebut digambarkan dalam hasil laporan pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang melibatkan perempuan dari 10 komunitas berasal dari 9 Provinsi, perempuan penghayat kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat. Pada konferensi pers yang dilaksanakan setelah diskusi, ketua komisoner Komnas Perempuan, Azriana, mengungkapkan bahwa persoalan diskriminasi terhadap perempuan penghayat kepercayaan masih terjadi pada faktanya. Selain itu perempuan juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun di lingkungan sosialnya. Indraswari anggota Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional/GK PKHN membacakan rilis hasil temuan Komnas Perempuan pada persoalan ini yang didasarkan pada pengungkapan 115 kasus dari 87 peristiwa kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat dari 11 komunitas yang tersebar di 9 Provinsi. Dari 115 kasus tersebut, 50 diantaranya adalah kasus kekerasan dan 65 lainnya kasus diskriminasi. Setidaknya ada enam jenis kasus yang dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk kekerasan, yaitu: (a) Kekerasan psikis dalam 14 kasus stigmatisasi/pelabelan dan 24 kasus intimidasi; (b) Kekerasan seksual dalam 7 kasus pemaksaan busana dan 3 kasus pelecehan seksual, serta; (c) Kekerasan fisik dalam 3 kasus penganiayaan dan 2 kasus pembunuhan. Sementara itu, lebih dari setengah dari 65 kasus diskriminasi adalah kasus pengabaian diabaikan dalam administrasi kependudukan. Selebihnya terdapat 9 kasus pembedaan dalam mengakses hak atas pekerjaan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut, 8 kasus pembedaan dalam mengakses pendidikan, 3 kasus dihambat dalam mengakses bantuan pemerintah, 3 kasus dihalangi akses pemakaman, 2 kasus dihalangi dalam mendirikan rumah ibadah, 5 kasus dihambat dalam beribadah, dan 1 kasus pelarangan berorganisasi keyakinan. Tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut dilakukan oleh sekurangnya 87 pelaku, 44 diantaranya adalah pelaku individual sementara 10 lainnya dilakukan berkelompok. Sebanyak 52 diantaranya adalah aparat pemerintahan dan 2 aparat hukum. Hal ini berkorelasi dengan temuan bahwa sebagian besar dari peristiwa kekerasan dan/atau diskriminasi yang dialami terjadi di ranah negara, yaitu sebanyak 62% atau 54 peristiwa. Sementara itu, di ranah publik tercatat 27 peristiwa. Juga terdapat 2 peristiwa kekerasan di dalam rumah tangga yang berkait dengan hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan; salah satunya bahkan menyebabkan penghilangan nyawa. Ada 9 faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan dan gender ini dapat terus berlangsung, yaitu: (a) Adanya produk hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi penghayat kepercayaan, a.l. UU No. 1 PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dan UU Administrasi Kependudukan dan kebijakan diskriminatif di tingkat daerah; b) Tata kelola insitusi pemerintahan yang membedakan penanggungjawab pemeluk agama dari penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur; c) Mekanisme pengawasan pelayanan publik yang tidak dilengkapi dengan perangkat pemeriksa operasionalisasi prinsip non diskriminasi; d) Kapasitas penyelenggara negara yang terbatas sehingga belum mampu mengoperasionalisasikan prinsip non diskriminasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraaan pemerintahan pada umumnya; e) Sikap penyelenggara negara yang menyepelekan konsekuensi yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan dan pemeluk agama leluhur akibat diskriminasi itu; f) Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku diskriminasi dan kekerasan; g) Pemahaman agama yang memposisikan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur sebagai pihak lian yang tidak beragama; h) Proses politik yang tidak dilengkapi dengan mekanisme pengaman pelaksanaan prinsip non diskriminasi sehingga memungkinkan hegemoni kepentingan kelompok tertentu, termasuk kelompok (pemeluk) agama, dalam penyusunan kebijakan publik dan; i) Sikap masyarakat yang masih menolerir kekerasan dan diskriminasi, termasuk yang berbasis agama/kepercayaan. Pada rilis yang dibacakan saat konferensi pers, Komnas Perempuan mengapresiasi terhadap sejumlah perwakilan dari kementerian/lembaga yang hadir untuk membuka dialog atas persoalan yang dihadapi, dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Komnas Perempuan meminta bahwa Negara perlu untuk terus melakukan sosialisasi atas terobosan yang telah dilakukan melakukan langkah-langkah tindak lanjut antara lain: 1) Perbaikan produk hukum dan kebijakan agar dapat secara sungguh-sungguh menegakkan hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; 2) Pengembangan mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan prinsip non diskriminasi, termasuk atas dasar keyakinan dan gender, dalam mencegah, menangani dan memastikan ketidakberulangan kekerasan dan diskriminasi, termasuk atas dasar keyakinan dan gender, dalam setiap aspek dan lembaga penyelenggara pemerintahan dan penegakan hukum; 3) Menggagas dan melaksanakan mekanisme dan perangkat pengawasan pada sikap aparatur pemerintah, pejabat publik dan penegak hukum untuk memastikan dilaksanakannya prinsip non diskriminasi; 4) Menghentikan impunitas pelaku tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan, termasuk terhadap pelaku non negara; 5) Mereformasi birokrasi, termasuk Kementerian Agama, guna memutus pelembagaan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur; 6) Mengintegrasikan penghormatan pada keragaman agama/keyakinan dalam kurikulum pendidikan nasional dan pendidikan publik untuk mengembangkan kecintaan pada kebhinnekaan Indonesia; 7) Kerjasama dengan komunitas korban dan masyarakat sipil yang selama ini telah teguh berjuang untuk pemenuhan hak konstitusional warga negara anggota komunitas minoritas keyakinan. (Andi Misbahul Pratiwi)  Dok. Yuliana Paramayana Dok. Yuliana Paramayana “Buku ini prosesnya saya bikin selama tujuh tahun. Saya menyambi, dulu pernah bekerja kantoran jadi fotografer di Kompas-Gramedia. Jadi setelah saya resign, saya lanjutkan. Awalnya saya membaca buku Fransisca Ria Susanti yang berjudul Kembang-Kembang Genjer. Saya bertemu dengan penulisnya dan kemudian bertanya. Kebetulan saya punya kawan dari salah satu ibu yang ada di sini yakni Ibu Pudjiati, Dialah yang membawa saya ke panti.” Berangkat dari kegelisahan Adrian bahwa terkadang isu 65/66 hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, maka ia dan beberapa kawan mencoba mencari cara menerbitkan sebuah buku yang dapat menarik perhatian generasi muda. Adrian Mulya telah membaca banyak buku, di antaranya novel Amba karya Laksmi Pamuntjak dan Pulang karya Leila S. Chudori. “Setelah saya mengobrol dengan satu kelompok diskusi buku di salah satu fakultas di kampus UI, saya tanya kok dia punya satu kelompok diskusi yang khusus ngomongin isu 65/66, kamu awalnya tertariknya isu ini dari mana?“ terang Adrian Mulya dalam diskusi buku foto Pemenang Kehidupan karyanya sendiri pada Kamis (28/7) di Komunitas Sinemain, Badran Solo. Dari membaca novel tersebut membuatnya berpikir bagaimana mengemas isu yang berat seperti isu 65/66 agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh generasi yang tadinya awam. Sebagai seorang fotografer Adrian memiliki potret beberapa simbah penyintas. “Lalu saya membuat konsep, ini lho ada potret seperti ini, paling nggak mereka tahu dan mulai tertarik. Pancingannya sudah kita berikan,” Adrian mengemukakan beberapa alasan dan motivasinya. Acara diskusi yang berlangsung selama 2 jam ini dipandu oleh Isyfi Afiani sebagai moderator dan menghadirkan Elizabeth Yulianti Raharjo, aktivis perempuan dari Jejer Wadon sebagai pembicara. Dalam diskusi buku foto tersebut Elizabeth mengemukakan bahwa beberapa program gerwani di masa lalu adalah di bidang pendidikan dengan memberantas buta huruf, mendirikan taman kanak-kanak, advokasi undang-undang perkawinan (asas monogami). Program-program tersebut sangat menyentuh problem mendasar para perempuan. Mereka ketika dipenjara mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis serta seksual. Kekerasan seksual yang dialami oleh penyintas perempuan 65/66 adalah sesuatu yang khas dialami oleh penyintas laki-laki 65/66. “Dan sampai saat ini pun kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius dan negara tidak punya konsep yang jelas dalam hal pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Saat ini beberapa teman jaringan melakukan advokasi pengesahan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual,” tutur Elizabeth. Mbah Pono, penyintas 65/66 yang hadir dalam diskusi mengatakan bahwa penyelesaian secara politik sulit. Tetapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Ibarat berperang dan melawan musuh, kemampuan kita sejauh mana untuk membela kemanusiaan. “Untuk itu saya sebenarnya ingin bertanya kepada generasi muda tentang peristiwa 65, apa yang sebenarnya terjadi. Kita tahu kalau berbicara peristiwa 65 maka PKI, Gerwani, pokoknya yang jahat-jahat itu ditempelkan kepada kita semua,” ujar mbah Pono. Kepada JP, Adrian Mulya menyampaikan harapan buku foto Pemenang Kehidupan lebih dikenal masyarakat. Dia melihat ada kesenjangan di antara orang-orang yang paham isu 65/66 dan generasi yang lebih muda atau kini biasa disebut generasi milenia. “Makanya kenapa buku itu saya buat ringkas. Foto dan orangnya jelas, saya foto dengan baik, tulisannya juga pendek, nggak banyak bertele-tele dan nggak terlalu panjang, serta fokus kepada saat-saat terbaik para Mbah,” pungkas Adrian Mulya dalam diskusi yang dijaga ketat intel kepolisian Surakarta. (Astuti Parengkuh) |
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
June 2024
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed