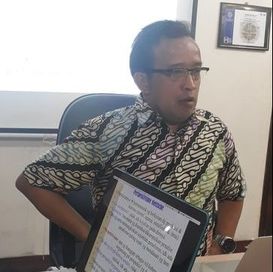 Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Kamis (12/4), Jurnal Perempuan mengadakan seri KAFFE ke-10 (Kajian Filsafat dan Feminisme) tentang Post-truth. Seri KAFFE pertemuan keempat ini diampu oleh Haryatmoko dengan tema Post-Truth dan Pemikiran Filosofis Di Baliknya. Pada tiga pertemuan sebelumnya, post-truth telah dibahas dalam berbagai perspektif seperti feminisme, media sosial dan politik. Sementara pada pertemuan keempat ini, Haryatmoko membahas post-truth dari perspektif filsafat. Haryatmoko menjelaskan bahwa post-truth adalah isu tentang kebenaran. Menurutnya bahasa sering menjadi media untuk memunculkan kebenaran. Akan tetapi, saat ini bahasa tidak lagi mengacu pada kebenaran, sebab banyak orang sering menggunakan logika biner atau cara berpikir biner yang menyebabkan adanya penentuan buruk dan baik dalam membandingkan hal tertentu. Hal ini mengakibatkan eliminasi atas fakta lain yang berbeda dari apa yang seseorang yakini. Haryatmoko menyampaikan bahwa menurut Derrida hal ini amatlah keliru dan berbahaya. Logika biner akan menyebabkan adanya pemaknaan tunggal dan itu berakibat pada pemaknaan yang otoriter. Selain itu Haryatmoko juga menegaskan bahwa bahasa terdiri dari ideologi konfliktual, dinamis atas sistem keyakinan dan nilai yang beroperasi pada waktu dan dalam budaya tertentu. Cikal bakal post-truth bisa jadi datang dari cara pandang yang erat dengan logika biner. Haryatmoko menegaskan bahwa konsep harusnya mampu mengidentifikasi identitas, baik identitas bahasa maupun ideologi di baliknya. Namun dalam post-truth yang terjadi berbeda, asalkan emosi kena, maka masuklah ke dalam post-truth. Konsep dari Derrida yang mencoba mendekonstruksi logika biner kemudian dikaitkan oleh Haryatmoko dengan perspektivisme Nietzsche. Perspektivisme Nietzsche merupakan konsep yang tidak memosisikan atau tidak mengejar hal yang benar atau salah, karena ketika kita mengejar benar atau salah maka kita hanya melakukan fact checking. Haryatmoko juga menjelaskan bahwa metode genealogi Nietzsche bermaksud melihat suatu pernyataan bukan dihitung benar atau salah tetapi siapa yang menyatakan hal tersebut dan apa kepentingan di baliknya. Dengan begitu ia menegaskan bahwa setiap fakta mengandung ideologi dan semua perspektif bersifat aksiologis dengan kata lain diarahkan oleh nilai dan tidak satupun bebas nilai. Selanjutnya, Haryatmoko memaparkan tentang bagaimana Michel Foucault menyuarakan permainan kebenaran sebagai sistem pelarangan. Dilihat dari kacamata Foucault, kekuasaan dahulu dan kini berbeda. Apabila dahulu kekuasaan terpusat pada suatu tempat misalnya penguasa, saat ini kekuasaan menyebar misalnya pada individu yang menjadi subjek penyebaran kekuasaan. Era post-truth memperlihatkan bahwa kekuasaan bersifat menyebar melalui individu dengan penyebaran berita hoax. Kekuasaan yang dahulu terpusat, saat ini menyebar dan melalui era post-truth kekuasaan yang menyebar ini menjadi lebih nyata. (Iqraa Runi)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan “Apa kira-kira sebutan yang paling ditakuti oleh orang Indonesia? Kalau anda orang Indonesia dan perempuan?” Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Gerwani. Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Atnike Nova Sigiro, M.Sc., Direktur Jurnal Perempuan, dalam sesi kuliah ketiga KAFFE ke-10 yang diselenggarakan oleh Jurnal Perempuan dengan tema “Post-truth dan Feminisme” pada Kamis (5/4). Lebih lanjut Atnike menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia sebagai perempuan maka salah satu stigma politis yang sangat diskriminatif dan terus direproduksi hingga detik ini adalah Gerwani. Stigma politis yang diskriminatif tersebut terus muncul dan hadir di dalam masyarakat hingga saat ini karena situasi paranoid yang diciptakan oleh post-truth. Post-truth sendiri merupakan suatu situasi ketika fakta objektif tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan emosi atau belief yang dipercaya oleh masyarakat. Mengangkat isu Post-truth dan Feminisme, Atnike menjelaskan bahwa situasi paranoid yang diciptakan oleh post-truth memberikan ruang bagi diskursus konservatif untuk berkembang dalam masyarakat. Akibatnya jargon-jargon konservatif dengan kultur patriarki yang sudah lama hidup di masyarakat mendapatkan lahan untuk terus tumbuh. Seksisme sebagai bagian dari patriarki semakin diperkuat melalui media sosial dalam situasi post-truth. Atnike mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan dalam dunia siber yang selalu menyudutkan perempuan dengan berbagai cara seperti mempermalukan, mengintimidasi, dan melecehkan. Situasi tersebut biasanya kita lihat pada saat momen politik, seperti pemilu/pilkada. Pada momen politik, target kekerasan yang diserang biasanya adalah para politisi perempuan dan para aktivis perempuan atau aktivis HAM. Atnike memberikan contoh beberapa tokoh perempuan yang mengalami situasi tersebut di media sosial pada saat pemilu/pilkada berlangsung di Indonesia. Komentar yang diberikan oleh warganet pada setiap pandangan yang disampaikan para tokoh perempuan di media sosial seringkali tidak berhubungan sama sekali dengan konteks yang disampaikan. Sebaliknya, mereka justru menyerang personal dan keperempuanan para tokoh tersebut. Serangan-serangan terhadap para tokoh perempuan di media sosial, menurut Atnike, merupakan wujud dari kekerasan terhadap perempuan dalam dunia siber. Dampak dari post-truth dan kekerasan terhadap perempuan dalam dunia siber dapat membuat perempuan menarik diri dari diskursus publik dan partisipasi politik. Dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melawan post-truth dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, antara lain, (1) gerakan feminis harus membangun strategi di dunia siber, (2) perlunya mendorong gerakan digital citizenship, (3) mendorong advokasi kebijakan untuk membedakan dan mengatur harassment versus real threat, serta (4) perlu adanya online support group. Atnike menjelaskan lebih lanjut terkait empat hal diatas, gerakan feminis harus membangun strategi di dunia siber karena ancaman terhadap perempuan atau kekerasan terhadap perempuan di dunia internet atau media sosial itu adalah ancaman yang nyata. Tidak menutup kemungkinan jika ancaman tersebut dapat terjadi di dunia nyata, misalnya akibat menyampaikan suatu pandangan politik atau pandangan pribadinya tiba-tiba ada pihak yang menggunakan komentar di dunia maya tersebut sebagai alat persekusi. Selanjutnya Atnike menyampaikan konsep gerakan digital citizenship yang tidak berbeda jauh dengan konsep citizenship di dunia nyata. “Bahwa dunia digital itu dunia para warga yang harus dibangun dengan etika dan saling menghargai,” ujar Atnike. Selain itu, advokasi kebijakan untuk membedakan dan mengatur harassment versus real threat menurut Atnike juga perlu diatur dengan ukuran yang jelas, tidak sekadar melakukan blokir. Adanya online support group juga dibutuhkan untuk mencari tujuan yang sama yaitu suatu kesadaran baru. Kekerasan terhadap perempuan dalam dunia siber tidak terlepas dari perkembangan post-truth dalam media, baik media massa maupun media sosial. Atnike menjelaskan bahwa dari televisi kita dapat belajar bagaimana post-truth berkembang sangat pesat di masa sekarang. Peran televisi sekarang ini telah berhasil menurunkan diskursus publik menjadi sebatas entertainment dan showbiz. Masyarakat tanpa disadari telah diajak untuk menelan informasi yang sepotong-sepotong dari televisi. Pergerakan informasi yang sangat cepat dan tidak tersampaikan secara menyeluruh menjadikan media televisi sebagai media yang fast and chaotic. Media yang seharusnya menjadi alat komunikasi justru menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi, jelas Atnike. Kita juga bisa melihat bagaimana post-truth berkembang dengan pesat di media sosial dengan setiap penggunanya telah memiliki kesimpulan dan kepercayaannya sendiri. “Mengapa media sosial menjadi penting? Meningkatnya penggunaan media sosial terjadi ketika media sosial memiliki peranan politik,” ujar Atnike. Penggunaan media sosial dalam praktik politik di diskursus publik saat ini merupakan hal yang penting dan tanpa disadari menimbulkan ketegangan diantara masyarakat dengan kepercayaan politiknya masing-masing. Merujuk pada Hannan (2018), Atnike menjelaskan perbandingan antara televisi dan media sosial. Jika televisi menjadikan diskursus publik sebagai showbiz maka media sosial menjadikan diskursus publik sebagai suatu kontes popularitas ala siswa-siswi SMU. Tanpa disadari, menurut Atnike, media sosial telah menciptakan suatu atmosfer hyperemotional dengan reaksi-reaksi spontan dan paranoid di dalam masyarakat. Jauh sebelum konsep post-truth menjadi populer, kita sudah sering mengenal adanya berita palsu atau kebohongan publik, namun pada saat itu ketegangan antar masyarakat tidak terjadi semudah dan secepat sekarang. Atnike menutup kuliah KAFFE malam itu dengan menyampaikan tiga hal yang perlu dipahami untuk memahami post-truth, yaitu: (1) siapa yang memiliki kontrol atas informasi di media massa, (2) bagaimana karakter media sosial dan penggunanya, dan (3) bagaimana situasi politik yang sedang berlangsung di dalam masyarakat. (Bella Sandiata)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Kamis (29/3) Yayasan Jurnal Perempuan mengadakan Kajian Filsafat dan Feminisme (KAFFE) dengan tema post-truth. Pertemuan kedua rangkaian KAFFE ke-10 tersebut membahas “Politik Media dan Post-Truth” dengan pembicara Rocky Gerung. Rocky mengawali kelas dengan melontarkan sebuah kalimat, “Aktifkan kecurigaan tentang asal-usul post-truth.” Pernyataan itu dilontarkan lantaran ia berusaha membawa pembahasan untuk lebih membidik isu di belakang post-truth bukan sekadar mempersoalkan post-truth itu sendiri. Hal ini ditekankan karena menurut Rocky selama ini banyak kesalahpahaman makna “truth” yang ada pada “post-truth”. Selama ini banyak orang mengira post-truth sebagai bentuk baru dari kebenaran. Namun, sejatinya post-truth tidak berkaitan dengan kedudukan epistemik dari kebenaran. Rocky menjelaskan bahwa post-truth adalah persoalan politik. Maksudnya, politik kini tidak lagi diiringi dengan etika politik dan hal ini menjadikan munculnya upaya kotor dalam berpolitik. Salah satu munculnya ketiadaan etika politik adalah ketika kita temukan tidak hidupnya suara oposisi. Rocky juga menjelaskan bahwa problem pada post-truth diawali ketika seseorang tidak mungkin berkonsensus dan pada titik inilah seseorang tidak lagi memercayai kebijakan merupakan barang yang dihasilkan dari aktor politik sebagai agen rasional. Post-truth sebagai paradigma baru memunculkan masalah pada politik. Masalah ini tentunya tidak serta-merta dihasilkan oleh kehadiran post-truth. Akan tetapi masalah muncul ketika ada lack of knowledge dari warga negara, sehingga menjadi bahan untuk membawa banyak orang pada kondisi post-truth. Informasi yang kita baca sejatinya perlu dibekali oleh fakta, tetapi ketika kita berbicara fakta maka ada pembelaan melalui data-data yang seolah-olah identik dengan kebenaran. “Selama ini orang tertipu oleh data, karena data dianggap merepresentasikan kebenaran jadi hanya data yang mereka butuhkan untuk memercayai bahwa hal itu benar, tetapi itulah post-truth, benar karena yakin,” tutur Rocky. Dalam memilah informasi, kita hanya membutuhkan ketahanan intelektual dan hal ini tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagi Rocky pembicaraan orang Indonesia kebanyakan tidak bisa dibawa kepada ruang rasional sehingga mereka menggunakan media sosial untuk menyalurkan kemarahannya. Sementara di media sosial terdapat banyak produk post-truth seperti hoax, yang dihasilkan dari kepentingan politik yang tidak mengacu pada etika politik. Rocky memaparkan bahwa stasiun televisi di Indonesia dimiliki oleh tiga hingga empat orang. Informasi yang beredar di televisi tergantung dari permintaan pemilik, hal ini membuat hilangnya etika jurnalisme. Rocky menjelaskan bahwa hoax bukan hanya diproduksi dari suara oposisi, tetapi bisa juga diproduksi oleh pemerintah dalam upaya mempertahankan kekuasaan. Bagi Rocky di tahun politik seperti sekarang, post-truth akan semakin mudah menyerang orang-orang tanpa ketahanan intelektual. Media akan menggunakan post-truth sebagai alat untuk promosi politik baik secara sehat maupun tidak. Kegelisahan akan menurunnya kualitas pengetahuan melalui media menakutkan banyak orang, terutama ketakutan akan masuk pada lingkar post-truth. Oleh karena itu Rocky mengungkapkan ketahanan intelektual yang didasari oleh etika politik dapat digunakan untuk menghindari post-truth. Sementara politik yang sehat dapat dimunculkan dengan kembali pada virtue dan truthfullness. (Iqraa Runi)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Jumat (23/3) bertempat di Auditorium LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan diskusi “Gender dan Kebangsaan: Merawat Keindonesiaan”. Acara ini sekaligus memperingati ulang tahun tokoh perempuan Sjamsiah Achmad yang ke-85. Kiprah Sjamsiah Achmad dalam menyuarakan kemanusiaan juga hak perempuan menjadi pokok pembicaraan pada acara ini. Melihat mulai terkikisnya rasa kemanusiaan mendorong Sjamsiah Achmad untuk kembali membicarakan relasi antara perspektif gender dengan rasa kebangsaan. Acara yang dimoderatori oleh Henny Supolo Sitepu, Ketua Yayasan Cahaya Guru membahas tentang kiprah perempuan dan masalah perempuan yang ada di Indonesia. Andy Yentriyani, Ketua Yayasan Suar Asa Khatulistiwa yang hadir sebagai salah satu narasumber menyatakan ketika kita berbicara mengenai kebangsaan maka masalah perempuan terletak pada kebinekaan sebab sering kali kita temukan warga negara tidak memahami arti bineka secara utuh dan mendalam. Hal ini mengakibatkan timbulnya makna “kami” dan “mereka”. Andy menegaskan, ketika kita tidak secara utuh memahami arti kebinekaan maka timbul perpecahan identitas antara yang satu dan lainnya. Andy juga menceritakan diskusinya dengan Sjamsiah Achmad mengenai perempuan dan kebangsaan. “Ibu Sjamsiah Achmad menyatakan kepada saya memaknai kebinekaan diawali dari keluarga, ketika dalam keluarga perempuan dan laki-laki setara maka keluarga tersebut tidak gagal, pun ketika kita keluar kita akan terus menganggap orang lain setara. Dengan begitu kebinekaan akan terus bertumbuh,” tutur Andy. Sementara Ruth Indiah Rahayu, peneliti Institut Kajian Kritis dan Studi Pembangunan Alternatif (Inkrispena) menyatakan bahwa sebelum Indonesia merdeka tepatnya tanggal 22 Desember 1928, Kongres Perempuan Indonesia sudah membicarakan tentang nasionalisme. Imaji kebangsaan mulai terbentuk sejak sebelum Indonesia merdeka. Ruth menjelaskan Siti Sundari tokoh yang membicarakan ide nasionalisme mengibaratkan kebangsaan sebagai taman bunga yang berisi banyak jenis bunga, namun tetap terlihat indah ketika bersama. Akan tetapi ide ini menjadi berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara, kebangsaan bukan lagi dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga. Sementara itu kita mengetahui bahwa ide keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang memiliki pemimpin. Setelah itu mulailah makna kebangsaan dan kebinekaan bergeser sedikit demi sedikit. Ruth menegaskan bahwa pembicaraan maupun pemikiran perempuan telah lama hadir dalam dunia politik, hanya saja perempuan tersubordinasi sejak dari dalam ide bernegara yang berubah dari taman bunga menjadi keluarga. Kamala Chandrakirana, Ketua Komnas Perempuan 2004-2007 yang hadir sebagai pembicara ikut serta menyuarakan tentang ide kebangsaan. Baginya kebangsaan adalah konstruksi sosial yang kemungkinan tidak membawa perempuan pada posisi sebagai warga negara yang memiliki hak. Kesadaran berbangsa setelah 20 tahun reformasi tidak kunjung membawa perempuan pada posisi yang mereka dambakan. Pada tahap ini sangatlah perlu bagi perempuan untuk membuat sejarahnya sendiri atau herstory. (Iqraa Runi) |
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
June 2024
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed