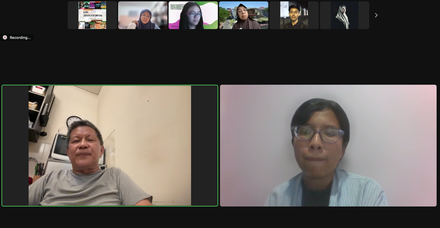 Menurut data dari World Bank (2019), negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di ruang politik formal. Ketika sudah berpartisipasi pun, perempuan yang terlibat dalam ruang publik tidak jarang mendapat pembatasan karena tekanan dan stigma yang diberikan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Yayasan Jurnal Perempuan membuka kelas Kajian Feminisme dan Filsafat (KAFFE) edisi November dengan tajuk “Peran Perempuan di dalam Ruang Publik” yang diadakan pada Jumat (10/11/2023), dengan diampu Rocky Gerung, selaku akademisi filsafat dan pengamat politik Indonesia. Rocky memulai diskusi dengan menjelaskan kerangka dasar pembahasan, berupa pengertian ruang politik, fungsi perempuan di ruang politik, serta implikasi dari eksistensi perempuan ketika perempuan bergerak dalam ruang politik di Indonesia. Menurut Rocky, ruang politik seharusnya adalah ruang distribusi kekuasaan. Namun, melihat kondisi saat ini, muncul pertanyaan, apakah ruang ini merupakan ruang yang dihasilkan dari produksi kekuasaan yang adil atau ruang yang hanya menjadikan perempuan sebagai pelengkap saja?
Pada dasarnya, jika menilik dari sejarah Yunani Kuno sebagai peradaban yang pertama kali menerapkan konsep demokrasi, maka bisa dilihat bahwa sudah ada distribusi ruang pada laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dicampur-adukkan. “Ada ruang yang disebut ruang laki-laki, yaitu ruang depan yang harus terbuka aksesnya ke jalan raya; dan ada ruang yang disebut sebagai ruang perempuan, yang sifatnya adalah menampung bahan makanan. Jadi, ruang politik perempuan dari awal adalah ruang untuk memelihara kesejahteraan rumah tangga,” jelas Rocky. Berdasarkan sejarah tersebut, bisa dikatakan bahwa perempuan diposisikan pada peran untuk mendistribusikan kemakmuran dan keadilan. Akan tetapi, distribusi ini berevolusi, sehingga apa yang disebut ruang politik pada hari ini adalah ruang yang dikendalikan sepenuhnya oleh kebijakan laki-laki. Menurut Rocky, pada awalnya manusia berada di rahim ibu (ruang perempuan–red) dengan kasih sayang dan relasi yang kuat dengan perempuan yang direpresentasikan oleh sosok ibu. Namun, setelah lahir, ia berpindah dari rahim perempuan menuju ruang laki-laki yang dianalogikan sebagai rahim laki-laki. "Setelah si bayi lahir, dia tumbuh sedemikian cepat, lalu dia pindah dari rahim perempuan ke rahim laki-laki, rahim laki-laki itu namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rahim laki-laki laki itu namanya kebijakan publik, rahim laki-laki itu namanya keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Nusantara (IKN), rahim laki-laki itu adalah keputusan untuk mempercepat proyek-proyek strategis yang di dalamnya tidak ada unsur keadilan karena diputuskan secara sepihak oleh kepentingan laki-laki," jelas Rocky. Menurutnya, keputusan politik selalu dibuat atas dasar urgensi kepentingan laki-laki. Hal itulah yang menjadi dasar dari adanya patriarki. Meskipun saat ini ada upaya untuk menciptakan kebijakan yang disebut sebagai gender mainstreaming, tetapi kebijakan tersebut biasanya hanya ada di level normatif dan tidak benar-benar diciptakan dengan mempertimbangkan kesejahteraan perempuan secara general. Artinya, kebijakan yang dinilai hadir untuk memberikan keadilan bagi perempuan, tetap tidak bekerja ketika perempuan tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Hal tersebut menciptakan kondisi di mana perempuan, pada akhirnya, ditindas oleh dua hal. Pertama, oleh dunia yang patriarki, "Karena dia perempuan, dia disingkirkan dari pembuatan kebijakan," jelas Rocky. Kedua, oleh kebijakan pemerintah itu sendiri yang kebanyakan dibuat untuk kepentingan laki-laki. Ketika perempuan sudah masuk dalam lembaga formal pembuatan kebijakan pun, Rocky melihat bahwa tetap ada upaya untuk menyingkirkan perempuan melalui pembuatan lembaga khusus perempuan. "Kekhususan itu justru menghalangi perempuan untuk masuk dalam pembuatan kebijakan di lembaga-lembaga pusat," ujar Rocky. Pada pembahasan selanjutnya, Rocky berusaha melihat mekanisme kontrol politik terhadap perempuan. Sejak awal, perempuan sudah dianggap sebagai the second sex (gender nomor dua), sebab tidak seperti laki-laki yang bisa masuk ke ruang publik, perempuan hanya bisa memasuki ruang domestik. Ketika berbicara tentang posisi perempuan dalam ruang politik pun, perempuan biasanya dianggap hanya sebagai pemanis partai untuk memenuhi kewajiban kuota 30% bagi perempuan. Bagi laki-laki, hal ini tidak adil sebab perempuan dianggap tidak perlu bersaing untuk menjadi partisipan formal dalam ruang politik. Namun, bagi Rocky, hal tersebut tidaklah tepat, sebab laki-laki justru telah berutang kepada perempuan. "Karena selama 25 abad ini, perempuan dianggap bukan player dalam politik," pungkas Rocky. Belum lagi ditambah dengan anggapan bahwa perempuan tidak bisa berpikir logis yang telah muncul sejak zaman Aristoteles, tentu hal ini memunculkan sinisme bagi setiap perempuan yang masuk dalam ruang politik. Ada juga semacam anggapan bahwa perempuan yang hendak menjadi pemimpin politik akan menjadi arogan, seperti kata Rocky, mereka dianggap "seperti lebah yang menghisap pekerja laki-laki untuk memuaskan seksualitasnya." Dengan kata lain, pemimpin perempuan dianggap akan memiliki queen bee syndrome, sebuah sindrom ketika pemimpin perempuan justru berlaku patriarkis. Rocky juga menilai bahwa ini didukung oleh fakta bahwa tidak ada partai oposisi dalam panggung politik Indonesia. Dengan kata lain, perempuan tidak bisa menunjukkan nilai mereka yang sebenarnya karena tidak ada partai-partai yang mau mencalonkan pemimpin perempuan. "Sebagai pembuka-pembuka atau pendahulu-pendahulu yang memberi kritik pada kebijakan pemerintah," tutup Rocky. (Dian Agustini) Comments are closed.
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
June 2024
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed