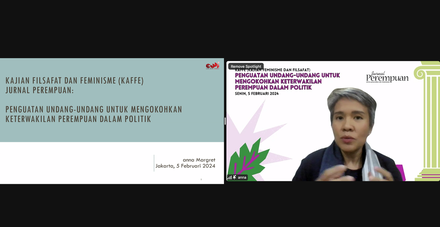 Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Pada Senin (5/2/2024) Jurnal Perempuan menggandeng Anna Margret Lumban Gaol, seorang dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) sekaligus Ketua Cakra Wikara Indonesia (CWI), sebagai pengajar kelas Kajian Feminisme dan Filsafat (KAFFE) Februari 2024. Kelas kali ini membahas tentang penguatan undang-undang untuk mengokohkan keterwakilan perempuan dalam politik. Bahasan ini menjadi sangat penting, terutama karena Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dalam kebijakan-kebijakan pemilu, Indonesia menggunakan sistem afirmasi untuk menjamin keterwakilan dan keikutsertaan perempuan. Aturan ini bersumber dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender. Diharapkan dengan kebijakan ini perempuan mendapat jalur yang lebih mudah dalam masuk ke lembaga legislatif, partai politik, maupun penyelenggara pemilu. Sebab, bukan rahasia lagi bahwa perempuan jauh lebih sulit masuk ke ruang-ruang tersebut dibanding laki-laki.
Anna Margret memulai paparannya dengan mendefinisikan kebijakan afirmasi. Salah satu definisinya adalah sebagai pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh—komitmen hukum—untuk mendukung perempuan. Pada sejarahnya, afirmasi menjadi bentuk rekognisi dari pemerintah atas ketertinggalan suatu kelompok. Di Indonesia sendiri, kebijakan afirmasi 30 persen dapat ditemui di beberapa lembaga: partai politik, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, dan lembaga legislatif. Namun untuk lembaga legislatif, kebijakan ini hanya menekankan pencalonan, bukan komposisi di dalam parlemen. Pada lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), komposisi 30 persen ini juga sukar terwujud. Data yang dibawa oleh Anna menunjukkan, dari 38 KPU provinsi, hanya 4 KPU provinsi yang diketuai perempuan. Sementara itu, dari 13 dari 38 Bawaslu provinsi tidak memiliki anggota perempuan sama sekali. Dalam partai politik pun praktik tokenisme representasi perempuan kerap terjadi. Kuota perempuan hanya dipertahankan hingga masa pendaftaran dan masa pemilu. Setelah selesai, kepengurusan partai kembali didominasi oleh laki-laki. Pun para calon legislatif (caleg) perempuan jarang mendapat nomor urut kecil di kertas suara. Akibatnya, masyakarat jarang yang melirik mereka. Adanya Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 yang mengatur pembulatan ke bawah untuk angka minimal representasi perempuan memperumit kondisi ini. “Ini menunjukkan bagaimana logika afirmasi dan filosofi afirmasi sudah ditinggalkan, dan justru dikhianati dengan menggunakan logika matematika,” ujar Anna. Penggunaan perhitungan matematika untuk membulatkan angka keterwakilan perempuan menjadi cacat logika. Anna juga mengemukakan pertanyaan bagi peserta kelas: apakah perempuan di parlemen benar-benar mewakili kepentingan perempuan? Pemikiran ini menjadi salah satu problematika dari politik afirmasi. Dosen Departemen Ilmu Politik itu kemudian menggunakan pemikiran Hanna Pitkin (1967) untuk mendekati masalah tersebut. Pitkin menjelaskan, politik afirmasi menghasilkan kontradiksi, sebab untuk memastikan representasi berjalan, perlu dipastikan mereka yang direpresentasikan harus betul-betul tidak hadir agar dapat direpresentasikan. Untuk mengatasinya, Pitkin menawarkan pendekatan baru untuk mengkaji politik afirmasi, yaitu dengan representasi substansi. Prinsip utamanya adalah stand for (menjadi bagian dari kelompok yang dibela) dan act for (bertindak mewakili kepentingan kelompok yang dibela). Representasi substantif harus didasarkan pada responsiveness atau tanggapan yang berupa keberpihakan. Dalam memilih wakil yang benar-benar merepresentasikan perempuan, pemilih perempuan harus mempertimbangkan identitas caleg dengan sungguh-sungguh. Sebab, identitas perempuan tidak pernah tunggal. Anna memberi contoh, banyak sekali caleg perempuan yang berasal dari politik dinasti—seperti istri atau anak dari pemimpin daerah. Namun, mereka justru lebih menyuarakan kepentingan perempuan dan kelompok minoritas dibanding caleg perempuan tanpa perspektif gender. Di sisi lain, latar belakang dinasti mereka membuat masyarakat sangsi untuk mendukung mereka. Sayangnya, kesangsian ini seringkali hanya terjadi pada caleg perempuan. Sehingga latar belakang dapat menjadi pertimbangan rumit sekaligus tantangan bagi masyakarat untuk mempercayakan suaranya pada caleg perempuan. Problem ketidakpercayaan rakyat juga ada pada partai politik. Padahal sejatinya kebijakan afirmasi di Indonesia diharapkan diselenggarakan dari skala partai politik. Di samping itu, partai politik pun masih belum dipercaya masyarakat, yang alih-alih lebih mempercayai kredibilitas tokoh politik. “Orang jauh lebih percaya pada figur dibanding identitas partai, tapi kebijakan afirmasi kita bertumpu pada partai sebagai agensi,” jelas Anna. Untuk mengupayakan afirmasi perempuan yang sehat dan tepat sasaran, masyarakat perlu mengenali isu-isu dan kepentingan yang dibawa oleh caleg perempuan. Dengan begitu, kita bisa menyeleksi caleg perempuan mana yang benar-benar pro pada perempuan dan kelompok minoritas. Bukan saja sebagai token politik. (Nada Salsabila) Comments are closed.
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
June 2024
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed