Diskusi ini menyinggung gerakan feminisme sebagai gerakan politis perempuan guna mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Abby menjelaskan bahwa feminisme adalah gerakan poltis perempuan yang berjuang untuk kesetaraan dan keadilan sosial. Basis dari feminisme adalah mendorong dan mewujudkan kesetaraan untuk semua gender. Selanjutnya, Abby menyebutkan bahwa di dalam pendekatan feminisme, konsep cinta (romantis) kerap dikritisi sebab berhubungan erat dengan patriarki dan heteroseksualitas penindasan perempuan. Cinta kerap dijadikan alasan terselubung dari penindasan, terutama penindasan dalam ranah domestik.
Berdasarkan Catahu Komnas Perempuan tahun 2021, kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan personal sangat besar, yaitu sebanyak 79 persen dari total kasus terlapor, atau sebanyak 6.480 kasus. Salah satu bentuk penindasan tersebut adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Data yang sama juga menunjukan bahwa kekerasan terbanyak dialami oleh istri, yaitu sebanyak 50 persen dari total kasus terlapor, atau sebanyak 3.221 kasus. Perempuan menjadi pihak yang paling rentan terhadap kekerasan domestik. Berdasarkan penuturan Abby, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari konstruksi masyarakat atas perempuan, dimana perempuan diidentikkan dengan sifat-sifat feminin. Dengan dilekatkannya konstruksi tersebut, masyarakat memiliki ekspektasi sosial terhadap perempuan; menuntut perempuan menjadi sosok yang lembut, memaafkan, mengalah dan menjadi pendukung di dalam suatu relasi. Cinta pada perempuan dikonstruksikan dengan kepatuhan dan kepasrahan pada sosok dominan—seringnya adalah ayah atau suami. Hal tersebut membangun ideologi mengenai relasi heteronormatif berdasarkan stereotipe gender—laki-laki memerintah, perempuan menurut, dan sebagainya. Perasaan cinta seperti itu melahirkan relasi yang timpang, dimana perempuan diletakkan pada posisi yang subordinat dan inferior--toxic relationship. Ideologi patriarki yang berselubung dalam konsep cinta kemudian menyebabkan hubungan menjadi tidak setara dan dibayang-bayangi oleh kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah manifestasi dari ketimpangan relasi gender dan konsep dominasi dalam keluarga atau dalam ranah personal. Berdasarkan pengalamannya menerima kasus laporan KDRT, dalam beberapa kasus, baik pelaku dan korban kekerasan sama-sama teredukasi dan memahami bahwa hubungan yang sarat kekerasan adalah hubungan yang berbahaya dan tidak sehat, tetapi dengan kesadaran demikianpun beberapa korban tidak dengan mudah untuk keluar atau memutus mata rantai kekerasan yang dialaminya. Beberapa pertimbangan yang membuat korban memutuskan untuk mempertahankan relasinya dengan pelaku antara lain adalah rasa malu. Malu karena akan mendapat stigma seperti pelabelan “janda” yang bernada negatif, kerap dituding sebagai pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dan dianggap memberikan aib bagi keluarga besar dan/atau kepada anak. Dalam budaya patriarki, pemaknaan perempuan kerap direduksi pada peran reproduktifnya—peran dalam rumah tangga sebagai istri dan sebagai ibu, implikasinya kesuksesan dan kegagalan perempuan sebagai manusia kerap kali ditakar melalui kehiupan rumah tangganya. Lebih lanjut Abby menyatakan bahwa keluar dari hubungan toxic itu cukup sulit dilakukan, terutama bila salah satu pihak bergantung secara sosial maupun ekonomis pada pasangannya. Memiliki pemahaman dan kesadaran mengenai nilai-nilai feminisme terkadang tidak serta-merta membuat seseorang dengan mudah keluar dari hubungan penuh kekerasan. “Kadang-kadang, untuk melangkah atau melakukan perubahan, untuk keluar dari hubungan yang toxic itu selain dengan pengetahuan, dibutuhkan juga keberanian, dibutuhkan juga support system yang kuat,” ujar Abby. Dalam diskusi tersebut, Abby juga menyoroti tentang salah satu bentuk KDRT yang sangat melanggar HAM perempuan tetapi kerap dianggap tidak ada yaitu marital rape. Sayangnya, meskipun data Komnas Perempuan menunjukkan adanya sejumlah kasus-kasus marital rape di Indonesia, beberapa kelompok dengan justivikasi nilai moral dan agama menyatakan bahwa kasus demikian tidaklah ada. Asumsinya adalah kewajiban istri untuk melayani kebutuhan seksual dari suaminya. Sehingga kesejahteraan fisik dan mental dari perempuan tidak diperhitungkan—begitu juga persetujuannya. Untuk menghentikan berbagai praktik kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk juga marital rape, Abby menyatakan bahwa dibutuhkan pendekatan yang komprehensif mencakup perubahan terhadap pola pikir dan perilaku individu, kelompok dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi formal dan informal, media sosial dapat mengambil peran dengan mempromosikan mengenai pemahaman akan relasi yang setara dalam perkawinan, relasi pacaran dan lain sebagainya. Selain itu, dari sisi negara, komitmen penghapusan kekerasan seksual perlu ditunjukkan dengan dihadirkannya produk hukum yang secara khusus merespons pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual termasuk didalamnya terkait marital rape. “Mesti komprehensif, baik dari masyarakat, media, lewat tataran pendidikan, dan dari negara yang menyediakan alatnya (RUU Pencegahan Kekerasan Seksual—red) juga,” jelas Abby. (Nada Salsabila) Comments are closed.
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
June 2024
Categories |
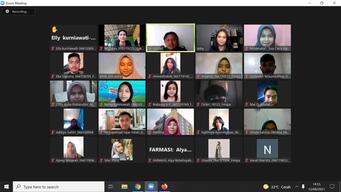

 RSS Feed
RSS Feed