 Dok. Pribadi Dok. Pribadi Masih segar dalam ingatan kita, dalam beberapa tahun terakhir ini marak sekali kekerasan seksual terhadap anak dan terhadap perempuan. Kedua hal ini terpisah, antara kekerasan yang terjadi terhadap anak dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Sebenarnya kasus demi kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, sama sekali bukan hal kontemporer. Kejahatan seksual sudah lama terjadi terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hanya saja sering terlupakan, timbul tenggelam dalam pemberitaan media massa. Dalam kata lain kekerasan seksual hanya booming ketika terdapat korban, setelah itu selesai, tanpa adanya upaya perbaikan-perbaikan manusianya (masyarakat). Tentu kita menyaksikan dalam pemberitaan media, bahwasannya baru-baru ini presiden Republik Indonesia menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini atas dasar menyikapi kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Namun darurat kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada anak-anak, tetapi juga terhadap perempuan. Perppu No. 1 Tahun 2016 merupakan perlindungan anak terhadap kejahatan seksual, lalu Perppu apa untuk perlindungan perempuan terhadap kejahatan seksual? Disisi lain dengan adanya ancaman hukuman kebiri kimiawi di dalam Perppu tersebut, menurut penulis bukan langkah semestinya dalam menyikapi kasus kekerasan seksual. Kemudian keberadaan Perppu ini hanya akan berlaku jika kekerasan seksual terjadi kepada anak-anak. Lalu bagaimana dengan kekerasan seksual terhadap perempuan (orang) dewasa dan bahkan laki-laki dewasa? Bukankah mereka juga butuh perlindungan hukum? Dalam menyikapi kekerasan seksual terhadap anak, UU Perlindungan Anak sudah cukup jelas untuk kita pahami bersama. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur secara lebih baik dalam arti memberi jaminan terhadap anak-anak untuk tidak mengalami kekerasan seksual, ancaman pidana terhadap pelakunya lebih tinggi, dan terdapat ancaman minimal, bila dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP[1]. Berarti bahwa sudah terdapat jaminan hukum bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual. Pertanyaannya apakah dengan demikian kejahatan seksual akan berkurang? UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014, tidak juga memberikan perubahan signifikan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2016. Materi hukumnya sudah sangat luar biasa baik, terdapat pula tambahan hukuman berupa pemasangan alat deteksi dan hukum kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Perlu menjadi catatan bahwasannya menyikapi perilaku kekerasan dan kejahatan seksual ini bukan semata pada materi penghukuman. Melainkan lebih dari itu, pendidikan moral dalam keluarga, lembaga pendidikan, dan kemasyarakatan juga perlu menjadi perhatian. Misalkan, seseorang yang berasal dari keluarga miskin, tidak bersekolah, keluarganya berantakan, pendidikan moral kurang, tidak memiliki pekerjaan, hal ini juga dapat menjadi pemicu seseorang menjadi pelaku kejahatan (termasuk kekerasan seksual). Jadi menurut hemat penulis, kekerasan dan kejahatan seksual itu merupakan ciptaan dari lingkungan sosial pelaku, bukan persoalan libido yang tidak terkendalikan. Sigmund Freud mengatakan bahwa dorongan libido pada diri manusia selalu menggedor-gedor dan meronta-ronta ingin dilampiaskan[2]. Pada kutipan ini, kata “manusia” perlu digarisbawahi. Manusia berarti semua orang tanpa pengecualian, termasuk saya dan anda adalah manusia. Apakah saya dan anda adalah pelaku kekerasan seksual? Karena alasan itu, kita (manusia) harus dikebiri kimiawi untuk menidurkan libido yang meronta-ronta itu. Pada kenyataannya, tidak semua manusia menjadi pelaku kejahatan seksual. Konteks manusia dalam teori Libido Sigmund Freud adalah general, tidak spesifik. Pada bagian lain tulisannya Freud mengatakan libido dalam diri manusia dapat dilampiaskan dengan berbagai cara, seperti membaca, memasak, bekerja, dan aktivitas lain. Menurut penulis landasan ini tidak dapat menjadi acuan untuk pemberlakuan kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual. Karena pelampiasan libido manusia bukan semata-mata pada aktivitas seksual. Pada sisi lain di dalam Perppu No. 1 Tahun 2016, menurut penulis peraturan ini hanya berorientasi kepada penghukuman pelaku. Sedangkan korban kekerasan seksual terabaikan. Tidak tercantum bagaimana si korban memperoleh keadilan hukum yang seadil-adilnya, tidak tercantum bagaimana langkah pemulihan psikologis dan sosial korban, dan tidak tercantum bagaimana keluarga korban mendapatkan perlindungan (serangan media massa dan lain sebagainya). Dalam UU No. 23 Tahun 2002 ayat (2): “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.[3] Namun disisi lain, media massa memiliki otoritas dan wewenang untuk publish identitas siapa anak yang menjadi korban dan pelaku. Justru kerapkali korban dan pelaku dikriminalisasi oleh media massa dan media sosial. Tidak lupa dalam ingatan kita kasus perkosaan sadis yang menggunakan gagang cangkul, korban kemudian menjadi meme tren di media sosial. Demikian juga pelaku yang masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) menerima hujatan di media sosial. Patut dipertanyakan perasaan empati masyarakat kita yang terepresentasi oleh media sosial. Like dan share yang dengan gampang dilakukan, merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat kita belum teredukasi dalam menggunakan media sosial. Bagaimana perasaan keluarga korban, atau bahkan keluarga pelaku? Dalam hal ini penulis melihat bahwa penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab juga menimbulkan pelaku-pelaku baru atas kasus kekerasan seksual yang terjadi. Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Apakah dengan hukuman kebiri kimiawi, kemudian kejahatan seksual akan selesai, atau setidaknya menurun? Berdalih kebiri kimiawi ini merupakan suatu tindakan terapi, itu sangat tidak benar. Memasukkan cairan kimia ke dalam tubuh orang yang tidak sakit, menurut hemat penulis adalah bentuk penyiksaan, terlebih terdapat unsur pemaksaan. Dalam penjelasan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap manusia memiliki non-derogable rights, satu diantaranya adalah hak untuk bebas dari penyiksaan[4]. Manusia tidak terlahir sebagai penjahat. Tetapi setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi penjahat. Pemberlakuan hukuman kebiri kimiawi ini adalah bentuk kriminalisasi balik kepada pelaku. Sehingga yang tadinya orang itu sebagai pelaku, menjadi sebagai korban karena pemberlakuan hukuman kebiri ini. Sedangkan pembenahan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga yang merupakan tempat bernaung anak-anak seakan diabaikan. Perlindungan anak-anak hanya berfokus kepada tindak penghukuman terhadap pelaku saja, sedangkan antisipasi agar tidak terdapat korban masih belum terealisasi. Menyikapi kekerasan seksual (baik yang terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa) merupakan upaya kita bersama agar tidak terdapat korban yang berjatuhan. Revitalisasi masyarakat kita yang cenderung individualis menjadi catatan penting dalam memerangi kejahatan seksual. Dengan kepedulian terhadap sesama, saling melindungi, konsep mengasihi satu sama lain akan menjadi pemicu perdamaian, sehingga kekerasan dan kejahatan seksual akan terperangi. Catatan Akhir: [1] Irianto, Sulistyowati, "Hukum yang Tak Peduli Korban". Jurnal Perempuan. Edisi November 2011. Hal. 41-52. [2] Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [4] Dewi, Kurniasari Novita, 2015, HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar oleh Ani W. Soetjipto (ed). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Akhiriyati Sundari (Mahasiswa Islam dan Kajian Gender UIN Sunan Kalijaga) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Pendahuluan Tubuh perempuan selalu memasuki hiruk-pikuk pembahasan di segala ranah. Karenanya tidak ada diskursus lain yang memiliki daya tanding lebih yang mampu menyamai atau menyaingi diskursus ramai atasnya kecuali perbincangan tentang tubuh perempuan. Tubuh perempuan dari masa ke masa selalu mengalami kontestasi untuk diperebutkan oleh pihak-pihak yang berasal dari luar dirinya. Konstruksi sosial yang ditopang oleh ragam struktur sosial, berkembang setingkat dinamika yang mengiringi laju jaman. Ada titik yang dibidik sekaligus disasar dari perebutan wacana dan tubuh perempuan, yakni ketundukan dan kepasrahan. Dalam hal ini pihak laki-laki adalah tertuduh utama dengan bias sekaligus eros patriarkalnya, yang selalu merasa memiliki ‘hak istimewa’ untuk membuat berbagai penilaian atas tubuh perempuan. Laki-laki merasa seakan memiliki privilese untuk mengintervensi dengan meletakkan standar nilai tertentu kepada tubuh perempuan. Semuanya bekerja dalam bingkai patriarki yang mendudukkan posisi perempuan dan tubuhnya dalam posisi subordinat. Dimensi kekuasaan digunakan sebagai mesin kerja untuk mencapai tujuan. Foucault dalam masterpiece-nya tentang seksualitas mengatakan bahwa gagasan seksualitas dan kekuasaan sangat membantu analisis sosial dalam mengurai berbagai ketimpangan akibat relasi kekuasaan yang tidak seimbang terutama dalam kehidupan modern. Dalam perspektif ini, kekuasaan sebagai rezim wacana dianggap mampu menggapai, menembus, dan mengontrol individu sampai kepada kenikmatan-kenikmatan yang paling intim. Kekuasaan sebagai rezim wacana ini dianggap sebagai praksis yang mampu mengubah konstelasi sosial. Darinya lalu muncul pengetahuan sebagai daya topang kekuasaan. Hubungan kekuasaan dan pengetahuan ini menurut Foucault adalah ketika wacana yang ada menahbiskan dirinya sebagai yang memiliki otoritas, otonomi atas klaim kebenaran dan kontekstual, seperti yang ada pada psikiatri, kedokteran, pendidikan, dan agama. Di dalam Islam, tubuh perempuan diidentifikasi sebagai yang memiliki rahim. Konteks mikronya bahwa hal ini mengindikasikan perempuan sebagai jenis kelamin yang ‘membawa kehidupan’, lengkap dengan sifat rahim [baca: kasih sayang] yang meng-endors pada wujud rahim di dalam tubuhnya. Sedang konteks makronya adalah perempuan memiliki keistimewaan yang khas dan tak bisa dipertukarkan. Karenanya Islam sangat menghormati perempuan sebagai manusia utuh yang sama dengan laki-laki. Titik tekan Islam paling utama dalam membingkai perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah pada tingkatan amal saleh. Yakni sejauh mana kedua jenis kelamin berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dan bermanfaat bagi orang lain. Suara Islam yang genius ini kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat dimana konstruksi sosial patriarkalnya amat parah. Budaya yang lestari pada akhirnya menjadi tungkai bajak dan mengeliminir semangat universal Islam yang terkandung dalam kitab suci. Membincang Seksualitas dalam Wacana Islam: Pernikahan Wacana Islam dimaksud di sini adalah segala hal yang terbingkai dalam segala dialektika dan perdebatan tentang Islam. Bangunan terpenting yang menjadi acuan wacana ini adalah bersumber dari kitab suci [Syafiq Hasyim, 2002]. Bagaimana Al-Qu’ran sebagai kitab suci berbicara tentang seksualitas? Tentu saja hal ini terkait dengan pola relasi laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Ranahnya adalah seputar perkawinan, perceraian, relasi pergaulan suami-istri di dalam rumah tangga, masa tunggu sesudah bercerai [iddah], hingga persoalan yang menyangkut homoseksualitas. Kitab suci membingkai urusan seksualitas di dalam Islam hanya boleh dilakukan melalui lembaga perkawinan. Hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan dianggap ilegal disebut sebagai zina. “Dan janganlah kamu mendekati zina karena itu sekeji-kejinya perbuatan” [QS Al-Isra (17): 32], ayat yang keras melarang perbuatan zina dengan penekanan ‘mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan’ ini sesungguhnya hendak merespon masa lalu, dimana jaman pra-Islam, kegiatan seksual dapat dilakukan dengan bebas tanpa ikatan pernikahan sekalipun. Terpapar di dalam kitab suci pula bentuk respon terhadap masa lalu adalah dengan membatasi kepemilikian istri menjadi maksimal empat. Struktur sosial bangsa Arab pada masa pra-Islam yang disebut sebagai jahiliyah telah menempatkan perempuan sebagai istri yang bermakna ‘properti’. Hanya barang yang diambil kegunaannya semata sehingga dalam satu keluarga sebagai struktur sosial terkecil, adalah lumrah terdapat sembilan bahkan ratusan istri [poligami, pada kepala-kepala suku bangsa pagan kala itu]. Lantaran barang yang hanya diambil kegunaannya maka si pemilik properti [suami] bebas untuk berbuat sesuka hatinya, misal dengan mencampakkan begitu saja ketika merasa si istri sudah tidak berguna. Dari sini tampak secara jelas bahwa poligami bukanlah ajaran Islam, melainkan telah ada sebagai produk sosial umat terdahulu. Semangat yang disuntikkan Islam adalah memartabatkan manusia dalam resapan-resapan cinta melalui hubungan perkawinan sebagai hal alami yang naluriah. Lebih lanjut Al-Qur’an kemudian memberikan topangan spiritual bagaimana laki-laki dan perempuan yang terikat di dalam lembaga perkawinan itu seharusnya bergaul. Ada relasi yang setara dan seimbang, sebagai prasyarat mutlak yang harus diketahui untuk mencapai tujuan harmoni, bermartabat, dan bermoral. Metafora indah “mereka [para istri itu] adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka” [QS Al-Baqarah [1]: 187], menunjukkan bahwa masing-masing relasi adalah resiprokal seimbang. Pakaian bersifat menutupi, memperindah, dan melindungi. Seyogyanya demikian pula dalam relasi suami-istri. Kasih sayang dan cinta kasih adalah perlambang adibusana, karenanya suami-istri secara moral dilarang saling menyakiti, secara moral harus menghargai dan menghormati satu sama lain dengan menghindari hegemoni-dominasi, termasuk dalam urusan seksual. Fatima Mernissi menyebut bahwa Al-Qur’an sesungguhnya tidak pernah menjustifikasi poligami. Justru Al-Ghazali lah yang melakukannya, karenanya Mernissi menganggap bahwa bahwa ada kekeliruan dari para pemikir Islam, yang tidak melihat poligami sesungguhnya sangat merugikan perempuan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan perempuan yang harus dipertimbangkan dalam praktik pergaulan yang ma’ruf tersebut, terutama pada kebutuhan seksual istri. Poligami dipandang sebagai lebih jauh dari sekadar memberikan hak seksual laki-laki, yakni menyediakan ruang bagi laki-laki untuk memperturutkan hawa nafsu seksualnya tanpa kenal batas. Padahal dalam adagium populer telah gamblang dikatakan bahwa ‘nafsu [seksual] itu seperti anak kecil [bayi] yang menyusu, ia akan terus meminta’. Selain sumber kitab suci, dalam wacana Islam terkait seksualitas, sunnah Nabi Muhammad SAW adalah rujukan penting kedua. Sunnah Nabi mencakup ucapan, tindakan/perilaku dan hal-hal atau peristiwa apa saja yang dilangsungi selama hidupnya. Nabi Muhammad sebagai orang suci dan dipilih oleh Tuhan dengan status ma’shum, bebas dari salah—lantaran seluruh makrokosmos dan mikrokosmos hidupnya adalah wahyu Tuhan, menjadi duplikasi yang tampak mata sebagai ejawantah ajaran kitab suci. Sejarah hidup Nabi mengisahkan perkawinannya dengan Siti Khadijah didahului oleh lamaran yang dilakukan Khadijah. Bukan oleh Nabi sendiri, melainkan Khadijah yang meminta. Perkawinannya dilandasi cinta dan saling penghormatan. Garis bawah dari sejarah telah mencatat bahwa Khadijahlah yang aktif dan Nabi pasif, menerima. Terlepas dari status kelas yang melekat pada diri Khadijah sehingga yang bersangkutan dimungkinkan memiliki ‘daya aktif’ melamar, di situ sekali lagi memperlihatkan ada keterlibatan perempuan dalam tindakan ‘memulai lebih dulu’ terhadap pasangannya. Tidak ada penolakan sama sekali dari Nabi, artinya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Landasan ini pulalah yang dapat dipakai sebagai teropong bahwa dalam kehidupan seksual suami-istri, kedua belah pihak setara, tidak selalu suami yang aktif, tetapi istri pun. Tidak ada ordinat dan subordinat dalam relasi perkawinan Nabi dan Khadijah. Bahkan tidak mempermasalahkan status diri Khadijah sebelum menikah dengan Nabi. Kekuasaan Pengetahuan: Memasung Seksualitas Perempuan Perebutan wacana di dalam fungsi otorisasi akan klaim kebenaran terhadap tubuh perempuan sesungguhnya telah berlangsung sekian lama di dalam Islam. Idealisasi yang termaktub dalam kitab suci berikut sejarah Islam awal yang dibangun oleh Nabi Muhammad direduksi secara kasar sejak Nabi wafat. Dimulai dari jaman kekhalifahan empat hingga mengecambah ke dinasti-dinasti politik sesudahnya, posisi perempuan ‘dikembalikan’ ke dalam rumah. Ke ranah domestik. Ketika jaman Nabi perempuan turut pula terlibat aktif di ranah publik tak terkecuali dalam urusan ibadah ritual di masjid, maka sesudah Nabi wafat perempuan bahkan tidak boleh pergi ke masjid. Maka dimulailah aneka ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan itu termasuk di ranah seksual. Perempuan mengalami berbagai tindakan tidak adil juga kekerasan terkait seksual. Mengutip Abdul Munir Mulkhan [2002], sedikitnya ada tiga persoalan menyangkut ketidakadilan seksual pada perempuan; pertama, tradisi Islam dalam fikih [formula aturan hukum yang berkembang pasca Nabi] yang menempatkan perempuan sebagai ‘pelayan kebutuhan seksual laki-laki’ dan ‘pembangkit birahi seksual’. Kedua, kecenderungan konsumerisme tubuh perempuan dalam peradaban industri modern. Ketiga, tradisi lokal [khususnya Jawa] yang masih melekatkan stereotype kepada perempuan sebagai ‘penumpang’ kemuliaan [kelas sosial] laki-laki. Ketiga, persoalan itu berkelindan dan melahirkan gagasan subordinasi pada perempuan. Gagasan yang menumbuh pada relasi kuasa yang timpang ini tak ayal menumbuhkan bibit-bibit kekerasan seksual terhadap perempuan. Perempuan hanya dilihat sebagai seonggok daging bernama tubuh seksual. Subjek yang melihat adalah laki-laki. Melihat di sini dimaknai sebagai penguasa tatapan. Foucault menganasir hal ini sebagai tindakan kekuasaan-pengetahuan yang menerapkan strategi kekuasaannya untuk mengatur [seksualitas] perempuan. Ada histerisasi tubuh perempuan yang menunjukkan bahwa tubuh [perempuan] dikaitkan dengan tubuh sosial untuk menjamin kesuburan dan semua bentuk kewajiban yang datang dari keluarga termasuk kehidupan anak. Jadi tubuh perempuan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab biologi dan moral. Khasanah fikih klasik hingga hari ini masih memberikan kacamata patriarki yang sarat bias gender dalam mengatur seksualitas perempuan. Khitan perempuan, sebagai contoh, dikatakan bahwa ia adalah perintah agama. Padahal sesungguhnya sunat perempuan adalah tradisi yang berasal dari 4000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Ada pada masa Fir’aun, karenanya dulu dikenal dengan istilah pharaonic circumcisium [Jurnalis Uddin, 2013]. Hingga kini hanya di Yaman, Irak, Iran, Pakistan, India, Malaysia, dan Indonesia. Alasan dibalik pelaksanaan khitan perempuan ini adalah untuk mengerem nafsu seksual perempuan, yang dianggap lebih besar kadarnya daripada laki-laki sehingga membahayakan. Anggapan ini semata adalah mitos. Produk sosial dari jaman Fir’aun. Akan tetapi, institusi agama melestarikannya sebagai bagian dari ajaran agama. MUI tahun 2008 melakukan penolakan terhadap edaran Kementerian Kesehatan tahun 2007 yang melarang pelaksanaan khitan perempuan dari sudut pandang medis [Jurnal Perempuan 77]. Ketegangan pihak pemegang otoritas agama terhadap entitas di luarnya, adalah bentuk dari perebutan wacana tubuh perempuan. Sebagai medan politik, tubuh perempuan ditundukkan. Tubuh perempuan dipindai dengan tatapan laki-laki dus patriarki dalam sederet stigma negatif. Ada yang buruk dalam tubuh perempuan sekaligus ada yang menguntungkan dari tubuh perempuan. Tatapan patriarki ini lalu dilanggengkan dalam struktur sosial, mengokohkan diri sebagai pemegang kekuasaan. Strategi kedua menurut Foucault dari permainan kekuasaan-pengetahuan adalah pedagogisasi seks anak dengan tujuan anak jangan sampai jatuh dalam aktivitas seksual, karena mengandung bahaya fisik dan moral serta dampak kolektif maupun individual. Pedagogisasi ini juga untuk melawan onanisme [Haryatmoko, 2013]. Dalam setiap generasi sejak kecil, diajarkan tentang bahaya seksualitas yang dilakukan tidak di dalam pernikahan. Institusi agama membingkainya dalam fikih yang masih normatif, yang mengajarkan hanya ketakutan tanpa didukung oleh pengetahuan positif yang memadai. Anak tidak diberikan pendidikan seksualitas sejak dini lantaran anggapan tabu. Sehingga anak telah sejak dini pula dijauhkan dari pengetahuan yang memadai tentang tubuhnya. Otoritas agama hanya berkutat di seputar fikih yang lebih banyak mengatur soal thoharoh [tata aturan kebersihan] dalam kaitannya dengan sembahyang wajib [termasuk di dalamnya batasan tentang menutup aurat di dalam sholat]. Disusupkan pendidikan moral di dalamnya semata bahwa lagi-lagi tubuh perempuan adalah ‘sumber dosa’, karena itu jangan dekat-dekat. Walhasil, tidak mengherankan ketika pedagogisasi ini di lain pihak justru mengungkung hak anak untuk mengetahui kesehatan reproduksi secara benar. Saat marak kasus pernikahan dini, pernikahan anak-anak usia remaja ke bawah, persoalan-persoalan terkait kesehatan reproduksi dan seksual ini menjadi kian rumit dan blunder. Tidak ada kesiapan mental dan fisik. Anak-anak didorong begitu saja masuk ke kegelapan dunia seksualitas sehingga rentan dengan bahaya yang sulit dihindari seperti AKI, anemia, pendarahan, ekslampsia, juga tidak menutup kemungkinan penyakit menular seksual. Kasus pernikahan anak ini juga tidak bisa begitu saja dilepaskan dari konstruksi masyarakat yang digarisbawahi oleh tafsir-tafsir agama. Kerapkali misalnya, menganggap bahwa pernikahan anak akan menyelamatkan si anak dari pergaulan buruk yang menggiring pada hubungan seksual diluar pernikahan sebagaimana dilarang oleh agama, apalagi anak perempuan korban perkosaan [kekerasan seksual]. Ada pula yang menyandarkan diri pada sejarah Nabi bahwa pernikahannya dengan Siti Aisyah adalah termasuk pernikahan dini, karenanya dipandang sebagai sebuah syariat yang harus dipatuhi. Belum ditambah lagi argumen yang dipaksakan dan direkayasa secara panjang oleh konstruksi sosial stigmatis di masyarakat, bahwa pernikahan anak lebih baik daripada perempuan yang sudah ‘cukup umur’ namun belum menikah. Status single perempuan distigmatisasi oleh patriarki sebagai ‘kerawanan sosial’. Pernikahan anak juga tidak jarang bermotifkan ekonomi yang lagi-lagi ditopang oleh agama bahwa menghindari kemiskinan itu wajib agar tak terjerembab ke kekufuran. Tidak bisa tidak menurut tafsir ini, solusinya adalah menikahkan anak. Instrumen ini secara terus-menerus melanggengkan relasi kuasa yang timpang dalam mengatur seksualitas perempuan. Selanjutnya menurut Foucault, adanya sosialisasi perilaku prokreatif dimaksudkan untuk kesuburan pasangan; sosialisasi politik dilaksanakan melalui tanggung jawab pasangan terhadap tubuh sosial; dan sosialisasi medik termasuk praktik kontrol kelahiran atau KB. Pada masa Orde Baru, tangan otoritas keagamaan bergandeng tangan dengan kekuasaan untuk melakukan pengontrolan tubuh perempuan melalui program KB. Nilai keagamaan berlabuh dalam program yang sarat kepentingan politik negara dalam biopolitik modern. Tubuh perempuan menjadi sasaran utama ragam alat kontrasepsi tanpa mempertimbangkan kebutuhan kesehatan tubuh perempuan itu sendiri. Perempuan ditekan untuk tidak memiliki kedaulatan atas tubuhnya sendiri. Strategi kuasa pengetahuan sebagaimana diungkap Foucault di atas sejatinya dijadikan instrumen oleh agama melalui pengendalian atas tubuh perempuan. Subjek yang saling mengait ini memiliki tujuan yang satu yakni kepatuhan dan ketundukan. Darinya maka sebuah rezim akan langgeng dalam status quo. Seluruh peristiwa ini dibingkai dari frame patriarki yang mengusung rezim seksualitas dalam agama. Kuasa pengetahuan selanjutnya hadir dalam problem modernitas yang melahirkan anak kandung bernama kapitalisme. Di wilayah ini, tubuh perempuan diperebutkan kembali untuk dijadikan objek konsumerisme. Tidak terkecuali tubuh perempuan yang ditarik melalui wilayah keagamaan yang dipromosikan melalui media. Terdapat rezim kapitalisme di sini yang berhasrat hanya untuk penumpukan kapital. Standar tubuh perempuan dilabeli oleh patriarki melalui narasi-narasi perempuan ideal, cantik, langsing, berkulit putih, lembut, berambut panjang, bisa melahirkan anak, dan sederet panjang ukuran-ukuran subjektif lainnya, kemudian direproduksi oleh media secara massif dan vandalistik. Tidak terbatas pada media-media yang hanya dipajang dan dilihat secara dekat melalui media elektronik dan media cetak, persepsi patriarki atas tubuh perempuan dinarasikan pula secara jauh melalui ‘sampah visual’ yang bertebaran di ruang-ruang publik dengan tak terkendali. Baliho-baliho, spanduk, dan billboard berkibar gemebyar, menyesaki ruang-ruang publik di jalanan, berjajar-jajar tak karu-karuan dengan tiang-tiang serta kabel-kabel listrik yang bergelantungan sebagai penanda buruknya sistem tata kota di negara yang gamang dengan modernitas ini. Idealitas dalam wilayah tafsir agama yang membungkus perempuan dengan penertiban moral, turut pula diblow-up media dengan narasi-narasi ‘iklan syariah’. Iklan perempuan berjilbab sebagai contoh, tak ketinggalan memasuki arena publik dalam promo massal produk-produk tertentu berlabel agama [contoh jilbab zoya bersertifikat halal]. Tubuh perempuan lagi-lagi direbut otonominya di sini sebagai pendulang pundi-pundi dalam bingkai kapitalisme. Bahwa perempuan muslim yang kaffah selain membungkus tubuhnya dengan hijab agar tak mengundang birahi laki-laki, juga harus memastikan bahwa produk yang dipakainya adalah halal [berlisensi islami]. Begitu ribetnya tubuh perempuan harus didorong melesak ke dalam kapitalisme berjubah agama. Rezim seksualitas dihasilkan dari koalisi halus antara kapitalisme dan agama. Penutup Tubuh perempuan disorot dan diregulasikan dalam kancah paling esensial dari laku hidup manusia [agama], melalui penertiban perilaku, pakaian, dan segmen-segmen hidup yang lain. Tafsir-tafsir agama diwacanakan secara massif tanpa celah kritis sedikit pun, untuk memberikan satu narasi tunggal tentang stereotype perempuan melalui presentasi sebagai konstruksi cultural, yakni media. Bahwa media adalah struktur yang paling berperan dalam mereproduksi cara masyarakat mendudukkan dan memandang perempuan. Cara pandang ini diadopsi untuk memperlihatkan kekuatan media dan otoritas mainstream keagamaan dalam membentuk opini yang mendukung pandangan dominan tentang perempuan. Tubuh perempuan dikontrol agar menjalani ketundukan dan kepatuhan dengan frame patriarki, ditopang secara kokoh oleh sebuah rezim seksualitas. Pada akhirnya, dalam gerusan modernitas yang terus-menerus dipiyuh oleh kapitalisme ini, tubuh perempuan mulai kehilangan otonomi. Pada setiap laju sejarah, hal ini akan terus dimainkan sebagai ajang politik, padahal sejatinya justu menunjukkan sebuah tontonan lemah dari patriarki yang tidak pernah bisa menundukkan ego pallus-nya. Daftar Pustaka: Jeremy R. Carette (ed.), Agama, Seksualitas, Kebudayaan; Esai, Kuliah, dan Wawancara Terpilih Michel Foucault, Yogyakarta: Jalasutra. 2011. Mochamad Sodik (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. 2004. Christina Siwi Handayani, Gadis Arivia, dkk, Subyek yang Dikekang; Pengantar ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone de Beauvoir Michel Foucault, Jacques Lacan, Jakarta: Komunitas Salihara. 2013. Michel Foucault, Kuasa/Pengetahuan, Yudi Santosa (penerj.), Yogyakarta: Bentang Budaya. 2002. Irwan Abdullah, Nasaruddin Umar, dkk, Islam dan Konstruksi Seksualitas, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. 2001. Abdul Moqsit Ghozali, Badriyah Fayumi, dkk, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Cirebon: Rahima. 2002. Jurnal Perempuan edisi 15, “Wacana Tubuh Perempuan”. 2001. Jurnal Perempuan edisi 71, “Perkosaan dan Kekuasaan”. 2011. Jurnal Perempuan edisi 77, “Agama dan Seksualitas”. 2013. remotivi.com, “Perempuan tanpa Otonomi; Wajah Ideologi Dominan dalam Sinetron Ramadhan”. 2014.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita menyaksikan pembunuhan masal? Tidak beradab dan aksi terorisme. Inilah yang terjadi di sebuah klub malam di Orlando, Florida, US beberapa hari lalu. Portal berita luar negeri, NBC News menyebutkan terdapat 50 orang meninggal dan 53 orang terluka dalam tragedi itu, dan disebutkan “deadliest mass shooting in U.S. history”. Ini berarti aksi terorisme pertama kalinya yang menelan korban paling banyak di US. Hal ini merupakan sebuah tragedi kemanusiaan, terlepas dari siapa yang menjadi korban. Namun tak sedikit diantara kita (orang Indonesia) yang mengamini tragedi ini, merespons karena LGBT selayaknya, sepantasnya, sepatutnya layak diperlakukan seperti itu. Saya menilai bahwa respons seperti ini merupakan suatu ancaman bagi kelompok LGBT di Indonesia. Bolehkah sejenak kita merespons sebuah kejadian tanpa melihat identitas? Mereka merupakan manusia, yang seharusnya hidup aman dan damai, terlepas dari orientasi seksualnya. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang Indonesia membenarkan tragedi ini, bahwasanya terdapat kelompok-kelompok yang mengutuk kejahatan kemanusiaan itu. Termasuk saya pribadi, sangat mengutuk tragedi ini. Tragedi ini merupakan sebuah aksi terorisme, dimana terdapat korban berjatuhan. Teroris sendiri menggunakan kekerasan untuk menarik perhatian akan maksud atau alasan dibalik tindakan mereka. Ibarat bom waktu, aksi teroris dapat terjadi kapan pun dan di mana pun, tanpa dapat kita prediksi. Aksi ini merupakan ancaman serius bagi keamanan internasional dan nasional. Terorisme memang bukan satu-satunya ancaman terhadap keamanan global dalam konteks human security, tetapi aksi terorisme juga patut diperhitungkan dalam mengancam keamanan hidup kelompok tertentu (human security dalam konteks lokal dan nasional). Terdapat tipologi terorisme menurut Gregory D. Miller yaitu terorisme separatis-nasional, terorisme revolusioner, terorisme reaksioner, dan terorisme religius (Winarno, 2014). Pendapat saya, aksi terorisme di Orlando termasuk di dalam tipologi terorisme reaksionisme. Kelompok teroris ini memang berjumlah kecil dan sulit untuk di lacak keberadaannya. Mereka ini reaktif terhadap isu-isu yang mengemuka, dan ini merupakan reaksi atas keberadaan kelompok LGBT di Orlando, bisa saja dari kelompok anti-LGBT. Miller (dalam Winarno, 2014) menegaskan bahwa kelompok teroris ini melakukan aksi teror dengan cara membunuh orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan pikiran mereka. Benar adanya, aktor teroris ini membunuh dengan brutal orang-orang tanpa alasan. Kelompok “anti” ini memang tidak terorganisir, tetapi mereka akan meniru aksi yang sama untuk mencapai tujuan mereka—yang notabenenya adalah sama pula. Hal ini menunjukkan bahwa tragedi Orlando ini dapat menjadi pintu bagi aksi terorisme lainnya di berbagai belahan dunia, terlebih di Indonesia, dimana terdapat sejumlah besar kelompok anti LGBT (homophobia). Berarti bahwa terdapat ancaman serius bagi kelompok LGBT di Indonesia, karena aksi teror serupa bisa saja terjadi oleh kalangan “anti” ini. Meskipun pelaku teroris di Orlando tidak terdapat hubungan dengan kelompok homophobia di Indonesia, tetapi aksi serupa dapat saja dilakukan dengan tujuan serupa pula. Pada dasarnya terorisme terhadap kelompok LGBT sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Bagaimana bisa? Menurut Wilkinson (dalam Winarno, 2014) yang mengkategorisasikan terorisme menjadi empat tipe, yaitu: (1) kriminal, (2) psychi, (3) perang, (4) political. Dalam hal ini saya cenderung melihat aksi teror yang terjadi di Indonesia adalah tipe yang pertama dan kedua, dimana tidak sedikit anggota kelompok LGBT yang dikriminalkan (mengalami kekerasan, dan lain-lain), dan kerapkali diserang secara psychi (dianggap menyimpang, sakit jiwa, dan lain-lain). Hal ini merupakan aksi terorisme yang dilakukan oleh berbagai kalangan homophobia terhadap kelompok LGBT di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kelompok “anti” ini sangat membenci LGBT. Terlebih lagi, tidak ada payung hukum yang menjamin keberadaan kelompok LGBT di Indonesia, sehingga tindakan kriminal (teror) itu bisa dari kalangan apa saja. Karena aksi teroris ini menginginkan perhatian, dan mereka ingin semua orang tahu apa yang mereka maksud dan mereka mau. Seperti pendapat ahli media dan terorisme, Brigitte Nacos (dalam Winarno, 2014), “Terrorists do not win the hearts of...the people their target and even not those who look on in the international realm”. Realitas ini sudah seharusnya menjadi pembuka mata pemerintah Indonesia untuk membuat suatu regulasi konkret untuk perlindungan bagi kelompok LGBT. Bahwa tragedi Orlando dapat menciptakan iklim sosial baru, yang mana kekerasan dan kriminal mengancam anggota kelompok LGBT. Negara tidak seharusnya diam saja atas ketidakamanan yang dirasakan oleh salah satu kelompok warganya, terlebih mereka adalah kelompok minoritas. Bahwasannya siapapun korban dan pelakunya, aksi terorisme merupakan musuh kita bersama.  Judul Buku : Politik Hukuman Mati di Indonesia Editor : R. Robet dan Todung Mulya Lubis Penerbit : Marjin Kiri, Tanggerang Cetakan : I, Maret 2016 Halaman : 292 hlm Hukuman mati di Indonesia masih tetap dipertahankan meski banyak penolakan dari masyarakat internasional, terutama dari negara yang sudah menghapus hukuman mati. Data yang dilansir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa sejak Desember 2014, 160 dari 193 negara anggota PBB telah menghapus hukuman mati, dan memberlakukan moratorium. Bahkan dalam sebuah forum terbuka, Sekjen PBB, Ban Ki-Moon mengatakan dengan tegas hukuman mati tidak memiliki tempat di abad ke-21.
Di tengah menguatnya dukungan dari berbagai negara di dunia untuk menghapus hukuman mati, Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati secara legal. Peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati diantaranya, KUHP, UU Narkotika, dan UU Anti terorisme. Alasan utama hukuman mati tetap diberlakukan karena masih kuatnya kepercayaan pemerintah dan juga masyarakat bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera dan efek penggentar (general deterrence). Dengan sanksi hukuman mati, diharapkan memberi rasa takut di kalangan pelaku kejahatan agar tidak terulang di masa depan. Inilah alasan yang seringkali disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk tetap melanjutkan eksekusi terpidana hukuman mati dan menolak permohoan grasi yang diajukan para tersangka. Sikap “tegas” Presiden Jokowi mendapat dukungan luas dari masyarakat dengan minimnya suara protes atas hukuman mati (berkaitan dengan presentase masyarakat yang pro dan kontra perlu diteliti lebih lanjut). Namun jika hendak dikaji lebih mendalam, benarkah hukuman mati dapat meminimalisir tindakan kejahatan? Buku Politik Hukuman Mati di Indonesia yang ditulis oleh lintas akademisi ini memberikan penjelasan bahwa efek jera yang “dijanjikan” dari hukuman mati hanyalah mitos. Hukuman mati tidak lepas dari konfigurasi politik yang mempengaruhi. Hal ini tampak dari diskursus hukuman mati yang didominasi oleh elit, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam artian, belum ada keterbukan pemerintah untuk membahas hukuman mati ini melibatkan masyarakat luas, terutama pihak-pihak yang menolak hukuman mati. Buku ini diawali oleh tulisan Wilson yang meninjau hukuman mati persepektif historis. Artikel yang berjudul "Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati" membahas praktik hukuman mati dari zaman kerajaan, masa penjajahan, hingga pasca Indonesia merdeka. Dalam artikel ini, Wilson memaparkan bahwa hukuman mati yang bersifat kejam sudah ada sejak zaman feodalisme kerajaan yang pernah besar di Nusantara pada abad ke-16, seperti kerajaan Mataram di Jawa dan kerajaan Islam Aceh di Sumatera. Pada masa kerajaan, hukuman mati dikenakan bagi mereka yang memberontak sang raja. Melalui hukuman mati, raja membangun legitimasi kekuasaannya sehingga rakyat bisa tunduk dan patuh. Kemudian hukuman mati berlanjut diterapkan oleh Belanda di era VOC dan melalui sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Tujuan hukuman mati sejak dulu sama, yakni menegakkan supremasi ekonomi-politik dan supremasi moral penguasa untuk melakukan “kontrol” atas tertib sosial dan politik (hlm. 4). Sedangkan Iqrak Sulhin mengulas hasil penelitian yang pernah dilakukan di Amerika Serikat tentang hukuman mati. Melalui artikel berjudul Mitos Penggentar Hukuman Mati, Sulhin menemukan bukti empiris berupa hasil riset di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati, bahkan pasca eksekusi sekalipun tidak serta merta menurunkan angka kejahatan. Salah satu riset yang diulas hasil penelitian Radelet dan Lacock yang dituangkan dalam artikel “Do Executions Lower Homicide Rates? The Views of Leading Criminologists”.Temuan menarik penelitian yang dilakukan tahun 2009 itu menunjukkan hanya 2,6% dari responden yang setuju dengan pernyataan bahwa eksekusi mati memberikan efek penggentar, dan 86,9% lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi, mayoritas kriminolog Amerika Serikat meyakini bahwa hipotesis penggentarjeraan hanyalah mitos dan tidak memiliki bukti yang akurat (hlm. 95). Artikel lain yang lebih reflektif ditulis oleh Todung Mulya Lubis. Artikel ini berada di urutan terakhir, seakan menjadi penanda bahwa sudah waktunya hukuman mati diakhiri di Indonesia. Dalam artikel berjudul "Hukuman Mati dan Tantangan ke Depan: Suatu Studi Kasus tentang Indonesia", pengacara dan aktivis HAM ini memberikan catatan penting kenapa hukuman mati mesti dievalusi dan direkomendasikan untuk dihapus dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa argumen yang diajukan, diantaranya: Pertama, hukuman mati bertentangan dengan HAM, padahal konsitutsi Indonesia berupa UUD 1945 mengakui dengan tegas bahwa HAM tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kedua, tidak ada bukti hukuman mati berdampak mencegah kejahatan. Sehingga dalih hukuman mati dapat membawa efek jera tidak memiliki pondasi yang kuat. Ketiga, risiko salah menghukum. Dalam kasus ini, Lubis mencontohkan kasus yang menimpa Sengkon dan Karta yang dihukum karena pembunuhan yang tidak pernah mereka lakukan. Keempat, korupsi hukum, di kalangan para hakim, pengacara, jaksa dan polisi masih marak tindakan korupsi. Kultur lembaga peradilan yang koruptif akan membuat proses hukum cacat dan tidak adil (hlm. 263-365). Kesembilan artikel yang ada dalam buku ini membangun narasi yang sama, bahwa hukuman mati di Indonesia selama ini ditopang oleh dasar yang tidak kokoh. Namun karena ortodoksi dalam pandangan hukum, hukuman mati tetap dipaksa menjadi bagian dari sanksi hukum yang ada di Indonesia. Buku ini mengajak pemerintah dan masyarakat untuk mendiskusikan kembali hukuman mati sebagai diskursus terbuka. Jika memang pemerintah meyakini bahwa hukuman mati dapat membawa efek jera, sudah semestinya keyakinan itu ditopang dari riset yang kredibilitasnya dapat diuji, bukan hanya sekadar dari asumsi politik semata.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Saya pertama kali mendengar kata postfeminisme dalam kelas paradigma feminis yang diajar oleh Ikhaputri Widianti. Aneh sekali, saya pikir feminisme dengan tiga gelombang dan dalam masing-masing gelombang berisi banyak lagi variasinya. Itu tenyata belum cukup. Feminisme sebagai Ilmu dan gerakannya ternyata punya banyak sekali jenis dan cabang. Feminisme sebagai sebuah gerakan memang universal, tapi tidak menyatukan. Karena perempuan berbeda-beda, dan patriarki--yang lebih tua dari kitab suci, punya bentuk berbeda-beda pada setiap wilayah. Hal ini yang membuat feminisme jadi beragam. Postfeminisme saya ketahui sebagai teori terakhir pada pemetaan teori feminisme. Teori ini dianggap kelanjutan dan bisa juga dianggap sebagai masa ketika feminisme dianggap selesai. Postfeminisme juga dilihat sebagai kritik terhadap feminisme gelombang kedua yang membuat feminisme menjadi sebuah slogan dengan memasukan kata atau label ‘perempuan’ dalam sesuatu yang membuat sesuatu tersebut seakan-akan menyuarakan feminisme. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana postfeminisme dilihat dalam konteks perempuan Indonesia khususnya kelas menengah perkotaan. Postfeminisme, Feminisme Masa Kini? Dalam tulisan Angela McRobbie berjudul Post Feminism and Popular Culture. Postfeminisme merupakan kritik kultural atas feminisme yang dipopulerkan oleh media massa seperti televisi dan iklan, membawa perempuan pada belitan ganda (double entanglement). Belitan ganda antara kapitalisme dan media massa menjebak perempuan dalam dilema baru, antara nilai-nilai konservatif dan keberhasilan feminisme yang membuat perempuan menjadi mandiri dan bebas memilih. Nilai-nilai konservatif seperti menikah, mempunyai anak, berpenampilan menarik tidak hilang seiring dengan kesadaran perempuan dan kemampuannya untuk memilih dengan sadar dan bebas. Media meyakini, melalui budaya populer, ada sebuah permasalahan baru yang merupakan dampak dari feminisme yakni ketakutan akan kesendirian dan kepedulian pada diri sendiri. Keadaan tersebut yang dijadikan kesempatan oleh Kapitalisme untuk mengarahkan perempuan-perempuan muda ini melakukan konsumsi untuk menyenangkan dirinya sendiri dan menciptakan budaya baru, konsumerisme. Postfeminisme juga dianggap sebagai kritik terhadap feminis gelombang kedua dengan slogannya “thanks to feminisme” yang diproyeksikan bahwa feminisme yang diangap sudah selesai dengan tercapainya hak-hak perempuan dalam politik, kepemilikan, dan hukum. Feminisme menjelma menjadi kata-kata yang identik dengan gerakan feminisme seperti feminis, femininitas, feminin, perempuan dan gender dilekatkan pada segala hal dan membuat seakan-akan feminisme benar-benar masuk ke segala bidang dan menjadi bukti keberhasilan (atau justru kegagalan) dari feminisme. Belum lagi pukulan balik dari gerakan feminisme, kehadiran orang-orang yang menolak, bahkan anti dengan feminisme yang ‘liar’ dan identik dengan kelompok Femmen. Beberapa dari kelompok anti feminisme kadang menyebut dirinya sebagai Menininist[1]. Adanya pukulan balik dari gerakan feminisme, belitan ganda antara nilai-nilai konservatif yang tidak membebaskan di satu sisi digiringnya perempuan pada jebakan konsumerisme menghadirkan gelombang feminisme keempat, yang disebut Gadis Arivia dalam kuliah Postfeminisme di UGM (2/5/2016) lalu, feminisme masa kini. Obral Feminisme Dalam kasus Indonesia, kritik postfeminisme bisa dipakai untuk mengkritik kebijakan pengarusutamaan gender yang dianggap gagal. Kebijakan pengarusutamaan gender dilakukan dengan memasukan kata ‘perempuan’ kemudian ‘gender’ sebagai pengganti perempuan. Dan dengan menyematkan kata tersebut maka mampu menghasilkan sebuah kebijakan yang adil gender. Kebanyakan kata ‘perempuan’ atau ‘wanita’ dalam kebijakan sering digunakan untuk membuat suatu kebijakan tersebut pro-perempuan. Padahal penggunaa terminologi perempuan, gender, wanita atau feminis yang dilakukan oleh kapitalisme seperti mengangkat perempuan untuk dihempaskan kembali. Contoh yang bisa dilihat akhir-akhir ini adalah diluncurkannya bus khusus wanita berwarna merah jambu pada perayaan hari Kartini 21 April oleh DKI Jakarta. Alih-alih memberikan bus transjakarta khusus wanita[2] (atau ruangan khusus wanita lainnya) lebih baik pemerintah mendukung peraturan yang menjamin tubuh perempuan di ruang publik, bukan justru memisahkan jenis kelamin agar terkesan ‘aman’. Pemerintah di sini, mengambil jalan pintas dengan memisahkan ruang publik antar jenis kelamin bukan menjamin keamanan tubuh perempuan atau memberikan pemahaman bahwa melecehkan perempuan adalah sebuah tindakan kriminal (dalam KUHP perkosaan dan pelecehan terhadap perempuan hanya dikategorikan sebagai tindakan asusila). Menyedihkannya lagi, hal ini dilakukan untuk merayakan hari Kartini. ‘Obral’ kata-kata perempuan banyak juga kita temui apabila mendekati hari-hari khusus perempuan seperti hari Ibu 22 Desember, Women’s International Day, atau hari Kartini 21 April. Kita akan menemukan banyak iklan bertebaran menyajikan diskon khusus untuk pembeli perempuan untuk produk make up, tas, ataupun sepatu. Dan kini kapitalisme mengobral kata ‘perempuan’ semakin lebih canggih dengan embel-embel agama. Kata perempuan dan Islam dilekatkan untuk sesuatu yang dianggap pro-perempuan muslimah dalam produk khusus seperti susu kalsium khusus perempuan muslimah. Belitan Ganda Hijabers Media massa membuat ukuran bahwa feminisme dianggap sudah selesai dengan menghasilkan perempuan-perempuan yang mandiri, memiliki penghasilan, memiliki pilihan dan sistem hidupnya tersendiri tetapi masih berkutat dalam pikiran penampilan, berat badan, gaya hidup sehat, dan ‘membutuhkan lelaki sebagai pasangan hidup yang cocok’. Perempuan Indonesia berterimakasih pada Kartini yang memperkenalkan ‘emansipasi’[3] memberikan model perempuan untuk meraih pendidikan dan pekerjaan seperti laki-laki. Ideologi gender Orde Baru yang menjadikan perempuan sebagai tenaga kerja yang bisa diberikan upah murah (karena bekerja bukanlah peran utama bagi perempuan). Tapi hal ini juga membuka kesempatan perempuan untuk memiliki pekerjaan walau tetap harus berkarier sebagai ibu. Pada masa reformasi, mulai tumbuh kembali gerakan-gerakan dan organisasi perempuan yang membuat perempuan kini sudah memiliki kesadaran dan bangga akan identitas keperempuanannya. Khususnya pada perempuan perkotaan, dewasa ini seiring dengan semakin luasnya kelas menengah Indonesia[4] dan Islamisasi. Saya mengambil contoh postfeminisme yakni komunitas Hijabers. Hijabers adalah sebutan yang disematkan pada perempuan muslim Indonesia perkotaan yang memilih secara sadar untuk menggunakan jilbab sebagai bentuk ibadah dan syarat untuk menyempurnakan agama Islam dengan negosiasi untuk tetap menjadi menarik dengan memodifikasi jilbabnya dan menjadikannya selain sebagai ibadah, juga bagian dari fashion. Dalam pandangan saya, Hijabers adalah contoh dari postfeminisme. Perempuan muda masa kini yang berada dalam belitan ganda tersebut. Para hijabers hampir seluruhnya berasal dari perempuan muda kelas menengah perkotaan yang mengenyam pendidikan tinggi, masuk ruang publik dan memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Kemudian, perempuan hijabers masih berhadapan dengan nilai konservatif seperti berpenampilan cantik sesuai syariat, keinginan untuk menikah dengan pasangan yang cocok, menggunakan hijab sebagai bagian untuk menolak identitas perempuan modern ‘ala Barat’. Dan di satu sisi perempuan hijabers ini ditaklukan oleh konsumerisme. Hijab yang awalnya sebagai pakaian muslim biasa dijadikan sebuah komoditas dan tidak tanggung-tanggung Dolce & Gabbana, merk fashion ala Barat terkenal, kini ikut mengeluarkan koleksi pakaian muslimahnya.[5] Keterputusan Feminis Apakah feminisme benar-benar sudah selesai? Kita tidak memungkiri beda permasalahan tiap-tiap lokasi yang dialami perempuan yang berbeda. Akan tetapi kita juga tidak bisa menyangkal kata ‘feminis’ dan ‘perempuan’ akan menjadi jangkar bagi pemikiran dan gerakan feminis untuk kesetaraan. Jikalau saya sebagai generasi Millenial melihat situs 9gag.com[6], saya menemukan backlash yang kencang dari para anti feminisme. Bisakah kita berdialog dengan orang-orang yang sudah alergi terhadap feminisme kalau begitu? Bisakah kita mengambil subtansi dari feminisme dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari tanpa menggunakan label ‘feminis’ dan perempuan? Mengambil substansi dari feminisme saya rasa tidak menghentikan feminisme itu sendiri. Catatan Akhir: [1] Meninist adalah sindiran terhadap Feminist, bergerak pada media populer seperti Twitter dan LINE lihat berita selengkapnya dalam https://www.buzzfeed.com/rossalynwarren/men-are-calling-themselves-meninists-to-take-a-stand-against diakses 6 mei pukul 9:39 WIB [2] “Tampilan Bus Transjakarta Khusus Wanita” dalam http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/21/14091871/Tampilan.Bus.Transjakarta.Pink.Khusus.Wanita diakses 5 mei 2016 pukul 23:22 WIB [3] Emansipasi dianggap berbeda dengan feminisme yang dianggap ala Barat. Emansipasi adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dan feminisme disamakan dengan pseudo-feminisme yang menginginkan perempuan lebih tinggi drajatnya dari laki-laki. Emansipasi dengan Feminisme dibeda-bedakan melalui media budaya populer seperti yang saya temukan dalam website populer konsultasi percintaan http://kelascinta.com/women/feminisme-emansipasi-setara diakses 6 mei 2016 pukul 9:46 WIB [4] Kelas menengah muncul di desa-desa tetapi khususnya pada perkotaan. Karena kelas menengah berasal dari pola konsumsi bukan pola pendapatan dan penentuan klasifikasi tentang kelas menengah di Indonesia diukur berdasarkan kepemilikan ponsel dan sepeda motor dalam rumah tangga. lihat Gerry van Klinken, 2016, “Demokrasi, Pasar, dan Kelas Menengah yang Asertif” dalam In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah, Jakarta: KITLV dan Yayasan Pustaka Obor hlm 1-2 [5] “8 Desainer dan Brand Luar Negeri yang Mengeluarkan Koleksi Hijab Baju Muslim” dalam http://kawankumagz.com/Fashion/8-Desainer-Dan-Brand-Luar-Negeri-Yang-Mengeluarkan-Koleksi-Hijab-Baju-Muslim diakses 6 mei 2016 pukul 1:25 WIB [6] 9gag.com adalah situs jokes yang berisi meme atau lelucon bergambar yang ebrsifat internasional, populer sejak tahun 2009. Menurut dugaan saya, 9gag mempelopori budaya meme yang populer di Indonesia melalui dunia virtual media sosial. Budaya meme dari 9gag kemudian berkembang emnjadi situ serupa dengan cita rasa lokal seperti 1cak.com meme comic indonesia sampai dagelan.co 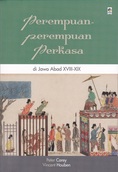 Judul : Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX Penulis : Peter Carey dan Vincent Houben Penerbit : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Cetakan I : Maret, 2016 Halaman : xiv + 114 ISBN : 978-602-6208-16-3 Pada Agustus 1900, RA Kartini (1879-1904) sebagai salah satu pengamat dan penulis budaya Jawa terpenting menulis, “Kami perempuan Jawa terutama sekali wajib bersifat menurut dan menyerah. Kami harus seperti tanah liat yang dapat dibentuk sekehendak hati.” Kartini menggunakan pronomina ‘kami’: sekian banyak perempuan Jawa yang dia saksikan, perjuangkan, dan sekaligus menjadi keprihatinan terbesarnya.
Bagi Kartini, juga pejuang hak emansipasi perempuan berikutnya, semua itu menjadi pertanyaan penting: “Apa sebab wanita sampai dapat dijadikan objek kesenangan laki-laki, seakan mereka tidak mempunyai pikiran dan pendapat atau perasaan sendiri? Apa sebab kaum laki-laki sampai menganggap wanita sebagai sebuah ‘golek’, sebuah boneka, barang mati yang boleh diperlakukan semaunya, seolah-olah wanita itu bukan manusia?” Di sinilah buku kecil Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX, karya sejarawan Peter Carey dan Vincent Houben, menjadi penting. Karya karier awal dua sejarawan kawakan ini mencoba menelusuri kuasa dan pengaruh wanita Jawa dalam arus politik, pergerakan militer, penjaga tradisi budaya, kepenulisan sastra, penjunjung agama, pembimbing-pendidik anak-anak (penguasa) Jawa, pemelihara trah pertalian wangsa, sebagai pengusaha, dan pengendali finansial politik. Semua ruang publik dan domestik ini menjadi arena kajian penting buku dua sejarawan tersebut. Abad ke-18 dan ke-19, atau era sebelum Kartini, biasanya disebut sebagai era pemerintahan kolonial yang sesungguhnya (high colonial period) yang terbentang antara Perang Jawa/Diponegoro (1825-1830 M) dan awal pendudukan militer Jepang (1942-1945). Bagi Carey dan Houben pada awal sebelum Perang Jawa dan masa-masa sesudahnya adalah masa yang krusial dalam menelusuri perubahan peran dan kuasa perempuan Jawa, sebelum begitu terpengaruh kuasa kolonialisme Eropa yang didominasi lelaki patriarkis sekaligus sebelum kuasa Islam-Jawa patriarkis begitu dominan. Di pinggir surat seorang residen Jogja, Marsekal Daendels (1808-1811) menulis catatan yang penuh sentimen male chauvinist (pemujaan kejantanan): “perempuan tidak punya tempat dalam penghormatan umum, dan terhadap perempuan hanya ada urusan pribadi!” Tokoh veteran Perang Revolusi Prancis dan Perang Napoleon ini, juga penguasa atau birokrat kolonial Belanda berikutnya, menyadari bahwa perempuan Jawa sering begitu kuat menentukan arus politik dan budaya dan dengan sendirinya mengancam hasrat kolonialisme Eropa. Dalam catatan Serah Terima Jabatan (Memorie van Overgave), meski begitu didominasi kaum lelaki, terkadang ada catatan tokoh perempuan Jawa yang begitu berpengaruh. Salah satu tokoh perempuan Jawa yang begitu berpengaruh secara politis militer, politik keraton, pendidikan anak raja, dan sebagainya adalah Ratu Ageng Tegalrejo/Raden Ayu Serang (ca. 1732-1803). Dia adalah permaisuri pertama raja pertama Jogja (Sultan Mangkubumi) yang menjadi komandan pertama “Korps Srikandi” kesultanan. Dia memiliki keahlian naik kuda, menggunakan senjata, dan paham strategi perang. Di usia cukup dewasa, bekas prajurit èstri ini pindah ke Tegalrejo, menjadi pengikut tarekat Shaţţārīyah, dan terutama mengangkat-mengasuh Pangeran Diponegoro sebagai anak-didik terpentingnya sampai dewasa. Saat terjadi Perang Jawa, perempuan kesatria sakti dan pertapa ini angkat senjata memimpin pasukan berkekuatan 500 orang melawan Belanda. Tentu dua sejarawan itu wajib mengisahkan korps prajurit èstri yang terkenal sebagai pasukan elite. Para perempuan ningrat itu terlatih dan piawai menggunakan aneka senjata seperti tameng, busur, panah beracun, tombak, tulup, atau bedil, selain dilatih menari, menyanyi, dan memainkan musik. Dalam buku hariannya, Jan Greeve (Gubernur Pantai Timur Laut Jawa) mencatat hasil kunjungannya ke Surakarta (Solo) pada 31 Juli 1788: prajurit perempuan menembakkan salvo “dengan teratur dan tepat sehingga membuat kita kagum” sambil “menembakkan senjata tangannya [karben kavaleri] sebanyak tiga kali dengan sangat tepat…diikuti tembakan senjata kecil [artileri].” Jika selama ini sering terdengar pemberontakan dan kudeta oleh kaum lelaki, Carey dan Houben mengingatkan akan pentingnya kuasa dan peran Ratu Kedaton dan Ratu Kencono, dua aktor kunci pemberontakan gagal sang anak, Raden Mas Muhammad (Pangeran Suryèngologo) terhadap Sultan Yogya ketujuh pada 1883 di Kedu. Tentu saja peran sentral perempuan (ningrat yang tak mesti berdarah biru) Jawa adalah sebagai ibu dan sekaligus sebagai pendidik-pengajar, yang cukup sering memicu perseteruan internal keraton dalam perebutan penobatan putra mahkota. Peran ini memosisikan perempuan sebagai penjaga wali setia adat Jawa. Selain itu, banyak perempuan Jawa menguasai tradisi tulis-menulis, seperti Raden Ayu Purboyoso (ca. 1756-1822) yang terkenal mahir aksara pegon (Jawi gundul) dan memiliki koleksi versi Jawa karya sastra Islam Arab. Maka, melalui karya kecil dan penting ini, Carey dan Houben hendak mengingatkan: priyayi dan perempuan Jawa, setidaknya sampai akhir Perang Jawa, memiliki dan menikmati kebebasan dan kesempatan bertindak dan mengambil inisiatif pribadi yang lebih luas daripada saudari perempuan mereka pada akhir abad ke-19, seperti pada zaman Kartini. Dua sejarawan ini juga hendak merevisi citra Raden Ayu di Jawa sebagai “boneka yang tersenyum simpul dan meniadakan diri sendiri...perempuan elok namun kepalanya kosong”, seperti yang tersebar dalam banyak literatur (sastra) kolonial Belanda. Memang, kajian yang dilakukan dua sejarawan ini masih tahap pengantar ringkas tapi cukup luas, sebagaimana diakui keduanya. Setidaknya, mereka berhasil menyimpulkan bahwa memudarnya kuasa perempuan model matriarki gaya Polinesia sedikit banyak dipengaruhi oleh Islam dan terutama kolonialisme Eropa khususnya Belanda yang tak menghendaki kuasa besar perempuan termasuk ambisi Raden Ayu Sekar Kedaton menjadi raja Jawa. Yang jelas, perempuan Jawa pra-Kartini, seperti terpapar dalam lembar buku ini, jauh lebih berkuasa dan perkasa. |
AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
September 2021
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed