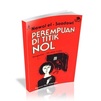 obor.or.id obor.or.id Judul buku : Perempuan di Titik Nol Pengarang : Nawal El Sadaawi Penerbit : Yayasan Obor Indonesia Tahun Terbit : 2002 “Betapapun juga suksesnya seorang pelacur, dia tidak pernah dapat mengenal semua lelaki. Akan tetapi semua lelaki yang saya kenal, tiap orang di antara mereka telah mengobarkan dalam diri saya hanya satu hasrat saja; untuk mengangkat tangan saya dan menghantamkannya ke muka mereka.” (Nawal El Saadawi 2002, h. 149)
Kutipan diatas merupakan sepenggal dialog yang terdapat pada novel Perempuan di Titik Nol yang ditulis Nawal El Saadawi. Novel ini mengisahkan sisi gelap yang dihadapi perempuan-perempuan Mesir di tengah kebudayaan Arab yang kental dengan nilai-nilai patriarki. Ketika perempuan masih mengalami ketimpangan hak dan tidak tidak pernah mendapatkan hak yang sama seperti yang didapatkan laki-laki. Seperti halnya bangsa Arab, budaya patriarki menjadi salah satu dasar perdebatan akan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan masih menuai konflik. Mengenai hak-hak perempuan yang kurang terjamin, kebebasan dalam dunia politik, serta kungkungan hierarkis suami membuat perempuan terbelakang dalam segala kesempatan, mengalami diskriminasi, kekerasan, serta kemiskinan. Negeri Arab yang dikenal dengan kondisi perempuan yang amat terbelakang menghadirkan sejuta cerita mengenai perempuan korban budaya patriarki. Nawal El Saadawi seorang doktor berkebangsaan Mesir menghadirkan sebuah novel yang menunjukkan perjuangan perempuan Mesir untuk merebut kedudukan dan hak-hak yang sama dan untuk mendapatkan perubahan nilai dan sikap laki-laki Mesir terhadap perempuan yang sepenuhnya belum tercapai. Lewat tokoh Firdaus, Nawal menguak sebuah alur cerita yang sangat pedas, keras, dan berani yang mengandung jeritan pedih, protes terhadap perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang diderita, dirasakan, dan dilihat oleh perempuan itu sendiri. Perempuan di Titik Nol merupakan novel yang menghadirkan figur perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam budaya patriarki. Ia adalah seorang perempuan yang diciptakan oleh masyarakat yang sangat laki-laki menjadi makhluk kelas kedua yang berarti inferior. Firdaus: Identitas Perempuan yang Dinomorduakan “Jika salah satu anak perempuan mati, ayah akan menyantap makan malamnya, Ibu akan membasuh kakinya, dan kemudian ia akan pergi tidur, seperti itu ia lakukan setiap malam. Apabila yang mati itu seorang anak laki-laki, ia akan memukul ibu kemudian makan malam dan merebahkan diri untuk tidur.” (Nawal El Saadawi 2002, h. 26) Hidup di tengah-tengah keluarga patriarkat sudah dirasakan oleh Firdaus sejak kecil. Hidup di tengah keluarga miskin, tak jarang Firdaus merasakan dan melihat seorang ayah diperlakukan seperti seorang raja oleh istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki (ayah) diperlakukan sebagai individu nomor satu di antara individu-individu lainnya. Relasi ini menunjukkan ketidaksetaraan di dalam sebuah keluarga, bahwa di posisi inipun perempuan mengalami dampak budaya patriarki. Begitu juga dalam lingkungan sosial, tokoh Firdaus kerap mengalami ketidakadilan sosial karena ia seorang perempuan. Saat Firdaus memasuki masa remaja, ia ingin sekali belajar di Kairo mengikuti jejak pamannya. Namun, ia tidak diperbolehkan belajar di sana karena dia adalah seorang perempuan. “Apa yang akan kau perbuat di Kairo, Firdaus?” Lalu saya menjawab: “saya ingin ke El Azhar dan belajar seperti paman.” Kemudian paman tertawa dan menjelaskan bahwa El Azhar hanya untuk kaum pria saja. El Azhar merupakan suatu dunia yang mengagumkan dan hanya dihuni oleh laki-laki saja, dan paman merupakan salah seorang dari mereka. Dan dia adalah seorang laki-laki. (Nawal El Saadawi 2002, h. 22 dan 30) Dalam budaya patriarki seorang perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua atau yang disebut liyan oleh Simone De Beauvoir. Konstruksi masyarakat yang menganggap bahwa wilayah perempuan adalah pada arena domestik menciptakan suatu hubungan yang terdominasi dan tersubordinasi, hubungan antara perempuan dan laki-laki bersifat hierarkis, yakni laki-laki berada pada kedudukan yang dominan sedangkan perempuan subordinat (laki-laki menentukan, perempuan ditentukan). Akibat adanya ketimpangan relasi ini tak jarang perempuan dibatasi ruang geraknya antara privat dan publik. Privat bermuara pada wilayah rumah tangga yang stereotipnya diperuntukan bagi perempuan, kemudian wilayah publik seperti lapangan pekerjaan dan negara diperuntukkan bagi laki-laki. Budaya patriarki juga yang membuat perempuan inferior lantaran tubuhnya. Keadaan inilah yang membuat perempuan mengalami diskriminasi dalam segala hal baik ekonomi, politik maupun sosial. Dalam esainya yang berjudul “Inti Problematika Perempuan Mesir”dalam Pergolakan Pemikiran dan Politik Perempuan (2007), Nawal pernah mengemukakan bahwa mayoritas kaum laki-laki dari Partai Sosialis Arab menganggap bahwa menghimpun kekuatan politik kaum perempuan adalah pemikiran yang salah dan dianggap sebuah usaha untuk memecah belah barisan persatuan kaum laki-laki dan perempuan. Ini juga dianggap usaha mengalihkan perjuangan dari tujuan pokoknya, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, sehingga menjadi perseteruan antara kaum laki-laki dan perempuan. Relasi Patriarki terhadap Tubuh Perempuan Dalam budaya patriarki, sisi laki-laki yang sangat dominan menciptakan identitas perempuan menjadi makhluk kelas dua. Akibat budaya patriarki ini sejak kecil Firdaus kerapa kali mengalami tindak kekerasan dan sewenang-wenang dari laki-laki. Ayah Firdaus adalah sosok yang ditakuti dalam keluarganya. Sebagaimana dalam budaya patriarki, ayah mempunyai peranan dominan dalam keluarga. Tak jarang Firdaus mendapatkan kekerasan dari ayahnya yang membiarkannya lapar dan membasuh kaki ayahnya apabila sedang kedinginan. Ayahnya pula yang menciptakan identitas Firdaus sebagai pelayan rumah tangga pengganti ibunya. Pelecehan seksual kerap kali didapatkan oleh Firdaus dari pamannya sejak kecil. “Saya melihat tangan paman saya bergerak-gerak dibalik buku yang sedang Ia baca menyentuh kaki saya. Saat berikutnya saya merasakan tangan itu menjelajahi paha saya.”(Nawal El Saadawi 2002, h. 20). Perlakuan inilah yang nantinya membentuk identitas Firdaus menjadi perempuan lacur. Ketika Firdaus memasuki usia remaja, ia dinikahkan oleh pamannya kepada seorang laki-laki bernama Syekh Mahmoud seorang laki-laki tua yang berperangai kasar dan kikir. Firdaus ditukar dengan mahar yang sangat mahal. Dalam rumah tangganya tidak jarang Firdaus mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya karena dia adalah seorang istri dan seorang perempuan. “Pada suatu peristiwa ia memukul badan saya dengan sepatunya. Muka dan badan saya menjadi bengkak dan memar. Lalu saya pergi dari rumah dan pergi ke rumah paman.”(Nawal El Saadawi 2002, h. 63) Identitas Firdaus sebagai seorang perempuan yang dianggap sebagai makhluk kelas dua membuat Firdaus pasrah menerima perlakuan kekerasan dari suaminya. Di tengah-tengah budaya patriarki kejadian tersebut dianggap lumrah, ketika seorang suami memukul istri. Bahkan pamannya berkata bahwa ia juga sering memukul istrinya. Kewajiban seorang istri ialah kepatuhan yang sempurna. Pengalaman demi pengalaman yang dialami oleh Firdaus sejak kecil memberikan pelajaran kepada Firdaus bahwa identitasnya sebagai seorang perempuan hanyalah dijadikan sebagai objek yang dapat ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang. perlakuan sewenang-wenang yang diterima Firdaus mengajarkan bahwa ia juga pantas menerima sebuah kebebasan, tanpa kontrol dan siksaan dari laki-laki. Dalam kondisinya yang miskin Firdaus lebih memilih menjalani profesinya sebagai pelacur. Dalam mencapai kesusksesan menjadi pelacur yang bebas tersebut, Firdaus sampai pada permenungan bahwa peran laki-laki dalam budaya patriarki mempunyai peran besar membentuk tubuhnya menjadi pelacur. “Saya tahu bahwa profesi saya diciptakan oleh seorang laki-laki. Karena saya seorang yang cerdas, saya lebih menyukai menjadi seorang pelacur yang bebas daripada menjadi seorang istri yang diperbudak.” (Nawal El Saadawi 2002, h. 133) Diskriminasi Perempuan dalam Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik Masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu lalu berbagai negara dibelahan bumi mengadakan demonstrasi besar-besaran melawan kekerasan terhadap perempuan atau yang dikenal dengan istilah femicide. Di Indonesia sendiri angka kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis, menurut Catatan Akhir Tahun 2014 Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014. Tidak hanya sampai di situ, berbagai Perda diskriminatif kemudian muncul mengatur tubuh perempuan, misalnya larangan beraktivitas malam bagi perempuan oleh pemerintah kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Berbagai bentuk penindasan pun kerap kali diberitakan dialami oleh perempuan. Penindasan tersebut dapat dialami dengan berbagai bentuk, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, serta pemecatan di tempat kerja. Tidak jarang pula kita sering disuguhi dengan berita diskriminasi lainnya, seperti anggapan tentang baik tidaknya tubuh perempuan, larangan bagi perempuan beraktivitas malam, larangan bagi perempuan memakai celana, serta peraturan-peraturan diskriminatif lainnya. Tindak diskriminatif dalam bidang pekerjaan sangat terlihat. Nilai patriarkal yang menganggap bahwa tempat perempuan adalah di rumah dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan dengan menjadikan perempuan sebagai tenaga kerja tambahan yang dapat digaji dengan murah, tanpa jaminan sosial dan hak-hak kerja lainnya. Begitu juga dalam bidang politik, budaya patriarkis mengonstruksikan bahwa yang berhak memerintah adalah seorang laki-laki. Budaya patriarkis menciptakan suatu mitos bahwa ruang perempuan adalah mengurus rumah tangga (domestik) sedangkan wilayah publik atau politik dianggap sebagai ruang bagi laki-laki. Tidak heran jika sampai saat ini jumlah perempuan dalam jabatan publik masih sangat minim. Dalam budaya patriarki identitas perempuan diidentikkan dengan sifat lemah lembut dan membutuhkan perlindungan untuk membuatnya semakin lemah dan mudah didominasi. Mitos yang diciptakan tentang perempuan dalam budaya patriarki menghalangi perempuan untuk mengembangkan kekuatan serta potensi yang ada pada tubuhnya dan bukan untuk membuatnya kuat serta mampu bertahan dan berkreasi dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Di dalam budaya patriarki kelemahan tubuh perempuan dijadikan sebagai kelemahan absolut sebagai jenis kelamin kedua. Jonathan Manullang (Kurator Film) [email protected] & Yulaika Ramadhani (Bergiat di Community for Interfaith and Intercultural Dialogue Indonesia) [email protected] 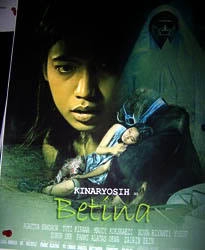 Ideologi Orde Baru menuntut perempuan Indonesia untuk selalu memberi dukungan total bagi sang suami dari balik layar, dan seringkali tanpa kebebasan yang cukup guna mengekspresikan pribadinya sendiri. Lebih lanjut, ideologi tersebut mengurung perempuan secara harfiah—ruang geraknya terbatas di area sekitar rumah yang diwakili slogan populer “dapur, sumur, kasur”. Keterbatasan perempuan ini turut tertuang dalam khasanah sinema nasional secara umum pada masa itu. Setelah OrdeBaru runtuh dan sinema nasional kembali menggeliat, muncul sebuah fenomena anyar terkait cara bertutur sinematik yang berusaha melepaskan diri dari konstruksi ideologi tersebut. Salah satu contoh menonjol fenomena ini adalah keberanian sineas mengeksplorasi tema seksualitas perempuan. Rhavi Bharwani memaparkan kepasrahan seorang sinden terhadap tradisi berbau seksualitas di sebuahkampung dalam ImpianKemarau. Nia Dinata mengamati relasi lesbian di Berbagi Suami. DjenarMaesa Ayu mengisahkan relasi antara seorang perempuan korban kekerasan seksual dengan laki-laki yang sudah berkeluarga melalui Mereka Bilang, Saya Monyet. Di ranah film pendek kita mendapati Edwin yang menampilkan kesadaran naluriah seorang perempuan tentang kapan dan bagaimana dirinya tengah diperhatikan oleh laki-laki lewat A Very Boring Conversation. Yang masih segar dalam ingatan tentu saja About A Woman, film arahan Teddy Soeriaatmadja yang berfokus pada gejolak hasrat seorang janda paruh baya terhadap anak laki-laki remaja. Lola Amaria ikut meramaikan keragaman penggarapan tema seksualitas perempuan melalui debut penyutradaraannya bertajuk Betina.Namun pilihan yang ia ambil sungguh unik: menghadapkan seksualitas perempuan—secara konvensional disepakati sebagai proses awal kelahiran—dengan antitesisnya: kematian. Sebuah kombinasi paradoks yang sejatinya masih jarang dilirik oleh film-film Indonesia. Lola bermain dengan banyak sekali atribut simbolik dalam debutnya ini. Atribut-atribut ini dapat kita temukan dalam relasi sosial dan pemaknaan kematian yang senantiasa berkelindan dengan bahasan seksualitas Betina, sang karakter utama. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menjelaskan kedalaman dimensi Betina adalah dengan mendedah dan melucuti atribut-atribut simbolik di sepanjang film. Terdapat dua macam relasi sosial dalam film, yaitu relasi protagonis dengan keluarga dan protagonis dengan masyarakat. Relasi keluarga tercermin dari hubungan Betina dengan ibunya yang tidak dekat alias berjarak secara emosional. Depresi berkepanjangan sang ibu membuat proses tumbuh besar Betina serba kekurangan kasih sayang. Konsekuensinya, sang anak mencari pemenuhan dari hal-hal lain, seperti menghabiskan banyak waktu bersama sapi peliharaannya. Pada bagian klimaks malah terlihat sekali pembuat film meniatkan posisi ibu dan anak sebagai sebuah antagonisme. Hal ini menyepakati nilai-nilai yang mengarahkan seorang anak yang ingin melepaskan diri dari otoritas maternal [1]. Keberjarakan dengan sang ibu tersebut hadir guna menonjolkan identitas sang anak sebagai subjek yang berhak atas orientasi seksualnya sendiri. Teori tersebut mengamini pernyataan Chodorow [2] bahwa anak perempuan lantas memasrahkan dirinya pada hukum yang tunduk pada ayah, pada anak laki-laki, lalu mencari pengganti ayah seraya sesekali menengok ke belakang demi meyakinkan keterpisahannya dari ibu. Di sisi lain, kedua tokoh ini memiliki kesamaan pula, yakni dalam hal keabsenan figur laki-laki. Seorang perempuan kehilangan suami dan seorang anak perempuan tumbuh tanpa kasih sayang ayah. Dari sini, Lola menggiring penonton kepada jenis keabsenan lain: fungsi seksual suami istri. Konsekuensi paling mencolok dari keabsenan terakhir jelas berupa lahirnya fantasi-fantasi seksual dari kedua belah pihak. Sembari film berjalan, Lola kemudian tampak berkonsentrasi membawa penonton menilik seksualitas perempuan secara khusus dalam dimensi psikososial. Dimensi ini meliputi faktor-faktor psikis (emosi, pandangan, dan kepribadian) yang berkolaborasi dengan faktor sosial, yakni tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya secara seksual [3]. Dimensi ini hadir secara gamblang melalui interaksi Betina dengan para tokoh laki-laki di sekelilingnya. Secara khusus, antusiasme dan kerinduan protagonis kepada sosok pemimpin prosesi pemakaman menjadi paradoks bagi berbagai gestur penuh hasrat dari hampir seluruh tokoh laki-laki atas tubuhnya. Betina selalu senang mendengar berita kematian. Ia kerap tampil bersemangat dan kegirangan menyambut kabar duka apapun. Ia sadar bahwa kematian adalah satu-satunya jalan guna bersua dengan pemimpin prosesi pemakaman yang diam-diam ia sukai. Melalui peristiwa kematian pula kita dapat menyaksikan perwujudan sisi emosional karakter Betina. Di titik ini, Lola tampak sengaja melawan stigma perempuan yang sering dinilai pasif dan tidak responsif, meski tetap menempatkan laki-laki selaku agresor seksual. Bukti penempatan laki-laki selaku agresor bertebaran sepanjang film. Bandar susu yang melecehkan Betina di bagian pembuka, pemilik peternakan sapi yang mencoba memerkosanya, serta kecenderungan seksual Luta terhadap tubuh Betina. Contoh-contoh ini menegaskan metafora bagi kondisi di dunia nyata: kaum laki-laki masih amat digdaya dalam konteks penguasaan tubuh lawan jenis. Lebih jauh, adegan-adegan tersebut agaknya ingin menyindir bahwa seks tidak semata-mata mengemban fungsi reproduksi, tetapi juga rekreasi. Yang menarik, Lola kemudian memukul balik unsur-unsur maskulin tersebut. Tidak tanggung-tanggung, ia ‘membunuh' semua laki-laki yang berniat menguasai tubuh Betina. Pembunuhan terhadap semua karakter laki-laki selaku agresor seksual sekaligus melenyapkan pembahasan tentang relasi kuasa. Konsekuensinya, kita tidak menemukan satupun laki-laki pemegang kuasa atas tubuh perempuan di lingkup keluarga bahkan level masyarakat. Sebagian dimatikan sementara sebagian lagi sempat berusaha menasbihkan kendali atas tubuh Betina walau berakhir dengan kegagalan. Frederich Engels dalam The Origin of the Family, Private Poperty and State merumuskan bahwa pembatasan peran perempuan dimulai dari kepemilikan pribadi. Sejak lahir ia telah disosialisasikan sebagai milik laki-laki, sebelum menikah ia bergantung dan menjadi milik sang ayah, sedangkan ketika menikah ia menjadi milik suami [4]. Mengacu pada hal itu, keabsenan sosok suami, ayah, dan pasangan laki-laki di film ini seakan memberi gambaran yang lebih luas tentang posisi dan peran perempuan yang bebas dari kuasa laki-laki. Kelangkaan laki-laki juga menghasilkan suatu kondisi dimana perempuan menjadi pihak superior, baik secara populasi maupun politis. Di sini pembuat film seakan ingin menyuguhkan situasi utopis yang bersih dari gangguan libido laki-laki. Namun di sisi lainkelangkaan laki-laki justru mengganggu proses alami seksualitas seorang perempuan, sehingga tarik ulur kekuasaanpun masih terjadi, ditandai oleh kecemburuan Betina terhadap sang ibu pasca berduaan bersama pemimpin prosesi pemakaman. Kecemburuan tersebut sedemikian kuat memengaruhi pribadi Betina sampai mampu mendorongnya untuk membunuh ibunya sendiri. Tak pelak, pembunuhan ini meresmikan Betina sebagai pemegang kuasa mutlak atas bermacam keadaan yang mungkin terjadi selanjutnya. Windu Jusuf pernah menyebutkan, motif kematian pada film umumnya berperan sebagai semacam vanishing mediator [5]. Karakter-karakter dalam cerita pasca kematian dibawa menuju situasi baru. Posisi kematian sebatas menunjukkan perubahan pola-pola relasi. Melalui Betina, Lola Amaria melampaui premis tersebut. Ia menasbihkan kematian sebagai agen ganda: pengubah pola-pola relasi sekaligus juga pintu masuk pembahasan seksualitas. Kematian sebagai pengubah pola relasi tercermin lewat dua peristiwa: kematian Luta dan kematian ibu Betina. Pemakaman Luta menjadi ajang pertemuan ibu Betina dengan sang pemimpin prosesi pemakaman. Bila kita cermat memerhatikan prosesi pemakaman dalam film, penonton mampu mendeduksi sebuah informasi anyar mengenai tugas lain pemimpin prosesi pemakaman. Tugas khusus ini ia jalankan di lokasi spesifik yang tersembunyi serta jauh dari pengamatan publik: rumah pribadinya yang terletak di tengah-tengah area pemakaman. Di sana, ia ‘menghibur’ para janda atau kerabat perempuan yang ditinggal oleh almarhum sanak saudaranya segera setelah prosesi pemakaman usai. Di titik ini, fungsi rekreasi seks berkembang sedemikian rupa. Ia menjadi sebentuk upaya menenangkan gejolak emosional yang muncul akibat duka mendalam. Semacam terapi bagi jiwa yang tengah kehilangan. Hal menarik berikutnya yang patut kita telaah adalah ritual 'penghiburan' melalui seks tersebut. Pemimpin prosesi pemakaman menghidangkan sejenis jamur sembari merapal mantra. Ibu Betina memakan jamur itu sambil mengulangi mantra yang sama sampai akhirnya ia jatuh tertidur. Menurut keterangan tekstual di awal film, jamur ini berjenis Psilocybe atau jamur tahi sapi. Jamur tersebut berpotensi menimbulkan halusinasi berkelanjutan bahkan sampai mengakibatkan kematian. Berhenti pada fungsi halusinogen jamur, penonton dibiarkan memeriksa ulang pernyataan awal mereka perkara penghiburan. Hubungan seks antara pemimpin prosesi pemakaman dan ibu Betina di layar bisa jadi punya dua kemungkinan. Hubungan seks itu berada pada alam bawah sadar tapi bisa juga berada pada alam sadar. Kemungkinan pertama menegaskan fantasi ibu Betina selaku janda yang kehilangan figur laki-laki dalam kehidupan seksual, sedangkan kemungkinan kedua sungguh menjadi bentuk kenakalan pembuat film menggambarkan seksualitas perempuan. Sebagaimana fungsi halusinogen jamur pada umumnya, Psilocybe juga memiliki efek samping berupa kecenderungan adiktif. Ibu Betinapun kembali ke rumah sebagai seorang pecandu, dan sialnya, ia harus berhadapan dengan sang putri yang kadung cemburu. Adegan makan malam sesaat sebelum pembunuhan terjadi adalah bukti gamblang betapa akutnya level kecanduan si ibu sehingga ia mulai mengeluarkan respons-respons spontan yang sangat mengganggu. Sementara bagi Betina, respons-respons absurd ini dengan cepat terakumulasi bersama rasa benci yang terlanjur mengakar dalam hatinya. Akumulasi itu menghasilkan sebuah gagasan brutal yang kelak mengkhianati sosoknya sebagai anak. Kematian sang ibu memang berhasil mengantarkan Betina pada 'kedudukanterhormat' dalam prosesi pemakaman. Ia akhirnya mendapat keistimewaan guna dihibur secara eksklusif oleh sang pemimpin prosesi—meskipun berakhir pada kekecewaan lain: sebuah kematian pamungkas yang begitu sinis walau sesungguhnya berniat memproteksi seksualitas dan eksistensi Betina. Segala pengalaman dan perlakuan seksual yang dialami Betina jelas mencerminkan realitas sosial kita saat ini. Model patriarki masyarakat kita menunjukkan bahwa perempuan wajib tunduk pada laki-laki, terkekang ketika hendak menentukan jalan hidup pribadi, serta tabu mengekspresikan seksualitas di muka publik. Yang lebih parah, perempuan masih sebatas objek gairah. Ia senantiasa harus waspada menghadapi penggerayangan tiada henti, seringkali dari berbagai sisi. Dari segi struktur, Lola terhitung cermat memanfaatkan setiap elemen di filmnya. Pemilihan jamur tahi sapi sebagai medium fantasi (maupun alat membunuh)selaras dengan latar belakang karakter utama selaku pemerah susu sapi. Kemudian pada bagian penutup, setelah Betina sadar bahwa semesta tak pernah berkonspirasi mewujudkan keinginan terdalamnya, sang sutradara menggambarkan keputusasaan protagonis lewat satu shot yang amat ciamik berlatar kandang sapi. Menilik lebih jauh, adegan-adegan erotis di kandang sapi pula yang ia gunakan untuk menyatakan bahwa dalam hal seksualitas, manusia tak ada bedanya dari binatang. Seperti judul film saja yang luar biasa sarkas itu: Betina. Ah, Lola bisa saja! Referensi [1] Barbara Creed, The Monstrous Feminine: Films, Feminisme, and Psychoanalysis (London: Routledge, 1993) [2] Nancy Chodorow, dalam Rosemary Putnam Tong, Feminist Though: A More Comprehensive Introduction (St. Leonards NSW: Allen and Unwin, 1998] [3] Made Oka Negara. 2005. Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan. Dalam Jurnal Perempuan Vol 41. [4] Frederich Engels. 1884. The Origin of the Family, Private Poperty and State. Zurich: Marx/Engels Selected Works. Bisa diunduh di sini https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/origin_family.pdf [5] Windu Jusuf. 2011. Enter the Void: Kematian yang semakin Akrab. Diakses di http://cinemapoetica.com/enter-the-void-kematian-yang-semakin-akrab/pada tanggal 29 Februari 2016 |
AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
September 2021
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed