 Dok. Pribadi Dok. Pribadi Ada sebuah keprihatinan menyeruak dalam batin saya ketika harus menyampaikan bahasan tentang arus seksploitasi perempuan. Pasalnya, walaupun isu pengarusutamaan gender terus diangkat dan diperjuangkan bahkan hingga wacana affirmative action di parlemen, ternyata eksistensi atau keberadaan perempuan di negeri ini masih saja anomali. Istilah seksploitasi perempuan saya definisikan sebagai aktivitas eksploitasi citra tubuh perempuan untuk kepentingan pemuasan hasrat seksualitas publik, khususnya laki-laki. Bentuk seksploitasi ada pada gambar, foto, video hingga film, yang mensyaratkan perempuan dengan bentuk badan proporsional menampakkan hampir, sebagian atau bahkan seluruh bagian tubuh paling privatnya. Kita boleh bersepakat bahwa perempuan hari ini mulai menikmati pendidikan, mendapatkan akses informasi serta memperluas cakrawala dan kemerdekaan untuk mengambil peran dalam masyarakat. Namun demikian, pada saat yang sama ternyata citra atau image tentang perempuan tidak pernah berubah. Bahwa perempuan adalah makhluk lemah, manusia nomor dua, serta boleh diobjekkan adalah fakta. Ketimpangan gender tersebut nyata terlihat dalam wacana menyoal seksualitas, yakni, perempuan masih dilihat sebagai objek seks. Perempuan boleh kian bebas bekerja ke luar rumah, namun di kantor mereka boleh saja dilirik bos, digoda lelaki asing di jalan serta yang paling memprihatinkan ada pada level UU terkait pemerkosaan pun perempuan tidak mendapat area yang sama adil untuk memperjuangkan haknya. Term seperti wanita simpanan, wanita nakal, pelacur, wanita penggoda, semua dibebankan kepada perempuan. Dewasa ini, seksploitasi sebagai manifestasi pembendaan perempuan mencapai puncaknya dalam era kebudayaan pascaindustri lewat seluruh media massa. Aktivis perempuan, Marwah Daud Ibrahim, dalam makalah berjudul “Seksploitasi: Citra Perempuan dalam Media” sejak 1990 menduga bahwa eksploitasi citra tubuh perempuan di media terjadi karena chain of activities media massa di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia, dimana lelaki menempati segala posisi mulai dari fotografer, reporter, editor, layouter, kolumnis, dewan redaksi, loper dan bahkan pembelinya. Sehingga, wajar saja bahwa keindahan ditentukan menurut standar lelaki. Berdasarkan tesis tersebut, Marwah berpendapat bahwa seiring jumlah wanita yang bergelut dalam media massa yang semakin meningkat, maka cepat atau lambat akan mengubah cara pandang media terhadap perempuan. Faktanya, yang terjadi hari ini justru kian buruk meski perempuan benar-benar mendapat hak yang sama untuk memanusiakan dirinya. Sebut saja majalah-majalah wanita yang bertebaran di negeri ini, mulai dari skala lokal hingga nasional. Jika kita amati rubriknya, paling banyak seputar kecantikan. Iklan masih penuh dengan promosi busana dan kosmetika. Obsesi kebendaan menjadi penting seperti tips melangsingkan badan, memuluskan betis, dan mengatur rambut. Sesekali ada latihan kepribadian, pun juga hanya seputar cara bergaul dan sikap bicara, bukan tentang apa yang dibicarakan. Sebatas permukaan, bukan substansi. Industri kebudayaan yang materialistik, hedonistik, sekularistik dan individualistik tidak terpengaruh oleh partisipasi dan karya perempuan di sektor publik. Perempuan adalah objek konsumsi yang strategis bagi kapitalisme. Dampak dan Tantangan Globalisasi informasi semakin membuat arus seksploitasi tak terbendung. Dampaknya tentu tidak sederhana dan tidak bisa dianggap enteng. Tengok saja ketika anda mengakses laman-laman informasi atau berita dan juga akun media sosial, ruang-ruang iklan tidak lepas dari citra seksploitasi perempuan berupa foto-foto seronok. Hal tersebut sudah menjadi pemandangan biasa bagi generasi remaja abad modern. Kebiasaan melihat pemandangan serupa itu berpengaruh pada psikologis bawah sadar teman-teman lelakinya yang memandang bahwa seluruh teman perempuannya boleh juga dieksploitasi. Isu seksualitas tidak lagi ditempatkan pada ranah yang luhur dan sakral, namun sebatas syahwat fantasi-fantasi kotor. Alam pikir generasi muda menjadi kusut. Dampak lanjutannya tentu tidak akan tercipta generasi yang gemar belajar, membaca buku, mampu berpikir jernih serta analitis. Banyak sudah penyimpangan yang terjadi mulai dari pelecehan seksual, seks bebas usia remaja yang terus meningkat jumlahnya, hingga sadisme seks yang berujung kematian. Dalam hal ini, perempuan lebih sering menjadi korban sesuai stigma pasif dan masokis yang melekat pada dirinya. Skenario relasi wanita dan seks yang dikurung dalam bingkai komoditas harus dihalau lewat kerjasama semua pihak. Pertama, media tidak harus sekadar maskulin namun juga menjadi feminis, menjalankan fungsinya sebagai peradaban yang bergerak dan tak mesti limbung digilas mesin kapitalisme. Sebagai sikap pemihakan terhadap hak-hak perempuan, harus ada sikap serius agar media cetak maupun elektronik menurunkan intensitas pemanfaatan sensasi seksual perempuan dalam bentuk citra, kata maupun ideologisasi pelemahan perempuan. Selanjutnya, sebagian masyarakat pasti berpendapat bahwa supply citra seksploitasi perempuan dapat terjadi karena perempuan mengizinkan hal tersebut. Ini merupakan fakta ironis. Di satu sisi, wanita memang terindoktrinasi arus modern perihal kesuksesan instan yang dapat diraih dengan mengejar standar cantik ala iklan produk kecantikan. Namun, di sisi mentalitas, kesadaran perempuan menerima stereotip tersebut, bahwa kedudukan perempuan memang sebatas manusia kelas dua yang boleh diobjekkan. Maka, tantangan kedua adalah apa yang diungkapkan oleh Danarto dalam Perempuan, Pasar Film dan Kekuasaan (1996) bahwa perempuan kita hanya bisa ditolong oleh masyarakat perempuan sendiri. Bahwa kejahatan kemanusiaan berupa pembendaan manusia harus menjadi tanggung jawab bersama baik laki-laki maupun perempuan, namun bagaimanapun juga perempuan harus bekerja keras untuk terus mengedukasi dirinya sendiri dan kaumnya. Pendidikan adalah alat paling efektif dalam rangka pemerolehan kesadaran atas diri dan realitas Pada akhirnya, semoga perempuan tetap menjadi empu, dan seksualitas yang membawa pesan awal kehidupan (eros) tak hanya dicap sebagai ekstase hasrat yang nirmakna.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Beberapa minggu lalu, saya mendapat telepon mengejutkan dari pos jaga di depan kantor. “Mbak, ada dua tamu yang mengunggu di depan”, kata Pak Mado, satpam KontraS. Lebih terkejut lagi saya, tatkala bertemu dengan kedua tamu tersebut. Rupanya mereka masih muda dan berasal dari dua lembaga berbeda, masing-masing dari Arus Pelangi dan Perempuan Mahardika. Bukan hal mengherankan jika saya terkejut. Biasanya tamu yang saya terima lebih banyak berusia senja. Maklum, saya berada di Divisi Pemantauan Impunitas. Divisi khusus di KontraS yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Salah satu tamu tersebut bertanya dengan malu-malu, “Mbak, tanggal 20 November mendatang kami akan memperingati Hari Transgender Internasional. Bolehkah kami menyelenggarakan puncak peringatannya di Aksi Kamisan?”. Tentu, saya yang memiliki ketertarikan lebih pada kajian gender dan perempuan sangat antusias menyambut usul tersebut. Alangkah menyenangkan jika Aksi Kamisan yang seringkali hanya digelar bersama lima sampai delapan korban berusia senja, akan kedatangan sekitar 50-60 orang kawan transgender dari beberapa provinsi di Indonesia. Sampai hari itu tiba, saya sangat bersemangat mempersiapkannya. Upaya kecil mengajak kawan-kawan jaringan untuk hadir pun saya coba lakukan. Entah itu lewat pemberitahuan singkat di berbagai grup pertemanan, atau sekadar membuat kultweet singkat tentang agenda di Aksi Kamisan ke-375 tersebut. Seperti Kamisan-Kamisan sebelumnya di era pemerintahan baru ini, saya bertugas menjadi editor surat Kamisan yang akan diserahkan ke Sekretariat Negara—yang semoga kemudian disampaikan pula kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Betapa sedih rasanya ketika membaca surat Kamisan yang dikirimkan oleh komunitas pendamping kawan-kawan transgender. Tertera di dalamnya narasi beberapa kasus kejahatan yang umumnya menimpa mereka, diantaranya adalah stigmatisasi, diskriminasi (termasuk dalam beberapa akses layanan publik), kekerasan verbal maupun non-verbal, penolakan dan pengusiran secara paksa atas dasar kebencian, hingga tindak penghilangan nyawa yang seringkali disertai dengan tindak penyiksaan. Transgender Day of Remembrance merupakan sebuah hari yang sengaja diperingati untuk mengenang mereka yang menjadi korban saat mengampanyekan anti-transgender di berbagai belahan dunia. Adapun peringatan tersebut pertama kali dilakukan untuk mengenang Rita Hester, seorang transgender yang dibunuh pada 28 November 1998 di Allston, Massachusetts, Amerika Serikat. Transgender sendiri—sebagaimana yang didefinisikan oleh beberapa komunitas transgender di Indonesia—merupakan sebuah terminologi payung yang mencakup transgender wanita (waria), transgender pria (priawan/transmen), serta varian-varian gender lainnya yang belum terkonfirmasi secara normatif. Tahun ini, momentum peringatan Hari Transgender di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai wujud kepedulian atas berbagai bentuk ketidakadilan terhadap transgender yang masih berlangsung hingga hari ini, tetapi juga sebagai desakan kepada pemerintahan baru untuk segera mengakui gender ketiga. Menjelang pukul 14:00 di tanggal 20 November lalu, kantor KontraS telah dipenuhi sekitar 40 kawan-kawan transgender. Mereka semua menggunakan kaos hitam dengan tulisan “Akui Gender Ketiga di Indonesia, Sekarang!” yang berwarna kuning. Terasa betul semangat mereka di hari itu. Beberapa bahkan sudah berdandan dan berfoto bersama di depan instalasi yang berdiri di halaman depan kantor—padahal aksi baru akan digelar pada pukul 16:00. Saya kembali mendatangi Lutfi, panitia dari Arus Pelangi yang saban hari mendatangi kantor. Saya hendak meminta beberapa perwakilan dari kawan-kawan transgender membaca kembali surat yang telah saya edit. “Ini kenapa kasus pengusiran di Tambora tahun 2013 sih yang dimasukin?”, protes Fin, selaku koordinator lapangan. “Masih banyak kasus lainnya yang lebih up-date. Kalau nggak salah awal tahun ini ada teman kita yang dibunuh deh di Taman Lawang”, lanjutnya. Akhirnya saya dan Fina mencari berita tersebut di internet. Kami memasukan beberapa kata kunci, seperti “waria+pembunuhan+Taman Lawang” atau “Maret 2014+ pembunuhan+waria”, dan lain sebagainya. Sungguh menyedihkan ketika yang kami dapati adalah berita bernada minor yang mencemoohkan transgender. Sebagian besar berita malah memuat judul yang terkesan “esek-esek” dan sangat merendahkan kelompok waria pada khususnya. Lama kami mencari. Akhirnya kami menemukan satu portal berita yang memuat pembunuhan waria pada awal tahun 2014 ini. Pun artikel tersebut tidak ditulis dengan nada simpati, seperti kebanyakan berita pembunuhan lainnya yang juga menyertakan keterangan visum korban atau pernyataan keluarga korban. “Duh, ini sudah hanya satu, bahasanya begini pula yaa..”, keluh Fani. Baru kali itu saya mendengar langsung keluh dari seorang waria terkait pemberitaan media tentang kawan-kawannya. Begitu banyak tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas seksual di Indonesia, namun hanya sedikit sekali yang diberitakan oleh media—apalagi dengan komposisi perspektif HAM atau gender yang proporsional, nyaris tidak ada. Menjelang pukul 15:00, kami dikejutkan dengan informasi adanya aksi perwakilan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Indonesia di depan Istana Negara yang menuntut dibatalkannya kenaikan BBM bersubsidi. Tentu bukan momentum ideal bagi kawan-kawan transgender menggelar aksi bersamaan dengan mereka. Faktor keamanan menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan. Alhasil saya pun bergegas pergi ke lokasi guna memantau dinamika aksi di sana. “Ayash, sepertinya tidak memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan acara deh”, jelas Widy—salah seorang staf Divisi Program dari Arus Pelangi, “Soalnya beberapa bulan lalu kita sempat diserang waktu buat acara di Depok dan Jakarta. Mereka yang menyerang kita ada diantara barisan mahasiswa itu, Yash!”. Saya tetap bersikukuh soal keamanan kawan-kawan, mengingat banyaknya aparat kepolisian yang akan berjaga di sekitar lokasi Aksi Kamisan. Saya percaya mahasiswa masih memiliki rasa toleransi antar sesama. Pendapat bodoh tersebut luruh seketika tatkala Lutfi menelepon saya. “Yash, maaf sekali kami tidak bisa melanjutkan aksi. Kawan-kawan di sini beberapa masih ada yang trauma. Mereka pernah digebuki ketika menggelar aksi di daerah masing-masing. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi kasihan mereka kalau dipaksakan. Kami langsung balik ke wisma ya, Yash. Tolong sampaikan terima kasih dan maaf kami kepada Ibu Sumarsih, serta korban-korban pelanggaran HAM lainnya yang telah memberikan izin”. Hari itu kami memang tetap menggelar Aksi Kamisan. Surat Kamisan ke-5 yang bertajuk “Akui Gender Ketiga: Peringatan Hari Mengenang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Transgender (International Transgender Day of Remembrance)” pun tetap kami sampaikan ke petugas Sekretariat Negara. Hari itu kami juga tetap menggelar refleksi dengan tema serupa. Kami juga tetap membagikan surat yang sama ke beberapa rekan media dan mahasiswa yang datang meliput. Semua sama, tapi tentu ada yang berbeda tanpa kehadiran kawan-kawan transgender di sana. Di ruang-ruang kelas, kita sering berbicara tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kita juga sering berbicara tentang keadilan dan kesetaraan. Tetapi, di ruang-ruang masyarakatlah kita akan melihat bagaimana seluruh konsep tersebut melebur dengan realitas. Hari itu juga, saya mendapat kabar menyedihkan dari seorang kawan. Aksi simpatik kawan-kawan transgender di Yogyakarta mendapat serangan dari beberapa oknum yang mengatasnamakan agama. Beberapa kawan di sana terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Fear of crime Guna melindungi kepentingannya, beberapa kelompok masyarakat menganggap komunitas LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer) sebagai sebuah kelompok kriminal. Mereka takut. Oleh karena itu bagi mereka keberadaan komunitas LGBTIQ pantas dimusnahkan sampai ke akar-akarnya agar tidak menjadi bahaya laten seperti komunis. Itulah sebabnya saya percaya, bahwa tabu terhadap persoalan seksualitas di Indonesia sama bermasalahnya dengan tabu fakta kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Di sisi lain, ketakutan yang sama juga terjadi pada komunitas LGBTIQ di Indonesia. Mereka merasa takut pada kelompok-kelompok ekstremis yang intoleran atau anti terhadap keberagaman. Meski tak sedikit pun kawan-kawan LGBTIQ menganggap gerombolan tersebut sebagai kriminal yang pantas dibumihanguskan. Adalah pesan untuk hidup berdampingan tanpa stigma, diskriminasi, kekerasan, dan ketakutan semacam itulah yang hendak komunitas ini sampaikan kepada publik. Saya masih percaya—betapa pun saya telah menyaksikan sendiri ketakutan kawan-kawan transgender di hari itu—bahwa suatu saat masyarakat Indonesia belajar saling menghargai. Dengan bijak menolak kekerasan dan merawat kebebasan. Entahlah. Setidak-tidaknya, jika menggunakan perspektif gender dirasa masih sangat sulit untuk diterima, mungkin kita dapat belajar menggunakan perspektif kemanusiaan dalam menyikapi perbedaan. Bukanlah, manusia diciptakan untuk tidak saling melukai sesama?  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Saya menapaki tahun ketiga di perguruan tinggi. Ada jokes yang cukup populer bagi mahasiswa tingkat akhir seperti saya, “Anda Memasuki Semester dimana pengen Nyerah dan Nikah” tak ayal, seminar tentang pernikahan marak sekali di kampus-kampus dan pesertanya tidak pernah sepi. Dan lebih uniknya lagi, peserta seminar bertema pernikahan tersebut kebanyakan adalah perempuan. seakan-akan menikah adalah solusi segala permasalahan perempuan. Hal ini tidak bisa ditepis begitu saja, perempuan dibesarkan dengan kisah-kisah seperti Putri Salju, Putri Duyung, Timun Mas, Bawang Merah Bawang Putih, Lutung Kasarung yang semua akhir ceritanya ditutup dengan kabahagiaan pernikahan. Seakan-akan menikah adalah sumber penyelesaian segala problematika kehidupan. Tidak heran, bagi banyak perempuan, pernikahan adalah sebuah cita-cita. Cinta adalah alasan paling besar bagi perempuan tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka putus sekolah perempuan karena menikah usia 7-12 tahun sebesar 27,78 persen (Data Statistik Pendidikan, cbs, 2006). Belum lagi anak-anak perempuan yang terpaksa putus sekolah karena hamil di usia sekolah. Lembaga pendidikan menganggap anak perempuan ini sudah rusak dan tidak layak bersekolah karena hamil sebelum waktu ideal. Beberapa perempuan yang lulus pendidikan hingga SMA tergerus lagi untuk mencari kerja saja dan kemudian menikah oleh rekan kerjanya yang lebih tua. Ataupun yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi hingga ke tingkat semester atas seperti saya ini, digoda lagi oleh bujukan cinta dengan iming-iming menikah. Sehingga hanya tersisa 2% perempuan yang berhasil menerima gelar doktor di seluruh dunia. Melalui esai ini saya mengimbau bagi perempuan muda untuk tidak buru-buru menikah atas nama cinta. Pertama karena tubuh dan rahim yang belum siap. Pada umumnya perempuan sudah mengalami menstruasi sejak usia 14 tahun kurang atau lebih. Tetapi belum tentu rahim sudah siap untuk dibuahi. Kematangan rahim berada di usia 20-35 tahun. Jika melahirkan dibawah usia yang dianjurkan, perempuan akan rentan mengalami kecemasan saat hamil, kesehatan menurun atau kelahiran bayi prematur. Kedua, jika perempuan memilih menikah dan membina rumah tangga di usia muda dan meninggalkan sekolah, perempuan akan memiliki ketergantungan finansial yang tinggi kepada kepala rumah tangga yang sesuai undang-undang perkawinan negara adalah suami atau laki-laki. Ketergantungan finansial membuat perempuan lebih mudah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena perempuan akan sulit lepas dari sang suami dan menganggap adegan demi adegan kekerasan sebagai bumbu rumah tangga. Lalu, menikah di usia muda akan melenyapkan kesempatan-kesempatan mencoba hal-hal baru. Karena ketika menikah berarti kita berkomitmen terhadap pasangan hidup kita dan pastinya dilanjutkan membina keluarga. Sering identitas perempuan melebur dan kesempatan mencoba hal-hal baru akan berganti menjadi mengurus anak dan suami. Perempuan tidak memilih kesempatan untuk mendaki Himalaya, belajar diving, makan masakan Afrika, keliling dunia dan lain-lain. Kehidupan permpuan akan terpusat dalam urusan keluarga dan itu saja. Terakhir, perempuan yang orientasinya sudah terlanjur terpusat pada anak dan keluarga akan melewatkan kontribusinya untuk membangun bangsa dengan cara lain selain berreproduksi. Seringkali hamil dan melahirkan menjadi alasan bagi perempuan berkontribusi dan berkarya dengan menjadi mesin penghasil anak. Padahal ada banyak cara mengabdi pada negara kita selain beranak. Kita bisa menulis, membuat film, mengajar ke daerah pedalaman, menjadi aktivis politik, menyebarkan dan mewujudkan ide-ide dalam membangun sumber daya manusia yang adil dan beradab, mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan terbesar bagi perempuan dari godaan nikah adalah lingkungan yang menganggap hidup adalah arena balapan. Mereka saling kejar-mengejar siapa yang lulus duluan, nikah duluan, hamil duluan, anaknya lulus duluan, dan seterusnya. Terkadang, kita larut dalam balapan tanpa menikmati esensi hidup. 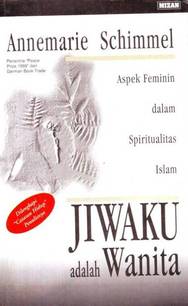 Sumber: http://toko-bukubekas.blogspot.com/2013/09/jual-buku-jiwaku-adalah-wanita.html Sumber: http://toko-bukubekas.blogspot.com/2013/09/jual-buku-jiwaku-adalah-wanita.html Alquran berbicara tentang para wanita yang saleh dan beriman, mu’minat, muslimat, dan bahkan menyebut-nyebut mereka dengan nada yang sama dengan para pria yang saleh dan beriman. Hanya ada satu tokoh wanita negatif dalam Alquran yaitu istri Abu Lahab QS:111. Kedudukan wanita dalam Alquran merupakan suatu peningkatan nyata dari keadaan di Arabia pra-Islam. Kaum wanita kini dapat mempertahankan dan membuat keputusan sendiri mengenai kekayaan yang mereka bawa serta atau yang mereka kumpulkan selama perkawinan mereka dan kini pun diizinkan, untuk pertama kalinya menerima warisan. Kadang-kadang izin yang ditetapkan QS 4:3 tentang poligami sering ditafsirkan salah. Aturan Alquran bahwa para wanita itu harus mendapatkan perlakuan yang adil telah mendorong banyak tokoh modernis untuk mendalilkan monogami sebagai bentuk ideal. Izin untuk menghukum istri yang membangkang diredakan oleh hadis nabi “Yang paling baik di antara kalian adalah yang memperlakukan istrinya dengan cara yang paling baik pula”. QS 2:187 “Kaum wanita itu adalah pakaian bagimu sebagaimana kamu adalah pakaian bagi mereka”. Pakaian merupakan alter ego-nya, yaitu objek yang paling erat terkait dengan kepribadiannya. Alquran hanya menyebutkan satu orang wanita dengan namanya yang sesungguhnya. Dialah Maryam, perawan yang menjadi ibu Isa. Hadis menyebutkan, “Dialah yang pertama-tama akan masuk surga. Untuk dialah pohon kurma yang kering menjatuhkan buah-buahannya ketika dia berpegang padanya saat merasakan kesakitan menjelang melahirkan, dan anaknya yang baru lahir menjadi saksi atas kesuciannya” QS 19:24, 30-33. Dialah jiwa pendiam dan rendah hati. Wanita yang pertama, Hawa. Dalam tradisi disebutkan tercipta dari tulang rusuk Adam. Goethe penyair terbesar dari Jerman mereproduksi syairnya dari hadis ini menasihatkan pria agar memperlakukan wanita dengan ramah dan sabar. Karena Tuhan mengambil tulang rusuk yang bengkok untuk menciptakannya, bentuk yang dihasilkan tidak bisa lurus sepenuhnya. Maka jika pria berusaha untuk menekuknya dia akan patah, dan jika dia membiarkannya tanpa diganggu, dia akan semakin bengkok. Perlakukanlah wanita dengan sabar dan hati-hati sebab tak seorang pun menginginkan tulang rusuk yang patah. Tak pernah sekali pun disebutkan dalam Alquran bahwa Hawa bertanggung jawab atas terusirnya mereka dari surga, dan dengan demikian membebaninya dengan tuduhan membawa dosa asal ke dalam dunia. Sesungguhnya Islam bahkan tak mengenal gagasan mengenai dosa asal. Hawa memang memainkan peranan penting. Kecantikannya digambarkan dalam warna-warna yang penuh cahaya, “Dia sama besar dan sama eloknya dengan Adam, punya 700 jalinan di rambutnya, dihiasi dengan chrysolite dan wangi kesturi. Kulitnya lebih lembut daripada Adam dan lebih indah warnanya, dan suaranya lebih merdu daripada suara Adam”. Juga diceritakan dalam tradisi bahwa Tuhan berfirman kepada Adam, “Belas kasih-Ku telah Kucurahkan seluruhnya untukmu dan hamba-Ku, Hawa dan tidak ada rahmat lain, wahai Adam, yang lebih besar daripada seorang istri yang takwa”. Legenda-legenda yang menggambarkan bersatunya pria pertama dengan wanita pertama itu mengemukakan seluruh perincian yang membuat perkawinan duniawi tersebut begitu meriah. Sebagian legenda bahkan menceritakan bahwa para malaikat menaburkan koin-koin surgawi ke atas kepala pasangan pengantin itu. Tapi begitu mereka terjerat godaan dari ular kecil yang memasuki taman dengan bersembunyi di dalam paruh burung merak, begitu mereka makan buah terlarang, pakaian mereka lepas. Cerita-cerita tradisional biasanya memanfaatkan bagian ini untuk menekankan kesembronoan Hawa. Gambaran-gambaran dramatis mengungkapkan bagaimana Hawa bertanya kepada Tuhan di mana dia membuat kesalahan dan hukuman apa yang akan diterimanya, dan Tuhan menjawab, “Aku akan mengurangi kemampuanmu dalam bidang pemikiran dan agama, dan juga untuk menjadi saksi dan menerima warisan.” Kata-kata ini diambil dari Alquran yang menyatakan bahwa dua orang wanita dibutuhkan untuk menjadi saksi sebagai pengganti satu orang pria QS 2:282 dan anak perempuan menerima warisan lebih sedikit daripada anak laki-laki QS 4:11. Dengan cara yang sama, hukuman ilahi selanjutnya “Memenjarakanmu seumur hidupmu” dikembangkan dari suatu pemahaman khas mengenai pingitan. Hawa juga diberi tahu bahwa tidak akan ada wanita yang ikut serta di dalam salat Jumat. Dia juga tidak diperbolehkan untuk menyalami siapapun. Hukumannya adalah menstruasi dan kehamilan dan seorang wanita tidak akan pernah menjadi nabi atau orang bijak. Semua ini hanya untuk menunjukkan betapa banyaknya asumsi-asumsi yang tersebar luas tanpa didasarkan pada kata-kata dalam Alquran melainkan pada tafsir-tafsir imanjinatif. Hawa bertobat atas pelanggaran yang dilakukannya dan diampuni. Tapi Adam dan Hawa dipisahkan setelah mereka diusir dari surga, dan legenda menyebutkan bahwa mereka bertemu lagi bertahun-tahun kemudian di pinggir kota Makkah. Jibril mengajarkan kepada Adam urutan-urutan ibadah haji ketika dia sedang beristirahat di bukit Safa dan Hawa di bukit Marwah, dan mereka mengenali satu sama lainnya ta’arafah di Padang Arafat. Istri kedua Ibrahim, Hajar. Berlari bolak balik antara Marwah dan Safa tujuh kali mencari air untuk Ismail dan pada perjalanan ke tujuh keluarlah mata air Zamzam. Tokoh lain dalam tradisi rakyat adalah putri Nimrud. Raja yang memerintahkan agar Ibrahim di bakar. Cerita ini mengisahkan bahwa gadis ini , terdorong oleh keyakinan Ibrahim, melemparkan dirinya ke dalam kobaran api dan seperti Ibrahim juga tetapi terlindung dari bara api. Istri Fir’aun, Asiyah wanita beriman yang menyelamatkan bayi Musa. Dengan cara inilah dia menemukan tempatnya di surga. Kecantikannya sebanding dengan Maryam, Khadijah dan Fatimah melampaui keelokan semua perawan di surga. Ratu Saba yang dikenal sebagai Bilqis QS 27 adalah penyembah matahari yang menantang Sulaiman dengan tiga tebakan. Wanita itu telah tertipu oleh pantulan dari lantai kaca di istana Sulaiman (mengira bahwa dia sedang berjalan melewati air) sehingga dia menaikkan gaunnya, dan memamerkan kedua kakinya QS 27:43. Sulaiman menjadi tahu bahwa Bilqis putri jin dan seorang manusia biasa mempunyai tubuh manusia normal. Ibn ‘Arabi menyebut kebijaksanaan Ilahi sebagai “Bilqis”, sebab wanita itu adalah anak teori yang halus dan anak praksis yang kasar, sebagaimana Bilqis yang sekaligus makhluk halus dan wanita biasa sebab ayahnya adalah jin dan ibunya seorang manusia biasa. Bagi Jami, Bilqis adalah seorang ratu yang bijaksana, yang pandangannya berimbang mengenai wanita yang baik dan yang jahat dan kritik lembut. Rumi menceritakan bagaimana Bilqis mengirimkan emas kepada Sulaiman dan bagaimana raja itu mengirimkan kembali pasukan sang ratu kepadanya. Bilqis lalu melakukan perjalanan panjang, dan selama perjalanan itu dia memisahkan dirinya semakin lama semakin jauh dari dunia, hingga seluruh kepribadiannya berubah menjadi kepribadian sang kekasih. Bilqis mengingatkan kita pada Zulaikha, istri Potiphar dalam Perjanjian Lama. Dalam tradisi Islam, Zulaikha berubah menjadi seorang wanita yang terobsesi oleh cinta dan mau melakukan apa saja untuk mendapatkan kekasihnya Yusuf. Ketampanan Yusuf membuat banyak perempuan terpesona sehingga secara tidak sadar memotong jari-jari mereka sendiri yang sedang mengupas jeruk. Zulaikha melakukan apa pun yang dapat dipikirkannya untuk merayu Yusuf. Dia memerintahkan istananya dihiasi dengan gambar-gambar yang membangkitkan nafsu sehingga Yusuf akan membayangkan dirinya bersama Zulaikha tenggelam dalam kenikmatan cinta ke mana pun pandangan matanya tertuju. Yang menarik dari adegan rayuan ini adalah sikap Zulaikha terhadap berhala yang disimpannya di kamarnya. Semua manusia harus belajar dari Zulaikha bagaimana menaati sopan santun ketika memikirkan objek pujaannya dan dia menutupi wajah berhalanya agar tidak menyaksikan hal yang tidak sopan. Yusuf bin Husain Ar-Razi (w. 916) mempunyai pendapat yang lebih mendalam, “Ketika dia menyingkirkan nafsunya, Tuhan mengembalikan kecantikan dan usia mudanya. Sudah menjadi hukum alam bahwa ketika sang pria maju, wanitanya diam menunggu. Jika sang pria sudah puas dengan cinta saja, maka wanitanya mendekat”. Zulaikha menjadi wanita-jiwa yang menjalani kehidupan dalam pertobatan yang berat dan kerinduan yang tak ada akhirnya. Cinta telah merobek Zulaikha dari selubung kesucian. Zulaikha menjadi lambang bagi semua orang yang merasakan penderitaan cinta dan kerinduan yang tak terbalas. Maka dia menjadi pahlawan wanita yang berani dan kuat, yang rela menahan apa saja demi Kekasihnya. Orang-orang selalu melihat pakaian Yusuf yang tersobek, tapi siapa yang melihat hati Zulaikha yang terluka dan patah? Para penyair menggambarkan Zulaikha yang sebelumnya sangat cantik, beranjak tua dalam kesengsaraan dan duduk dengan putus asa di sisi jalan, dengan harapan dapat menatap Yusuf sekilas saja. Seperti Ya’qub, Zulaikha pun menjadi buta karena terus-menerus meratap dan merindukan bau selintas saja kehadiran Yusuf. Hanya pikiran mengenai Yusuf yang membuatnya tetap hidup; dia hanya memikirkan namanya sebagaimana jiwa mestinya terus memikirkan Kekasih Ilahi. Ibn Arabi menceritakan bahwa Zulaikha pernah terluka oleh sebatang anak panah. Ketika darahnya menetes ke atas tanah, darah itu membentuk nama ‘Yusuf, Yusuf’ di mana pun ia jatuh; karena dia terus-menerus menyebutkan namanya, maka nama itu mengalir bagaikan darah di dalam urat nadinya. Setelah mengalami kerinduan dan keputusasaan, kesetiaan Zulaikha yang tak tergoyahkan akhirnya mendapatkan imbalan. “Ketika siksaan dan jiwamu lebih rendah dan kelemahan tubuhmu telah menjadikanmu tua dan membusuk, segarkanlah kembali jiwamu seperti Zulaikha dengan merindukan Sahabatmu”. Zulaikha yang penuh cinta akhirnya menjadi personifikasi jiwa manusia, nasf. Bau dari kemeja Yusuf menyentuh perasaannya dan mengungkapkan ketampanannya, sebab bau, nafas dari Yang Maha Pemurah, membawa kabar dari sang kekasih dan kedekatan dari sang kekasih menyegarkan kembali wanita yang melayu karena kesedihan. Zulaikha yang pernah ditunangkan dengan suami yang impoten, masih tetap perawan, dan kini Yusuf yang penuh cinta merobek kesucian lapisan pengantinnya sebagaimana dulu wanita itu merobek kemejanya. __________ * Ikhtisar salah satu bab dari buku karya Annemarie Schimmel, Jiwaku adalah Wanita: Aspek Feminin dalam Spritualitas Islam, yang diterbitkan oleh Mizan tahun 1998. Buku ini diterjemahkan dari bahasa Inggris dengan judul Meine Seele ist eine Frau: Das Weibliche im Islam, terbitan Kosel tahun 1995  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Perempuan abad 21 adalah perempuan bebas, merdeka. Stereotip 3M alias Masak, Macak, Manak adalah olok-olok masa lampau yang tak berlaku di zaman penuh gemerlap modernitas. Perempuan sudah begitu jauh melampaui dan menembus tapal sekat domestik hingga di jalanan dan di media cetak maupun elektronik penuh dengan citra perempuan, sebuah citra paradoks yang sayangnya terbatas pada obsesi imajinasi iklan. Citra perempuan adalah citra kecantikan yang diwakili oleh tubuh langsing, kulit putih mulus, serta rambut hitam lurus. Perempuan dalam obsesi iklan hanyalah salah satu contoh bagaimana kapitalisme menjadikan manusia tak lebih dari sekadar objek-objek tanpa entitas ruh, akal serta imajinasi. Kita akan menengok para perempuan heroik, nun jauh di Kabupaten Rembang, tepatnya di jalur Pegunungan Kendeng. Hampir enam bulan kaum perempuan melakukan aksi menentang pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia (Tbk) yang mereka anggap akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan alam tempat mereka tinggal. Aksi dipimpin oleh Yu Sukinah bersama 88 Ibu lainnya dimana tercatat 7 orang diantaranya hamil (Candraningrum dalam Seminar Ekofeminisme di Jurusan Sosiologi FISIP UNS, 2014). Mereka teguh tinggal di tenda-tenda, menyuarakan kehendak menolak industrialisasi di kawasan karst jalur Pegunungan Kendeng. Mereka lantang berteriak agar para komprador kapitalis tidak merampas hak hidup mereka, sebab alam bagi mereka adalah kehidupan. Pegunungan Kendeng adalah Ibu yang memberikan limpahan air kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Pati, Rembang dan Blora. Kapitalisme merongrong perempuan. Perempuan bergerak melawan kapitalisme. Buku berjudul Ekofeminisme II, Narasi Iman, Mitos, Air & Tanah (Jalasutra,2013) menarasikan berbagai upaya industri dalam mengapitalisasi perempuan dalam berbagai wajah mengerikan. Perempuan di satu sisi menjadi alam yang tinggi dan luhur seperti tergambar dalam idiom ibu pertiwi, gunung, laut. Di sisi lain, perempuan berdasar mitos-mitos dalam masyarakat juga sering disamakan dengan konotasi negatif, yaitu dengan tanah (lahan garapan), bunga, ayam, malam dan bulan. Narasi perempuan yang bekerja juga menyisakan ironi dalam industri-industri rumahan. Perempuan bekerja membatik di rumah (home workers), industri memanipulasi rumah yang berubah menjadi industri (secara fisik maupun ruh) dengan sistem POS (Putting Out System). Relasi produksi informal memanfaatkan perempuan dan ruang domestik perempuan sebagai arena produksi batik dengan upah yang sangat rendah atas nama efisiensi biaya. Pandangan bahwa perempuan bekerja hanyalah sebagai tambahan (daripada menganggur saja tanpa produktivitas) mengesahkan pemberian upah rendah pada perempuan. Akibatnya, jamak kita lihat pabrik-pabrik hari ini lebih senang mempekerjakan perempuan sebagai buruh, daripada laki-laki. Melalui POS, industri tidak perlu menyediakan tempat, peralatan kerja, fasilitas kerja dan pendukungnya seperti air, listrik, peralatan batik, dan lainnya (Hunga, 2013:189). POS adalah juga gabungan wajah penindasan kembar antara patriarki dan kapitalisme ketika industri tidak menyediakan jaminan biaya bagi pekerja seperti makan, transpor, kesehatan, dan kecelakaan. Inilah manipulasi ruang domestik yang mewujudkan cita-cita besar kapitalisme, yakni minimalisasi cost production yang berasal dari tenaga manusia untuk menghasilkan jumlah produksi sebesar-besarnya. Skema industri rumahan menghasilkan efek yang tak sesuai dengan keuntungan berupa upah tambahan, yakni kerusakan ekologis yang serius dan mengancam. Setiap tahunnya, industri batik memproduksi kadar emisi CO2 tertinggi di antara sektor UKM lainnya, yang umumnya merupakan hasil dari ketergantungan akan bahan bakar (minyak tanah) dan penggunaan listrik yang tinggi. Sejumlah besar UKM batik juga masih menggunakan lilin, pewarna kimia serta pemutih secara berlebihan yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat (Hunga,2004; Clean Batik Initiative, The German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce-EKONID, 2011). Industri rumahan dengan pola POS membuka peluang kerusakan ekologis skala rumah tangga dan perkampungan tanpa mendapat jaminan rehabilitasi lingkungan dari Pemerintah maupun industri. Gerakan Ekofeminisme Perspektif ekofeminisme mempromosikan strategi perlindungan relasi perempuan dan hak-haknya terkait alam dan lingkungan. Identitas ekologis penting untuk dibangun melalui agenda-agenda politik yang membentuk kesadaran dan perilaku perempuan terhadap lingkungan. Ekofeminisme membongkar ihwal keterkaitan manusia dengan alam yang tidak terkait gender. Perempuan Indonesia jamak memiliki kearifan khas perempuan mengenai bagaimana mengelola sumber daya lokal. Perempuan Indonesia mempunyai pengetahuan yang mendalam dan sistematis mengenai proses-proses alam serta meyakini bahwa keyakinan alam harus selalu dipulihkan. Narasi restrukturisasi ekonomi global yang mengapitalisasi perempuan dan alam harus dilawan, bukan dengan culture based tapi nature based. Antroposentrisme yang menjadikan manusia sebagai pusat wacana membuat kehendak akan kebenaran mengesampingkan kehendak akan kehidupan. Kehendak akan kebenaran modernitas dan globalitas mengesahkan mesin-mesin menggantikan hubungan intim manusia dengan alam. Kita telah semakin jauh dengan paparan Rozsak (1992) dalam Candraningrum (2014) yakni,”Ecopsychology seeks to heal the more fundamental alienation between the person and the natural environment.” Manusia telah mengalienasikan diri dari alam. Upaya penyatuan manusia dengan alam yang biasa termanifestasi dalam berbagai upacara, syukuran dan perjamuan tradisional adalah takhayul dalam narasi modernitas. Andi Misbahul Pratiwi (Mahasiswi Teknik Informatika Universitas Gunadarma dan Ketua Umum LISUMA) [email protected]  Sumber: http://puisina.blogspot.com/2014/04/puisi-drupadi-menggugat-edisi-arjuna.html Sumber: http://puisina.blogspot.com/2014/04/puisi-drupadi-menggugat-edisi-arjuna.html Banyak dari kita mengenal kisah Mahabharata dari cerita nenek moyang sampai dengan serial televisi. Kisah tentang kelima pandawa yang tersohor di kerajaan hastinapura, tentang pecahnya perang Bharatayudha, tentang para kurawa yang selalu menyimpan dendam, dan tentang perempuan-perempuan tangguh yang berpengaruh dalam masyarakat patriarki. Semenjak epik terpanjang dari india ini difilmkan di televisi semua kalangan usia ikut meraba-raba alur kisahnya. Mahakarya ini sungguh menyajikan sebuah pesan kehidupan. Bagaimana sebuah kemenangan dan kekalahan tidak berarti apapun ketika dendam masih terpelihara mengalahkan nila-nilai kehidupan yang apik. Sebuah kisah yang diawali dengan ratapan kesedihan sang raja, Drestarastra, serta diakhiri dengan kedamaian luar biasa yang dicapai dari pertarungan harga diri, pergulatan emosi dan pematangan berpikir para pelakunya. Sang Arjuna pun menjadi idola kaum hawa. Dengan wajah yang rupawan dan mengambil peran seorang bijaksana, Arjuna pun menghipnotis dunia, saya sebagai seorang awam ikut terbawa menikmati alur kisah ini bersama sang Arjuna. Memanjakan mata saya mengikuti setiap episodenya dan belajar bahwa ternyata ada perempuan hebat di belakang, di samping dan di depan sang Arjuna. Seorang perempuan yang ruangnya terbatasi oleh kultur patriarki. Siapakah dia? Seperti apa rupanya? Sejauh mana pemikirannya? Perempuan itu bernama Drupadi, anak perempuan yang dipertaruhkan ayahnya, Abiyasa, karena rupanya yang elok. Pelelangan tubuh itupun dimenangkan oleh Arjuna. Tubuh Drupadi tidak mendapat eksistensinya pada saat itu, dia tidak dapat memilih untuk tidak dipertaruhkan, karena dia merasa ayahnya adalah penanggung jawab atas dirinya. Seperti teori tentang manusia yang dikemukakan oleh Sartre seorang filsuf eksistensialis bahwa filsafat eksistensialisme mengenai “Ada” terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu, (1) Being in it self (tidak berkesadaran, objek), (2) Being for it self (sadar, subjek), (3) Being for others (sadar, hubungan antara subjek, hubungan sosial). Dari klasifikasi tersebut maka Sartre berusaha mendefinisikan eksistensi manusia, keberadaan manusia, kehadiran manusia sebagai suatu yang disebut “Ada”. Manusia adalah sebagai subjek, berarti manusia ada dalam kategori kedua (being for it self), kemudian bagaimana manusia itu bisa dikatakan sebagai subjek? Sarte mengatakan bahwa untuk menjadi subjek manusia harus bebas, harus memilih, harus bertanggung jawab. Manusia itu harus memiliki eksistensi yang berarti dapat menentukan hidupnya, bukan esensi yang hanya ditentukan pilihannya. Manusia adalah arsitek bagi hidup mereka sendiri. Bertolak dari teori Sarte mengenai eksistensialisme, maka jika Drupadi tidak dapat menolak untuk dipertaruhkan, ketika dia tidak dapat mengontrol kepemilikan tubuhnya, ketika dia tidak bisa mandiri dalam memilih dan bertanggung jawab, maka bisa dikatakan pada memoar itu Drupadi ditempatkan sebagai objek, sebagai benda, sebagai properti kepemilikan ayahnya, sebagai budak patriarki. Arjuna memenangkan Drupadi dalam sebuah arena pertarungan dan menjadikannya istri yang sah, kemudian membawa Drupadi ke istana Hastinapura. Arogansi relasi kuasa Arjuna untuk memenangkan Drupadi dan ketidakberdayaan gadis cantik pada saat itu membawa Drupadi menjadi seorang istri dari lima laki-laki anak raja yaitu Pandawa (Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa). Sebagai seorang perempuan yang bisa dikatakan poliandri, Drupadi harus melayani kebutuhan seksual suami-suaminya di kerajaan Hastinapura, dalam epik ini diceritakan bahwa setelah Drupadi melayani suaminya maka dia akan bersuci pada sebuah api kudus. Kita tahu bahwa cerita mengenai Mahabharata tentunya sangat erat kaitannya dengan perselisihan antara kurawa dan pandawa. Pada salah satu memoar wiracarita ini, kurawa menantang Yudhistira untuk bermain dadu, singkat cerita dengan latar belakang Yudhistira yang tidak terlalu mahir bermain dadu, kalahlah sang pangeran bijak ini dengan kurawa. Pada babak pertama harta benda sudah dipertaruhkan, pada babak kedua permainan dadu inipun Yudhistira kalah dan harus mempertaruhkan harga dirinya dan saudara-saudaranya, namun Yudhistira tetap melanjutkan permainan dan akhirnya dengan terpaksa mempertaruhkan Drupadi, untuk kedua kalinya Drupadi dijadikan bahan taruhan. Harta kekayaan Yudhistira pun sudah diserahkan kepada kurawa sehingga dia jatuh miskin, kemudian pada hari itu juga kurawa menyeret Drupadi ke istana Kuru dan memberitahukan bahwa ia telah dimenangkan oleh para kurawa dalam permainan dadu melawan Yudhistira (suaminya). Pada kegetiran perasaan Drupadi itu, Bisma berkata kepada kurawa bahwa, orang yang tidak memiliki kekayaan tidak bisa mempertaruhkan milik orang lain, tapi di sisi lain, Bisma menyimpulkan seorang istri harus selalu berada dibawah perintah dan kebijaksanaan suami. Namun bagaimana mungkin seorang suami mempertaruhkan istrinya kepada para penjahat, sungguh situasi ini menjelaskan betapa besar tembok patriarki. Bahkan kurawa mengatakan bahwa Drupadi adalah seorang perempuan yang bersuami lima, maka dia pantas untuk ditelanjangi di hadapan majelis kuru. Dengan rambut yang acak-acakan dan pakaian yang hampir lepas karena diseret oleh Dursasana, Drupadi termakan amarah. Tidak gentar Drupadi menjawab dengan berani bahwa raja Yudhistira telah diundang untuk bermain dadu dalam perjamuan ini, meskipun mereka tahu bahwa Yudhistira tidak punya keterampilan bermain dadu, dan Yudhistira telah dijebak untuk melawan penjudi jahat. “Bagaimana bisa kemudian dikatakan Yudhistira telah mempertaruhkan sesuatu dengan sukarela”, dengan tegas Drupadi melontarkan pertanyaan itu didepan majelis istana Kuru. Drupadi menegaskan bahwa ia adalah menantu Kurawa, ia adalah istri yang sah raja Yudhistira dan tindakan mereka hanya membuat Kurawa itu kehilangan harga diri. Kembali Drupadi menegaskan, ia masih ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaannya: apakah Drupadi dianggap dimenangkan atau tidak? Tidak ada satupun majelis kuru yang menjawab pertanyaan Drupadi. Singkat cerita majelis Kuru melepaskan Drupadi dari perbudakannya akibat pertaruhan. Sepenggal kisah yang saya deskripsikan diatas, dapat kita ketahui bahwa dalam sebuah epik Mahabharata ada sosok perempuan tangguh yang mempertahankan harga dirinya, yang saya sangat kagumi adalah keberaniannya untuk membela dirinya bahkan suaminya yang telah mempertaruhkan dirinya, tanpa menyulut api peperangan. Dengan demikian Drupadi telah menunjukkan eksistensinya sebagai seorang manusia, seorang perempuan yang berhak dan bertanggung jawab atas tubuh dan pilihannya. Kekuatan dan keberanian Drupadi menguatkan statusnya sebagai tokoh perempuan mandiri yang layak dipuja. Masyarakat India seantero negeri mengaitkan Drupadi dengan pemujaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di India Selatan, kultus Drupadi sangat kuat. Mereka memiliki kuil yang dipersembahkan untuk Drupadi dan ia dipuja sebagai dewi. Terlepas dari kisah bahwa ia memiliki lima suami, di India Selatan Drupadi disembah sebagai dewi yang perawan, yang memurnikan penyembahannya dari dosa dan membawa keselamatan. Pusat kultus Drupadi dikenal sebagai Gingee di Arcot Selatan, Tamil Nadu, India. Gingee diakui sebagai kuil utama sang dewi dan seringkali kuil-kuil baru menggunakan batu Gingee atau tanah Gingee untuk mengukuhkan citra sebagai kuil Drupadi. Pemujaan terhadap Drupadi juga tersebar diseluruh Tamil Nadu dan sekitarnya, bahkan hingga ke tempat-tempat yang jauh seperti Sri Lanka, Singapura, Fiji, dan Pulau Reunion[1]. Catatan Belakang: [1] Sharma, Kavita A. Terj. Perempuan-Perempuan Mahabharata. Jakarta: Gramedia, 2013. Terj. The Queens of Mahabharata, 2006.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Jokowi mengangkat delapan menteri perempuan dalam Kabinetnya, artinya terjadi kenaikan kuota perempuan hingga 100% dibanding pemerintah sebelumnya dalam kamar eksekutif, ini bisa dikatakan prestasi. Tetapi prestasi tidak hanya soal kuota. Susi Pudjiastuti yang akhir-akhir ini menjadi media darling, menyedot perhatian publik dan sukses menjadi simbolisasi citra baru perempuan. Seperti yang lama diperjuangkan gerakan feminis konstruktivis, sosok Ibu Menteri Perikanan dan Kelautan ini berhasil mengubrak-abrik citra perempuan baik-baik yang standarnya sangat patriarkis. Perempuan pemilik maskapai penerbangan Susi Air ini menunjukkan bahwa perempuan mampu dilihat dari kapabilitasnya dalam bekerja dan berkarya. Perempuan yang baik tidak harus mementingkan percintaan dan mengutamakan memiliki pasangan yang baik dibandingkan pekerjaan yang baik seperti yang selalu disebutkan dalam majalah dan tabloid wanita. Terlebih, media sosial menyebarkan gambar dalam bentuk meme akhir-akhir ini perihal Susi yang bertato, merokok, dan mempunyai suami pilot WNA disandingkan dengan Ratu Atut yag dianggap memiliki seluruh standar perempuan baik-baik tetapi tersandung kasus korupsi. Jokowi melakukan langkah yang tepat dalam melihat perempuan dari kemampuannya bukan dari kulitnya, penampilannya, dan pendampingnya. Lihat saja bagaimana sejarah “kelupaan” mencatat kehebatan kepemimpinan Cleopatra dan hanya memosisikan Cleopatra dalam seksualitasnya bersama pria-pria, Mark Antony dan Julius Caesar atau sejarah tidak memberikan perhatian pada kehebatan Elizabeth II dalam memimpin Inggris. Masyarakat terjebak pada citra perempuan yang merupakan tulang rusuk, pelengkap dan selalu saja perempuan tidak dilihat sebagai subjek. Secara simbolik pula, pada hari pelantikan Kabinet, Jokowi mendobrak kebiasaan memakai kebaya dan rok bagi perempuan. Pada pelantikan kabinet, kita bisa melihat para menteri perempuan yang dilantik menggunakan batik dan celana! Susi sebagai satu-satunya yang menggunakan Kebaya dan kain justru disorot, padahal hanya ia satu-satunya yang mengikuti rules berpakaian yang selama bertahun-tahun diterapkan istana ketika acara resmi pelantikan. Tampaknya pemerintahan Jokowi serius dalam mendukung kesetaraan gender. Hal ini dikonfirmasi pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan perkataan, “Menteri perempuan dan laki-laki sama saja, kita lihat dari hasil kerjanya”. Tampaknya, kita bisa berharap bahwa perempuan pada akhirnya bisa diperlakukan sebagai manusia bukan lagi sekadar pelengkap dimulai dari pemerintahan Kabinet Kerja, kini.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Dua tahun lalu saya mencoba hal baru dengan bergabung pada klub olahraga setingkat Universitas. Saya bergabung di Unit Selam Universitas Gadjah Mada, melakukan kegiatan penyelaman yang termasuk dalam olahraga paling ekstrem. Olahraga ekstrem dapat dipahami dengan kegiatan yang bisa memacu adrenalin, olahraga ini biasanya fokus pada menaklukkan rasa takut diri sendiri dan menghadapi tantangan alam. Olahraga ekstrem juga memerlukan pendidikan dan keterampilan khusus, bahkan beberapa diantaranya perlu lisensi. Dua tahun bergabung di klub selam membuat saya betah dengan kehidupan organisasi dan kegiatan lapangan bersama banyak teman laki-laki. Bila ditanya mengapa laki-laki? Karena jumlah anggota perempuan dalam klub selam saya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Saya tidak begitu bermasalah dengan banyaknya laki-laki dalam berkegiatan di organisasi. Namun setiap penerimaan anggota baru, klub selam sedikit kesulitan mendapatkan calon anggota perempuan. Hal semacam ini tidak terjadi hanya pada klub selam, namun juga klub olahraga ekstrem lainnya, misalnya klub pecinta alam setingkat universitas. Dari obrolan dengan ketua klub pecinta alam MAPAGAMA (Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Gadjah Mada), dari jumlah keseluruhan anggota selama tiga tahun terakhir 2011-2013 yaitu 59 orang, hanya terdapat 11 perempuan. Berawal dari situ, saya kemudian mencari tahu mengapa perempuan, khususnya di universitas saya enggan untuk bergabung di klub olahraga ekstrem. Saya memulai obrolan santai dengan teman yang tidak bergabung pada klub olahraga ekstrem. Salah satu teman laki-laki saya mengatakan sudah biasa bagi laki-laki melakukan olahraga ekstrem, karena kondisi fisiknya bisa dibilang lebih kuat dari perempuan. Menurutnya juga, mayoritas perempuan memang tidak lebih kuat secara fisik dari laki-laki, namun karena ingin menyalurkan hobi, sebagian dari mereka tetap memilih bergabung dengan klub olahraga ekstrem. Anggapan sebagian orang mengenai pembedaan laki-laki dan perempuan perihal kekuatan fisik juga dibenarkan oleh berbagai penelitian ilmiah yang sering saya dengar. Saya teringat pada sebuah diskusi kecil dalam mata kuliah kritik budaya yang saya ambil beberapa waktu lalu. Dalam grup kecil kami berdiskusi mengenai perempuan yang jarang atau tidak dilibatkan dalam “menulis” sejarah. Seorang teman berpendapat, penelitian mengenai perempuan yang mengedepankan emosi ketimbang logika, akan membuat sebuah pengetahuan tidak objektif. Saya mulai merasa tidak nyaman dengan pembenaran yang didasarkan atas penelitian-penelitian ilmiah dengan memojokkan perempuan. Terkadang saya juga mempertanyakan, mungkin saja penelitian itu sengaja dilakukan untuk membuat kita semua terus berpikir bahwa perempuan tidak lebih kuat dari laki-laki, lemah, sehingga tidak layak bekerja berat atau melakukan olahraga ekstrem. Sebagai perempuan, kami hanya pantas dan anggun ketika kami di dapur. Berbeda lagi dengan teman perempuan saya yang juga memilih untuk tidak bergabung dengan klub olahraga ekstrem. Dia mengungkapkan dua alasan yang membuat jumlah perempuan lebih sedikit ketimbang laki-laki dalam klub olahraga ekstrem. Yang pertama yaitu sulitnya izin dari orangtua, serta olahraga ekstrem yang dianggap sebagai kebutuhan laki-laki. Dalam anggapan di masyarakat misalnya, laki-laki dianggap lebih menarik bila mempunyai fisik yang kuat. Namun perempuan tidak diberi stigma seperti itu. Perempuan akan dianggap lebih menarik justru bila mereka tidak melakukan kegiatan atau olahraga yang tidak berhubungan dengan adrenalin, seperti memasak dan menyanyi. Dari obrolan dengan teman yang tidak melakukan olahraga ekstrem dapat saya simpulkan bahwa, anggapan mengenai keterbatasan fisik perempuan menjadi alasan utama minimnya keterlibatan perempuan dalam olahraga ekstrem. Lalu saya mencoba membuktikan kebenaran anggapan tersebut dengan meminta pendapat teman di klub olahraga ekstrem yang juga sering berkegiatan dengan perempuan. Semuanya membenarkan mengenai sedikitnya jumlah perempuan ketimbang laki-laki di klub olahraga ekstrem. Namun sewaktu saya ajukan pernyataan mengenai kekuatan fisik perempuan yang tidak lebih kuat dari laki-laki membatasi perempuan dalam olahraga ekstrem, mereka menolak anggapan tersebut. Berasal dari pengalaman, selama berkegiatan dengan perempuan mereka tidak banyak menemui kesulitan. Sebagian besar latihan yang diterapkan untuk anggota laki-laki dan perempuan juga sama. Ukuran kekuatan atau ketahanan fisik itu didasarkan pada kedisiplinan seseorang berlatih. Banyak juga perempuan yang berprestasi dalam keterlibatannya di olahraga ekstrem. Misalnya, Aryati Larasati yang mendapatkan peringkat ketiga dalam kejuaran olahraga kayak se-Asia Tenggara. Dalam hal ini, teman dari MAPAGAMA UGM bisa berbangga diri karena membuktikan pada kita semua bahwa seorang perempuan bisa melawan stigma atas fisik yang lemah dan tidak lebih kuat dari laki-laki. Saya juga tidak perlu mempertimbangkan berbagai penelitian ilmiah untuk berani mengatakan “Sebagai perempuan, kondisi fisik tidak membatasi saya untuk melakukan olahraga ekstrem!” Winanti Praptiningsih (Karyawati Bagian Obstetri dan Ginekologi FK UGM/RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Menarik untuk mengulas berbagai respons terhadap susunan Kabinet Kerja Jokowi. Saya mencoba membatasi untuk membaca diskursus yang berkembang terutama pada menteri-menteri perempuan Jokowi. Ada delapan menteri perempuan dalam tubuh kabinet Jokowi. Ini berarti jumlah kursi menteri perempuan terbanyak yang pernah ada dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Jika diukur dalam porsi kuantitas maka tentu dengan adanya pertambahan ini kita perlu mengapresiasinya. Catatan tulisan ini tidak bermaksud untuk mengulas bagaimana figur keseluruhan dari delapan menteri perempuan tersebut. Saya lebih tertarik untuk membaca fenomena tanggapan dan diskursus publik terhadap salah satu menteri perempuan yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Setidaknya respons publik yang cukup ramai terhadap Susi Pudjiastuti menyangkut kepercayaan atas kapasitas, integritas dan moralitas. Ketiga hal itu tentu saya akan dekati dengan berbagai persoalan politik wacana tubuh perempuan dan juga kuasa pengetahuan atas perempuan terutama pada korpus isu soal rokok, tato dan gelar pendidikan. Kalangan yang sinis terhadap figur perempuan pemilik Maskapai Susi Air ini lebih banyak mempersoalkan aspek kelayakan moral perempuan seperti penampilan yang non-mainstream, tidak punya gelar pendidikan tinggi, bertato dan punya kebiasaan merokok. Penampilan dan tubuh perempuan lebih banyak disorot dan sering dilekatkan dengan karakter “perempuan yang tidak baik” dan lebih jauh mungkin sebagai “perempuan tidak bermoral”. Mungkin ini juga bisa berlaku bagi tubuh laki-laki, tetapi catatan ini akan jauh berbeda jika diarahkan untuk tubuh perempuan. Barangkali problem ini tak semata hanya pada persoalan perbedaan atas tubuh laki-laki dan tubuh perempuan melainkan sudah menyangkut persoalan kuasa politik dan ideologi yang masih hidup hari ini. Dalam soal tato misalnya, hingga hari ini masih dianggap sebagai sebuah praktik budaya yang menyimpang dan bahkan diangap sebagai sebuah kultur yang bertentangan dengan moralitas mainstream. Tato selalu dikonstruksikan sebagai kriminal dan penjahat. Bahkan pada masa Orde Baru tato bisa dianggap sebagai musuh negara seperti halnya juga fenomena “rambut gondrong” yang juga pernah dilarang dan ditabukan pada masa-masa itu sebagai berandalan dan kaum kriminal. Tato bahkan hingga hari ini masih tidak dilihat secara kritis sebagai bagian kultural seperti yang diyakini suku-suku tertentu di Indonesia. Tato juga tidak dibaca sebagai bagian kultur seni modern yang hari-hari ini semakin digandrungi oleh masyarakat dan harus kita hargai sebagai bagian ekspresi kebudayaan. Tidak mengherankan ketika kemunculan fenomenal Susi Pudjiastuti kemudian diarahkan semata pada persoalan karena dia bertato. Jauh dari itu, sejarah politik Indonesia juga pernah memberikan contoh tragis bagaimana tato dan tubuh perempuan menjadi bagian praktik penegasan kuasa. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana ketika tragedi politik 1965, rezim Soeharto pada waktu itu menjalankan politik penangkapan dan pemenjaraan kaum perempuan yang diangap terlibat PKI menggunakan cara pendekatan politik atas tubuh perempuan bahkan sampai pada taraf yang paling harafiah. Banyak kesaksian yang pernah tercatat pada pengakuan perempuan-perempuan yang dituduh PKI dalam catatan sejarah tentang tragedi 1965 menunjukkan bahwa tato tubuh adalah sesuatu yang binal dan amoral. Pada berbagai operasi penangkapan, perempuan-perempuan diminta membuka penutup tubuhnya untuk melihat apakah dalam tubuh perempuan ada tato lambang Palu Arit atau tidak. Sebuah gambaran atas bentuk pelecehan tidak hanya pada tubuh perempuan tetapi juga pada bagaimana tato sejatinya dipahami dan dikonstruksi. Praktik serupa juga pernah diberlakukan pada peristiwa-peristiwa konflik seperti di Aceh terhadap perempuan-perempuan yang dianggap aktivis GAM. Kembali praktik kuasa politik bersentuhan dengan tubuh perempuan. Pada persoalan rokok sejatinya juga hampir memiliki nasib serupa. Oleh sebagian pandangan mainstream, perempuan perokok masih selalu dipahami sebagai sesuatu yang lekat dengan amoralitas. Kasusnya akan sedikit berbeda jika diberlakukan pada laki-laki. Merokok masih dianggap sebagai kosumsi laki-laki. Bukankah sejatinya ini juga sebagai persoalan politik diskriminasi tubuh perempuan? Tentu saja diakui bahwa perdebatan tentang budaya merokok yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana sosok dan moralitas kepribadian dipahami, hingga hari ini juga masih berlangsung tak hanya menyangkut soal perempuan. Di luar isu kontroversi kesehatan tentang merokok yang kemudian menjadi pertimbangan berbagai kebijakan, merokok juga menyangkut isu-isu berkait dengan moralitas keagamaan dan bahkan politik. Saya ingat bagaimana Orde Baru mengonstruksikan moralitas dengan rokok. Dalam film Pengkhianatan G30S/PKI karya sutradara Arifin C. Noer, digambarkan sosok pimpinan PKI, DN Aidit sebagai seorang perokok berat. Dalam sebagian adegan film tersebut, sosok Aidit yang sejatinya dalam realitas bukan perokok digambarkan sebagai perokok untuk menambahkan aspek keseraman dan kesadisan seperti halnya film-film mafia umumnya. Korpus pergunjingan tak hanya pada persoalan rokok dan tato, isu tidak adanya gelar pendidikan tinggi juga menjadi hal yang dipermasalahkan. Pertama, karena Susi adalah satu-satunya menteri yang menjabat di pemerintahan dengan berbekal ijazah SMP. Keberhasilan kerja yang dicapai sebelumnya oleh Susi kemudian tenggelam oleh ketidakyakinan apakah seorang yang bependidikan rendah akan mampu menjadi seorang pemimpin sebuah kementerian yang cukup besar cakupan tanggung jawab dan mandat kerjanya. Jika dibaca secara semiotik dalam kultur yang masih mengagungkan kuasa laki-laki dalam hal kerja dan kepemimpinan, seorang pemimpin harusnya mereka yang mempunyai kecerdasan dan kepintaran serta keahlian sebagaimana secara formal itu dibuktikan dalam pencapaian jenjang pendidikan. Hal ini mampu mengingatkan kita pada aspek historis bagaimana perempuan adalah subjek yang tidak terlalu penting untuk mengenyam pendidikan. Dan dalam arti itu juga, maka seyogyanya ia tidak layak memimpin dan hanya pantas bekerja pada wilayah domestik. Persis seperti cerita yang selalu diulang dalam buku pegangan wajib Bahasa Indonesia bagi anak-anak Sekolah Dasar pada era Orde Baru : “Bapak Budi kerja di kantor dan Ibu Budi memasak di dapur”. Mungkin lain soal jika Susi diganti oleh Eka Cipta Wijaya Pemilik Sinar Mas Grup atau Tirto Utomo pendiri Aqua atau Bill Gates atau sosok Mark Zuckerberg yang kesemua dari mereka adalah tidak menyelesaikan pendidikan tinggi tetapi menjadi sosok inspiratif yang banyak dikagumi orang. Mungkin persoalan Susi hanya satu, yakni karena dia “perempuan” dan bukan “laki-laki”. Maka label tidak berpendidikan, perokok dan bertato telah melengkapi bagaimana mata kuasa diskriminatif masih terus hidup dalam politik kita dan bahkan merambah pada aspek dimensi yang paling sublim. Dalam kultur pikir yang masih timpang dan bias ini pula, maka wajar jika sosok Susi Pudiastuti yang mampu menghadirkan figur fenomenal ini kemudian oleh sebagian publik yang sinis sepertinya belum bisa diterima dalam superego moralitas mainstream mereka. Bahkan banyak orang mengutuknya sebagai sebuah kesalahan. Wajah politik yang menghadirkan sosok baru sekaligus fenomenal seperti Susi Pudjiastuti sejatinya justru menjadi pemancaing dan pemantik bagaimana kesiapan mental kita sebagai bangsa yang ingin bergerak maju, bisa menerima dan menghargai hal tersebut. Revolusi mental sejatinya bukan perkara jauh di luar sana, melainkan adalah dekat dengan bagaimana nalar pikir dan kepekaan kita sendiri ditantang untuk bisa memilah secara kritis mana yang perlu digunakan untuk memajukan bangsa dan mana mentalitas pikir yang perlu kita tinggalkan. Saya pikir pemikiran yang hanya diletakkan pada kecenderungan diskriminatif dan bias kuasa gender seyogyanya harus sudah dibuang jauh. |
AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
September 2021
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed