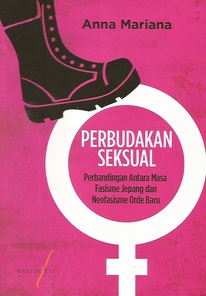 Judul : Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru Penulis : Anna Mariana Penerbit : Marjin Kiri Cetakan : I, 2015 Tebal : xiv + 180 hlm ISBN : 978-979-1260-40-4 Pengantar
Siapa yang bilang bahwa luka masa lalu itu sudah kering? Siapa yang bilang bahwa di negeri ini kekerasan di masa lalu dikoreksi dengan benar lalu dijadikan pelajaran untuk tidak diulangi? Siapa yang bilang bahwa para korban kekerasan dan pelecehan seksual di masa lalu tidak menanggung trauma yang sangat mendalam? Siapa yang bilang bahwa negara telah memberikan keberpihakan secara nyata kepada para korban yang dilecehkan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul setelah selesai membaca buku Perbudakan Seksual karya Anna Mariana ini. Terus terang, saya membaca buku ini dengan perasaan getir, hati yang pilu, sebab setiap kesaksian-kesaksian korban yang ada dalam buku ini begitu menggetarkan. Kesaksian korban seakan-akan menyeret saya untuk menjadi saksi bagaimana kekerasan dan perbudakan seksual itu berlangsung. Duh, betapa bangsa yang besar ini menyimpan begitu banyak luka di masa lalu. Luka yang mestinya dijadikan pelajaran agar tak diulangi. Sebagai anak muda yang masih belajar dan terus memahami sejarah bangsa ini dengan utuh, saya bersukur penelitian yang bermula dari tesis ini diterbitkan. Dari sini, penyebarluasan informasi mengenai kejadian kelam masa lalu bisa semakin terbuka dan menambah referensi buku “sejarah alternatif” yang sudah ada. Harus diakui, sampai saat ini negara cenderung abai dan tidak memberikan keberpihakan kepada korban, malah terkesan membiarkan kejadian kelam masa lalu “sengaja dilupakan” dengan tidak memasukkannya dalam narasi historiografi Indonesia. Proses Eksploitasi Fokus buku ini untuk melihat bagaimana kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan itu berlangsung ketika Indonesia dalam penjajahan fasisme Jepang dan di masa neofasisme Orde Baru. Melalui metode perbandingan, Anna berusaha menganalisis apa perbedaan dan persamaan pada kedua periode tersebut. Lebih khusus lagi, buku ini berusaha memotret; siapakah aktor-aktor yang terlibat? Bagaimana “peran” negara dalam melegitimasi tindakan tersebut? Mariana memulai buku ini dengan memberikan gambaran bahwa karakter fasisme Jepang dan neofasisme Orde Baru sama-sama menjadikan perbudakan seksual sebagai titik tolak pembangunan rezim. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942-1945. Pada tahun itulah Jepang membuat kamp-kamp Ianjo (tempat penampungan perempuan) untuk memberikan fasilitas seksual kepada militer Jepang agar tetap terpenuhi hasrat libido dalam keadaan Perang Dunia II. Sedangkan Orde Baru yang didominasi oleh militer melakukan perbuatan ekploitasi seksual kepada perempuan yang dianggap terlibat dalam peristiwa kudeta politik Gerakan 30 September (G30S) untuk menebar teror. Jika pun mereka tidak terlibat dalam peristiwa itu, mereka dipaksa melalui kekerasan untuk mengakuinya. Di masa Jepang, proses perbudakan seksual ini berjalan dengan sistematis, dan melibatkan banyak pihak. Mulai dari penguasa militer Jepang hingga penguasa pribumi terkecil, seperti kumicho (setingkat RT). Para perempuan yang dijadikan jugun ianfu (sebutan untuk perempuan penghibur dari pihak Jepang) tidak hanya perempuan dari Bumiputera, melainkan dari berbagai golongan termasuk perempuan kulit putih. Bagaimana rekrutmennya? Tentu menggunakan berbagai macam modus, mulai dari cara yang paling halus dengan dijanjikan pekerjaan yang lebih baik, sampai pada cara kasar dengan mengambil paksa dari keluarga mereka. Tidak ada orang tua atau keluarga korban yang berani melawan militer Jepang, karena konsekuensinya adalah pembunuhan (hlm. 37). Orde Baru yang diwakili oleh para militer ini memiliki cara tersendiri dalam melakukan eksploitasi seksual. Diawali terlebih dulu dengan memunculkan wacana tunggal di publik, baik melalui media massa maupun pengumuman bahwa organisasi Gerwani ikut terlibat dalam skenario pembunuhan para jenderal. Sejak itu, setelah peristiwa satu Oktober 1965, perempuan yang dianggap “musuh negara” itu dihancurkan dengan cara keji melalui kekerasan seksual saat proses interogasi, pemerkosaan, hingga praktik perbudakan seksusal di kamp pengasingan, seperti yang terjadi di kamp Tefaat Plantungan yang berlokasi di Kendal, Jawa Tengah (hlm. 120). Maka menjadi benar apa yang diungkapkan Antonio Gramsci bahwa hegemoni wacana memainkan peran penting dalam konstruksi kesadaran masyarakat. Setelah hegemoni Orde Baru itu bekerja dalam kuasa wacana, maka tindakan pelecehan seksual dilakukan dengan sadar sebagai bentuk kepatuhan terhadap negara, dan sang korban patut mendapatkan pelecehan tersebut karena dianggap “berkhianat” kepada negara (Arief, 1999). Mesin politik Orde Baru bekerja dengan melakukan teror dan kekerasan yang dilakukan aparat militer untuk membuat masyarakat tunduk. Kekerasan yang dilakukan oleh Orde Baru tercipta secara masif sebab mendapat legitimasi oleh nilai-nilai moral dan ideologis, yang dalam hal ini anti komunisme. Sehingga tidak heran jika pasca runtuhnya neofasisme Orde Baru, masyarakat masih memberikan stigma buruk kepada para mantan Tapol 1965 (Herlambang, 2013). Kenapa Mariana menyebutnya sebagai perbudakan seksual. Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat ditangkap dalam buku ini. Pertama, tindakan eksploitasi seksual, baik masa fasisme Jepang maupun neofasime Orde Baru dilakukan dengan cara sistematis, dan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari kalangan militer hingga sipil. Kedua, eksploitasi seksual ini dilakukan dengan paksaan dan penuh kekerasan. Hal ini bersumber pada kesaksian-kesakian korban, baik yang diwawancarai langsung maupun mendasarkan kepada referensi sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Ketiga, dalam kasus Jugun Ianfu, mereka dijadikan sebagai objek komoditi untuk mendulang keuntungan ekonomi layaknya pekerja seks komersil. Akan tetapi, para perempuan itu tidak mendapatkan uang bayaran. Sungguh kejam bukan? Sebagai catatan penutup, buku ini memang berhasil memberikan gambaran komprehensif tentang kekerasan seksual yang terjadi di masa pendudukan Jepang dan Orde Baru, akan tetapi dalam buku ini tidak ditemukan pembahasan lebih lanjut apakah kekerasaan seksual yang terjadi di masa pendudukan Jepang memiliki keterkaitan dengan masa Orde Baru, baik dari segi motif, ideologi, dan model kekerasan seksual. Sehingga buku ini terkesan hanya menjelaskan secara kronologis di masing-masing rezim. Namun demikian, buku ini menggunakan metode sejarah lisan yang mendasarkan pada kesaksian-kesaksian korban. Sehingga pembaca seakan-akan berhadapan langsung dengan para korban untuk mendengar kisah pilu mereka. Itulah yang saya rasakan ketika membaca buku ini.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Olivia (bukan nama sebenarnya) yang dipanggil Oli, gadis kampung yang melahirkan anak lelaki pertamanya sekitar tiga minggu yang lalu. Saya mengetahui hal ini setelah diberitahu oleh ayah saya di kampung. Oli adalah seorang anak dari kampung pedalaman di Kalimantan Barat, yang kebetulan adalah satu kampung dengan saya. Oli saat ini baru berumur 15 tahun, umur yang masih belia, dia berhenti sekolah di bangku kelas VII SMP empat tahun lalu. Jadi, jika Oli masih bersekolah saat ini, ia sudah duduk di bangku kelas X SMA. Namun sayang, nasib baik tidak berpihak kepadanya. Jarak sekolah yang jauh dari kampung, membuatnya enggan untuk pergi ke sekolah, apalagi dengan menggunakan sepeda. Jarak sekolah SMP yang berada di kecamatan cukup jauh dari kampung, sekitar satu jam dengan menggunakan sepeda. Oli bukan anak orang berada. Orang tua Oli bekerja sebagai petani biasa. Ketika memutuskan untuk berhenti bersekolah Oli sempat meninggalkan kampung dan bekerja di Kota Pontianak sebagai penjaga mini market. Dia adalah seorang tamatan SD, mencari pekerjaan di kota sangat sulit. Setelah sekian lama ia bekerja, dengan pengaruh dan pergaulan kota yang tidak terkontrol, sepulangnya ia dari bekerja tahun lalu, membawanya ke dalam masalah besar, Oli hamil. Kehamilannya bahkan tidak diketahui oleh siapapun, setelah lima bulan baru ayah dan ibunya mengatahui. Oli hamil tanpa seorang suami, bahkan hingga saat ia melahirkan. Masyarakat di kampung pun tidak mengetahui perihal kehamilan Oli, lantaran ia sangat jarang keluar rumah. Setelah kandungannya berumur tujuh bulan lebih, petua-petua adat di kampung menjatuhkan hukuman adat karena Oli hamil diluar pernikahan, dan tanpa seorang suami. Oli bukanlah satu-satunya anak perempuan di kampung kami yang hamil tanpa suami. Sebelumnya terdapat kasus serupa yang terjadi pada anak yang bahkan lebih muda dari Oli. Cerita Oli merupakan satu diantara ribuan kisah anak Indonesia lainnya yang mungkin saja berada di pegunungan Marauke, hingga pesisir pantai Sabang. Pernikahan di usia dini, bahkan melahirkan di umur belia merupakan kisah yang tidak dapat di pungkiri dari kehidupan sebagian anak perempuan di Indonesia. Menurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak (Candraningrum, 2016). Tidak terhitung jumlah angkanya, anak-anak usia belia yang sudah dipinang, sudah hamil sebelum menikah, bahkan hamil tanpa ikatan pernikahan. Dan para pemangku kebijakan masih berdiam diri tanpa adanya kekhawatiran yang berarti. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Demikian posisi Oli, yang merupakan korban, serta-merta dijatuhkan hukuman adat di suku Dayak Mali. Hukum adat yang dibebankan kepada seorang anak belia umur belasan tahun, rasanya tidak bertuan. Bahkan dalam hukum pidana dan perdata pun, posisi seorang anak diperhitungkan. Ketika seorang perempuan yang diketahui hamil diluar nikah, maka ketua adat dan pemuka masyarakat suku Dayak Mali cepat mengambil tindakan hukum (Niko, 2016). Posisi anak perempuan yang hamil di luar pernikahan resmi, akan menjadi pergunjingan serta buah bibir masyarakat. Bukan saja di satu kampung, namun dalam lingkup satu desa. Karena seluruh kampung akan di undang dalam upacara adat, jadi secara otomatis satu desa mengetahui pasal kehamilan Oli. Puluhan, ratusan bahkan ribuan anak-anak perempuan di daerah pedesaan Kalimantan menghadapi ancaman menikah di usia muda. Mulai dari anak-anak perempuan yang berada di daerah perkotaan hingga anak-anak perempuan yang berada di daerah terpencil pedesaan. Permasalahan ini seolah-olah tidak ada solusinya. Disisi lain banyak lembaga yang memang menaruh perhatian khusus terhadap anak dan perempuan, seperti Komnas Perempuan, Komnas Anak, KPAI, bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Namun belum ada usaha yang serius dan berarti untuk memutus mata rantai habit (selesai sekolah, nikah!) di pedesaan yang seakan menjadi budaya lama. Tidak ada jalan lain untuk sekolahkan anak-anak perempuan pedesaan. Mereka putus sekolah, kemudian menikah karena tidak memiliki pilihan lain. Disisi lain karena memang kondisi keluarga mereka yang tidak mampu (miskin), sehingga dengan menikah diharapkan dapat meringankan beban keluarga mereka. Decision maker juga dibutuhkan dalam menyelaraskan keinginan kita untuk menghentikan pernikahan anak di usia dini. Undang-undang perkawinan yang menyebutkan batas usia minimal anak perempuan 16 tahun untuk dapat menikah, bahkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih hanya sekedar formalitas saja. Toh, pada kenyataannya masih banyak praktik pernikahan dini yang terjadi pada anak perempuan di pedesaan, tanpa ada yang menggugat, bahkan dilanggengkan atas nama budaya dan adat. Masyarakat merasa tidak ada yang salah dengan adanya anak perempuan yang menikah di usia muda. Bukankah ini merupakan bentuk konstruksi budaya yang seharusnya tidak lazim? Sehingga harus dihentikan dengan pendekatan budaya (soft) pula. Disamping itu, sangat perlu penguatan akses dan informasi bagi lembaga terkait, misalnya lembaga Dharma Wanita atau PKK. Akses yang dimaksud adalah pemberian pemahaman oleh perempuan-perempuan yang memiliki pendidikan (tinggi) kepada mereka di pedesaan yang notabene banyak yang tidak tamat di bangku sekolah dasar. Namun, pada praktiknya hal ini tidak terjadi. Bahkan semacam terjadi sekat (strata) yang membedakan bahwa terdapat organisasi bagi ibu-ibu pejabat dan lain sebagainya. Sehingga penguatan akses pun non-sense terjadi pada perempuan bawah, yang mana anak-anak perempuan mereka sangat rentan mengalami putus sekolah, menikah usia dini sampai hamil di luar pernikahan resmi. Situasi ini pula yang melanggengkan kemiskinan yang mereka alami. Keterbatasan akses yang kemudian menimbulkan banyak komponen yang tidak terpenuhi. Misalkan saja hak atas pendidikan (the right to education) banyak wilayah-wilayah terpencil yang belum terpenuhinya akses terhadap sekolah, tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan formal dan nonformal yang memadai. Demikian pula akses kesehatan yang baik, tidak mengejutkan jika masih banyak kasus kematian ibu dan bayi di wilayah terpencil. Tidak terpenuhinya akses terhadap fasilitas Puskesmas atau rumah sakit, tenaga medis dan obat-obatan termasuk pelayanan kesehatan, ditambah lagi harga obat-obatan yang relatif mahal bagi ukuran masyarakat pedesaan. Anshor (2016) mengungkapkan bahwa isu lain yang penting terkait perkawinan anak adalah ketiadaan kesempatan pendidikan di sekolah bagi anak-anak yang sudah terlanjur menikah pada usia anak dan hamil. Dalam hal ini, negara merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewajiban dan wewenang sepenuhnya untuk menjamin terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat tanpa adanya diskriminatif. Eksistensi negara bukan dipandang dari anggota dewannya yang rajin berkunjung ke luar negeri, bukan negara yang menghisap rakyatnya (predatory state) atau sarang terjadinya praktik korupsi yang memiskinkan rakyat, namun lebih kepada negara eksis untuk kepentingan rakyatnya. Tentu kesejahteraan inilah cita-cita rakyat, untuk hidup dan menghidupi negara, dan menghilangkan ketidakadilan. Daftar Pustaka: Candraningrum, Dewi. 2016. “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?”. Jurnal Perempuan. Vol. 21, No. 1, Februari 2016. Hal. 4-8. Niko, Nikodemus. 2016. “Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat”. Jurnal Perempuan. Vol. 21, No. 1, Februari 2016. Hal. 83-95. Anshor, Maria Ulfah. 2016. Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak". Jurnal Perempuan. Vol. 21, No. 1, Februari 2016. Hal. 116-129. Nadya Karima Melati (Lulusan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dan Koordinator SRGC) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Saya berbincang di bawah langit malam di sebuah kos-kosan yang lokasinya berdekatan dengan universitas negeri terbaik di Surabaya. Saya bersama dua orang teman saya yang semuanya perempuan dan baru menginjak usia 22 tahun. Kami berbicara banyak hal, mulai dari kegalauan pacar, apakah karier terbaik setelah lulus kuliah nanti, sampai perilaku seksual kami. Saya berasal dari universitas negeri di daerah Depok dan kebetulan menginap dua hari di Surabaya untuk menghadiri Konferensi Nasional. Melalui bincang-bincang hingga larut malam tadi, kami tahu bahwa perilaku seksual anak usia kami baik yang berasal dari kota Surabaya, Depok atau desa pinggiran pun sama saja. Kami sudah paham dan mengenal aktivitas seksual. Ini semacam rahasia bersama kami. Kami merasa beruntung justru karena tinggal di kota, kami mudah mengakses internet. Internet adalah guru kami, kami menanyakan apapun ke internet tanpa merasa malu, tidak seperti bertanya kepada orangtua ataupun guru di sekolah yang suka memberikan penjelasan seadanya. Perbincangan itu terjadi dua tahun yang lalu, ketika saya masih mahasiswa. Globalisasi membuat dunia ini berubah begitu cepat, ayah saya (58 tahun) pernah bercerita ketika masih seumuran saya, rumahnya belum ada toilet seperti sekarang. Dia dan keluarganya terbiasa buang air besar di pinggir sungai, kini anak-anaknya bisa merasakan water closet, produk peradaban yang dahulu hanya dinikmati oleh kelompok raja. Sekarang hampir semua wilayah di Indonesia memiliki toilet yang berbentuk water closet. Yang hendak saya tekankan disini adalah bagaimana dalam waktu kurang dari 60 tahun, dunia berubah begitu cepat. Kehadiran internet juga memberikan pengaruh hebat sehingga peradaban melesat. Tapi kemanakah arah peradaban ini menuju? Dan apakah manusia-manusia yang menciptakan budaya dan peradabannya ini telah cukup siap menghadapi perubahan yang melesat cepat? Pentingnya Pendidikan Seksual Komprehensif Saya ingin kembali ke paragraf pembuka tulisan ini, saya memulainya dengan curhatan remaja akhir-dewasa muda atau menggunakan padanan kata yang lebih efisien, adolescence. Perilaku seks yang terjadi pada adolescence menjadi semacam rahasia bersama. Ya, kami berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, beberapa dari kami telah melakukan hubungan seksual sejak SMA ataupun ketika di bangku perkuliahan. Hal ini bukanlah hal baru yang terjadi di kota besar. Novel kumpulan cerita yang ditulis Ayu Utami dan kawan-kawan berjudul Kisah Orang-orang Scorpio sempat menceritakan bahwa perilaku seksual di kalangan anak muda ini bukan hal baru, tetapi ketika sang ibu tumbuh dewasa dan berumah tangga, ia merasa khawatir terhadap anaknya yang akan mengalami jalan hidup yang sama (melakukan seks merdeka dan bertanggung jawab) seperti dia. Lantas berita Harian Tempo (Senin, 7 Maret 2016) berjudul “Perilaku Seksual Remaja Ibu Kota Mengkhawatirkan” seakan-akan menunjukan bahwa keterbukaan seksual remaja ibu kota baru terjadi kini, di era internet. Revolusi seksual bergulir agar tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat ditekan, laju pertumbuhan penduduk terkendali, dan kualitas hidup masyarakat naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Semua ini dilakukan melalui pendekatan pendidikan seksualitas. SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) dijadikan pedoman, dan satu-satunya modul cetak yang berpedoman pada SRHR diterbitkan oleh SGRC (Support Group and Resource Center on Sexuality Studies) dalam bengkel kerja “Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus” pada akhir Oktober lalu. SGRC sebagai komunitas pendidikan seksualitas yang diusung mahasiswa UI memberikan modul ini secara cuma-cuma dengan mengunduhnya via website kami: https://sgrcui.wordpress.com/2015/10/23/modul-pencegahan-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-di-kampus/ . Sayangnya, website SGRC ini sempat mendapat surat teguran untuk ditutup oleh Kominfo berdasarkan informasi dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Belum banyak yang mengetahui SRHR sebagai landasan pendidikan seksual yang komprehensif. Pendidikan seksual memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena kita masih menganggap seks tabu dan perempuan yang membicarakan seksualitasnya adalah perempuan tidak bermoral. Padahal perkosaan banyak terjadi karena perempuan tidak memahami hak-hak tubuhnya dan kehamilan tidak direncanakan yang dialami anak perempuan di bangku sekolah disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan hak seksual dan kesehatan reproduksi. Seksualitas dan Penggunaan Internet Ketika mengkhawatirkan perilaku seksualitas remaja, saya rasa pemikiran ini berasal bahwa remaja ini tidak berdaya dan harus dilindungi. Rasa khawatir ini tidak salah, semua orang tua ingin yang terbaik dan selalu memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus. Akses informasi yang super cepat selalu dijadikan kambing hitam ketika para orang tua berupaya melindungi anak-anaknya. Blokir dan pembatasan pemakaian gadget dianggap menjadi solusi. Buat saya, disini ada pemikiran yang kurang lengkap, kita tidak bisa memosisikan remaja sebagai objek yang lemah dan tidak berdaya. Generasi millenial, paham tata cara penggunaan internet, generasi millenial lahir dan tumbuh besar seiring dengan perkembangan teknologi. Ini memberikan kultur generasi millenial cepat tanggap terhadap akses informasi dan adaptif dengan teknologi terbaru. Ada banyak jasa unblock sites, bahkan yang saya temui dalam untuk kasus pemblokiran web pornografi yang dilakukan pemerintah India malah justru memberikan daftar website dengan konten porno yang kelompok muda baru ketahui (dan dengan mudah juga kami retas). Internet justru menjadi kekuatan remaja. Internet berguna untuk networking dan mencari informasi. Generasi tua yang tidak biasa dengan internet menjadi ketakutan atas apa yang tidak mereka kuasai dan khawatir jika anak mereka akan salah arah dalam menyikapi dunia virtual. Kepanikan orang tua ini terjadi pula dengan pendidikan seksual terhadap anak dan remaja. Anak dan remaja dianggap tidak berdaya dan tidak mengetahui apa-apa dianggap akan menjadi hypersex apabila diberikan pendidikan seksualitas, apalagi jika dilakukan melalui media internet. Penutup Perang antar generasi akan menjadi perang yang tidak pernah berakhir. Kita semua, generasi tua dan muda, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, anak perempuan dan anak laki-laki, remaja awal maupun akhir dalam beragam gendernya sebagai bangsa Indonesia sebenarnya masih mengalami permasalahan yang sama. Tingginya AKI dan AKB, pernikahan anak, kehamilan tidak direncanakan yang membuat banyak perempuan putus sekolah. Ada baiknya jika kita menelaah berbagai faktor yang membuat kita tidak maju-maju dalam menyelesaikan masalah bersama ini. Generasi tua dan muda bukan saling bertengkar melalui medianya masing-masing kemudian mengadu pendapatnya. Seharusnya kita semua duduk bersama dan mau mendengar. Bukankah kesepakatan antar generasi yang mampu mengantarkan Indonesia menuju jembatan emas bernama proklamasi kemerdekaan? Akhiriyati Sundari (Mahasiswa Islam dan Kajian Gender UIN Sunan Kalijaga) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Pendahuluan Setengah abad genosida terbesar sepanjang abad 20 baru saja menandai titik waktunya di 30 September 2015 lalu. Sementara orang menyebutnya sebagai pembantaian manusia besar-besaran kedua usai pemusnahan masal yahudi Jerman oleh serdadu SS Nazi semasa rezim Hitler. Terdapat satu juta jiwa manusia Indonesia dilenyapkan nyawanya, bahkan Letkol Sarwo Edi Wibowo menyebut tiga juta, dihilangkan paksa, diciduk dan dipenjarakan dengan siksaan fisik yang sangat sadis dan sulit diterima nalar. Mereka dipisahkan kehidupannya dari keluarga, dari orang-orang yang dicintainya tanpa pengadilan. Mereka adalah simpatisan, anggota, atau bahkan orang yang dituduh sebagai anggota dan mereka yang pernah bersinggungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu orang-orang yang aktif bergabung dalam organisasi-organisasi underbow PKI, termasuk salah satu organisasi perempuan pada waktu itu, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) juga turut diberangus. Penumpasan satu lapisan sosial dalam kurun waktu 1965-1966 telah menyisakan luka tragedi yang tak terperi. Tuduhan demi tuduhan tak berdasar disematkan secara ‘abadi’ kepada Gerwani baik sebagai kelembagaan maupun kepada para perempuan yang aktif di dalamnya. Panggung sejarah tak luput diwarnai dengan goresan hitam terhadap organisasi paling progresif kala itu. Rezim Soeharto menjadi subjek paling bertanggung jawab atas jutaan nyawa manusia tak berdosa. Rezim Soeharto pula yang patut bertanggung jawab terhadap pengebirian dan pemusnahan sejarah manis gerakan perempuan yang pernah Berjaya itu, termasuk pembungkaman terhadap aktivitas perempuan sesudah 1965 hingga 32 tahun lamanya. Gerwani: Sejarah Progresif Gerakan Perempuan Indonesia Momentum 1928 ketika dimulai ‘kesadaran nasional’ dengan diprakarsai terbentuknya organisasi modern Budi Utomo diikuti oleh para perempuan yang menggelar Kongres Perempuan pertama, dan melahirkan perjuangan kesadaran masyarakat Indonesia pada entitas yang lebih luas. Gerwis (Gerakan Wanita Sedar) yang berdiri pada tahun 1950 yang kemudian bermetamorfosa menjadi Gerwani pada tahun 1954, tercatat sebagai gerakan perempuan paling progresif-revolusioner di Indonesia. Kesadaran kritis dengan ditopang garis perjuangan termaju saat itu, yakni feminisme, sosialisme, dan nasionalisme kala itu berhasil membawa Gerwani tampil sangat aktif dan menelurkan perubahan peradaban yang signifikan bagi bangunan kebangsaan dan keindonesiaan. Cakupan utamanya adalah perjuangan perempuan yang dibingkai feminisme. Sebagaimana produk yang dihasilkan dalam catatan-catatan perjuangan Kongres Perempuan sebelumnya, persoalan ‘ketertinggalan’ perempuan menjadi titik didih utama pula dalam perjuangan Gerwani. Terlebih pada kurun waktu antara kongres pertama dan kedua, feminisme begitu kuat memandu langkah-langkah perjuangan Gerwani. Tuntutan untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan--yang pada waktu itu dirasakan diskriminatif—menjadi demokratis terus diperjuangkan. Selain itu Gerwani juga berada di garda depan dalam merumuskan garis perjuangan menuntut upah yang adil bagi buruh perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik, menuntut penyediaan lapangan pendidikan yang baik bagi perempuan, menuntut pemberian fasilitas penitipan anak, perhatian serius terhadap kasus-kasus perkosaan, trafficking, serta merumuskan pembagian kerja yang adil antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Segmentasi yang demikian progresif di kalangan Gerwani kala itu tidak lantas begitu saja diterima dengan mudah bahkan oleh sesama aktivis perempuan dari organisasi lain. Catatan Saskia E. Wieringa mengemukakan bagaimana Gerwani begitu dijauhi oleh Ormas keagamaan kala itu seperti Aisyiyah dari Muhammadiyah, Muslimat dari Masyumi, serta Muslimat NU dari Nahdlatul Ulama. Persinggungannya jelas pada soal poligami. Hal tersebut merupakan wilayah ‘otoritas keagamaan’ yang masih menjadi keyakinan dalam Islam sehingga tak bisa diganggu gugat. Sementara Gerwani yang sejak awal tidak melandaskan organisasinya pada agama tampak tidak merisaukan hal itu. Gerwani dan Analisis Feminis Terdapat tiga aliran (teori) besar dalam feminisme yaitu liberal, radikal, marxis-sosialis (Gadis Arivia, 2003). Teori liberal lebih menekankan pada pendayagunaan akal atau rasio. Bagaimana perjuangan perempuan didudukkan pada porsinya untuk mengenali terlebih dahulu kapasitas yang ‘given’ dari Tuhan berupa perangkat otaknya. Untuk itu, perempuan mesti menuntut adanya ‘iklim berpikir’ luas yang terdapat dalam pendidikan. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan melalui sekolah-sekolah dengan tujuan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru untuk memberdayakan kapasitas berpikirnya. Feminisme radikal mencurahkan fokusnya pada ketertindasan perempuan. Segregasi antara ranah privat dan publik yang masuk dalam ‘pembagian kerja secara seksual’ adalah inti atau akar dari ketertindasan itu. Penindasan menurut paham ini berawal dari ranah privat. Perempuan didominasi dan dikendalikan secara seksual dalam ranah privat atau domestik. Maka munculah apa yang kemudian dikenal sebagai slogan “the personal is political”, “yang pribadi adalah politis”. Penindasan yang terjadi di ranah domestik adalah berarti penindasan di ranah publik juga. Sementara feminisme marxis-sosialis. Feminis sosialis lebih menekankan penindasan gender disamping penindasan kelas sebagai salah satu sebab dari penindasan terhadap perempuan. Sementara feminisme marxis beranggapan bahwa persoalan utamanya hanya terletak pada masalah kelas yang menyebabkan perbedaan fungsi dan status perempuan. Hal ini berbuntut pada pandangan bahwa bagi feminisme marxis, perempuan borjuis (kelas menengah ke atas) tidak akan mengalami penindasan yang sama dengan perempuan dari kelas proletar (kelas buruh). Secara ideologis, Gerwani lebih dekat pada PKI dengan marxis-sosialisnya. Secara praksis, semuanya menjadi kabur dan bahkan berbaur satu sama lain. Dimensi awal pergerakan Gerwani adalah menarik kasus Undang-Undang Perkawinan dalam setiap tuntutannya. Persoalan perkawinan pada aras tertentu adalah persoalan privat. Persoalan yang bersumber dari lingkup rumah tangga. Gerwani memandang ada diskriminasi di sini. Laki-laki boleh melakukan poligami. Laki-laki tanpa tindakan bertanggung jawab sedikit pun bisa berlenggang meninggalkan keluarganya, istrinya, demi kepentingannya sendiri. Terdapat penindasan perempuan di sini yakni si istri. Dalam hubungan rumah tangga, istri ‘ditundukkan’ secara seksual oleh suami. Aras perjuangan Gerwani bertolak dari hal ini, tidak saja istri yang akan mengalami penderitaan dari perilaku suami di ranah privat itu, namun anak-anak juga menjadi pihak tak kalah menderita. Reformasi Undang-Undang Perkawinan menjadi penting untuk diperjuangkan bagi Gerwani untuk melindungi perempuan. Progresif dan sosialis terwakili di sini. Bahwa ada perbedaan gender yang tidak setara dalam hubungan perkawinan. Tuntutan Gerwani terhadap hak-hak buruh perempuan agar mendapat jatah upah setara, dalam wilayah ini mengadopsi teori feminis marxis-sosialis. Ada warna kelas sosial yang mesti dipatahkan musabab penindasannya. Buruh perempuan digaji amat rendah dan tidak setara dengan laki-laki sementara beban kerja sama. Tak terkecuali buruh tani perempuan di desa-desa. Bergabung dengan Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerwani menuntut reformasi agraria agar dilaksanakan. Land Reform, agar dituntaskan meski kemudian dilakukan dengan ‘membuat kacau’ situasi sosial yakni adanya ‘aksi sepihak’ melawan Tuan Tanah sebagai salah satu dari ‘tujuh setan desa’ yang menjadi musuh perjuangan mereka. Pergerakan yang agresif Gerwani dengan kedekatannya dengan kalangan buruh kala itu, sudah memberikan simpulan tersendiri bahwa garis ideologis Gerwani mengarah pada komunis yang digunakan PKI. Romantisme kisah Clara Zetkin, pemimpin partai sosialis perempuan pertama di dunia yang berasal dari Jerman telah menginspirasi anggota Gerwani untuk melakukan hal yang sama, menggalakkan kerja-kerja mengorganisir buruh secara masif. Bahkan romantisme itu juga ditunjukkan dengan turut sertanya Gerwani merayakan Hari Perempuan Internasional yang digagas oleh Clara Zetkin dan digaungkan ke seluruh dunia. Setali tiga uang dengan ideologi PKI yang dekat dengan Gerwani adalah keikutsertaannya dalam WIDF (Women’s International Democratic Federation) dan memberi ‘warna’ dalam organisasi tersebut. Ketidaksetujuannya dengan butir-butir hasil kesepakatan dalam pertemuan internasional misalnya, ditunjukkan Gerwani dengan keluar dari organisasi internasional itu, lantaran Gerwani menganggap tak akan ada perdamaian dalam bingkai imperialisme. Kesadaran kolonial telah lebih dulu dimiliki Gerwani. Ini menjadi penting untuk sekali lagi menyimpulkan bahwa Gerwani sungguh-sungguh berkiprah aktif dalam masalah politik nasional Indonesia kala itu. Satu hal yang dianggap ‘ambigu’ adalah sikap ‘diam’ Gerwani terhadap perkawinan kedua Presiden Sukarno dengan Hartini. Satu sisi, Gerwani memperjuangkan secara radikal reformasi perkawinan, satu sisi Gerwani diam terhadap fakta bahwa terdapat kontraproduksi dari tuntutan perjuangan itu dan justru hal itu dilakukan oleh “Sang Bung Besar”. Dasar apologetiknya adalah persoalan imperialisme lebih penting dari sekadar persoalan privat macam perkawinan. Agaknya, ini adalah wujud dari tindakan politis Gerwani yang tengah mengubah haluan dari gerakan kader menuju pada gerakan massa. Artinya, terjadi ‘pemilahan wilayah’ secara tak disadari bahwa Gerwani mengakui ranah privat dan publik sebagai sesuatu yang ‘oposisi biner’. Sebuah sudut pandang lain menangkap ‘kemandirian’ Gerwani dalam berorganisasi, yakni menegaskan diri tidak terlibat dengan partai politik mana pun. Tidak menjadi organisasi sayap perempuan dari partai politik mana pun. Sebuah kenyataan yang bertolak belakang dengan narasi sejarah Orde Baru yang menempatkan Gerwani sebagai organisasi komunis underbow PKI. Garis struktural Gerwani adalah independen. Sementara, PKI sebenarnya juga memiliki sayap perempuan tersendiri, namanya Wakom (Wanita Komunis) yang dipimpin oleh perempuan anggota PKI garis keras, Suharti, masuk dalam struktur PKI sebagai partai politik. Ketegasan kemandirian Gerwani dalam organisasi ini menandakan sebuah kenyataan radikal. Segaris dengan ideologi komunis pada saat itu, Gerwani membangun ‘hubungan dekat’ dengan Sukarno dengan slogan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Hal yang kerap didengung-dengungkan adalah perjuangan progresif-revolusioner. Bahwa ‘revolusi belum selesai’. Karenanya, ada empat macam golongan kaum kontra-revolusioner yang menjadi musuh Gerwani, yakni kaum imperalis, kapitalis komprador, kapitalis birokrat, dan tuan tanah jahat. Perjuangan melawan imperialisme ditunjukkan Gerwani dengan turut aktif mengirim anggota untuk mengikuti pelatihan fisik menghadapi imperialis Belanda atas Irian Barat. Juga menghadapi ganyang Malaysia yang dituduh Sukarno sebagai negara imperialis boneka Belanda dan sekutunya. Sesudah Oktober 1965 Percobaan kup, pengambilalihan kekuasaan, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mendaku dirinya para perwira Angkatan Darat (AD) dengan menculik dan membunuh enam jenderal AD dan satu perwira, merupakan titik awal dari rangkaian sejarah berdarah amat panjang. Wajah Indonesia berubah total mulai saat itu. Terjadi pembasmian besar-besaran terhadap PKI beserta ‘antek-anteknya’ yang dikomandoi oleh Soeharto. Tak terkecuali para perempuan Gerwani. Seluruh organisasi yang berbau ‘kiri’ dinyatakan haram hidup di Indonesia. Hantu komunis diciptakan bergentayangan dalam memori kolektif seluruh bangsa. Museum, buku-buku sejarah, film, dan propaganda media massa yang ‘satu pintu’ sukses besar menghitam-putihkan kehidupan kebangsaan selama 32 tahun. Jutaan rakyat dibantai oleh saudara sebangsa sendiri. Militer di bawah Soeharto menerapkan politik adu domba di tingkat grass root, horizontal, yang menghadap-hadapkan sesama anak bangsa sambil mengibas-ngibaskan tangannya sebagai tanda ‘cuci tangan’. Para perempuan mengalami perlakuan sadis dalam tahanan, disiksa, diperkosa, hingga dibunuh. Sebuah tragedi berdarah terbesar negeri ini yang sukses mempersembahkan diri sebagai tumbal Orde Baru. Para penyintas itu, kini sebagian besar telah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun, stigma, bahkan setelah 50 tahun, masih disematkan kepada mereka sebagai orang yang tidak bersih di lingkungan, kotor, bejat moral, sundal, pemberontak dan sederet makian tidak manusiawi lainnya. Para perempuan Gerwani tidak pernah direhabilitasi nama baiknya. Tuduhan-tuduhan terhadap mereka sebagai bagian dari pembunuh jenderal dalam ‘ontran-ontran’ G30S/PKI di Jakarta tidak pernah terbukti. Tak ada pengadilan buat mereka. Sejarah hidup mereka dilubangi sedemikian dalam bahkan hingga di usia senja mereka, di saat keran kebebasan reformasi membuka lebar-lebar bagi hidup yang manusiawi. Kesimpulan Titik balik kehidupan berkebangsaan di Indonesia didemarkasi dalam kurun 1965-1966 melalui peristiwa genosida terhebat di negeri ini. IPT ’65 yang digelar di Den Haag Belanda pada medio November lalu pun terasa tak ada gayung bersambut hingga hari ini dari seluruh lapisan anak bangsa. Seluruh anak bangsa seakan masih hidup dan sengaja dibuat hidup dalam situasi ‘senyap’ sejarah berdarah. Perjuangan kemanusiaan yang dibalut feminisme telah dengan gemilang ditorehkan sejarahnya oleh Gerwani. Akan tetapi, merobohkan bangunan patriarki sesudah 32 tahun kokoh berdiri tentu tak mudah. Gesekan-gesekan dari perbedaan paham di masyarakat terhadap gerakan perempuan progresif, radikal, kekirian, masih saja menunjukkan batang hidungnya. Feminisme, bahkan telah direduksi besar-besaran maknanya pula di sebagian besar masyarakat sebagai ‘paham kiri baru’ dari barat. Perjuangan terhadap kesetaraan dan keadilan masih tampak merangkak hingga hari ini, setelah belum munculnya lagi gerakan perempuan feminis seperti Gerwani. Daftar Pustaka: Wieringa, Saskia. 2010. Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Yogyakarta: Galang Press. Julia Suryakusuma. 2011. Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru. Depok: Komunitas Bambu. Blackburn, Susan. 2007. Kongres Perempuan Pertama; Tinjauan Ulang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV. Gadis Arivia. 2003. Filsafat Berperspektif Feminis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. Cora Vreede-De Stuers. 2008. Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan dan Pencapaian. Depok: Komunitas Bambu. Engels, Friedrich. 2004. Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara. Jakarta: Kalyanamitra. --------------------. 2003. “Perempuan dalam Seni Sastra, Jurnal Perempuan edisi 30. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. --------------------. 2007. “Kami Punya Sejarah”. Jurnal Perempuan edisi 52. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. --------------------. 2003. “Peristiwa ’65-’66; Tragedi, Memori, dan Rekonsiliasi. Jurnal Tashwirul Afkar edisi 15. Jakarta: LAKPESDAM NU. Isyfi Afiani (Alumni Program Magister Pengkajian Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Surakarta) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Novel Fifty Shades of Grey (FSOG) karya E. L. James menarasikan relasi seksual BDSM antara Anastasia Steele dengan Christian Grey. Novel FSOG yang terbit pada tahun 2011 terjual lebih dari 70 juta kopi, dan menjadi topik pembicaraan sejak novel tersebut dipublikasikan. Respons pembaca terhadap novel FSOG sangatlah beragam, dari pendapat yang memunculkan isu dominasi laki-laki dan kekerasan seksual antara Anastasia dan Christian, hingga pendapat bahwa BDSM merupakan eksperimen seksual perempuan. Dalam artikel ini saya mencoba menarasikan secara deskriptif bagaimana relasi seksual BDSM tercermin dalam novel Fifty Shades of Grey karya E. L. James dengan menggunakan argumentasi dua sisi (both views opinions) dari perspektif psikologi dan feminisme. BDSM dalam Perspektif Psikologi BDSM adalah istilah yang mengacu pada perilaku erotis yang melibatkan Bondage & Discipline, Dominant/Submissive, dan Sadism & Masochism—walau tak semua pelaku BDSM mengaplikasikan syarat-syarat tersebut (Emulf dan Inalla, 1993), pengalaman traumatis (Stolorow, 1975; Valenstein, 1973), kegagalan perkembangan psikologis (Bychowski, 1959; Mollinger, 1982), dan konflik infantile (Blum, 1976). Beberapa pakar psikologi menghubungkan masokisme dan sadisme dalam BDSM dengan kondisi kejiwaan seperti kegelisahan/anxiety (Bond, 1981; Freud 1961; Socarides, 1974; Stolorow, 1975), dan depresi (Blum, 1988). Dari keragaman pendapat mengenai BDSM oleh pakar psikologi dan pengkaji BDSM tersebut, Berslow menyatakan ada kerancuan pada terminologi BDSM; apakah sadisme dan masokisme dianggap sebagai fenomena seksual, atau sebagai fenomena psikologi, atau justru keduanya. Karena itulah perlu adanya dasar yang kuat dari data-data empiris untuk menguji teori tentang istilah BDSM dengan tepat (Berslow, 1989). BDSM dalam Perspektif Feminisme Menurut McKinnon, erotisme kekerasan laki-laki terhadap perempuan adalah masalah utama dalam feminisme, karena paradigma tersebut muncul ketika seks dianggap sebagai pengekangan, gangguan, pelanggaran, dan objektifikasi (McKinnon dalam Cynthia Grant Bowman et. al ed. 2011, h. 121).
Menurut McKinnon, ketidaksetaraan gender muncul berdasarkan persetujuan;
Untuk mendukung pernyataan McKinnon tersebut, saya merujuk Robin West dalam The Difference in Women’s Hedonic Lives: A Phenomenological Critique of Feminist Legal Theory (2000). West mengkritik pandangan feminisme liberal—bahwa kebahagiaan manusia bergantung pada pilihan objektifnya—dan pandangan feminisme radikal yang mengolerasikan keadilan/kesetaraan dengan kebahagiaan. Selanjutnya, West menyatakan bahwa S/M adalah implementasi dari kepercayaan, ketimbang kepatuhan, karena dalam S/M memungkinkan Submisif untuk melampaui subjektivitasnya, sehingga ia mampu membebaskan dirinya dari belenggu. Bagi West, perbedaan antara submisi dari kepercayaan dan submisi dari kepatuhan terletak pada subjek dan bersifat subjektif (West 2000, h. 149 & 198).
Relasi BDSM dalam Novel Fifty Shades of Grey Dalam novel FSOG, E. L. James menarasikan bagaimana Anastasia Steele (tokoh utama perempuan), seorang mahasiswi Sastra Inggris di sebuah Universitas di Portland, jatuh cinta dengan sosok Grey (tokoh utama laki-laki) seorang miliarder muda yang kaya, tampan, pintar, dan metroseksual. Alur cerita berawal dari peristiwa dimana Ana harus menggantikan sahabatnya, Kate, untuk mewawancarai Grey—yang merupakan donator utama kampus mereka—sebagai tugas kuliah. Dalam pertemuan wawancara tersebut keduanya saling menunjukkan ketertarikan. Penampilan Ana yang lugu, innocent, dan pemalu, cukup menarik perhatian Grey. Dan Ana pun tak mampu menafikan karisma Grey sebagai sosok laki-laki tampan yang biasa ia jumpai di karya-karya sastra fiksi. Pertemuan tersebut berlanjut dengan kencan-kencan yang mereka jalani, hingga pada akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan relasi BDSM. Relasi BDSM antara Anastasia Steele dan Christian Grey mengacu pada sistem relasi Budak dan Tuan yang terikat dalam sistem kontrak (consents). Adapun isi kontrak/ perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak serta bagaimana relasi BDSM antara Ana dan Grey yang tercermin dalam novel FSOG adalah sebagai berikut: Kontrak (Consents) Pada dasarnya, isi kontrak antara Ana dan Grey mencakup posisi masing-masing individu dalam relasi BDSM—Grey sebagai Dominant dan Ana sebagai Submissive, serta hal-hal yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan oleh masing-masing dari mereka, terkait aksi seksual (sexual action) yang mereka lakukan. Poin-poin yang termaktub di dalam kontrak tersebut tentu saja lebih menguntungkan Grey sebagai Dominant, dan merepresi Ana sebagai Submissive. Poin-poin kontrak relasi BDSM antara Ana dan Grey mencakup disiplin bagi Submissive—pengaturan jam tidur, pola makan, olah raga, cara berpakaian, penampilan, kesehatan dan kebersihan, demi terjaganya kualitas diri Submissive yang berpengaruh pada kualitas performa seksual pada saat berhubungan seks (James 2012, h. 77), batas maksimal/hard limits—aksi yang tidak diperbolehkan saat berhubungan seksual seperti penggunaan api, ataupun jenis senjata tajam yang dapat melukai Submissive (James 2012, h. 80), dan syarat-syarat pelayanan (service provisions) diantaranya (1) Dominant harus harus menjaga keamanan dan kenyamanan Submissive, (2) memperlakukan Submissive sebagai propertinya untuk selalu dimiliki, diatur, didominasi, dan menggunakan tubuhnya sebagai objek seksual, (3) Dominant diperkenankan mendisiplinkan Submissive dengan mencambuk, memukul bagian pantat, serta mengikat Submissive sebagai bentuk hukuman ataupun untuk kesenangan Dominant, (4) Submissive harus menerima Dominant sebagai tuannya, dalam arti bahwa dirinya adalah properti bagi Dominant yang harus menuruti segala perintah Dominant, termasuk perintah untuk tidak menyentuh dan menatap mata Dominant secara langsung (James 2012, hh. 128-130). Aksi Seksual (Sexual Action)
Penggalan narasi diatas menunjukkan bagaimana Grey menjalankan peranannya sebagai Dominant dalam relasi BDSM yang dijalaninya dengan Ana. Grey memperlakukan Ana sebagai properti yang bisa ia atur dan disiplinkan sesuai dengan kehendaknya dan demi kepuasannya. Dan di setiap aksi seksual, Grey selalu melibatkan kekerasan fisik/sadisme seperti memukul pantat Submissive (James 2012, h. 200), mencambuk (James 2012, h. 230), dan mengikat tangan Submissive (bondage) (James 2012, h. 191) sebagai pola dari aksi seksualnya. Mengacu pada pendapat pakar psikologi bahwa BDSM adalah sebuah traumatic disorder—terjadi karena sebuah pengalaman traumatis—perilaku sadisme Grey tersebut bisa disimpulkan sebagai impact dari pengalaman seksual masa lalunya dengan Nyonya Robinson. Dalam novel FSOG dinarasikan bahwa saat usia anak-anak, Grey menerima perlakuan sexual abusive dari Nyonya Robinson yang berusia jauh lebih tua darinya (James 2012, h. 120). Pengalaman traumatis tersebut makin diperkuat ketika Grey menyebut dirinya sebagai the fifty shades of fucked up (James 2012, h. 198)—trauma seksual yang menyebabkan Grey tak ingin disentuh oleh pasangannya saat berhubungan seksual. Namun jika ditelaah lebih lanjut, berdasarkan data-data narasi yang terdapat dalam novel FSOG, sadisme yang dilakukan Grey terhadap Ana sebenarnya tidak ditujukan untuk menyiksa, namun untuk menstimulus (Ana) secara seksual agar Ana pun mendapatkan kenikmatan/ pleasure yang sama seperti Grey. Berikut penggalan narasi ketika Grey akan mencambuk Ana:
…he flicks again, this time hitting my nipple, and I throw my head back as my nerve endings sing… ….dia mengibaskan (cambuk) lagi, kali ini memukul putingku, dan aku menghempaskan kepalaku karena syaraf-syarafku mulai naik. “Does that feel good?” he breathes. “nikmat?” “Yes.” “Ya (James 2012, h. 230).” Pada dasarnya, relasi BDSM ini tidak akan terwujud tanpa adanya persetujuan antara ke dua belah pihak baik Dominant maupun Submissive. Lantas apa yang mendasari Ana untuk menerima posisinya sebagai Submissive? Saya mengacu pada West (2000) menyatakan bahwa S/M adalah implementasi dari kepercayaan, ketimbang kepatuhan. Berikut adalah narasi yang menunjukkan bahwa Ana menjalani perannya sebagai Submissive berdasarkan pada sebuah kepercayaannya kepada Grey: I can show you how pleasurable pain can be. You don’t believe me now, but this is what I mean about trust. There will be pain, but nothing that you can’t handle. Again, it comes down to trust. “Do you trust me, Ana?” Aku dapat meyakinkanmu tentang kenikmatan dalam sakit. Itulah yang kumaksud tentang kepercayaan. Akan ada sakit, tapi tak ada yang tak bisa kau atasi. “Kamu mempercayaiku, Ana?” “Yes, I do.” I respond spontaneously, not thinking… because it’s true – I do trust him. “Ya, aku mempercayaimu.” …karena itu benar—aku benar-benar mempercayainya (James 2012, h. 245). Di samping itu, West juga berpendapat bahwa dalam S/M memungkinkan Submissive untuk melampaui subjektivitasnya sehingga ia mampu membebaskan dirinya dari belenggu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan narasi tentang bagaimana Ana menikmati setiap aksi seksual yang diterimanya dari Grey sebagai bentuk kenikmatan/pleasure, bukan sebagai belenggu/bondage sebagai berikut: He hits me again across the buttocks. The crop stings this time. My eyes are closed as I try to absorb the myriad of sensations coursing through my body. Very slowly, he rains small, biting licks of the crop down my belly, heading south. I know where this is leading, and I try and psyche myself up for it – but when he hits my clitoris, I cry out loudly. Dia memukuli pantatku lagi. Dengan cambuk. Mataku terpejam seperti merasakan ribuan serangga menyerang tubuhku. Dengan perlahan, ia menyentuhkan ujung cambuk pada bagian perutku, dan terus ke bawah. Aku tahu kemana arahnya, dan aku mencoba, dan aku merasakannya—namun ketika dia menekan klitorisku, aku berteriak. “Oh… please!” I groan. “Oh…!” Aku mengerang. I am lost. Lost in a sea of sensation…completely seduced. Aku tersesat dalam sensasi yang luar biasa…nikmat…(James 2012) Kesimpulan Perdebatan BDSM sebagai penyimpangan ataupun kekerasan seksual perlu dikaji dengan pendekatan yang lebih intens seperti yang dikatakan pakar psikologi Berslow (1989), bahwa perlu adanya dasar yang kuat dari data-data empiris untuk menguji teori BDSM dengan tepat. Novel Fifty Shades of Grey karya E. L. James memberikan pandangan lain terhadap implementasi relasi seksual BDSM melalui kedua tokoh utamanya: Anastasia dan Grey. Analisis relasi seksual BDSM dalam novel FSOG menunjukkan bahwa baik Dominant maupun Submissive sama-sama mendapatkan kenikmatan seksual dari hubungan yang mereka jalani. Daftar Pustaka: Berslow, M. 1989. “Sources of Confusion in the Study and Treatment of Sadomasochism”. Journal of Sexual Behavior and Personality. Bond, A. 1981. “The Masochist is the Leader”. Journal of the American Academy of Psychoanalysis. Blum, H. 1976. Sadomasochism in Psychoanalytic Process, within and beyond the Pleasure. Bychowski, G. 1959. “Some Aspects of Masochistic Involvement”. Journal of the American Psychoanalytic Association. Emulf, K. E. & Inalla, S. M. 1995. Sexual Bondage: a Review and Unobtrusive Investigation. Archives Sexual Behavior. Freud, S. 1961. The Economic Problem in Masochism in Jay Strachey (Ed. And Trans). The Standard Edition of the Complete Psychological Work of Sigmund Freud, Vol. 18. London: Hoghart Press. James, EL. 2012. Fifty Shades of Grey. Great Britain: Arrow Books. MacKinnon, C. 2011. Sexuality, in Feminist Jurisprudence: Cases and Materials. (Cynthia Grant Bowman et. al ed). West, R. 2000. “The Difference in Women’s Hedonic Lives”. Psychoanalytic Quarterly. Socarides, C. 1974. “The Function of Moral Masochism with Special Reference to the Defense Process”. International Journal of Psychoanalysis Vol 39. Stolorow, R. 1975. “The Narcissistic Function of Sadomasochism (and Sadism)”. International Journal of Psychoanalysis Vol 56.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Seumur hidup saya tak akan pernah melupakan iklan shampoo di masa kanak-kanak dulu. Kala itu, semua iklan shampoo memakai model perempuan dewasa maupun anak-anak yang memiliki rambut berwarna hitam, panjang, dan lurus. Tak ada yang salah sebenarnya dengan gambaran itu. Sebagian besar perempuan di Indonesia memiliki rambut serupa. Tetapi, kepentingan industri di belakang iklan itu juga lupa kalau ada sebagian besar perempuan Indonesia yang memiliki rambut ikal, keriting, potongan pendek, atau mungkin rambutnya kecokelatan atau kemerah-merahan. Citra mereka jarang dan bahkan mungkin tidak pernah muncul di iklan shampoo Indonesia saat itu. Sialnya, imaji perempuan dewasa berambut panjang, lurus, dan hitam berkilau yang tersenyum puas karena rambutnya berhasil memikat pria tampan yang duduk di meja sebelah begitu menggiurkan. Masalahnya, saya dan sebagian besar perempuan lainnya, tak masuk dalam kategori rambut ideal tersebut. Citra ideal itu hidup dan perlahan mengikis rasa percaya diri terhadap tubuh sendiri. Kami lalu terdampar sebagai alien di tengah-tengah kelompok yang mengagung-agungkan rambut panjang, hitam, lurus. Ini hanyalah salah satu keadaan dimana perempuan belajar membenci tubuhnya. Di awal tahun 2000-an, serial Meteor Garden yang diimpor dari Taiwan meledak di Indonesia. Sanchai, tokoh utama perempuan di serial itu juga hadir dalam wujud perempuan berambut panjang, hitam, dan lurus (ini belum ditambah dengan kulit putih dan tubuhnya yang langsing). Bersamaan dengan itu, teknologi di bidang perawatan rambut memperkenalkan teknik pelurusan rambut yang disebut rebonding, smoothing, atau catok rambut yang pada saat itu dibandrol dengan harga mahal. Imaji rambut ideal yang dipendam sekian lama dan keinginan untuk menuruti kata “cantik” akhirnya mendapat pemuasannya. Rambut, seperti halnya bagian tubuh yang lain, juga mudah diotak-atik dan terluka. Banyak perempuan berambut keriting yang kemudian berbondong-bondong meluruskan rambutnya. Namun, tampaknya keinginan manusia tidak bisa membendung keadaan alam. Berkali-kali meluruskan rambut, berkali-kali pula rambut keriting tumbuh lagi. Kerontokkan dan kebotakan menjadi konsekuensi nyata bagi mereka yang berani meluruskan rambutnya. Tahun 2009, ketika saya berkunjung ke kota Ambon, saya menemukan sejauh mata memandang bahwa banyak sekali perempuan Ambon yang tak lagi memiliki rambut keriting mereka. Tante saya yang berkali-kali rebonding akhirnya terpaksa membeli wig karena rambutnya sudah mulai habis rontok. Rebonding tanpa disadari telah melunturkan identitas tubuh dan budaya mereka, berikut ancaman kebotakan. Selama bertahun-tahun, kita pernah mendapat kabar bahwa ada perempuan yang menderita eating disorder karena ingin langsing. Selama bertahun-tahun, kita pernah menjadi korban untuk menjadi cantik. Kita melukai tubuh untuk menjadi putih walaupun kenyataannya ras kita mengkodratkan kulit kecokelatan. Selama bertahun-tahun, kita belajar merekonstruksi fungsi wajah. Mata yang fungsinya untuk melihat mulai kelopaknya ditempeli warna-warni eye shadow. Bibir yang digunakan untuk berbicara, makan, dan mencium dibubuhi gincu. Bulu mata dan alis yang fungsinya untuk melindungi mata, kita otak-atik dengan bulu mata ‘anti badai’ atau men-atonya seperti logo iklan sepatu Nike. Selama bertahun-tahun, kita juga lupa bahwa tubuh menangis kesakitan setiap kali kita mereparasinya untuk memenuhi satu kata mutlak yaitu cantik. Tubuh telah menjadi persoalan pelik perempuan yang berusaha dibongkar oleh para feminis. Naomi Wolf adalah salah satu nama yang muncul dalam gerakan feminis gelombang ketiga di Amerika yang terkenal lewat bukunya The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women (1991). Ia mungkin bukan seorang akademisi yang aktif mengajar, tetapi sebagai lulusan Universitas Yale dan Oxford yang berprofesi sebagai penulis, jurnalis dan konsultan politik, Wolf telah memilih berada di jalur para aktivis feminis. Sewaktu kuliah di Universitas Yale, ia pernah mengalami pelecehan seksual oleh professornya, Harold Bloom, dan karena kasusnya tak mendapat respon dari kampus, Wolf dengan berani membawanya ke ruang publik. Karya-karya Wolf banyak berbicara tentang seksualitas perempuan, antara lain Fire With Fire (1993), Promiscuities: The Secret Struggle For Womanhood (1997), Misconception (2001), dan Vagina: A New Biography (2012). Melalui karyanya, Wolf ingin membicarakan dan menguatkan perempuan-perempuan untuk mengenal, menerima, memilih, dan merayakan seksualitas mereka. Dalam buku The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women, Wolf (2002:1-2) mengawali buku ini dengan menunjukkan bahwa selama ini perempuan-perempuan kulit hitam, kulit cokelat, maupun kulit putih di Amerika berhadapan dengan mitos kecantikan untuk menjadi perempuan yang sempurna yaitu memiliki tubuh tinggi, langsing, putih, dan berambut pirang. Kulit wajah mereka tidak boleh memiliki cacat sedikit pun dan lingkaran pinggang mereka haruslah sekecil betul ukurannya. Setiap pagi, para perempuan bangun tidur dengan perasaan yang tak nyaman tentang tubuh mereka. Fenomena eating disorder atau operasi pembesaran payudara hanyalah salah satu upaya mereka untuk memenuhi mitos kecantikan itu. Wolf menilai bahwa ada usaha dari industri kecantikan (kosmetik dan fashion) yang menjadi induk semang dari sistem patriarki untuk mengontrol kebebasan perempuan. Alih-alih menindas mereka secara langsung, patriarki dalam industri kecantikan menyerang perempuan dengan mitos kecantikan. Mitos kecantikan merupakan alat feminisasi perempuan yang membuat mereka terpenjara dalam ketidakpuasan terhadap tubuhnya, rasa tidak bisa memuaskan laki-laki, bahkan membenci dirinya sendiri (Wolf, 2002:10). Wolf menyebut bahwa mitos kecantikan lahir dari idealiasi yang melayani tujuan atau kepentingan tertentu. Wolf menyamakan mitos kecantikan di era modern seperti alat penyiksaan “iron maiden” atau konsep feminine mystique dari Betty Friedan yang awalnya dikira sudah tak mungkin terjadi lagi. Sayangnya, berkat iklan (media massa), mitos kecantikan yang sudah disuntikkan hegemoni patriarki terus-menerus direproduksi. Perempuan diserang secara fisik dan psikologis terhadap peran-peran mereka dengan cara menempatkan mereka dalam perasaan tidak pantas dan tidak nyaman. Berdasarkan pemikiran Wolf, kapitalisme dan patriarki sekali lagi bekerja sama untuk meraih tujuan yang berbeda. Ayu Utami dalam kumpulan esainya Si Parasit Lajang (2013:54) menyatakan bahwa kapitalisme memang hidup dari ketidakpuasan diri konsumen sehingga mereka terus-menerus mengonsumsi. Di satu sisi, patriarki terus-menerus mereproduksi dirinya untuk melanggengkan kekuasaan mereka atas kelompok yang tersubordinasi. Dengan kata lain, jika kapitalisme hidup dari uang perempuan, patriarki dengan berbagai cara berusaha menundukkan perempuan. Industri kecantikan menciptakan mitos tentang kecantikan. Mitos kecantikan dipelihara dan dipromosikan secara besar-besaran oleh media massa. Mitos kecantikan itu kita nikmati melalui figur perempuan di majalah-majalah kecantikan, para aktris yang filmnya kita tonton, para penyanyi tanah air yang belakangan membingungkan.Kita sebenarnya senang pada suaranya atau pada penampilan fisiknya, serta hegemoni kecantikan yang tiap hari dan berulang-ulang kita tonton melalui iklan di televisi. Pertanyaannya dari mana asal mitos kecantikan? Masing-masing budaya memiliki konstruksi sendiri tentang apa yang disebut cantik. Suku Karen di Thailand akan memandang cantik perempuan yang lehernya panjang seperti pula suku Dayak di Indonesia yang melihat cantik perempuan bertelinga panjang. Orang kulit putih mengidealkan kulit kecokelatan (yang biasa dilakukan dengan cara tanning) sementara orang Indonesia ingin sekali punya kulit putih (biasanya dengan pakai krim pemutih). Perempuan yang memiliki rambut lurus ingin memiliki rambut keriting dan perempuan berambut keriting ingin meluruskan rambutnya. Sebagai sebuah konstruksi kecantikan, idealisasi itu tidak abadi. Ia berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dan kepentingan. Konstruksi tidak perlu ditakuti selama sebagai perempuan kita telah memiliki pengetahuan dan mengenal diri sendiri. Dengan demikian, kepercayaan diri atas keunikan diri sendiri akan tumbuh dengan sendirinya. Hal yang mengerikan adalah mitos. Mitos hanya akan hidup bila dipelihara dan masyarakat mengamini. Mitos ini jika tidak segera dilupakan, akan mengubah semua perempuan menjadi boneka yang sama dan seragam. Hari ini saya menonton iklan shampoo di televisi dan tertawa. Konstruksi rambut ideal hari ini adalah rambut berwarna hitam, panjang, dan ikal bergelombang. Itu jenis rambut saya! Daftar Pustaka: Utami, Ayu. 2013. Si Parasit Lajang. Jakarta: KPG (diterbitkan pertama kali oleh Gagas Media tahun 2003). Wolf, Naomi. 2002. The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. New York: Harper Collins (diterbitkan pertama kali tahun 1991). Witriyatul Jauhariyah (Mahasiswa Program Studi Islam dan Kajian Gender, FIIS, UIN Sunan Kalijaga) [email protected] 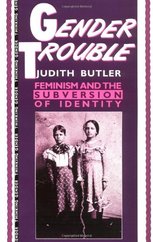 Judul : GENDER TROUBLE (FEMINISM AND THE SUBVERSION OF IDENTITY) Penulis : Judith P. Butler Penerbit : Routledge Tahun terbit : 1990 Tempat terbit : New York, United States of America Jumlah halaman: xii & 272 Judith P. Butler adalah filsuf post-strukturalis Amerika. Ia lahir di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, 24 Februari 1956, Judy–sapaan akrabnya--adalah guru besar di Jurusan Rhetoric and Comparative Literature, Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat. Dengan teori queer-nya, Butler memiliki kontribusi besar terhadap studi filsafat feminis, filsafat politik, dan etika. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah buku Gender Trouble (1990). Karya ini mendapatkan perhatian luas karena memperkenalkan teori performativitas untuk mengulas gender dan seksualitas. Bagi Butler, tidak ada identitas gender yang asli, semuanya dibentuk melalui ekspresi dan pertunjukan yang berulang-ulang hingga terbentuk identitas gender.
Buku ini juga menjadi referensi utama bagi pengembangan Queer Studies, yaitu kajian tentang keberagaman ekspresi gender dan seksualitas. Hal ini dilatar belakangi oleh kegelisahan Butler sendiri atas nasib pamannya yang harus terusir dari rumah karena seksualitasnya yang dianggap menyimpang. Selain itu, ia juga kerap menyaksikan ketidakadilan yang dialami para transgender yang mengalami kekerasan, seperti ditolak bekerja ataupun celaan stereotip. Maklum, selain sebagai akademisi ia juga aktif di kegiatan sosial, pergumulannya dengan kaum homoseksual dan heteroseksual banyak mengundang tanda tanya bagi dirinya. Gender Trouble adalah karya yang lahir dari sepuluh tahun perenungan dan bagian dari kehidupannya serta pergaulannya dengan komunitas-komunitas lesbian dan gay di Pantai Rehoboth, Amerika Serikat. Dalam bukunya, Gender Trouble, Butler menjelajahi bagaimana gender dan seksualitas dibakukan oleh angan-angan teori sosial. Ia terinspirasi sekaligus mendekonstruksi teori Foucault, Lacan, Freud, dan Simon de Beauvoir tentang seksualitas. Proyek kajiannya bertujuan menganalisis secara genealogis batas diskursus gender, seks, seksualitas, dan tubuh. Sebagai filsuf post-strukturalis sejati, Butler menerapkan konsep-konsep post-strukturalisme—tidak ada sesuatu di luar bahasa—secara konsisten. Strategi yang dilakukan Butler sangat unik, yakni mendekonstruksi “kosa gerakan” (the vocabularies of movement) yang telah menjadi pembatas manifestasi kemanusiaan, misalnya gender, seks dan tubuh. Fenomena sosial berkembang begitu cepat, sementara “kosa gerakan” berjalan di tempat sehingga kosa itu tumpul untuk memahami pergerakan realitas. Bagian pertama buku ini menyuguhkan “subject of sex/ gender/ desire”. Gender, bahkan seks, bagi Butler adalah “pertunjukan”, bukan esensi, atau ekspansi seks yang ada pada tubuh. Baginya, gender adalah drag, atau seperti drag, yaitu pertunjukan waria untuk menguji dan membuktikan mereka telah menghasilkan femininitas yang sebenarnya. Dalam pertunjukan itu, para juri telah menguji dan mengesahkan kehalusan kulit, kegemulaian gerak, kelembutan suara. Gender (kita) adalah “pertunjukan” atau hasil pertunjukan. Para jurinya adalah teman kita, orang tua kita, media dan sebagainya (1990: ix). Bagian kedua buku ini menyuguhkan tema “prohibition, psychoanalysis, and the production of heterosexual matrix”. Disini Butler mengungkapkan Masalah ‘ketidak normalan’ ini dapat lebih jelas dilihat apabila kita menggunakan salah satu kritikan Judith Butler tentang hubungan antara jenis kelamin dan gender yang disebut Butler sebagai Heterosexual Matrix. Menurut Butler, heterosexual matrix adalah :
Menurut Butler, dalam kerangka heterosexual matrix, jenis kelamin kita sudah ditentukan secara biologis. Dengan kata lain, jenis kelamin kita baik perempuan atau laki-laki berdasarkan konvensi budaya dan bahasa yaitu feminin dan maskulin. Jadi, yang menentukan apakah seseorang itu feminin atau maskulin adalah konstruksi sosial dan budaya berdasarkan jenis kelamin kita pada saat kita dilahirkan (1990: 35). Kepada Lacan, Butler mempertanyakan konsep psikoanalisis, terutama tentang “yang simbolik” (the symbolic) dan “yang nyata” (the real). Laki-laki adalah “yang nyata”, sedangkan perempuan adalah “yang simbolik”. Butler menyerang mengapa ada yang nyata dan ada yang tidak nyata. Bukankah ini bertentangan dengan konsep dasar orde simbolik: saya menyadari ada setelah menyadari saya yang ada dalam cermin (1990: 43). Bagian terakhir dalam buku ini menyuguhkan referensi tentang heteroseksualitas yang diciptakan melalui dialog dekonstruktif dengan karya-karya filsafat seperti Strauss, Irigaray, Foucault, dan de Beauvoir (1990: x). Salah satu filsuf yang diajak berdialog adalah Michel Foucault tentang kisah hidup Herculine Barbin. Barbin hidup pada 1838-1868, dia adalah seorang interseks yang diperlakukan sebagai perempuan setelah kelahirannya dan orang tuanya memberinya nama Alexina. Memoarnya mengungkapkan bahwa Alexina menganggap dirinya kurang atraktif dan sering menginap di rumah temannya, oleh karena itu sering dihukum. Tapi, Alexina anak pintar, pada 1858 dia melanjutkan pendidikan ke sekolah guru bergengsi Le Chateau. Di sana dia jatuh cinta kepada seorang guru bernama Sara. Walaupun sudah puber, Alexina belum menstruasi, dadanya juga masih rata. Dia sering mencukur kumis dan godeknya, tapi apa yang dilakukannya itu hanya membuat kumisnya lebih lebat. Kisah cinta Alexina dan Sara segera menyebar di sekolah. Karena mencintai sesama perempuan maka sekolah menghukumnya. Barbin mengaku dosa ke pendeta Jean-François-Anne Landriot di La Rochelle. Karena mendengar pengakuan Alexina terus-menerus, pendeta yang juga seorang perempuan menyarankan agar Alexina ke dokter untuk memeriksakan dan menemukan jenis kelaminnya yang sejati. Dokter yang memeriksa adalah Dr. Chestnet pada 1860. Dalam memoar tidak disebutkan hasil pemeriksaan itu, tapi dalam rekam medis disebutkan bahwa Alexina mempunyai penis yang sangat kecil, klitoris yang besar dalam vagina yang kecil, testikel dan tubuh laki-laki. Melihat klitoris yang besar, seseorang pasti mengharapkan vagina yang besar pula akan tetapi yang ada adalah cul-de-sac. Setelah kedokteran, Alexina berhadapan dengan pengadilan ketika hasil analisis dokter itu harus ditetapkan dalam hukum. Keputusan hukum menyebutkan bahwa Alexina adalah seorang laki-laki dan harus berpakaian laki-laki. Alexina berganti nama menjadi Abel Barbin. Abel Barbin meninggalkan pekerjaannya dan kekasihnya dan pergi ke Paris, dimana dia hidup dalam kemiskinan dan menulis memoar sebagai bagian dari terapi. Barbin akhirnya tewas bunuh diri dengan menghirup kompor gas. Foucault mempertanyakan dorongan pendeta, vonis dokter, dan keputusan hukum yang mengubah segalanya dan akhirnya menjadi penyebab kematian Barbin: “Bukankah secara komparatif, hermaprodit diperbolehkan dalam abad-abad sebelumnya?” Semasa Abad Pertengahan, setelah mencapai dewasa seorang hermafrodit diperbolehkan memilih mau menjadi laki-laki atau perempuan. Sedangkan dalam kasus Alexina, ilmu kedokteran memutuskan bahwa ia adalah seorang laki-laki dan aturan itu harus diikuti. Dianggap suatu penyelewengan bila identitas laki-laki tapi tidak menampilkan peran dan citra laki-laki (1990: 96). Memoar Alexina berisi dua hal utama perlawanannya terhadap strategi regulatif untuk kategorisasi seksualitas dan romantisasi masa sebelum dia divonis menjadi laki-laki. Alexina sangat menikmati sebelum ketetapan hukum ini sebagai the happy limbo of non-identity, fase ketika dirinya melampaui kategori seks dan identitas, kenikmatan dalam sistem sosial tanpa seks yang univocal. Ungkapaanya dalam bab terakhir : “Di satu sisi Foucault ingin mengatakan bahwa tidak ada jenis kelamin yang berdiri sendiri, yang tidak dihasilkan interaksi diskursus dan kuasa, tapi di sisi lain Foucault juga berpandangan ada sebuah keserbaragaman kenikmatan yang berdiri sendiri dan bukan efek dari pertukaran kuasa/diskursus. Dengan kata lain, Foucault mengakui adanya multiplisitas libidinal pradiskursif yang secara efektif mengasumsikan seksualitas di depan hukum, dan seksualitas menunggu emansipasi dari hambatan seks. Di sisi lain, Foucault secara resmi menyatakan bahwa seksualitas dan kuasa itu koekstensif seperti saudara kembar, dan kita tidak bisa berpikir bahwa dengan mengatakan “ya” kepada seks, “tidak” kepada kuasa. Dalam mode antiyuridis dan antiemansipatoris, Foucault yang “resmi” berargumentasi bahwa seksualitas selalu berada dalam matriks kekuasaan, yaitu selalu diproduksi dan dikonstruksi dalam praktik kesejarahan tertentu, diskursif dan institutional” (1990: 123). Menurut Butler, ada dualisme pemikiran Foucault. Di sinilah masalahnya menurut Butler. Disatu sisi Foucault, mengakui ada kenikmatan di luar konstruksi sosial. Namun disisi lain menurutnya segala sesuatu terbentuk oleh relasi kuasa (dibentuk oleh kostruksi sosial). Dalam pandangan Butler, memoar Alexina menawarkan kesempatan untuk membaca Foucault against himself karena mengungkapkan penderitaan, tekanan, tipuan, kerinduan dan kekecewaan yang mendalam. Alexina tidak pernah menyebut keadaan anatominya, tapi dia sering mengaitkan kelaminnya itu sebagai “kesalahan alami, kegelandanganan metafisis, nafsu yang tidak pernah puas” yang ditransformasikan dalam kemarahan kepada laki-laki dan berikutnya kepada dunia secara keseluruhan menjelang bunuh dirinya. Satu yang disenanginya adalah ketika berada di atas kuburan ayahnya: karena memberi pengertian dia bisa menginjak-injak tulang, dan dia membayangkan dokter yang telah memvonisnya sebagai laki-laki itu seratus meter terkubur di dalam. Ditulis dalam nada yang sentimental dan melodramatik, kemudian itu menginformasikan semacam krisis tidak kunjung usai yang diakhiri dalam tindakan bunuh diri. Inti dari pemikiran Butler adalah tidak adanya kondisi alamiah bagi manusia selain penampakan tubuhnya. Seks, gender, maupun orientasi seksual adalah konstruksi sosial. Hal ini dapat dicontohkan melalui fenomena transseksual. Seorang yang telah melakukan transseksual, yang diasumsikan telah ‘merubah’ kondisi alamiahnya. Misalnya seorang pria yang merasa beridentitas feminin, mengubah jenis seksnya menjadi tubuh perempuan. Maka secara otomatis, setelah seks sebagai fakta biologis tersebut diubah menjadi yang sebaliknya, akan berdampak terhadap perubahan yang menentukan keabsahan dari individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan the fixed rules atas seks, gender, dan orientasi seksual. Kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah baik seks, gender, maupun orientasi seksual adalah sesuatu yang sifatnya cair (fluid), tidak alamiah, dan berubah-ubah, (serta dikonstruksi oleh kondisi sosial). Maka jika ditinjau dari pemikiran Judith Butler, transgender dan homoseksual bukanlah suatu penyimpangan sosial, melainkan suatu variasi dalam identitas manusia yang didasarkan pada tindakan performatif (1990: 96). Salah satu teori yang juga dikemukan Judith Butler dalam buku ini adalah teori performativitas. Dalam teorinya ini Butler menolak prinsip identitas yang memilki awal dan akhir. Dari sinilah dapat dimengerti bahwa pandangan Butler seseorang dapat memilki identitas maskulin dan feminin dalam waktu yang bersamaan atau feminin dan maskulin di waktu yang berbeda. Demikian pula dengan male feminine atau female maskulin. Hal ini tentu berpengaruh pula pada persoalan orientasi seksual. Jika identitas seksual seseorang tidak final, tidak stabil, seharusnya tidak ada keharusan seorang perempuan menyukai pria dan sebaliknya. Namun masyarakat tentu tidak menghendaki yang demikian. Seperti yang juga telah disebutkan di atas, subjek dibentuk oleh culture dan diskursus, dimana ada suatu aturan yang disebarkan melalui repetisi. Aturan ini membuat suatu fenomena seolah-olah heteroseksual merupakan hubungan yang normatif antara seks, gender, dan orientasi sesksual. Seorang dengan tubuh male, harus berprilaku maskulin dan menyukai female sebagai lawan jenisnya, dan sebaliknya. Aturan ini sudah terpasung dari awal, yang dikutip Butler dari Melancolia Frued bahwa bayi telah menolak incest dan homoseksual. Sehingga apa yang berbeda dari kewajiban alamiah tersebut dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan norma (1990: 57). Dalam paradigma heteroseksualitas, gender sangat menentukan tindakan-tindakan manusia. Sedangkan dalam pemikiran Butler, gender atau identitas seksual hadir setelah individu melakukan tindakan performatif. Inti pemikirannya adalah tidak adanya kondisi alamiah bagi manusia kecuali penampakan tubuhnya. Dengan kata lain, seks, gender, maupun orientasi seksual adalah konstruksi sosial. Fakta ini dapat dilihat pada fenomena transseksual, misalnya seorang pria yang merasa beridentitas feminin, mengubah jenis seksnya menjadi tubuh perempuan. Maka, dia harus bertindak sesuai dengan ketentuan (the fixed rules) atas seks, gender,dan orientasi seksual (1990: 66). Teori performativitas gender memperlihatkan bagaimana diskursus maupun tindakan yang terus dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang menghasilkan pengertian tentang seks dan gender baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Proses materialisasi gender yang selama ini dilakukan berada dalam sistem hegemoni heteroseksual, sehingga jika gender seseorang keluar dari norma sosial yang berlaku, dikatakan menyimpang. Inilah kekerasan gender dari hasil konsepsi performativitas yang tunduk pada hegemoni tertentu. Untuk itu dibutuhkan proses negosiasi terhadap norma-norma sehingga menghasilkan performativitas gender yang lebih terbuka dan tanpa kekerasan. Teori performativitas gender memperlihatkan bahwa gender terjadi karena proses materialisasi dan konstruksi. Maka disinilah letak kajian gender yang bersentuhan dengan pemikiran Judith Butler yang membongkar paradigma gender khususnya yang telah dilakukan oleh para feminis, yang secara tajam melakukan pemilahan antara seks (sebagai kodrat) dan gender (sebagai konstruksi). Dalam pemilahan tersebut, yang dipahami sebagai seks sebenar-benarnya adalah gender itu sendiri, sebab jika seks laki-laki dan perempuan dikatakan kodrat dengan segala kriteria yang mengikutinya, bukankah kriteria tersebut juga adalah konstruksi, sebagaimana gender juga dipahami konstruksi. Teori performativitas gender memperlihatkan bagaimana diskursus maupun tindakan yang terus dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang menghasilkan pengertian tentang seks dan gender baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Proses materialisasi gender yang selama ini dilakukan berada dalam sistem hegemoni heteroseksual, sehingga jika gender seseorang keluar dari norma sosial yang berlaku, dikatakan menyimpang. Inilah kekerasan gender dari hasil konsepsi performativitas yang tunduk pada hegemoni tertentu. Untuk itu dibutuhkan proses negosiasi terhadap norma-norma sehingga menghasilkan performativitas gender yang lebih terbuka dan tanpa kekerasan. Akhiriyati Sundari (Mahasiswi Islam dan Kajian Gender Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga) [email protected]  Judul : Penghancuran Gerakan Perempuan (Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI) Penulis : Saskia E. Wieringa Penerbit : Galang Press Tahun terbit : 2010 Tempat terbit : Yogyakarta Tebal buku : 542 halaman kami bukan lagi
bunga pajangan yang layu dalam jambangan cantik dalam menurut indah dalam menyerah molek tidak menentang ke neraka mesti mengikut ke sorga hanya menumpang kami bukan juga bunga tercampak dalam hidup terinjak-injak penjual keringat murah buruh separuh harga tiada perlindungan tiada persamaan sarat dimuati beban kami telah berseru dari balik dinding pingitan dari dendam pemaduan dari perdagangan di lorong malam dari kesumat kawin paksaan “kami manusia!” (Sugiarti, Lekra 1962:65) Sepintas, puisi di atas menggambarkan sesosok perempuan yang mewakili kaumnya, memberontak terhadap aneka pandangan berikut fakta yang melingkupi mereka dalam hidup sehari-hari. Perempuan adalah sosok mandiri dalam kesejatian sebagai manusia. Seutuhnya. Tidak tergantung pada entitas lain dalam hal ini laki-laki, dimana akidah mengatupkan kelopak kebebasannya, jika si laki-laki atau suami ke surga maka perempuan hanya follower, sementara jika suami ke neraka maka perempuan pun turut ikut. Puisi adalah sisi terdalam pikiran manusia yang ditumpahkan melalui bahasa. Akan tetapi, jika saja, ya jika saja puisi separuh pamflet sebagaimana puisi Widji Thukul—apa adanya, membatasi hanya sedikit metafora—yang menggambarkan perjuangan yang menyalak—dalam baris terakhir, “kami manusia”—tidak dibungkam oleh sejarah paling hitam di Indonesia, peristiwa 1965, adalah niscaya sejarah menorehkan tinta kemilau bagi nasib perempuan. Adalah Saskia Eleonora Wieringa, seorang profesor Universiteit van Amsterdam di Belanda dan baru-baru ini menjadi Ketua IPT 1965 (International people’s Tribunal 1965) yang menggelar sidang pengadilan rakyat internasional tersebut pada pertengahan November 2015 lalu di Belanda, menuliskan apa yang selama ini disebut “sejarah yang disembunyikan” dari gerakan perempuan paling progresif dan revolusioner di Indonesia, Gerwani, dalam buku bertajuk Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca kejatuhan PKI. Buku ini dilarang beredar dan bahkan penulisnya dicekal untuk masuk ke Indonesia di zaman rezim orde baru Suharto. Pada malam 1 Oktober 1965 itu beberapa perempuan Gerwani melakukan penyiksaan sadis terhadap enam Jenderal Angkatan Darat dan seorang perwira yang diculik dan disekap di kawasan Lubang Buaya sebelum kemudian mayat para jenderal itu dimasukkan ke dalam sumur. Dikabarkan bahwa mereka mencungkil mata, menyilet-nyilet penis para jenderal hingga berdarah-darah, memegang dan menggosok-gosokkan penis itu ke vagina mereka sendiri, lalu merangkumnya dalam pesta seks berlatar tarian “Harum Bunga”. Bugil, liar dan nakal. Diiringi lagu Genjer-Genjer, lagu daerah Banyuwangi yang telah direproduksi maknanya sedemikian rupa sebagai magis-mistis dan subversif. Demikian cuplikan film Pengkhianatan G30S/PKI yang populer di tahun 1980-an hingga sebelum 1998 lantaran sebagai film wajib tonton saban tahun di TVRI dan ungkapan nan populer, “Darah itu merah, Jenderal!” kerap didengung-dengungkan. Sekelumit narasi juga dipropagandakan secara masif dalam berita-berita yang ditulis oleh koran Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Dua harian yang hidup dan diperbolehkan hidup pada saat itu untuk membungkam media-media lain dari ‘situasi panas’ karena peristiwa malam 30 September/ dini hari 1 Oktober 1965. Seikat dengan narasi itu dikobarkan berita yang berapi-api bahwa perempuan-perempuan Gerwani adalah perempuan tak bermoral, bejat, dan terminologi sundal lainnya. Lebih jauh, narasi itu dikemas dan ‘disejarahkan’ sebagai monumen ingatan dalam relief museum Lubang Buaya. Kini, 50 tahun telah terlipat waktu. Suara-suara yang selama ini disenyapkan membuka diri. Dokter yang mengautopsi jenazah para jenderal kala itu pun menyangkal narasi itu dengan mengatakan bahwa tak ada temuan sedikitpun bahwa penis para jenderal ada bekas sayatan silet maupun mata yang tercungkil. Sempurna sudah fitnah terhadap Gerwani, demikian simpulan usai membaca buku ini. Gerwani: Organisasi Perempuan Militan Sejarah berdirinya gerwani diwarnai proses panjang dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun sejak organisasi Gerwis pertama kali berdiri sebelum kemudian bermetamorfosis menjadi Gerwani. Pada tanggal 4 Juni 1950, enam wakil organisasi perempuan berkumpul di Semarang, sebuah kota yang secara historis memiliki ‘nilai’ lantaran PKI didirikan di kota ini. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk membuat organisasi perempuan bersama yang dinamakan Gerwis (Gerakan Wanita Sedar). Enam organisasi yang mendirikan Gerwis adalah Rukun Putri Indonesia (Rupindo, Semarang), Persatuan Wanita Sedar (Surabaya), Isteri Sedar (Bandung), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo, Kediri), Wanita Madura (Madura), dan Perjuangan Putri Republik Indonesia (Pasuruhan). Para pendiri Gerwis ini berasal dari latar belakang sosial berbeda, bahkan banyak di antaranya dari keturunan priayi rendah. Terdapat pula beberapa orang yang pernah ambil bagian dalam gerakan bawah tanah dengan ilham komunisme, misal Umi Sardjono (hlm. 214-215). Semua pendiri ini adalah para perempuan yang terjun dalam gerakan nasional, bahkan banyak diantaranya yang menjadi anggota pasukan bersenjata. Dalam pertemuan tersebut disepakati ketua pertama Gerwis adalah Tris Metty yang pernah menjadi anggota Laskar Wanita Jawa Tengah. Konstitusi yang dirumuskan Gerwis adalah menegaskan diri sebagai organisasi non politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Namun, secara tak langsung PKI memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam proses pembentukan hingga arah politik Gerwis. Sebagaimana yang dijelaskan Ny. Chalisah, salah satu pendiri Gerwis, bahwa ‘partai meminta saya untuk membangun organisasi perempuan komunis di dalam partai’ (hlm. 218). Tetapi, keinginan para pemimpin PKI ini bukanlah satu-satunya faktor penyebab berdirinya Gerwis. Lebih besar dari itu, hasrat bersama untuk tercapainya kemerdekaan nasional dan berakhirnya praktik feodalisme adalah faktor terbesar berdirinya Gerwis (hlm. 219). Kongres pertama Gerwis berada dalam masa yang sulit mengingat beberapa anggotanya masih berada dalam penjara. Dalam kesempatan ini, komponen komunis dan feminis bercampur dalam satu organisasi, lalu beberapa langkah diambil untuk mengucilkan sayap feminis sebagaimana direpresentasikan oleh S.K. Trimurti (istri dari Sayuti Melik, tokoh penting dalam Proklamasi Kemerdekaan 1845, yaitu pengetik naskah Proklamasi). Trimurti mengundurkan diri dari pencalonan, 1957 ia menarik diri dari jajaran pimpinan, 1965 ia keluar dari keanggotaan (hlm. 225). Pengalaman perdana bulan-bulan awal dibentuknya Gerwis adalah berada di garda depan perang kemerdakaan, turut aktif dalam menentang Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia. Gerwis juga menentang perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) yang mereka anggap hanya akan mengembalikan modal asing ke Indonesia. Sepanjang kongres pertama dan kedua, Gerwis aktif dalam tiga front: pertama, dalam bidang politik mereka berjuang terhadap ‘elemen reaksioner’, yakni peristiwa 17 Oktober di mana sejumlah komandan Angkatan Darat (AD) melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang hendak mengurangi kekuasaan militer. Kedua, dalam tataran feminisme mereka menentang PP 19 yang mengatur masalah perkawinan yang diskriminatif. ketiga, mendukung perjuangan umum bagi Undang-Undang Perkawinan Demokratis serta dengan lunak menghindari konfontrasi langsung dengan Presiden Soekarno. Selain itu, di tingkat lokal, Gerwis ikut serta dalam kampanye BTI (Barisan Tani Indonesia) melawan tindakan pemerintah yang berusaha mengusir kaum tani dari bekas perkebunan yang telah mereka duduki (hlm. 227-228). Tidak tanggung-tanggung, mereka berani ‘pasang badan’ terhadap traktor maut yang hendak merebut tanah itu. Kongres kedua Gerwis pada tahun 1954 mengubah dirinya menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan memilih Umi Sarjono–yang juga merupakan anggota PKI−sebagai ketuanya. Perkembangan pesat tampak mencolok. Di Surabaya, Gerwis memiliki 40 cabang dengan 6.000 anggota dan pada tahun 1954, anggotanya telah meliputi 80.000 orang. Pada aras ini ada arah yang berubah dari Gerwani, yakni dari organisasi kader menjadi organisasi massa. Tawaran dilakukan kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin tanpa memandang latar belakang sosial. Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) misalnya, para pemimpinnya berasal dari keluarga Pamong Praja, atau memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Strategi ini berhasil merekrut banyak kader, karena perempuan yang bergabung menilai Gerwani sebagai satu-satunya pihak yang sudi membantu memecahkan persoalan mereka sehari-hari. Selain itu, Gerwani juga dinilai sebagai organisasi alternatif di luar organisasi perempuan yang sudah ada dan menawarkan solusi konkret atas permasalahan yang terjadi sehari-hari. Lalu pada saat kongres ketiga, Gerwani mulai menampakkan diri dengan condong kepada isu perpolitikan nasional. Pergeseran ini tampak pada isu yang disuarakan, dari semula persoalan-persoalan feminis seperti masalah perkawinan, menjadi masalah ‘sosial’ yakni kenaikan kebutuhan harga bahan pokok makanan. Gerwani ingin mengubah dirinya betul-betul menjadi organisasi massa dengan skala nasional lebih luas. Untuk itu Gerwani memfokuskan diri pada bagaimana memimpin gerakan yang lebih luas, membangun gerakan massa—sebagaimana garis PKI dalam emansipasi perempuan yang merumuskan bahwa sosialisme harus dicapai lebih dulu sebelum bicara masalah spesifik tentang urusan perempuan. Gerwani juga merambah partisipasi dalam politik nasional seperti terlibat dalam Trikora, perang memperebutkan Irian Barat dan menyerukan agar gerakan perempuan bersatu untuk itu. Dari sini mulai ditemukan titik jelas bahwa Gerwani sebagai organisasi pergerakan perempuan yang memiliki militansi kuat di antara pengikutnya. Hal tersebut juga tak bisa dilepaskan dari ideologi yang mewarnai garisnya. Feminisme, sosialisme, dan nasionalisme, dalam Tujuan dan Kewajiban Gerwani (1954), Gerwani membuat rumusan bagaimana kondisi perempuan kala itu yang “setengah kolonial setengah feodal” sesungguhnya adalah gerakan perempuan yang independen tidak berafiliasi atau menjadi underbouw partai politik manapun (hlm. 234-235). Bahkan, periode antara kongres pertama dan kedua itulah Gerwani dapat dikatakan paling menampakkan ideologi feminisnya. Sementara pada ranah Sosialis jelas sekali bagaimana Gerwani mampu kerjasama dan mengorganisir dirinya dengan BTI dan SOBSI untuk menuntaskan kasus-kasus upah rendah di kalangan buruh perempuan. Pada pandangan politik secara umum—berbingkai nasionalisme. Gerwani mengadakan perayaan Hari Perempuan Internasional (HPI) 1955 dengan aksi perdamaian dan protes terhadap percobaan persenjataan nuklir serta pendudukan Belanda atas Irian Barat. Kemudian pada Januari 1957 melakukan penuntutan atas melambungnya harga bahan pokok. Ide Gerwani terkait sosialisme bisa ditengarai dari kedekatan mereka dengan PKI. Pergulatannya menjadi menantang. Kaitannya dengan sosialisme dus marxisme, Gerwani bergulat dengan sejumlah problem teoritis, yakni pertama, perjuangan perempuan harus ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan kelas. Ketika komunisme ditegakan, maka perempuan sebagai subordinasi keluarga akan lenyap dan ‘keluarga proletar bahagia’ akan menggantikannya (hlm 83). Tentu saja perspektif ini bermasalah, sebagaimana dikemukakan Wieringa, pandangan Engels tentang keluarga yang ditulisnya dalam The Origin of the Family (1884) dianggap ahistoris, terutama tentang masyarakat suku. Kedua, karena perempuan berada dalam rumah tangga, maka teori marxis hanya memiliki sedikit pengertian terhadap peran perempuan di tengah masyarakat. Ketiga, karena eksploitasi perempuan dalam keluarga dipandang sebagai penemuan kapitalis, maka pemecahannya dicari di luar rumah tangga, yakni perempuan harus memasuki produksi masyarakat, pekerjaan rumah tangga harus disosialisasi. Dan lalu, lantaran penindasan seksual dihubungkan dengan kapitalisme, sosialisme akan memberikan jalan keluar dan oleh karena itu tidak perlu adanya perjuangan perempuan secara sadar guna memperbaiki perilaku laki-laki maupun mengubah hubungan antar-pribadi. Gerwani dan Pergerakan Perempuan Lokal hingga Global Panggung Gerwani yang dirumuskan secara pasti membangun sebuah gerakan massa, menjadikan Gerwani merangkul dan mencoba memengaruhi gerakan perempuan Indonesia. Garis sosialisme mesti dicapai terlebih dahulu baru kemudian perjuangan feminis bisa didapatkan, demikian ujaran yang didapat dari PKI. Sebagaimana ‘tidak ada tindakan revolusioner/sosialis tanpa melibatkan perempuan’. Gerwani berhubungan baik dengan Perwari dan di tingkat lokal Gerwani ‘bergandengan’ dengan BTI mengorganisir buruh tani dan terlibat beberapa pelaksanaan land reform agraria. Akan tetapi, Gerwani sempat ‘dijauhi’ organisasi-organisasi perempuan yang lain karena bersikap pasif terhadap perkawinan Sukarno dengan Hartini dalam sistem poligami. Garis ‘halus’ yang digunakan Gerwani dianggap sebagai apologetik belaka. Di sini tampak sikap yang mendua, memperjuangkan sosialisme namun kembali ‘tunduk’ pada feodalisme. Di tingkat global, Gerwani memperluas kancahnya dengan menjadi anggota dari WIDF (Women’s International Democratic Federation), Gerwani turut berpartisipasi dalam Congress of Women di Paris. Adapun tujuan WIDF secara garis besar adalah memperjuangkan hak kaum perempuan sebagai ibu, pekerja dan warga negara, memperjuangkan hak anak-anak untuk hidup, kesejahteraan dan pendidikan, mendukung kemerdekaan nasional, penghapusan apartheid, diskriminasi rasial dan dan fasisme. Kendati hubungan diantara Gerwani dan WIDF awalnya sangat harmonis dan saling mendukung, sejak tahun 1960 mulai tegang dan puncaknya terjadi pada kongres WIDF 1963. Meningkatnya militansi Gerwani dan makin dekatnya Gerwani dengan Tiongkok menjadi salah satu penyebabnya. Gerwani yang ikut memobilisasikan kadernya dalam perjuangan pembebasan Irian Barat--dirasa tidak sesuai dengan asas WIDF yaitu perdamaian—menjadi penyebab yang lain. Pada tahun 1963, hubungan Gerwani dengan WIDF semakin memburuk. Dalam kongres bulan Juni, timbul pertentangan karena mayoritas anggota hendak membawa organisasi ke arah ‘feminis dan pasifis’. Bagi Gerwani, tidak akan ada perdamaian selama imperialisme masih ada di dunia. Meskipun WIDF masih bisa memahami apa yang dilakukan Gerwani dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat adalah dalam rangka perjuangan nasional dan kemerdekaan 100 persen, tetapi dalam isu konfrontasi dengan Malaysia, WIDF sama sekali tidak mendukungnya karena dinilai tidak memiliki alasan yang kuat. Sementara ranah persinggungan sedari awal yang juga berbuntut ‘panas’ adalah sikap Gerwani yang terlalu frontal terhadap Undang-Undang Perkawinan Demokratis, di mana Gerwani menolak poligami, sementara organisasi perempuan Islam sebaliknya. Bila menilik ke belakang, dikeluarkannya Tris Metty dari keanggotaan juga lantaran dipandang memberi warna legal pada lesbianisme, sesuatu yang kala itu menjadi paradoks perjuangan ‘perempuan timur yang bermoral’. Fitnah Gerwani: PKI, Sukarno, dan Peristiwa Lubang Buaya Dari 1954 hingga 1965, Gerwani menyatakan diri sebagai organisasi yang tidak berpihak pada partai politik. Baru kemudian ketika pemerintah menginstruksikan kepada organisasi massa untuk memilih pasangan partai politik dalam kerangka Nasakom, maka Gerwani dipaksa berafiliasi dengan PKI. Aspirasi ideologis Gerwani dalam hal ini adalah berdasarkan tokoh Srikandi, yang menyematkan perjuangan di area politik. Langkah Gerwani misalnya dalam memberikan ‘kursus-kursus’ penyadaran politik di tingkat daerah menjadi kontroversi besar-besaran di desa-desa dengan reaksi konservatif yang keras. Gelombang progresivitas Gerwani juga diluapkan dalam majalah Gerwani yakni Api Kartini, agar menyulut kesadaran perjuangan perempuan. Wacana ‘feminisme’ dan ‘sosialisme’ dalam tubuh Gerwani menjadi ‘kabur’ pada saat itu, lantaran perjuangan politik yang lebih populis sangat diutamakan. Kedekatan secara pribadi anggota Gerwani dengan orang-orang PKI tak ayal memberi warna pula dalam tubuh organisasi. Tak jarang ditemukan ketika si suami anggota PKI, si ibu anggota Gerwani sekaligus BTI sekaligus SOBSI, lalu sang anak anggota Pemuda Rakyat. Dialektika demikian membantu pembacaan akan ‘warna merah’ dalam Gerwani. Kurun Demokrasi Terpimpin Sukarno, Gerwani pun tak kalah ‘intim’ dekat dengan Sukarno. Tercatat begitu berapi-apinya Sukarno hadir dan memberikan sambutan dalam Kongres Gerwani keempat--terakhir sebelum meletus peristiwa G30S. Sukarno kian membakar api semangat anggota Gerwani dengan pemikiran Sukarno yang kala itu cenderung ke kiri. Nama Clara Zetkin, pemimpin perempuan sosialis dan partai sosialis terbesar dari Jerman berulang-ulang diucapkan sebagai role type perempuan sosialis pejuang. Maka tak mengherankan kala itu, anggota Gerwani terbiasa melek dengan bacaan-bacaan sosialis-marxis. Gerwani tampil menjadi organisasi perempuan ‘radikal’ yang berjuang di garda depan politik Nasakom Sukarno. Pengiriman delegasi pada pelatihan fisik demi menghadapi Trikora di Irian Barat dan Dwikora dalam pengganyangan Malaysia, kian memampatkan dugaan kemesraan Gerwani dengan arah politik Sukarno. Pada akhirnya, meletusnya malam 30 September 1965 menjadi penutup rangkaian panjang 15 tahun Gerwani hidup di Indonesia. Sebuah gerakan kup terhadap pemerintahan resmi Sukarno yang diwarnai banjir darah para jenderal AD, membuat si kambing PKI berikut organisasi-organisasi underbouw-nya, simpatisannya, sekaligus siapa saja yang pernah dekat dengannya tak terkecuali Gerwani turut terseret dalam bumi hangus yang dilakukan oleh Suharto. Pencidukan paksa, penghilangan nyawa, pemenjaraan, penyiksaan, penghilangan paksa, pemutusan mata rantai hidup kemanusiaan orang-orang di sekelilingnya dilakukan pada periode panjang sepanjang Suharto berkuasa secara ‘ganjil’, yakni dengan selembar surat perintah yang kontroversial bernama Supersemar itu. Tuduhan sadis dan keji diawali dari Gerwani dianggap sebagai sayap perempuan PKI. Kemudian berlanjut pada Gerwani adalah organisasi bejat tidak bermoral, ateis yang terlibat dalam pembunuhan sadis para jenderal di Lubang Buaya yang di kemudian hari dinamai Pahlawan Revolusi. Kesimpulan Dibumihanguskannya Gerwani hingga ‘ke akar-akarnya’, tak pelak menandai babak baru lenyapnya organisasi perempuan yang begitu penting bagi bangunan keindonesiaan pasca kolonial. Orde baru menanam benih hibrida dengan pembungkaman perempuan dalam fungsi ‘kodrati’ dalam rumusan mereka. Para perempuan ditalikan kuat dalam satu ideologi ibuisme melalui organisasi-organisasi bentukan negara dari tingkat pusat hingga keluarga. Tak ada yang tak berada dalam kontrol orde baru. Perempuan ditarik total dalam misi ‘domestik’ dalam naungan ideologi patriarki. Gemilangnya hasil-hasil pemikiran dan gerakan progresif-revolusioner Gerwani pada bangunan Indonesia dilenyapkan dari panggung sejarah. |
AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
September 2021
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed