|
Witriyatul Jauhariyah (Mahasiswa Program Studi Islam dan Kajian Gender, FIIS, UIN Sunan Kalijaga) [email protected] 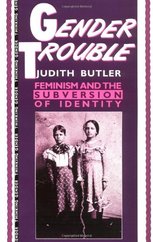 Judul : GENDER TROUBLE (FEMINISM AND THE SUBVERSION OF IDENTITY) Penulis : Judith P. Butler Penerbit : Routledge Tahun terbit : 1990 Tempat terbit : New York, United States of America Jumlah halaman: xii & 272 Judith P. Butler adalah filsuf post-strukturalis Amerika. Ia lahir di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, 24 Februari 1956, Judy–sapaan akrabnya--adalah guru besar di Jurusan Rhetoric and Comparative Literature, Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat. Dengan teori queer-nya, Butler memiliki kontribusi besar terhadap studi filsafat feminis, filsafat politik, dan etika. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah buku Gender Trouble (1990). Karya ini mendapatkan perhatian luas karena memperkenalkan teori performativitas untuk mengulas gender dan seksualitas. Bagi Butler, tidak ada identitas gender yang asli, semuanya dibentuk melalui ekspresi dan pertunjukan yang berulang-ulang hingga terbentuk identitas gender.
Buku ini juga menjadi referensi utama bagi pengembangan Queer Studies, yaitu kajian tentang keberagaman ekspresi gender dan seksualitas. Hal ini dilatar belakangi oleh kegelisahan Butler sendiri atas nasib pamannya yang harus terusir dari rumah karena seksualitasnya yang dianggap menyimpang. Selain itu, ia juga kerap menyaksikan ketidakadilan yang dialami para transgender yang mengalami kekerasan, seperti ditolak bekerja ataupun celaan stereotip. Maklum, selain sebagai akademisi ia juga aktif di kegiatan sosial, pergumulannya dengan kaum homoseksual dan heteroseksual banyak mengundang tanda tanya bagi dirinya. Gender Trouble adalah karya yang lahir dari sepuluh tahun perenungan dan bagian dari kehidupannya serta pergaulannya dengan komunitas-komunitas lesbian dan gay di Pantai Rehoboth, Amerika Serikat. Dalam bukunya, Gender Trouble, Butler menjelajahi bagaimana gender dan seksualitas dibakukan oleh angan-angan teori sosial. Ia terinspirasi sekaligus mendekonstruksi teori Foucault, Lacan, Freud, dan Simon de Beauvoir tentang seksualitas. Proyek kajiannya bertujuan menganalisis secara genealogis batas diskursus gender, seks, seksualitas, dan tubuh. Sebagai filsuf post-strukturalis sejati, Butler menerapkan konsep-konsep post-strukturalisme—tidak ada sesuatu di luar bahasa—secara konsisten. Strategi yang dilakukan Butler sangat unik, yakni mendekonstruksi “kosa gerakan” (the vocabularies of movement) yang telah menjadi pembatas manifestasi kemanusiaan, misalnya gender, seks dan tubuh. Fenomena sosial berkembang begitu cepat, sementara “kosa gerakan” berjalan di tempat sehingga kosa itu tumpul untuk memahami pergerakan realitas. Bagian pertama buku ini menyuguhkan “subject of sex/ gender/ desire”. Gender, bahkan seks, bagi Butler adalah “pertunjukan”, bukan esensi, atau ekspansi seks yang ada pada tubuh. Baginya, gender adalah drag, atau seperti drag, yaitu pertunjukan waria untuk menguji dan membuktikan mereka telah menghasilkan femininitas yang sebenarnya. Dalam pertunjukan itu, para juri telah menguji dan mengesahkan kehalusan kulit, kegemulaian gerak, kelembutan suara. Gender (kita) adalah “pertunjukan” atau hasil pertunjukan. Para jurinya adalah teman kita, orang tua kita, media dan sebagainya (1990: ix). Bagian kedua buku ini menyuguhkan tema “prohibition, psychoanalysis, and the production of heterosexual matrix”. Disini Butler mengungkapkan Masalah ‘ketidak normalan’ ini dapat lebih jelas dilihat apabila kita menggunakan salah satu kritikan Judith Butler tentang hubungan antara jenis kelamin dan gender yang disebut Butler sebagai Heterosexual Matrix. Menurut Butler, heterosexual matrix adalah :
Menurut Butler, dalam kerangka heterosexual matrix, jenis kelamin kita sudah ditentukan secara biologis. Dengan kata lain, jenis kelamin kita baik perempuan atau laki-laki berdasarkan konvensi budaya dan bahasa yaitu feminin dan maskulin. Jadi, yang menentukan apakah seseorang itu feminin atau maskulin adalah konstruksi sosial dan budaya berdasarkan jenis kelamin kita pada saat kita dilahirkan (1990: 35). Kepada Lacan, Butler mempertanyakan konsep psikoanalisis, terutama tentang “yang simbolik” (the symbolic) dan “yang nyata” (the real). Laki-laki adalah “yang nyata”, sedangkan perempuan adalah “yang simbolik”. Butler menyerang mengapa ada yang nyata dan ada yang tidak nyata. Bukankah ini bertentangan dengan konsep dasar orde simbolik: saya menyadari ada setelah menyadari saya yang ada dalam cermin (1990: 43). Bagian terakhir dalam buku ini menyuguhkan referensi tentang heteroseksualitas yang diciptakan melalui dialog dekonstruktif dengan karya-karya filsafat seperti Strauss, Irigaray, Foucault, dan de Beauvoir (1990: x). Salah satu filsuf yang diajak berdialog adalah Michel Foucault tentang kisah hidup Herculine Barbin. Barbin hidup pada 1838-1868, dia adalah seorang interseks yang diperlakukan sebagai perempuan setelah kelahirannya dan orang tuanya memberinya nama Alexina. Memoarnya mengungkapkan bahwa Alexina menganggap dirinya kurang atraktif dan sering menginap di rumah temannya, oleh karena itu sering dihukum. Tapi, Alexina anak pintar, pada 1858 dia melanjutkan pendidikan ke sekolah guru bergengsi Le Chateau. Di sana dia jatuh cinta kepada seorang guru bernama Sara. Walaupun sudah puber, Alexina belum menstruasi, dadanya juga masih rata. Dia sering mencukur kumis dan godeknya, tapi apa yang dilakukannya itu hanya membuat kumisnya lebih lebat. Kisah cinta Alexina dan Sara segera menyebar di sekolah. Karena mencintai sesama perempuan maka sekolah menghukumnya. Barbin mengaku dosa ke pendeta Jean-François-Anne Landriot di La Rochelle. Karena mendengar pengakuan Alexina terus-menerus, pendeta yang juga seorang perempuan menyarankan agar Alexina ke dokter untuk memeriksakan dan menemukan jenis kelaminnya yang sejati. Dokter yang memeriksa adalah Dr. Chestnet pada 1860. Dalam memoar tidak disebutkan hasil pemeriksaan itu, tapi dalam rekam medis disebutkan bahwa Alexina mempunyai penis yang sangat kecil, klitoris yang besar dalam vagina yang kecil, testikel dan tubuh laki-laki. Melihat klitoris yang besar, seseorang pasti mengharapkan vagina yang besar pula akan tetapi yang ada adalah cul-de-sac. Setelah kedokteran, Alexina berhadapan dengan pengadilan ketika hasil analisis dokter itu harus ditetapkan dalam hukum. Keputusan hukum menyebutkan bahwa Alexina adalah seorang laki-laki dan harus berpakaian laki-laki. Alexina berganti nama menjadi Abel Barbin. Abel Barbin meninggalkan pekerjaannya dan kekasihnya dan pergi ke Paris, dimana dia hidup dalam kemiskinan dan menulis memoar sebagai bagian dari terapi. Barbin akhirnya tewas bunuh diri dengan menghirup kompor gas. Foucault mempertanyakan dorongan pendeta, vonis dokter, dan keputusan hukum yang mengubah segalanya dan akhirnya menjadi penyebab kematian Barbin: “Bukankah secara komparatif, hermaprodit diperbolehkan dalam abad-abad sebelumnya?” Semasa Abad Pertengahan, setelah mencapai dewasa seorang hermafrodit diperbolehkan memilih mau menjadi laki-laki atau perempuan. Sedangkan dalam kasus Alexina, ilmu kedokteran memutuskan bahwa ia adalah seorang laki-laki dan aturan itu harus diikuti. Dianggap suatu penyelewengan bila identitas laki-laki tapi tidak menampilkan peran dan citra laki-laki (1990: 96). Memoar Alexina berisi dua hal utama perlawanannya terhadap strategi regulatif untuk kategorisasi seksualitas dan romantisasi masa sebelum dia divonis menjadi laki-laki. Alexina sangat menikmati sebelum ketetapan hukum ini sebagai the happy limbo of non-identity, fase ketika dirinya melampaui kategori seks dan identitas, kenikmatan dalam sistem sosial tanpa seks yang univocal. Ungkapaanya dalam bab terakhir : “Di satu sisi Foucault ingin mengatakan bahwa tidak ada jenis kelamin yang berdiri sendiri, yang tidak dihasilkan interaksi diskursus dan kuasa, tapi di sisi lain Foucault juga berpandangan ada sebuah keserbaragaman kenikmatan yang berdiri sendiri dan bukan efek dari pertukaran kuasa/diskursus. Dengan kata lain, Foucault mengakui adanya multiplisitas libidinal pradiskursif yang secara efektif mengasumsikan seksualitas di depan hukum, dan seksualitas menunggu emansipasi dari hambatan seks. Di sisi lain, Foucault secara resmi menyatakan bahwa seksualitas dan kuasa itu koekstensif seperti saudara kembar, dan kita tidak bisa berpikir bahwa dengan mengatakan “ya” kepada seks, “tidak” kepada kuasa. Dalam mode antiyuridis dan antiemansipatoris, Foucault yang “resmi” berargumentasi bahwa seksualitas selalu berada dalam matriks kekuasaan, yaitu selalu diproduksi dan dikonstruksi dalam praktik kesejarahan tertentu, diskursif dan institutional” (1990: 123). Menurut Butler, ada dualisme pemikiran Foucault. Di sinilah masalahnya menurut Butler. Disatu sisi Foucault, mengakui ada kenikmatan di luar konstruksi sosial. Namun disisi lain menurutnya segala sesuatu terbentuk oleh relasi kuasa (dibentuk oleh kostruksi sosial). Dalam pandangan Butler, memoar Alexina menawarkan kesempatan untuk membaca Foucault against himself karena mengungkapkan penderitaan, tekanan, tipuan, kerinduan dan kekecewaan yang mendalam. Alexina tidak pernah menyebut keadaan anatominya, tapi dia sering mengaitkan kelaminnya itu sebagai “kesalahan alami, kegelandanganan metafisis, nafsu yang tidak pernah puas” yang ditransformasikan dalam kemarahan kepada laki-laki dan berikutnya kepada dunia secara keseluruhan menjelang bunuh dirinya. Satu yang disenanginya adalah ketika berada di atas kuburan ayahnya: karena memberi pengertian dia bisa menginjak-injak tulang, dan dia membayangkan dokter yang telah memvonisnya sebagai laki-laki itu seratus meter terkubur di dalam. Ditulis dalam nada yang sentimental dan melodramatik, kemudian itu menginformasikan semacam krisis tidak kunjung usai yang diakhiri dalam tindakan bunuh diri. Inti dari pemikiran Butler adalah tidak adanya kondisi alamiah bagi manusia selain penampakan tubuhnya. Seks, gender, maupun orientasi seksual adalah konstruksi sosial. Hal ini dapat dicontohkan melalui fenomena transseksual. Seorang yang telah melakukan transseksual, yang diasumsikan telah ‘merubah’ kondisi alamiahnya. Misalnya seorang pria yang merasa beridentitas feminin, mengubah jenis seksnya menjadi tubuh perempuan. Maka secara otomatis, setelah seks sebagai fakta biologis tersebut diubah menjadi yang sebaliknya, akan berdampak terhadap perubahan yang menentukan keabsahan dari individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan the fixed rules atas seks, gender, dan orientasi seksual. Kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah baik seks, gender, maupun orientasi seksual adalah sesuatu yang sifatnya cair (fluid), tidak alamiah, dan berubah-ubah, (serta dikonstruksi oleh kondisi sosial). Maka jika ditinjau dari pemikiran Judith Butler, transgender dan homoseksual bukanlah suatu penyimpangan sosial, melainkan suatu variasi dalam identitas manusia yang didasarkan pada tindakan performatif (1990: 96). Salah satu teori yang juga dikemukan Judith Butler dalam buku ini adalah teori performativitas. Dalam teorinya ini Butler menolak prinsip identitas yang memilki awal dan akhir. Dari sinilah dapat dimengerti bahwa pandangan Butler seseorang dapat memilki identitas maskulin dan feminin dalam waktu yang bersamaan atau feminin dan maskulin di waktu yang berbeda. Demikian pula dengan male feminine atau female maskulin. Hal ini tentu berpengaruh pula pada persoalan orientasi seksual. Jika identitas seksual seseorang tidak final, tidak stabil, seharusnya tidak ada keharusan seorang perempuan menyukai pria dan sebaliknya. Namun masyarakat tentu tidak menghendaki yang demikian. Seperti yang juga telah disebutkan di atas, subjek dibentuk oleh culture dan diskursus, dimana ada suatu aturan yang disebarkan melalui repetisi. Aturan ini membuat suatu fenomena seolah-olah heteroseksual merupakan hubungan yang normatif antara seks, gender, dan orientasi sesksual. Seorang dengan tubuh male, harus berprilaku maskulin dan menyukai female sebagai lawan jenisnya, dan sebaliknya. Aturan ini sudah terpasung dari awal, yang dikutip Butler dari Melancolia Frued bahwa bayi telah menolak incest dan homoseksual. Sehingga apa yang berbeda dari kewajiban alamiah tersebut dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan norma (1990: 57). Dalam paradigma heteroseksualitas, gender sangat menentukan tindakan-tindakan manusia. Sedangkan dalam pemikiran Butler, gender atau identitas seksual hadir setelah individu melakukan tindakan performatif. Inti pemikirannya adalah tidak adanya kondisi alamiah bagi manusia kecuali penampakan tubuhnya. Dengan kata lain, seks, gender, maupun orientasi seksual adalah konstruksi sosial. Fakta ini dapat dilihat pada fenomena transseksual, misalnya seorang pria yang merasa beridentitas feminin, mengubah jenis seksnya menjadi tubuh perempuan. Maka, dia harus bertindak sesuai dengan ketentuan (the fixed rules) atas seks, gender,dan orientasi seksual (1990: 66). Teori performativitas gender memperlihatkan bagaimana diskursus maupun tindakan yang terus dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang menghasilkan pengertian tentang seks dan gender baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Proses materialisasi gender yang selama ini dilakukan berada dalam sistem hegemoni heteroseksual, sehingga jika gender seseorang keluar dari norma sosial yang berlaku, dikatakan menyimpang. Inilah kekerasan gender dari hasil konsepsi performativitas yang tunduk pada hegemoni tertentu. Untuk itu dibutuhkan proses negosiasi terhadap norma-norma sehingga menghasilkan performativitas gender yang lebih terbuka dan tanpa kekerasan. Teori performativitas gender memperlihatkan bahwa gender terjadi karena proses materialisasi dan konstruksi. Maka disinilah letak kajian gender yang bersentuhan dengan pemikiran Judith Butler yang membongkar paradigma gender khususnya yang telah dilakukan oleh para feminis, yang secara tajam melakukan pemilahan antara seks (sebagai kodrat) dan gender (sebagai konstruksi). Dalam pemilahan tersebut, yang dipahami sebagai seks sebenar-benarnya adalah gender itu sendiri, sebab jika seks laki-laki dan perempuan dikatakan kodrat dengan segala kriteria yang mengikutinya, bukankah kriteria tersebut juga adalah konstruksi, sebagaimana gender juga dipahami konstruksi. Teori performativitas gender memperlihatkan bagaimana diskursus maupun tindakan yang terus dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang menghasilkan pengertian tentang seks dan gender baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Proses materialisasi gender yang selama ini dilakukan berada dalam sistem hegemoni heteroseksual, sehingga jika gender seseorang keluar dari norma sosial yang berlaku, dikatakan menyimpang. Inilah kekerasan gender dari hasil konsepsi performativitas yang tunduk pada hegemoni tertentu. Untuk itu dibutuhkan proses negosiasi terhadap norma-norma sehingga menghasilkan performativitas gender yang lebih terbuka dan tanpa kekerasan. Comments are closed.
|
AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
September 2021
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed