|
Kita bisa memandang dari dua sisi yang berbeda untuk menyikapi batal tayangnya sinema Fifty Shades of Grey ke Indonesia atau yang biasa disingkat 50SOG. Satu, bersyukur karena 50SOG menampilkan tayangan yang para penulis dan penggemar sebut BDSM dan konten seksualitasnya memang cukup sulit untuk masyarakat kita yang masih menabukan seks. Kedua, sedih karena film ini cukup populer dan menjadi bagian dari globalisasi, kita sebal dengan sikap masyarakat yang menabukan seks dan memandang seksualitas dalam sinema tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Saya tidak akan banyak menyinggung tentang konten 50SOG di tulisan ini, saya hanya ingin berkomentar perihal ramainya jokes menyindir 50SOG di dunia maya berupa meme yang nyaris tidak bisa dihitung lagi melalui 9gag.com. Situs 9gag.com adalah situs jokes internasional yang berupa gambar atau meme. Jokes yang menyasar secara visual gambar dan tulisan, secara fungsi meme memang bersifat sebagai hiburan.
Uniknya, 50SOG sebagai fenomena ditentang oleh para laki-laki. Melalui meme-meme yang saya contohkan di pembuka tulisan ini, terlihat gender dan jenis kelamin pembuat meme. Fenomena meledek 50SOG oleh para laki-laki ini penah terjadi ketika Novel Twilight Saga karya Stephenie Meyer dibuat dalam versi layar lebar. Walau ketika kemunculan perdana Twilight tidak mendapat serangan berupa meme, para laki-laki menolak dengan tegas Twilight yang menurut mereka cerita dan tokohnya tidak masuk akal. Laki-laki tidak mengerti mengapa para perempuan menggandrungi cerita picisan tersebut dan kita perempuan tidak mau memahami mengapa para laki-laki membenci kedua film tersebut. Baik Christian Grey dan Edward Cullen tokoh utama laki-laki dalam kedua film tersebut dianggap membuat standar maskulin yang tidak realistis. Mana mungkin seorang pria bisa punya kekuatan berlari atau mengangkat barang seperti Superman dan menggunakan hal itu hanya untuk menolong wanita yang pada kedua sinema tersebut pasif, pendiam dan suka memberi kode-kodean. Grey seorang Milioner yang bertampang bak model pakaian dalam yang para pria menganggap tidak mungkin hal itu bisa dilakukan. Baik Grey dan Cullen mengunakan kekuatan uang ataupun fisik untuk membuat gadis pujaannya berada dalam genggamannya. Dan si gadis dibiarkan takluk dan menurut. Para pria tidak menyukai standarisasi seperti Grey ataupun Cullen, mereka tidak mau dipaksa untuk jadi serba bisa dan selalu tampan. Selain itu, jalan cerita kedua sinema tersebut punya tipe yang sama, a Cinderella stories, perempuan biasa saja yang mendapatkan pria kaya. Mereka, para pria lelah dituntut untuk menjadi super duper kaya dan bisa membeli perusahaan tempat si perempuan idaman bekerja, karena untuk mengurus dirinya saja mereka sudah pontang-panting. Para laki-laki sudah menolak untuk mengikuti standar yang dibuat media untuk dianggap menjadi tampan dan maskulin. Bagaimana dengan kita perempuan? Ketika ada sinema yang membuat si tokoh utama pasif dan berpendidikan rendah dengan wajah dan tubuh supermodel apa kita menolak mereka seperti yang dilakukan para pria? Tidak, kita justru terjebak dan menyukai si tokoh, kita mendambakan untuk menjadi si tokoh utama yang cukup dengan modal wajah cantik, tubuh langsing dan pasif bisa mendapatkan pria kaya raya hidup bahagia selama-lamanya. Kita mau saja dihipnotis media untuk mengikuti standar cantik berkulit putih seperti yang ditampilkan model iklan losion di televisi ataupun majalah. Kita tidak marah dan menuntut balik pria melalui meme menolak penggambaran seksi yang harus seperti Megan Fox dalam film Transformers. Kita malah terobsesi dan mengikuti standar imposible tubuh dan wajah Megan Fox dengan diet yang ketat tanpa olahraga dan baca buku. Padahal jika kita mengamati film kesukaan laki-laki, Transformers atau Iron Man, sosok perempuan idaman mereka adalah yang tangkas, aktif, berani dan cerdas seperti Pepper dan Mikaela. Para laki-laki memang melihat maskulinitas sebagai kewajiban tetapi mereka menolak standar-standar mustahil yang dibuat. Sedangkan perempuan, masih dipilihkan untuk menentukan kewajiban cantik yang tidak pernah selesai.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Beberapa waktu yang lalu sebuah tayangan berita singkat di beberapa stasiun televisi swasta menjadi sorotan para pemerhati isu perempuan dan dalam waktu singkat menuai pro kontra. Razia Jilbab, begitulah headline dari berita tersebut. Kasus yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur ini diawali oleh imbauan pemerintah setempat bagi penduduk daerahnya yang berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam untuk mengenakan jilbab. Dari imbauan tersebut, petugas Satpol PP Probolinggo bergerak melakukan razia di satu pusat perbelanjaan di daerah Kraksaan. Hasilnya, banyak orang yang menolak peringatan dari petugas dikarenakan tidak ada aturan atau perda yang sah mengenai aturan pemakaian jilbab di Probolinggo. Selain kasus razia jilbab, beberapa waktu yang lalu publik sempat membahas mengenai kasus tes keperawanan. Berawal dari terkuaknya praktik tes keperawanan terhadap para Polwan hingga munculnya suatu usulan dari salah satu anggota DPRD Jember mengenai pemberlakuan tes keperawanan bagi siswi SMA sebagai salah satu syarat kelulusan mereka. Yang belakangan ini kabarnya dilatarbelakangi oleh tingginya kasus HIV dan hubungan seksual di luar nikah di Jember. Bukan hanya pemerintah daerah Jember rupanya yang memiliki ide ini. Anggota pemerintah daerah Jambi, Indramayu dan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih di Sumatera Selatan pun pernah menyuarakan gagasan yang serupa. Masalahnya adalah lagi-lagi perempuanlah yang dibatasi haknya padahal tentu dalam sebuah hubungan seksual bukan hanya perempuan yang berperan. Kedua kasus ini, baik kasus razia jilbab dan tes keperawanan baru berbentuk sebuah gagasan. Gagasan yang datangnya dari orang-orang yang tidak memahami betul mengenai gender dan hak perempuan akan tubuhnya. Berlandaskan ajaran satu atau beberapa agama dan juga dengan alasan untuk melindungi perempuan, gagasan-gagasan serupa timbul di masyarakat. Namun pada kenyataannya, perda-perda yang membatasi hak-hak perempuan ini tidak menyumbangkan hal yang positif melainkan justru hanya menambah daftar kerugian bagi perempuan. Mari kita ingat kembali beberapa peraturan daerah yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang diberlakukan di kota Tangerang adalah salah satu perda yang terbukti diskriminatif terhadap perempuan. Salah satu pasalnya misalnya, yaitu pasal keempat ayat yang pertama menyebutkan: setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong atau tempat-tempat lain di daerah. Bisa dibayangkan apa yang bisa dan sudah terjadi ketika perda ini mulai diberlakukan di Tangerang. Para perempuan yang masih berada di luar rumah pada malam hari dan mengenakan busana yang dianggap provokatif dapat ditangkap oleh petugas hanya berdasarkan asumsi semata. Pada kenyataannya, perda ini pernah memakan korban yaitu seorang ibu yang bekerja di sebuah rumah makan dan baru selesai bekerja pada malam hari. Ibu ini ditangkap oleh petugas meskipun ia telah menyatakan bahwa ia sudah bersuami. Kasus-kasus penangkapan lain juga terjadi dan menimpa perempuan-perempuan yang dengan alasan apapun sedang berada di luar rumah pada malam hari. Akibatnya, warga perempuan di kota Tangerang merasa resah dan juga merasa dibatasi haknya untuk bekerja dan berada di luar rumah. Selain perda diskriminatif yang diberlakukan di Tangerang, kita juga mungkin masih ingat perda larangan asusila Depok, perda syariah di Aceh, serta perda larangan asusila di Bekasi dan juga aturan bagi warga perempuannya untuk mengenakan jilbab. Tak hanya dua, ada begitu banyak peraturan-peraturan daerah yang nyatanya meminggirkan hak-hak perempuan. Pada tahun 2014, Komnas Perempuan mencatat ada lebih dari 300 perda yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia. Keberadaan perda-perda ini tentunya melanggar aturan yang secara kedudukan lebih tinggi ketimbang perda yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Undang-undang yang merupakan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) ini mengikat Indonesia dengan kewajiban untuk membentuk dan mengawasi hukum yang diberlakukan di dalam negeri agar tidak bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Ini berarti negara Indonesia seharusnya menjamin persamaan hak dan turut mendukung pemberdayaan masyarakatnya yang berjenis kelamin perempuan. Jika terdapat undang-undang atau peraturan yang ternyata mendiskriminasi perempuan maka seharusnya pemerintah mencari solusi atau mengambil tindakan agar undang-undang atau peraturan tersebut tidak lagi merugikan kaum perempuan. Sayang pada kenyataannya jumlah perda yang mendiskriminasi perempuan bukannya menurun melainkan justru meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Kembali lagi pada dua kasus diskriminasi yang sedang ramai yaitu tes keperawanan dan razia jilbab. Membicarakan diskriminasi terhadap perempuan seringkali tidak berhenti pada satu titik. Ketika kita membicarakan tes keperawanan dan razia jilbab, kita tidak hanya membicarakan hak perempuan akan tubuhnya yang dilanggar. Kala kita membicarakan razia jilbab atau pengaturan busana bagi perempuan, kita juga melihat risiko keamanan bagi perempuan yang tidak mengenakan jilbab atau busana seusai ketentuan. Dalam kasus tes keperawanan, kita juga dapat membayangkan risiko perempuan yang hak akan pendidikannya terancam dicabut. Belum lagi trauma psikologis yang mungkin diderita oleh mereka yang harus menjalani tes tersebut (mengingat para Polwan, yang secara umur sudah jauh lebih matang ketimbang remaja seumuran SMA atau SMP, yang ketakutan bahkan pingsan ketika menjalani tes tersebut). Ratusan perda diskriminatif yang telah telanjur disahkan oleh pemerintah-pemerintah di berbagai daerah pada mulanya juga berawal dari gagasan segelintir “wakil rakyat” yang tidak memiliki perspektif gender. Berawal dari gagasan kemudian menjadi imbauan lalu diterapkan dalam bentuk razia atau sosialisasi hingga pada akhirnya dirapatkan dan menjadi sebuah produk hukum. Dalam waktu setahun tanpa terasa puluhan perda baru yang semakin mempersempit ruang gerak perempuan dicetak. Razia jilbab maupun tes keperawanan adalah kasus lama yang telah muncul berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa kursi-kursi pemerintah daerah membutuhkan orang-orang dengan perspektif gender yang benar dan mengerti betul bagaimana merumuskan kebijakan yang tidak mendiskriminasi warga perempuan yang memercayakan suaranya pada mereka. Kasus-kasus ini juga seharusnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak memandang remeh gagasan konyol yang sewaktu-waktu dapat menjelma menjadi aturan hukum yang mengikat. Daftar Pustaka Luluhima, Achie Sudarti (ed.). 2007. Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Ihromi, T.O., Irianto, S., dan Luhulima, A.S. 2000. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Penerbit Alumni. http://video.viva.co.id/read/38644-tanpa-payung-hukum--probolinggo-gelar-razia-jilbab_1 http://www.lbh-apik.or.id/perda%20tangerang.htm http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/07/355021/dprd-jember-usulkan-tes-keperawanan-syarat-kelulusan-siswa http://icrp-online.org/2014/03/03/komnas-perempuan-dorong-judicial-review-perda-diskriminatif-gender/ http://www.leimena.org/en/page/v/578/contoh-kasus-akibat-perda-diskriminatif  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Menjadi perempuan yang lahir di tanah Sunda tentulah mempunyai tantangan tersendiri. Sunda yang religius dan sebagian besar penduduknya muslim menyebabkan tata cara hidup di Sunda berdasarkan agama mayoritas yaitu Islam. Perempuan di Sunda adalah makhluk mayoritas. Jika kita membaca ulang sejarah, perempuan Sunda mendapat tempat yang luhur, sebut saja Dayang Sumbi. Ibunda Sangkuriang ini menjadi tokoh sentral di cerita legenda Jawa Barat. Dayang Sumbi mempunyai harga diri yang kuat juga yakin akan kebenaran pendiriannya mampu menolak Sangkuriang dengan caranya. Ada pula Purbasari, sosok putri yang cantik lahir batin. Jika dua tokoh dalam sastra Sunda tersebut Sangkuriang dan Purbasari merupakan tokoh imajiner, saya akan tampilkan tokoh perempuan Sunda yang riil yakni Dewi Sartika. Siapa yang tak mengenal Dewi Sartika? Perempuan Sunda asli yang kala itu dengan gagah berani berpikir mengenai kaumnya. Pergerakan Dewi Sartika dimulai ketika banyak perempuan sunda yang datang kepadanya dan mengeluh tak punya kepandaian dan keterampilan apapun. Dewi Sartika berpikir pentingnya kaum wanita mendapat pendidikan agar bisa hidup sendiri, tidak semata-mata bergantung ke suami. Akhirnya Dewi Sartika pada tahun 1904 mendirikan sakola istri. Ada juga Inggit Garnasih, yang dari tangannya melahirkan negarawan Soekarno. Sunda kaya akan cerita legenda yang menempatkan perempuan sama tingginya dengan laki-laki. Juga kisah heroik Dewi Sartika yang sudah satu abad lalu dengan pemikiran yang gemilang. Tentunya kita berharap bahwa perempuan sunda adalah perempuan tangguh yang mandiri. Tetapi kenyataannya saya masih melihat banyak ketidakadilan terjadi pada perempuan sunda. Perempuan yang menikah di usia muda banyak di jumpai di ranah Sunda, sebut saja, Majalengka, Garut, Ciamis, Tasikmalaya. Menurut pengamatan saya sebagai perempuan yang lahir dan besar di tanah Sunda, saya terbiasa melihat pemandangan seorang perempuan, seorang ibu menjadi kepala rumah tangga. Bukan hanya sebagai pencari nafkah tetapi menjadi pelayan bagi semua anggota keluarganya. Suami menjadi raja yang harus dilayani, laki-laki baik dewasa maupun muda mendapatkan tempat nomor satu di rumah. Banyak sekali saya temui perempuan sunda yang sudah menjadi janda di bawah 25 tahun. Cukup banyak perempuan sunda yang kurang mendapatkan pendidikan yang baik sehingga mereka tidak memiliki keahlian dan akhirnya menjadi tidak produktif. Suami adalah tumpuan bagi mereka untuk menaruh hidupnya. Ketika di dalam rumah tangga mengalami KDRT pun, kebanyakan perempuan sunda akan bertahan karena faktor ekonomi. Banyak yang saya lihat perempuan sunda ini menyerahkan kehidupannya pada suami, lantas ketika ada anak mereka menitipkan harapan pada anak-anaknya untuk menjadi sumber kebahagiannya, semua itu dilakukan karena ketidakmampuannya untuk membahagiakan diri sendiri. Sunda adalah suku yang besar. Pepatah “banyak anak banyak rezeki” sepertinya diterapkan orang-orang Sunda dahulu, sehingga saya selalu melihat keluarga Sunda adalah sebuah keluarga besar. Darah menjadi pengikat yang erat di Sunda, tidak jarang saya melihat uwak, mamang maupun bibi ikut campur terhadap urusan ponakannya. Saya seperti melihat suatu kelompok besar dengan pemikiran yang nyaris sama, sehingga menjadi salah satu yang berbeda itu adalah tantangan besar. Islam, agama yang rahmatan lil alamin, menjadi pondasi untuk masyarakat sunda berkiblat, tetapi saya menyayangkan penafsiran yang salah tentang poligami dalam islam juga kekuasaan laki-laki atas perempuan. Hadis yang populer didengung-dengungkan di tengah keluarga saya “menikah dan perbanyaklah anak karena aku akan bangga memiliki anak yang banyak” menjadi salah satu alasan banyaknya perempuan sunda yang dipoligami. Inggit Garnasih perempuan sunda yang cerdas dan berani mengatakan tidak untuk dipoligami, meski kekuasaan di depan mata ditolaknya dengan tegas. Saya kemudian menjadi rindu pada sosok Dewi Sartika juga Inggit Garnasih, setiap kali saya melewati rumah bersejarah Inggit Garnasih juga ketika saya melewati jalan Dewi Sartika sambil mencari buku di tukang loak, mata saya langsung beriak. Ada perempuan hebat di Sunda! Ya, dulu. Sekarang, jarang saya melihat tampilnya perempuan Sunda di dunia sastra atau di ranah akademik yang mencolok. Saya tidak menampik, ada banyak perempuan Sunda yang populer, tapi itu tidak cukup mengingat penduduk Jawa Barat adalah yang terbanyak di Indonesia. Apa perempuan Sunda bodoh? Tidak! Nyata sekali bahwa penggerak sekolah perempuan pertama ada di Sunda yakni Dewi Sartika, nyata sekali bahwa legenda Sunda Dayang Sumbi menjadi legenda nasional dengan menempatkan tokoh perempuan menjadi sentral juga. Saya percaya, di balik gunung Papandayan yang menjulang itu, perempuan cerdas Sunda bersembunyi, saya juga percaya di bawah kaki bukit gunung Ciremai itu, banyak perempuan Sunda yang sedang mengasah pena nya. Untuk Sunda yang saya cintai, lahirkanlah perempuan hebat dari perutmu.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Saya sedang iseng berselancar di dunia maya dan menemukan artikel ini, artikel yang cukup miris sekaligus lucu bagi saya. Artikel itu berasal dari sebuah web konsultasi pernikahan yang mengungkapkan kegelisahan seorang suami terhadap istri yang baru dinikahinya, berikut petikannya:
Maukah kita mencoba memahami posisi laki-laki mengapa ia merasa ditipu dan tidak menerima bahwa kiranya istri yang baru dinikahinya tidak perawan? Laki-laki dibebani untuk selalu menjadi maskulin dan yang paling maskulin diantara para laki-laki. Sosialisasi gender melalui permainan yang ditujukan kepada anak laki-laki dibumbui persaingan, berbeda dengan permainan anak perempuan yang biasanya bersifat bekerjasama, sedari kecil, si anak laki-laki ini sudah diajarkan bahwa menjadi laki-laki adalah sebuah persaingan untuk menjadi pemenang. Hingga ada ungkapan bagi laki-laki yang terjebak dalam perlombaan maskulinitas ini “men never satisfied with their size, except for cancer or tumor”. Laki-laki yang dianggap tidak maskulin akan menjadi cemoohan dalam perkumpulan mereka, mereka selalu ingin menjadi paling maskulin, seperti tagline obat kuat pil biru yang mudah ditemui di pinggir jalan raya, Obat Alat Vital (penis): lebih besar, lebih kuat, tahan lama. Menikahi perempuan perawan dan memerawani perempuan adalah sebuah kebanggan bagi laki-laki terhadap sesamanya. Dalam pergaulan para laki-laki ini akan ada ‘the most wanted female’ yang kerap dibicarakan dan menjadi idaman setiap orang, mendapatkan perempuan tersebut menjadi prestise seakan-akan perempuan tersebut adalah sebuah trofi berjalan. Patriarki menempatkan laki-laki untuk wajib menjadi maskulin, buas dan penguasa atas perempuan dan tubuhnya. Para laki-laki dipaksa berlomba untuk jadi maskulin, jadi jantan, mendapatkan gadis impian semua. Tapi, apa laki-laki tersebut secara sadar melakukan perlombaan maskulinitas mengejar keperawanan perempuan? Toh nyatanya kemauan penis untuk ereksi tidak ditentukan dari perawan atau tidaknya vagina. Yang menginginkan perempuan perawan adalah perlombaan maskulinitas. Laki-laki bisa saja jatuh cinta kepada perempuan lebih tua, seorang janda, bahkan ibu-ibu muda yang masih bersuami. Tetapi masyarakat akan menggunjingkannya, menganggap ia tidak mampu mendapatkan yang lebih baik, seorang gadis. Gadis yang paling muda dan cantik di lingkungannya. Patriarki mengatur kepada siapa kita harus jatuh cinta, baik perempuan dan laki-laki. Sebenarnya kita menderita. Lantas bagaimana dengan poligini? Saya akan mengambil kasus seorang tetangga saya yang kebetulan menjadi pemuka agama dan dihormati oleh pengikutnya, sebut saja namanya A. A ini pada 17 tahun yang lalu sempat mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi kepada istrinya namun tidak dikabulkan oleh istrinya, dan pada tahun lalu, A mengungkapkan lagi keinginannya untuk memadu istri, dan uniknya kali ini dengan perempuan yang berbeda dibandingkan permintaannya pada 17 tahun yang lalu. Jika memang A ingin poligini berdasarkan cinta, tentunya permintaannya untuk menikah seharusnya masih dengan perempuan yang sama. Tapi justru perempuannya berbeda, tentunya lebih muda. Selidik punya selidik, ternyata seluruh saudara kandung A yang berjumlah empat orang dan laki-laki semua itu semuanya memiliki istri lebih dari satu, A tentu saja merasa “kalah” dari saudara-saudaranya yang lain karena A hanya memiliki satu istri. Poligini dilakukan untuk melengkapi atribut kekuasaan (phallus) karena perempuan adalah sebuah trofi. Padahal, maskulinitas adalah perlombaan yang tidak pernah bisa dimenangkan. Daftar Pustaka http://www.eramuslim.com/konsultasi/keluarga/istri-tidak-sesuai-harapan.htm#.VONYU_mUdQE diakses pada hari Selasa, 17 Febuari 2014 pukul 10.34 Beavoir, Simone de. 1972. The Second Sex (Trans: H.M. Pahrsley). New York: Pinguin Books  Dok. Pribadi Dok. Pribadi “I’m White, I’m Black, And I’m Asian” sincerely, Panda. Kalimat tersebut merupakan satire dari sikap rasisme terhadap manusia non-kulit putih Eropa. Panjang sudah sejarah manusia berjalan, tetapi sikap rasisme primitif masih ada. Rasisme lebih mudah dideteksi karena rasisme menyangkut penampilan fisik seorang manusia yang bisa dengan mudah diidentifikasi dalam sekali tatap, tapi bagaimana dengan perilaku mendiskriminasi yang lain dan justru lebih populer tapi jarang kita sadari? Heteroseksisme dalam Ilmu Sosiologi merujuk pada perilaku mendiskriminasi orang-orang yang memiliki orientasi seksual berbeda dengan mayoritas. Karena mayoritas menyukai lawan jenis--baik untuk jatuh cinta maupun hubungan seksual—maka yang memiliki “selera” berbeda dengan mayoritas didiskriminasi. Heteroseksisme ada dimana-mana. Dan kita jarang menyadari telah melakukan diskriminasi jenis ini. Lelucon tentang homo, lesbian atau gay sering kali kita dengar bahkan sering kita jadikan obrolan sehari-hari. Sikap Heteroseksis bisa berupa ucapan, tindakan bahkan kekerasan. Lihat panda, dari struktur tubuhnya, panda seharusnya menjadi hewan karnivora. Badannya gempal dan besar seperti beruang dengan cakar tajam yang bisa merobek mangsa dan gigi-gigi yang juga runcing untuk memakan daging mentah. Tapi panda memilih memakan daun bambu. Dan kita tidak masalah dengan itu. Kita malah menganggap panda lucu dan menggemaskan karena ia memakan bambu dan tidak menjadi hewan karnivora seperti koleganya, Beruang. Orientasi seksual juga perihal selera, seperti panda yang walaupun secara biologis dilahirkan sebagai pemakan daging kemudian dia memilih untuk memakan tumbuhan. Mengapa panda melakukan itu? Apa karena efek dari evolusi? Apa panda dipaksa makan bambu oleh sesama binatang lain? Apa karena bambu lebih bergizi? Panda makan bambu karena dia suka bambu. Dan karena panda makan bambu dan seluruh panda di seluruh dunia ini makan bambu, panda tidak mengikuti hukum dan kaidah biologisnya. Apa hal itu membuat panda menjadi punah? Tidak. Panda masih jadi salah satu binatang unyu nan menggemaskan yang masih bisa kita lihat di kebun binatang. Kita bisa menoleransi panda yang memakan bambu karena seleranya, mengapa kita tidak bisa menoleransi sesama manusia karena seleranya? Saya menolak menggunakan kata orientasi seksual melainkan selera untuk mengganti kata orientasi. Hasrat adalah selera, kita tidak bisa menjelaskan mengapa kita jatuh cinta seperti halnya panda yang jatuh cinta pada daun bambu. Hasrat seksual juga selera, bukan berarti jika saya memiliki penis kemudian saya harus berpasangan dengan vagina. Hasrat penis menyukai penis atau vagina menyukai vagina atau bagaimanapun telah ada pada diri dan itu tidak berpengaruh atas eksistensi seseorang sebagai manusia. Ambil contoh Alan Turing, ilmuwan yang seorang homoseksual ini pemikirannya menjadi pijakan bagi penemuan komputer yang kita pakai sekarang. Oprah Winfrey yang acara talkshow-nya memengaruhi kebudayaan Amerika sekarang adalah seorang aseksual. Selera seks, kamu boleh memilih dan mengapresiasinya sama seperti ada beberapa teman kita yang menyukai durian dan ada yang tidak. Kita luput memperlakukan manusia sebagai manusia. Kita lebih menerima panda yg memilih selera berbeda dibandingkan manusia yang punya selera yang tidak mengikuti mayoritas. Padahal, jika memang kita bersikap antroposentris menempatkan manusia lebih superior dari makhluk lain, mengapa kita justru tidak menyukai perbedaan selera antar sesama manusia? tidak ada yang salah dalam perbedaan selera seks, dan perbedaan tersebut tidak mengancam keberlangsungan dan peradaban hidup manusia. Praktik homoseksual sudah ada dan beriringan dengan perjalanan sejarah dan peradaban manusia. Dan selama itu pula, perbedaan selera seks tidak membuat manusia menjadi punah. |
AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
September 2021
Categories |
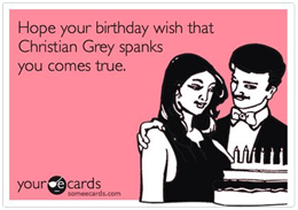


 RSS Feed
RSS Feed