Roro Sawita, Gde Putra, Emma Baulch: Citra Perempuan Indonesia dalam Iklan Produk Provider30/5/2014
Oleh: Roro Sawita, Gde Putra dan Emma Baulch ([email protected]  Iklan Provider dan Perempuan Dalam Perebutan Runtuhnya rezim sentralistik Orde Baru mengubah konstelasi sosial politik di Indonesia. Persoalan-persoalan perempuan yang ditabukan pada zaman Orde Baru mulai diberikan ruang untuk didiskusikan secara terbuka. Istilah pemberdayaan perempuan, perempuan di parlemen, kuota untuk perempuan, kepemimpinan perempuan, ataupun independensi perempuan mulai sering terdengar. Bukan berarti riuh suara pembebasan itu yang mendominasi lapangan sebab upaya pemenjaraan tubuh perempuan meriah juga di era reformasi. Saat ini upaya kontrol terhadap tubuh perempuan dilakukan oleh sipil berjubah agama. Lihat misalnya di layar TV, sangat terang-terangan Front Pembela Islam (FPI) terekam menyerbu tempat hiburan malam dan melakukan razia kemaksiatan di tempat mahasiswa indekos. Tidak jarang kelompok sipil mengatasnamakan organisasi agama tertentu mengeluarkan pernyataan dihadapan wartawan dengan mencela beberapa artis dangdut perempuan atau selebriti perempuan lainnya yang dikenal berpakaian “seksi”. Upaya kontrol tubuh perempuan juga terealisasikan pada ranah kebijakan negara. Terbukti dengan disahkannya undang-undang pornografi. Alih-alih untuk mengriminalkan pelaku industri pornografi, beberapa pasalnya malah menyudutkan perempuan.[1] Atas nama otonomi daerah, beberapa wilayah di Indonesia melahirkan perda-perda syariah yang diskriminatif terhadap perempuan.[2] Aksi sensor dan aturan tak ramah perempuan tersebut ingin membuat masyarakat meyakini pandangan bahwa tubuh perempuan bisa berbahaya dan mengganggu tatanan sosial jika tidak diawasi. Karena itu sudah sepantasnya tubuh perempuan didisiplinkan. Walaupun perempuan mulai memegang tampuk pimpinan di beberapa daerah, namun penyepelean terhadap kepemimpinan perempuan masih kuat. Seringkali berhembus isu perempuan menjadi kepala daerah atau anggota dewan karena diuntungkan oleh jaringan politik dari suaminya. Penolakan kepemimpinan perempuan juga muncul baru-baru ini, seperti kasus penolakan Lurah Susan di Lenteng Agung Jakarta. Lurah Susan ditolak bukan hanya karena tidak beragama islam tetapi juga statusnya sebagai perempuan. Atau lihat ke belakang saat PDIP memenangi pemilu tahun 1999. Isu Megawati Soekarno Putri dijegal sebagai presiden karena dia perempuan. Pemandangan menjadi terbalik jika mata diarahkan ke layar TV disaat iklan provider mengisi jeda acara sinetron, berita atau talk show. Adalah Iklan Simpati dengan Agnes Monica sebagai bintang iklannya.[3] Sosok perempuan single, non Muslim, beretnis minoritas Tionghoa, independent secara ekonomi, kerap berpakaian minim dan hidup di dunia hiburan ini dijadikan sosok utama dalam iklan tersebut. Arahkan juga penglihatan kita ke sosok Anggun C Sasmi di iklan Mentari.[4] Perempuan berdarah Yogyakarta ini adalah sosok artis perempuan yang lama merantau jauh dari kampung halaman dan menikah dengan laki-laki Prancis. Kedua sosok ini mewakili perempuan yang berani berkarier keluar dari rumah ataupun keluar dari negerinya, serta berani single seperti Agnes ataupun berani memilih pujaan hati beda agama, ras, suku, etnis dan warga negara seperti Anggun. Kemunculan dua sosok artis ini menandakan telepon genggam termasuk kebutuhan perempuan. Dapat dibaca bahwa kehadiran Agnes Monica dan Anggun C Sasmi adalah strategi untuk memperlebar jangkauan profit korporasi provider dengan menjadikan perempuan sebagai bagian dari konsumen mereka. Alat komunikasi tersebut seakan menjadi barang wajib bagi semua orang entah laki-laki maupun perempuan. Sejumlah 225 juta orang Indonesia pada tahun 2012 menjadi pelanggan seluler. Jumlah ini hampir mencapai 100% dari populasi penduduk Indonesia.[5] Meskipun mobilephone diciptakan untuk menanggulangi persoalan jarak dan waktu, namun hanya berfungsi jika diisi pulsa. Dalam hal ini, perusahaan Provider yang memiliki wewenang menyediakan pulsa dan internet. Di Indonesia, tercatat 11 perusahaan provider ikut bersaing dengan berbagai macam produk dalam meraih pelanggan.[6] Jika kita menempatkan iklan-iklan produk provider ke dalam arena perebutan konsepsi keperempuanan ideal pasca Orde Baru, maka kehadirannya seolah-olah menjadi tandingan kelompok fundamentalis agama. Sekilas ide-ide feminisme tentang independensi perempuan, kepemimpinan perempuan, dan kebebasan perempuan mengekspresikan serta menggerakkan tubuhnya terwakilkan oleh sosok-sosok di iklan produk provider ini.[7] Prinsip mobile phone sebagai alat yang memudahkan manusia melangkah, berkomunikasi dan mengakses informasi dapat dimaknai sebagai spirit untuk mendobrak tembok kekangan yang menghambat manusia untuk menjelajah dunia dan berinteraksi. Dalam konteks persoalan perempuan kehadiran benda ini diterjemahkan oleh iklan-iklan provider sebagai sebuah bentuk dukungan terhadap segala macam upaya pengekangan terhadap perempuan. Namun jika kita menggunakan teori semiotika maka tidak ada tanda yang netral. Selalu ada motif ideologi yang tersiar dalam tanda tersebut. Tulisan ini ingin menelisik mitos-mitos “pembebasan perempuan” yang tersiar di iklan tersebut, serta melihat bagaimana seharusnya teknologi HP digunakan menurut versi provider dalam konteks persoalan perempuan. Menurut Hermawan membaca iklan televisi tidak ubahnya membongkar praktik ideologis yang bekerja secara manipulatif di dalam sebuah situasi sosial tertentu.[8] Sebelum mengarah pada mitos apa yang berusaha disebarkan oleh iklan-iklan ini sudah sepantasnya kami menjabarkan sekilas apa itu semiotika. Setelah itu mendeskripsikan iklan-iklan yang dimaksud dan kemudian menjelaskan nilai-nilai “pembebasan perempuan” yang berusaha dimitoskan iklan tersebut. Iklan dan Semiotika Dalam lingkungan kebudayaan populer keberadaan iklan di dunia perdagangan menjadi penting. Fungsinya tidak sebatas alat promosi akan barang dan jasa namun termasuk menanamkan citra kepada konsumen mengenai produk yang ditawarkan. Citra yang terbentuk oleh iklan kemudian menggiring setiap pelanggan untuk percaya, loyal dan terus bertahan mengonsumsi produk tersebut. Sehingga pembacaan arti iklan menjadi bermanfaat untuk memahami komunikasi yang ditawarkan oleh sebuah produk. Iklan-iklan yang muncul diberbagai media memiliki banyak pesan baik secara verbal maupun non verbal dan bersifat komunikatif. Pembacaan sebuah iklan memiliki pertalian kuat dengan semiotika. Semiotika merupakan teori pemikiran filsafat yang berkembang di Eropa dan Amerika. Secara epistimologis Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “semeion” yang artinya penafsir tanda. Semiotika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang tanda, makna dan cara tanda-tanda serta makna-makna tersebut bekerja. Secara luas semiotika berarti studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda, bagaimana cara kerjanya, dan apa manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dengan perantara tanda-tanda manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya, sekaligus mengadakan pemahaman yang lebih baik terhadap sesuatu. Menurut Roland Barthes sebuah tanda memiliki dua pemaknaan yaitu denotasi (makna sebenarnya sesuai dengan kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal).[9] Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang menandai suatu kesan hasil interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultur penggunanya. Ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi berkembang menjadi makna denotasi maka akan menjadi mitos. Contoh yang diberikan Barthes dari sampul Paris-Match adalah seorang pria muda berkulit hitam sedang memberi hormat militer dalam seragam militer. Mata pria muda itu diangkat ke atas, mungkin sedang menatap bendera. Kenyataannya memang ada pria berkulit hitam yang difoto dalam pose dan pakaian itu. Tapi ada makna lain bahwa Prancis adalah kerajaan yang besar, bahwa semua warga negaranya tanpa diskriminasi warna kulit setia melayani dibawah benderanya. Pengertian ini terhadap teks kebudayaan tidak terhindarkan, karena ideologi adalah proses dimana yang bersifat historis dan diciptakan oleh budaya-budaya tertentu dihadirkan tanpa masa, universal dan alami.[10] Mitos tidak lagi menjadi penanda yang netral tetapi memainkan pesan-pesan tertentu yang bisa berbeda dengan makna asalnya. Dalam contoh di atas Barthes mengungkapkan kenapa anak berkulit hitam yang dipilih? Mengapa menggunakan atribut Prancis? Mengapa sorot mata menatap ke atas? Dengan jeli Barthes menafsirkan bahwa saat itu situasi politik Prancis sedang berkonfrontasi dengan Aljazair atau tepatnya menjajah Aljazair yang penduduknya berkulit hitam. Realitas itu menunjukkan bahwa Prancis adalah negara imperialis dengan wilayah jajahan sebagian besar penduduk berkulit hitam dan perjuangan Aljazair sedang mendekati kemenangan. Frustasi yang tersembunyi dari Prancis diliput oleh majalah Paris Match sebenarnya hanyalah mitos dari keagungan Prancis.[11] Kehebatan mitos adalah pengaburan sebuah ideologi tertentu dengan meyakinkan subjek dengan tanda-tanda yang mampu membuat ideologi itu tidak perlu digugat, namun absah dan benar untuk diyakini. Produksi mitos dalam teks tertentu membantu pembaca menggambarkan situasi sosial budaya dan juga politik yang ada disekelilingnya. Melalui mitos makna menjadi masuk akal dan diterima pada satu masa maupun tidak pada masa yang lain, sehingga kebenaran mitos menjadi relatif. Tulisan ini mengajak pembaca untuk melihat mitos apa yang berusaha disebarkan oleh iklan-iklan provider untuk meyakinkan pemirsa. Iklan adalah hasil pembacaan pihak korporasi provider tentang manusia ideal Indonesia dalam hal ini perempuan. Disaat yang sama jenis perempuan ideal Indonesia yang disodorkan korporasi bukanlah suara kejujuran, namun memiliki motif atau ideologi tertentu yang seolah-olah ideal karena itu iklan adalah mitos atau dusta. Di bawah akan dijabarkan lebih lanjut mitos yang berusaha dibangun. Iklan Simpati dan Agnes Monica http://www.youtube.com/watch?v=RY8iGhNyaL0 (14 november 2012) Denotasi Makna denotasi di iklan Simpati ini dijabarkan sebagai berikut; nyanyian Agnes menggema diiringi suara menggaung mirip sebelum film di bioskop yang akan diputar. Di saat yang sama muncul visual “Simpati Mempersembahkan” dengan latar merah menyala sebagai simbol Simpati. Agnes Monika bersama para penari latarnya sedang latihan di sebuah studio. Agnes mengenakan pakaian senam ketat yang membuat kita bisa melihat lekuk tubuhnya yang sehat dan langsing. Agnes Monica sebagai pemimpin yang mengomandoi gerakan para penari latarnya. Dia menyemangati para penari dengan mengucapkan “speaking up your mind”. Dia mengucapkan kalimat itu dengan suara menghentak. Kemudian adegan berganti Agnes dengan pakaian senamnya sendiri menatap kosong, setelah itu muncul visual kalimat “single terbaru Agnes Monica” dengan latar merah. Adegan berubah ke sebuah studio rekaman. Di sana terlihat Agnes dengan penuh semangat menyanyikan lagu single terbarunya. Lirik lagu yang didendangkan Agnes adalah “hidupku itu adalah aku”. Agnes mengenakan pakaian putih ketat sambil mengenakan jaket di dalam studio musik tersebut, dia tersenyum sambil bergoyang. Adegan kemudian berpindah ke sebuah panggung yang menjadi tempat show Agnes. Dia bersama penarinya melakukan geladi resik di atas panggung sebelum pentas. Di saat geladi resik itu Agnes sebagai pemegang komando, dan semua penari latar mengikuti gerak Agnes. Artis perempuan ini menari dengan menggunakan celana pendek hitam dan baju putih ketat sambil mengenakan jaket hitam. Tayangan kemudian berubah di balik panggung. Ditampilkan sebuah suasana heroik ketika Agnes menyemangati para penari latarnya sebelum konser dilaksanakan. Kemudian Agnes bersama penari keluar dari belakang panggung menuju ke tempat pementasan, dan ditutup oleh simbol Simpati dengan tulisan dibawahnya “Eksklusif hanya untuk pengguna Simpati”. Adegan terakhir kembali ke studio rekaman, di sana agnes berujar “Simpati is my style”. Konotasi dan mitos yang diharapkan Agnes Monica adalah artis papan atas Indonesia, dan penggunaan Agnes sebagai bintang iklan pertanda Simpati ingin memengaruhi penggemar Agnes agar mau menjadi pelanggan produk ini. Jumlah followers Agnes di twitter sampai dengan Juli 2013 menembus angka 8 juta dan fanspage facebook telah mengumpulkan 4.2 juta penggemar. Rayuan tidak hanya lewat penggunaan artis idola tetapi dengan memberikan bonus lagu single terbaru Agnes yang berjudul “Muda (Le O Le O)” dan “Walk”. Makna konotasi yang lain dari iklan ini adalah Simpati mendukung secara simbolik perempuan sebagai pemimpin. Analisa ini tampak saat Agnes menyemangati penari latarnya yang mayoritas laki-laki itu dengan kalimat “Speaking up your mind” yang artinya “keluarkan pendapat mu”, atau dalam konteks menari kalimat itu bisa diartikan “ekpresikan isi hati saat kamu menari”. Kalimat ini keluar karena para penari terlihat kurang lepas dalam menari. Kemunculan kalimat itu mempertegas Agnes berjiwa pemimpin karena jeli melihat situasi dan kondisi orang-orang yang dia pimpin. Agnes juga terlihat kuat dan bersemangat ketika Agnes menari dengan begitu lincah dan bernyanyi dengan penuh gairah dalam iklan ini. Agnes dicitrakan memiliki wawasan dan tidak puas berada di dalam zona nyaman. Ini terasa saat kita mendengar bahasa Inggris Agnes yang tidak kaku saat mengucapkan “speaking up your mind”, ataupun “Simpati is my style” pada akhir iklan. Dari kepiawaian berbahasa Ingris ini terkesan Agnes ingin memperlebar popularitas. Tidak cukup hanya berpuas-puas diri dengan ketenarannya di Indonesia. Pengucapan bahasa Inggris yang sempurna dari Agnes memberikan kesan bahwa perempuan berhak melangkahkan kaki sejauh-jauhnya demi meraih harapan. Apalagi jika kita kaitkan dengan kisah-kisah di luar iklan tentang Agnes yang seringkali diberitakan sibuk berpentas di luar negeri, dan berkolaborasi dengan artis internasional seperti Keith Martin, Christian Chavez, Michael Bolton dan Timbaland. Patut diingat tahun 2013 Agnes Monica sudah berusia 27 tahun dan belum menikah, dia jarang secara terbuka menunjukkan pasangan-pasangan yang pernah dia pacari. Gambaran single woman sangat melekat pada diri artis yang sudah terasah bernyanyi dari sejak masih kecil. Kehadiran Agnes dalam iklan ini memberikan pandangan bahwa perempuan lajang bisa survive dan sukses secara ekonomi. Hal ini juga tampak pada iklan Simpati terlihat dari pakaian mahal Agnes serta aksesori yang dikenakannya dalam iklan ini. Kesuksesan dapat digapai dengan kerja keras, hal ini terlihat dari keseriusan Agnes menari saat geladi resik sebelum tampil di atas panggung. Kehadiran para penari latar melakukan latihan dan pentas bersama Agnes bisa kita duga mereka bekerja untuk Agnes. Pemandangan itu menandakan Agnes mampu memberikan pekerjaan kepada orang lain. Agnes adalah bos dari para pria yang bekerja untuk dia. Makna konotasi dari iklan ini adalah perempuan bisa mencapai kemapanan dan ketenaran berdasarkan kualitas dirinya. Ketika kualitas diri perempuan berkembang maka yang bisa mendapatkan rezeki bukan hanya perempuan tersebut, namun laki-laki seperti para penari Agnes. Walaupun tubuh Agnes ditutupi pakaian senam, namun tetap terlihat lekukan tubuh langsing artis perempuan ini. Lihat juga saat Agnes melakukan geladi resik, dia begitu percaya diri menari walau mengenakan celana pendek di atas lutut. Makna konotasi dari adegan di iklan ini adalah perempuan berhak mempertunjukkan tubuhnya kepada siapa pun. Tidak ada yang berhak mengaturnya, semakin dipertegas dengan lirik lagu yang didendangkan Agnes Monica “hidupku itu adalah aku”. Hanya “Aku” yang berhak menentukan “hidupku”, bukan “mereka” yang berada di sana. Istilah “mereka” bisa dimaknai kelompok mayoritas atau sistem dominan seperti patriarki. Kehadiran Agnes sangat bertolak belakang dengan wujud perempuan ideal yang disuarakan kelompok agama di tanah air yang menggebu-gebu ingin menutupi aurat tubuh perempuan lewat UU anti pornografi ataupun Perda Syariah. Jika kita amati makna konotasi dari iklan Simpati ini maka posisi iklan Simpati sejalan dengan spirit wacana kepemimpinan perempuan yang mulai muncul secara terbuka di era reformasi. Runtuhnya Orde Baru dirayakan sebagai era runtuhnya otoritarianisme negara. Otonomi daerah muncul sebagai solusi, agar jatah pembangunan tidak melulu jatuh dan ditentukan oleh elite Jakarta. Kelompok masyarakat yang dikekang pada masa itu mulai bersuara. Isu-isu yang jarang dimunculkan pada zaman Orba sekarang mulai terbuka dan diperbincangkan termasuk isu persoalan perempuan. Perempuan diberikan ruang berpolitik di parlemen sebesar 30% dan ini diatur secara hukum. Diskusi tentang kemandirian perempuan juga mencuat, Komnas Perempuan dibentuk, dan perempuan mulai berkiprah diseluruh bidang kehidupan.[12] Istilah “speaking up your mind” yang diucapkan Agnes sesuai dengan situasi masyarakat yang gerah karena selama ini diredam ekspresinya oleh rezim. Berdasarkan penjabaran di atas maka mitos yang berusaha dibangun oleh iklan ini adalah kebebasan bagi perempuan ketika perempuan berada di luar rumah dan berjuang di luar ruang domestik. Simpati berusaha membentuk tafsir sosial bahwa produknya mendukung kaum hawa untuk menggunakan HP sebagai alat meraih cita-cita di luar sana. Simpati ingin mengajak perempuan mengakses globalisasi dan menggunakan globalisasi untuk meraih mimpi. Apalagi produk HP sekarang tidak hanya untuk berkomunikasi semata namun bisa digunakan untuk mengakses internet. Ketika perempuan ber-HP maka selayaknya perempuan tersebut mempergunakan pulsanya untuk mengakses dunia di luar sana dan melepaskan diri dari tirani rumahan. Simpati menunjukkan kesiapannya untuk ini. Produknya kuat untuk melintas batas. Perjuangan perempuan adalah merebut karier dan berani melangkah sendiri keluar dan bukan cepat-cepat menikah, berakhir menjadi istri atau ibu rumah tangga yang menggantungkan diri secara ekonomi kepada suami. Menjadi merdeka adalah mandiri secara ekonomi, begitu nilai yang ingin ditanam oleh iklan ini. Dari iklan ini kita bisa menduga produk ini ingin menyentuh kelompok wanita muda modern yang sibuk meniti karier. Kelompok ini sangat membutuhkan HP agar memperlancar komunikasi dan memperat jaringan bisnis mereka. Wanita karier sering dicitrakan sebagai wanita modern yang berani lepas dari kurungan tirani tradisi, independen secara ekonomi, berasal dari kelas menengah atas, punya jaringan internasional, berpendidikan dan berwawasan. Bukankah membebaskan perempuan dari tirani rumahan adalah ide mulia sebab faktanya tirani rumahan mengerdilkan perempuan, membunuh perempuan sebagai agensi atau pelaku aktif, membungkam independensinya karena diarahkan untuk menggantungkan diri kepada laki-laki, serta bisa mengubah prasangka “perempuan nakal” yang didengungkan kelompok konservatif agama menjadi “perempuan mandiri”? Di sinilah letak mitosnya, sebab pengerdilan terhadap perempuan juga kerap terjadi di luar rumah. Bagi wanita karier yang bergelut di dunia hiburan malam semacam Agnes tentu saja citra-citra negatif bisa diminimalisir. Tempat pentas Agnes adalah di konser besar, kafe atau klub elite yang jarang diserbu oleh kelompok agama penghujat perempuan. Justru image dia terangkat sebagai artis perempuan eksklusif, elite dan modern. Akan berbeda cerita jika Agnes artis kelas bawah, semisal artis dangdut yang menggunakan HP-nya untuk mengontak agen atau kenalan agar bisa diberikan lapangan pekerjaan di luar rumah dengan menggelar konser mini di kafe remang-remang. Label negatif dan pelecehan terhadap mereka kerap terjadi. Aksi sweeping kemaksiatan sering dilakukan di tempat kafe “underground” ini oleh kelompok fanatik agama, dan aparat pemerintah. Memang secara gender Agnes termasuk kategori subordinat jika menempatkannya pada ranah budaya kita yang kental dengan budaya patriarkinya. Artis perempuan yang menyabot banyak penghargaan nasional maupun internasional ini secara etnis dan agama juga berada dalam posisi subordinat. Agnes Monica adalah beretnis Tionghoa dan beragama Kristen Protestan. Kelompok agama dan etnis yang seringkali mengalami diskriminasi oleh kelompok yang mengaku mayoritas di Indonesia. Lihat misalnya kerusuhan di ibu kota menjelang kejatuhan Soeharto, rumah dan aset bisnis warga beretnis Tionghoa menjadi korban perusakan serta pembakaran, bahkan tidak sedikit perempuannya menjadi korban pemerkosaan. Kalau dalam konteks agama pemandangan gereja yang selalu dijaga ketat oleh aparat saat perayaan hari Natal masih kerap terjadi, atau pembangunan gereja yang selalu diprotes oleh warga setempat. Lewat identitas Agnes Monica iklan ini secara tidak langsung menyelipkan semangat bahwa manusia yang terdiskriminasikan bisa mendobrak tembok penghambat kemajuan untuk mereka dalam meraih cita-cita. Istilah “speaking up your mind” yang diucapkan Agnes kala menyemangati penarinya adalah pertanda sudah saatnya mereka yang terbungkam berani mengutarakan isi hati. Sedangkan kalimat penutup Agnes saat mengucapkan “My Simpati is my style” menandakan keberpihakan Simpati kepada manusia Indonesia yang ingin meniru keberanian Agnes dalam mengejar harapan sejauh mungkin. Simpati ingin menciptakan sensasi bahwa produknya sangat sesuai untuk umat manusia yang memiliki cita-cita tinggi namun dihambat rantai sistem patriarki, rasisme dan politik mayoritas vs minoritas. Walaupun Simpati bermodalkan ketenaran Agnes, bonus lagu Agnes, sejarah identitas Agnes dan nilai-nilai pembebasan yang tersisip dalam iklan namun kehebatan produk ini tetaplah mitos. Berfungsinya HP tergantung pada sinyal dan pulsa. Faktanya tidak semua perempuan atau kelompok subordinat lainnya yang ingin meraih mimpi dan mendobrak batas-batas kekangan bisa menikmati sinyal yang lancar karena posisi mereka bukan di wilayah ramah sinyal Simpati. Begitu juga tidak semua perempuan atau kelompok subordinat lainnya bisa menikmati kelancaran komunikasi meskipun berada di wilayah Simpati sebab pulsa mereka bodong, sehingga posisi kelas sangat menentukan. Oleh karena itu iklan ini dusta atau mitos. Namun terlepas dari semua mitos-mitos yang berusaha dikonstruksi Simpati, sosok perempuan ideal Indonesia yang ingin ditonjolkan oleh Simpati adalah perempuan penjelajah yang berani memilih untuk single dan percaya diri dengan kualitas diri untuk bertanding di kancah internasional. Sosok perempuan yang jarang diberikan ruang untuk dipuja pada zaman Orde Baru. Rezim ini lebih senang kalau perempuan tunduk, berada dibawah dan lebih lemah daripada pria. Di bawah akan dijelaskan sosok Anggun dari iklan Indosat Mentari yang juga menawarkan sosok perempuan ideal namun berbeda arah dengan versi Simpati. Iklan Mentari dan Anggun C Sasmi http://www.youtube.com/watch?v=b9exSLH_E88 Dalam membahas Iklan Mentari versi Anggun C Sasmi, penulis tetap menggunakan teori Roland Barthes yang bersifat denotasi, konotasi dan memunculkan mitos. Sama seperti iklan Simpati, Mentari juga menggunakan artis perempuan sebagai ikonnya. Denotasi Di iklan ini Anggun digambarkan berada di sebuah ruangan besar yang didominasi warna putih. Anggun berpakaian putih dan berambut hitam panjang. Anggun terlihat duduk di bagian atas piano yang berwarna hitam. Kemudian Anggun mengucapkan kalimat ”aku dilahirkan untuk musik dan sejak itu kami tak pernah terpisahkan”. Tampak peralatan menulis (pulpen, pensil dan kertas) berada di atas meja. Tangan Anggun mengambil salah satu pulpen tersebut dan menulis di secarik kertas yang hampir kusut. Anggun kemudian mengucapkan kalimat “Bagaikan dua elemen yang menciptakan harmoni” sambil menggerakkan jari jemarinya diatas piano, Anggun kembali melanjutkan ucapannya “Saling melengkapi, mengisi satu sama lain seperti Indosat Mentari baru yang diciptakan khusus untuk mengoptimalkan smartphone.” Saat itu anggun tidak hanya duduk memainkan piano, namun juga tampak telungkup, terlihat kakinya menggunakan kaos kaki berwarna putih dengan wajahnya mengarah ke kamera. Sambil bernyanyi di depan mikrofon, Anggun membentangkan lengannya dan tersenyum. Nyanyiannya diiringi dua laki-laki berkulit putih, satu laki-laki berambut panjang sambil memainkan gitar dan satu lagi laki-laki berkepala botak, berkulit hitam dengan memainkan kontrabas. Adegan beralih ke sebuah smartphone berwarna putih dan tampak jari Anggun menggeser layar handphone dari lambang Mentari yang berwarna kuning ke lambang WhatsApp berwarna hijau dikelilingi garis putih. Di saat duduk Anggun menempatkan handphone-nya yang bercover kuning di bagian belakang sambil menelepon atau menerima telepon sambil tersenyum. Dalam satu adegan muncul dua wajah Anggun. Pertama dia menunjukkan handphone-nya dengan layar menyala berisi lambang Mentari dan yang kedua Anggun menunjukkan kertas kover kartu Mentari. Kali ini Anggun mengucapkan “Smartphone dan Indosat Mentari itulah harmoni”. Adegan ditutup oleh munculnya kover mentari berwarna putih berisi lambang mentari dengan warna kuning bertuliskan Indosat Mentari. Bagian bawah kanan terdapat tulisan designed for smartphone dan gambar empat handphone. Terakhir muncul Anggun sambil tersenyum menampakkan giginya yang berwarna putih. Konotasi dan mitos yang diharapkan Penggunaan Anggun sebagai bintang iklan secara konotasi dapat dimaknai bahwa Mentari ingin menjadikan penggemar Anggun sebagai pelanggan produk ini. Target pasar yang dikehendaki oleh Indosat Mentari adalah dari kalangan kelas menengah atas. Keberadaan alat tulis seperti pulpen, pensil dan kertas menunjukkan Anggun adalah perempuan terpelajar yang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Keterampilannya bernyanyi, menciptakan lagu dan piawai memainkan alat musik berupa piano menandakan Anggun berasal dari kelas menengah atas. Melodi yang dihasilkan Piano merupakan kegemaran kaum elite dan perlambang dari status kemapanan masyarakat Eropa. Harga piano yang mahal menjadikan alat musik ini sebagai barang mewah yang tidak sembarang dimiliki oleh orang kebanyakan. Ketika Anggun mengucapkan “aku dilahirkan untuk musik dan sejak itu kami tak pernah terpisahkan”, dan setelah itu disusul kalimat “bagaikan dua elemen yang menciptakan harmoni” adalah pengertian harmoni dari produk Indosat Mentari. Anggun dan musik adalah dua elemen yang padu dan saling mengisi. Langgengnya hubungan Anggun dan musik kemudian dilekatkan kepada hubungan Mentari dan smartphone lewat kalimat “Smartphone dan Indosat Mentari itulah harmoni”. Harmoni bagi Mentari adalah sebuah hubungan keselarasan atau sinergitas dua unsur yang padu dan tidak saling bertentangan. Mentari juga ingin menampilkan sisi harmoni dari pewarnaannya. Perpaduan ruang yang didominasi warna putih dengan sedikit sentuhan hitam menyiratkan kesejukan. Dominasi warna putih melambangkan kebersihan dan kesucian sebagaimana terlihat dari pakaian dokter, suster ataupun pegawai rumah sakit yang tampak higiene. Putih juga dianggap sebagai netral, tidak berpihak atau keseimbangan sehingga warna putih sesuai dengan konsep harmoni. Putih yang netral, bersih, serta tidak berpihak menandakan sifat harmoni yang menolak pertentangan dan gonjang-ganjing antar berbagai macam elemen. Harmoni atau keselarasan juga muncul dalam bentuk tubuh Anggun. Ia dikonotasikan sebagai perempuan ideal karena tidak gemuk dan tidak terlalu kurus. Ia menggunakan pakaian yang hampir menutupi lengannya, bercelana panjang dan berkaos kaki sehingga memunculkan kesan berpakaian sopan. Anggun terlihat sebagai perempuan yang berperilaku halus, sopan, tenang, dan tidak ambisius. Keberadaan Anggun di suatu ruangan mirip rumah ini menunjukkan Anggun taat “posisi” sebagai perempuan Jawa. Secara normatif dalam tradisi Jawa aktivitas kaum perempuan ada di dalam rumah, sedangkan laki-laki beraktivitas di luar rumah. Posisi Anggun di dalam rumah, pakaian Anggun yang sopan dengan karakternya yang halus menandakan dia tidak berlebih-lebihan, tidak ambisius serta taat posisi. Karakter yang pas dengan prinsip harmoni. Pada saat Anggun bernyanyi, Ia diiringi oleh dua laki-laki berkebangsaan asing. Satu laki-laki memegang gitar dan laki-laki lainnya memainkan kontrabas. Kehadiran pemusik asing ini menandakan Anggun memiliki relasi internasional. Anggun dan kedua orang asing itu tampak kompak sebagai tim dikala mereka latihan memainkan sebuah lagu di rumah Anggun. Makna konotasi yang ingin dibangun adalah “orang dalam” dan “orang asing” bisa berselaras atau Anggun sebagai representasi orang “Timur” bisa harmoni dengan “Barat” yang diwakilkan oleh dua orang asing pemain alat musik tersebut. Anggun memiliki modal sejarah sebagai penunjang popularitasnya. Modal sejarah adalah track record prestasi Anggun, kisah hidupnya dan gosip-gosip tentangnya yang menunjang perempuan ini menjadi idola. Ketika melihat Anggun dalam sebuah iklan, maka fokus penonton bukan hanya pada kisah di iklan atau produk di iklan melainkan juga menyimak si bintang iklan. Penonton akan teringat sejarah atau kisah-kisah tentang bintang iklan tersebut. Ia adalah musisi perempuan Indonesia yang terkenal di era Sembilan puluhan. Ia berkesempatan hijrah keluar negeri untuk mengadu nasib sebagai musisi. Anggun memiliki lima album internasional dan sering berkolaborasi dengan musisi dunia. Lagu “Deep Blue Sea” dan “Snow On The Sahara” adalah dua lagu yang membuat nama Anggun melambung di Eropa. Kalau dilacak ke belakang lagu Anggun juga pernah meledak di Indonesia pada era tahun sembilan puluhan yang berjudul “Tua-Tua Keladi”.[13] Ketika Mentari menggunakan jargon Harmoni maka arah audience akan melihat prestasi Anggun yang tidak hanya terkenal di dalam negeri namun juga di luar negeri sebagai sebuah bentuk harmoni. Seolah-olah sejarah popularitas Anggun tidak timpang, tetapi selaras dan padu. Sebagai penyanyi yang sibuk di luar negeri, Anggun tidak lupa menggelar konser di Indonesia. Bukan hanya lagu berbahasa Prancis dan Inggris yang dibawakannya, namun Anggun juga tetap membawakan lagu berbahasa Indonesia saat konser di tanah airnya. Anggun bisa dianggap sebagai sosok manusia yang selalu ingat “akar” sebab tetap ingat untuk pulang ke kampung halamannya (mudik). Nilai harmoni yang menempel pada bintang iklan Mentari ini adalah perempuan berhak berada di luar, sekaligus jangan kebablasan hingga lupa pulang ke rumah. Perempuan boleh bergaul dan berkelana ke luar meniti karier, namun harus ingat untuk balik ke tempat dimana dia dibesarkan. Nilai keharmonisan ini bertentangan dengan perspektif kelompok agama yang getol ingin mengkerangkeng perempuan di dalam rumah, dan mendisiplinkannya lewat razia tempat-tempat hiburan malam, membuat Perda Syariah ataupun UU Pornografi. Pandangan harmoni berkontradiksi dengan wacana “anti Barat” yang digelorakan oleh kelompok Islam garis keras. Mereka merespons Barat dengan hujatan dan makian sebab bagi mereka Barat adalah hegemoni. Kelompok ini memandang bahwa “Barat” adalah musuh, bahkan istilah “kafir” mereka lekatkan kepada Barat. Bagi mereka Barat adalah sumber kerusakan moral yang menyebabkan kawula muda terpengaruhi seks bebas serta menjadi individualis.[14] Sedangkan di iklan Mentari justru terbalik, “Barat” bukanlah musuh yang harus dijauhi namun bisa bersinergi dengan “Timur”. Anggun adalah perempuan Jawa yang menikah dengan seorang penulis berkebangsaan Prancis yaitu Cryil Montana. Sikap Mentari memilih Anggun sebagai bintang iklannya tentu sebuah sikap oposisional dengan pemikiran fanatisme etnis ataupun agama tentang perempuan ideal. Menurut kelompok fanatik ini perempuan ideal adalah ketika perempuan memilih pasangan sesama agama, etnis, kasta ataupun daerah. Konsep harmoni Mentari dalam konteks kisah romantika Anggun jelas menolak pemahaman bahwa perempuan harus menikahi laki-laki seidentitas. Jika kita menggunakan kaca mata harmoni maka kisah romantika Anggun ketika memilih pasangan beda identitas dalam hal ini beda negara bukanlah sebuah aksi pengkhianatan atau keterlepasan perempuan menjadi milik sang suami. Melainkan sebuah hubungan yang bersinergi, atau keselarasan. Harmoni menurut Indosat Mentari adalah dua elemen yang tidak terpisahkan, maka hubungan beda negara tidak dengan serta merta menghilangkan ke-Indonesiaan Anggun dan ke-Eropaan pasangannya, melainkan bersinergi saling mengisi. Mentari seolah-olah ingin mengajak audiens bahwa di era liberalisme politik ini masyarakat jangan terpaku ke dalam fanatisme agama atau kedaerahan, dan jangan juga terlalu terpukau terhadap “Barat” sampai-sampai tidak mau untuk balik ke “rumah”. Kehadiran smartphone yang ada fasilitas internetnya selayaknya tidak digunakan kaum perempuan sebagai jalan keluar untuk memutus “akar” tempat mereka dibesarkan dan dilahirkan, melainkan sebagai jembatan mengharmonikan kedua-duanya. Layaknya Anggun yang nyaman beraktivitas di dalam rumah tetapi tetap melek informasi di dunia luar, dan bergaul dengan orang asing. Mentari lewat iklan ini ingin menciptakan mitos bahwa produknya bisa digunakan di dalam rumah maupun di luar rumah. Kartu ini ingin menunjukkan bahwa sinyal produk ini kuat entah digunakan di dalam gedung ataupun di luar gedung. Kadang kala jika HP digunakan di dalam gedung ataupun di luar gedung sinyal bisa terganggu karena produk providernya lemah menangkap sinyal. Penampakan Anggun yang asyik menggunakan Smartphone di dalam gedung menandakan sinyal produk providernya kuat. Mentari ingin menampilkan kepada khalayak bahwa produknya pantas untuk menyinergikan atau mengharmonikan dua ruang. Namun mengapa harmoni itu mitos? Bukankah keserasian, keselarasan dan keseimbangan itu indah. Kalau kita membalikkan cara membacanya dengan arah yang berlawanan maka iklan ini dengan sendirinya merontokkan mitos harmoni yang berusaha dibentuk oleh Mentari. Keserasian dalam dominasi warna putih sebagai lambang bersih dan suci sekiranya menegaskan kembali kolonialisasi bangsa Eropa. Sebelum Belanda hadir di nusantara, jajaran pulau-pulau memiliki banyak corak dan pewarnaan. Contohnya rumah-rumah masyarakat terbuat dari bambu dan kayu dengan warna asli yang keluar dari bahannya, tetapi semenjak kota-kota baru dibentuk oleh Belanda bermunculan gedung-gedung berarsitektur Eropa bercat dasar putih.[15] Pakaian orang melayu berupa kemben dan destar, yang disesuikan dengan warna alam seperti warna kayu dan daun berubah menjadi gaun atau kemeja yang didominasi warna putih. Dominasi warna putih yang seakan-akan memberi kedamaian dan ketenangan dalam konteks sejarah didasari oleh penaklukan suatu wilayah. Sudah barang tentu penaklukan ini memakan banyak korban. Indosat Mentari memitoskan Anggun seolah-olah adalah musisi yang berhasil bersinergi dengan dunia internasional. Padahal kalau dicermati Anggun bagaikan pemain sepak bola atau atlet bulu tangkis yang dilekatkan dengan istilah jago kandang, terbukti dengan belum ada lagi lagu-lagu internasional yang setenar dulu. Bisa dilihat dari kecenderungan Anggun sekarang ini yang sering melakukan konser di Indonesia untuk menyelamatkan eksistensinya sebagai musisi kelas atas.[16] Kembalinya Anggun ke tanah air bahkan menjadi ikon produk Mentari bukanlah sebuah harmoni, melainkan ketimpangan sebab dia tidak tenar lagi di luar sehingga akhirnya balik ke dalam agar populer lagi. Berbeda dengan artis Asia Jacky Chan yang tenar di luar negeri juga tenar di dalam negeri. Terbukti terus berproduksinya film Jacky Chan dengan artis-artis hollywood dan diundang ke acara festival film bergengsi dengan skala internasional.[17] Biasanya istilah mudik diterjemahkan ketika anak kampung yang bekerja di kota atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kembali ke kampung halamannya untuk membagikan rezeki hasil kerja kerasnya. Anggun justru berbeda, Ia kembali ke “kampung halaman” untuk mencari nafkah dan menyerahkan hasil kerja kerasnya ke luar negeri. Mengapa begitu? Karena Anggun adalah warga negara Prancis dan hidup di Prancis. Biaya hidup di Prancis jelas lebih mahal, sangat mungkin uang dari kerja keras Anggun digunakan membayar pajak di negeri menara Effiel itu. Secara simbolik mudiknya Anggun bukanlah harmoni melainkan sebuah hubungan tidak seimbang karena mengeruk keuntungan di tanah air sendiri tetapi dipersembahkan untuk mendukung eksistensi kelas atau statusnya di Prancis. Rapuhnya mitos Harmoni yang berusaha dibentuk Mentari membuat kita melihat kehadiran dua lelaki kulit putih sebagai pengiring Anggun di iklan tersebut bukanlah hubungan kesetaraan. Bisa saja ditafsirkan kedua laki-laki kulit putih itu bekerja untuk Anggun sebagai band pengiring. Kedua lelaki itu ibaratnya “pegawai” dan mereka memainkan musik mengikuti selera sang bos yaitu Anggun. Jika kita melihat ke belakang bangsa kita pernah dijajah bangsa Eropa sekian lama dan tertanam di dalam kepala kaum terjajah untuk ingin membalas dendam. Apalagi wacana Orientalis masih kuat melekat bahwa bangsa “Barat” lebih unggul dari bangsa “Timur”. Hal-hal ini menstimulus masyarakat terjajah untuk berganti posisi. Keberhasilan Anggun sebagai representasi bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa dalam mempekerjakan “orang Eropa” sebagai pengiring lagunya mewakili mimpi “ganti posisi” bangsa terjajah. Sensasi berada lebih di atas dari bangsa penjajah terwakilkan oleh iklan Mentari. Hubungan antara “timur” dan “barat” ini bukanlah sebuah keselarasan namun mewakili the sense of revenge kaum terjajah atau bangsa yang selama ini dianggap terbelakang. Kehadiran Mentari sebagai jembatan keselarasan dua elemen berubah menjadi jembatan ketimpangan, penyelamatan karier, revenge, dan ganti posisi. Telekomunikasi seluler dan pulsanya bukan semata alat komunikasi yang mempertautkan dua dunia secara seimbang melainkan sebagai saluran untuk menyelamatkan eksistensi, merawat dominasi, mengembangkan kuasa. Terlepas dari keroposnya harmoni yang dikonstruksi Indosat Mentari, kita bisa melihat sikap Mentari bahwa perempuan ideal adalah perempuan yang berhak berpetualang, meniti karier keluar dari kampung halamannya, bergaul dengan orang luar, bahkan menikah dengan orang luar tetapi tetap jangan lupa untuk balik ke kampung halaman. Perempuan ideal adalah perempuan yang mampu menyinergikan dua elemen antara rumah dan di luar rumah ataupun dikotomi Timur dan Barat. Namun tidak semuanya seberuntung Anggun yang pulsanya bisa dia gunakan untuk mengontak agen tiket pesawat agar bisa pulang kampung. Banyak perempuan Indonesia yang berada di luar bekerja sebagai buruh migran tidak bisa pulang karena paspornya ditahan majikan, sehingga pulsa digunakan mereka sebagai jembatan penyambung rindu semata. Penutup Dari penjabaran di atas kita bisa menyimak “bagaimana seharusnya perempuan Indonesia” versi Simpati dan Mentari secara semiotika. Simpati menampilkan perempuan energik, tangkas, sigap dalam memimpin serta siap menuju ke luar dari zona nyaman di negeri sendiri. Sedangkan Mentari menampilkan sosok perempuan lembut dan tenang yang berada di dalam rumah serta memiliki kesejarahan pernah tenar di luar negeri ataupun di dalam negeri. Simpati menargetkan jenis perempuan yang baru meniti karier dan masih menggebu-gebu menaklukkan “Barat”. Berbeda dengan Mentari yang menampilkan sosok perempuan dewasa, sudah menikah, sudah pernah menaklukkan “Barat” dan balik lagi ke kampung halaman. Ada yang sama dari kedua sosok perempuan dalam iklan itu yaitu tidak mau memilih menjadi ibu rumah tangga. Agnes di usianya yang matang ini belum menikah sedangkan Anggun walau sudah menikah tetap memilih untuk meneruskan kariernya sebagai musisi. Hadirnya dua sosok ini semacam pertanda perubahan sebab di era Orde Baru perjalanan hidup perempuan diarahkan negara untuk berakhir menjadi ibu rumah tangga. Yaitu sosok perempuan yang hidupnya mengurus dapur, anak dan melayani suami. Tentu kita ingat pada zaman Orde Baru istilah “ibu memasak di dapur” sangat membumi diajarkan di sekolah-sekolah. Sedangkan di era reformasi lebih berdinamika karena konsep perempuan ideal tidak lagi dikontrol ketat oleh negara. Ruang terbuka ini memberikan peluang berbagai macam pihak untuk ikut serta menawarkan sosok idealnya termasuk korporasi semacam Telkomsel Simpati dan Indosat Mentari. Namun janganlah terlena dengan mulianya ide-ide pembebasan perempuan, karena dalam konteks era liberalisme pasar jelas memiliki kepentingan tertentu. Kepentingan yang menggerakkan perempuan untuk berada di luar. Walau perempuan berhasil meminggirkan pilihan untuk tidak dikurung dalam tirani rumahan, namun tirani di luar rumah sama terjalnya yaitu tirani pasar. Memalingkan pilihan sebagai perempuan yang mengonsumsi bahan makanan untuk dimasak buat keluarga atau deterjen untuk mencuci pakaian suami serta anak tersayang berubah menjadi mengonsumsi merek-merek terkenal agar bisa terlihat anggun di luar rumah, tampak seksi saat hangout di klub atau diskotek, tampil elegan ketika konser dan kerja di kantor. Kuasa patriarki juga berada di luar yang lagi-lagi mendaulat perempuan ideal sejatinya adalah sosok pesolek. Tidak cukup dengan bedak dan parfum untuk tampil “cantik” tetapi harus mengenakan pernak-pernik aksesori tertentu sesuai arahan majalah-majalah mode terkenal. Untuk tampil bugar di luar, perempuan diarahkan untuk melakukan operasi plastik, mengonsumsi vitamin tertentu ataupun ikut gimnastik. Pulsa Simpati dan Mentari berada didalam lingkaran kuasa yang mengarahkan tubuh perempuan ke luar rumah untuk dijadikan target pasar para bos mode busana, losion pemutih, botox, vitamin, dan lain sebagainya. Menarik jika kita melihat ke lapangan, usaha Simpati dan Mentari dalam menyebarkan pemahaman-pemahaman tertentu lewat sosok Agnes dan Anggun dengan tujuan mencari pelanggan bisa jadi tak berfungsi. Acapkali pelanggan pulsa tidak melihat sosok-sosok itu. Maksudnya faktor penyebab orang membeli produk provider bukan karena kehadiran bintang iklan namun karena paket bonus, gratis dan murah. Selain itu juga faktor efisiensi sebab mayoritas teman atau keluarga si pelanggan menggunakan kartu yang sama. Dari pembicaraan kami dengan beberapa pemilik kios HP, alasan orang membeli kartu atau pulsa adalah karena faktor tadi, yaitu efisiensi dan irit. Kecenderungan itu tidak mengenal kaya miskin. Gengsi kelas dan status bermain di merek HP bukan produk provider karena Produk HP terlihat oleh mata sedangkan produk provider tak tampak di penglihatan. Apalagi produk provider tidak lagi mahal seperti awal-awal kehadiran HP yang hanya dimiliki segelintir orang. Situasi seperti bisa membuat kerja keras para pembuat iklan yang ingin membuat produk providernya mewakili kelas-kelas tertentu atau perempuan-perempuan tertentu bisa berakhir mubazir. Terlepas dari iklan yang tidak memengaruhi pelanggan untuk membeli, kesan-kesan perempuan ideal yang ditonjolkan oleh iklan Simpati dan Mentari sebenarnya ikut mengarahkan isi kepala pemirsa Indonesia untuk menilai bagaimana seharusnya perempuan. Iklan bisa masuk ke ranah privat dan memengaruhi isi kepala sebab televisi sudah menjadi benda umum yang berada di kamar tamu ataupun kamar tidur. Dalam konteks ini iklan bukan lagi sekadar menawarkan produk, namun sebuah pemahaman atau ideologi tertentu yang ikut meramaikan gelanggang pertempuran antar pemahaman tentang perempuan. Kompetisi ini masih sulit untuk diprediksikan versi siapa sebagai pemenangnya. Catatan Belakang: [1] Lihat Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi [2] Menurut Komnas Perempuan terdapat 342 Perda diskriminatif terhadap perempuan atas nama agama dan moralitas yang dikeluarkan pemerintah daerah. Tercatat yang banyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif adalah Jawa Barat, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatra Selatan, Kalimantan [3]http://www.youtube.com/watch?v=RY8iGhNyaLO (14 November 2012) [4]http://www.youtube.com/watch?v=b9exSLH_E88 [5]http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/05/telekomunikasi-pelanggan-seluler-sentuh-255-juta-orang/ [6]Berikut adalah provider dan produknya; 1.Axis telpon Indonesia dengan produk Axis 2.Bakri Telcom dengan produk Esia, Aha.dan Wifone 3. Hutchison 3 dengan produk 3 (tri). 4. Indosat dengan produk StarOne, Matrix, IM3 dan Mentari. 5. Mobile-8 dengan produk Friend, Mobi dan Hepi. 6. Sampoerna Telkom dengan produk Ceria. 7. Smart Telcom dengan produk Smart. 8. Telkom dengan produk Flexi. 9. Telkomsel dengan produk Kartu As, Kartu Hallo, dan Simpati. 10. XL Axiata dengan produk XL. 11. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dengan produk byru pasti. [7] Ann Brooks (trj. S. Kunto Adi Wibowo), Posfeminisme & Cultural Studies Sebuah pengantar Paling Kontemporer, Jalasutra, Yogyakarta [8] Anang Hermawan, Membaca “Iklan Televisi: Sebuah Perspektif Semiotika”, http://communication.uii.ac.id/jurnal/editorial-jurnal/editorial-3-volume-2-nomor-1-oktober-2007.html [9] Melody Violine, Roland Barthes: kehidupan, Karya dan pemikiran, Academia.edu [10] Ibid [11] Ibid [12] Komnas Perempuan, Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perjalanan Bangsa, Jakarta, 2009, hlm 209 [13] Awal tahun 1990-an lirik lagu “Engkau lupakan, anak cucumu” menjadi fenomenal diberbagai kalangan. Tidak ada yang menyangka lagu sedahsyat tua-tua keladi dinyayikan Anggun C Sasmi saat masih berusia 15 tahun. http://hiburan.kompasiana.com/musik/2012/11/12/lima-diva-legendaris-indonesia-508325.html [14] Fathurin Zen, Radikalisme Retoris, Bumen Pustaka Emas, Jakarta, 2012, hlm183-191 [15] Gaya kolonial kental dengan pengaruh Eropa, sering kali mirip dengan gaya klasik yang didominasi warna putih dengan penggunaan lantai marmer. Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial belanda di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogjakarta, 1995. [16] Dalam Twitternya https://twitter.com/Anggun_Cipta/status/272286192836440064 di tahun 2013 Anggun akan lebih banyak menghabiskan waktu di Asia. Ia diangkat menjadi juri X-Faktor Indonesia yaitu ajang pencarian talent show di Indonesia. Kehadirannya banyak digunakan untuk menetapkan standar yang tinggi di ajang tersebut. [17] http://www.hollywood.com/static/the-best-of-jackie-chan  Memorabilia, kata yang menjelaskan tentang mengingat suatu peristiwa di waktu tertentu, dan kita pernah berada di sana. Memorare dari bahasa Latin, yang berarti "membawa ke dalam memori”. Memorabilia memecahkan teka-teki ingatan, manusia didesain memiliki memori, juga didesain untuk melupakan. Dalam ingat dan lupa itu, kita dimediasi oleh apa yang disebut sejarah. Dibalik memori dan melupakan itu, sesungguhnya ada masalah filosofis yang dalam. Memori tidak akan ada bila pada saat peristiwa itu kita tidak memikirkannya. Tentu kita pernah bertanya, kemana memori pergi? Atau bahkan hampir seluruhnya lenyap? Paul Ricoeur, filsuf Prancis yang banyak menulis tentang filsafat hermeneutika menghasilkan sejumlah pertanyaan tentang sejarah, memori, dan melupakan, mengapa peristiwa sejarah besar di dunia seperti Holocaust menempati garis depan kesadaran kolektif dibandingkan peristiwa-peristiwa besar lainnya yang dekat dengan hidup kita, bangsa kita? Menarik sebuah karya penting dalam filsafat Paul Ricoeur, meneliti hubungan timbal balik antara "mengingat dan melupakan", menunjukkan bagaimana hal itu memengaruhi persepsi, pengalaman, sejarah, dan produksi narasi sejarah. Bagaimana sejarawan menetapkan kebenaran dan keakuratan cerita mereka. Apakah ada suatu kebenaran historis yang objektif, atau semua sejarah konstruksi dari sudut pandang tertentu, mengekspresikan kepentingan mereka yang memiliki kekuatan untuk menulis itu. Memori perlu dianalisis dalam hubungannya dengan lawannya, yaitu lupa. Dan sejarah selalu dalam ketegangan antara memori dan lupa, dan akan menjadi dua kutub yang selalu bertentangan. Maka pertanyaan penting tentang memori adalah “mengapa kita lupa?”. Ricoeur menyatakan, manusia mampu membuat memori dan membuat sejarah atau bahkan melupakan hal-hal tertentu dalam memori. Dengan kata lain, baik memori dan melupakan, keduanya tunduk pada kekuasaan, dan dengan demikian juga tunduk pada penyalahgunaan. Atas hal ini, Ricoeur menyatakan soal “perlunya keadilan pada memori”. Ricoeur mengatakan bahwa sejarah—atau dapat disebut “kenangan kolektif “—memori seharusnya lebih berkaitan dengan tugas oleh dan untuk keadilan. Keadilan dan harapan macam apa yang kita miliki bila kita lupa? Dalam On the Genealogy of Morals, Nietzsche menjelaskan apa yang disebut "lupa aktif" dan juga mengingatkan kita bahwa lupa bukan hanya kegagalan memori, melainkan penyangkalan. Memori Kolektif yang Hilang Mei 1998 adalah peristiwa yang nyaris hilang dalam memori kolektif bangsa ini, meskipun sebagian besar dari kita pernah ada dalam suasana tersebut. Memori yang muncul saat kita pernah ketakutan menggantungkan sajadah di pagar, menuliskan kata “pribumi” di tembok rumah. Hal-hal itu adalah pengingat peristiwa bahkan dengan panca indra, yang disertai penyerangan dan pembakaran ke toko-toko, mall-mall, supermarket, dan rumah-rumah pribadi. Paling terekam di media massa waktu itu adalah ratusan orang hangus terbakar di dalam Mall Yogya Klender. Dibalik bangunan-bangunan hangus itu, ada lapisan memori yang paling dalam, yaitu di jalan-jalan jembatan tol dimana perempuan-perempuan dicegat, diturunkan, ditelanjangi, diseret dan dianiaya dan ditonton orang. Korban-korban saat ini telah menjadikan “lupa sebagai penyembuhan” dan membangun kehidupan baru untuk keluar dari luka yang belum tentu sembuh. Tetapi apa yang mengakibatkan kerusuhan itu sendiri terjadi, sampai hari ini kita tidak tahu dan kita hanya menjadikannya sebagai mimpi buruk saja. Kita bisa mengetahui bencana Krakatau di masa Perang Dunia Kedua, tetapi kita lupa dengan bencana kerusuhan yang baru saja lewat 16 tahun yang lalu? Bagaimana sikap negara atas memori kolektif yang hilang dalam tragedi bangsanya? Telah terjadi penyangkalan oleh negara yang berlangsung sampai sekarang dengan tiadanya investigasi, bahwa kerusuhan, kematian massal, dan serangan seksual benar-benar terjadi. Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) terbentuk pada tanggal 23 Juli 1998 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita dan Jaksa Agung, antara lain menyimpulkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual terjadi dalam kerusuhan Mei 1998. Kekerasan Mei 1998 menjadi perhatian dunia, dan merupakan wujud paling ekstrim akibat represi yang luar biasa dalam penghancuran martabat kemanusiaan di rezim Orde Baru. Kesimpulan TGPF menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam kerusuhan Mei yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang berarti dari pihak negara. Selama tidak ada realisasi keadilan bagi korban dan masyarakat umum, maka bangsa ini tidak sehat karena belum bisa menyembuhkan lukanya. Keadilan pada Memori, Keadilan pada Bangsa Raymond A. Knight meneliti bahwa perkosaan bukan soal penyaluran seksual, melainkan soal kekuasaan. Perkosaan pada tragedi Mei 98 menunjukkan perkosaan sebagai upaya penaklukan, untuk membangun trauma dan rasa takut untuk melawan. Perkosaan dilakukan dalam konteks represi politik adalah tentang cara mengontrol korban dan menghapus otonomi dan kemanusiaan mereka. Oleh karena itu kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 98 adalah memori yang sengaja dilupakan. Terdapat hubungan antara memori dengan identitas bangsa. Keterbukaan sebuah negara atas sejarahnya menunjukkan kedewasaan politik dan sistemnya, menunjukan moral yang baik di hadapan dunia. Sudah 16 tahun yang lalu peristiwa tragedi Mei terjadi, dan sampai saat ini tidak ada jawaban dan peringatan yang serius dari para elit politik, bahkan cenderung menanamkan “kelupaan kolektif” kepada masyarakat dengan menyangkalnya. Bekasi, 24 Mei 2014 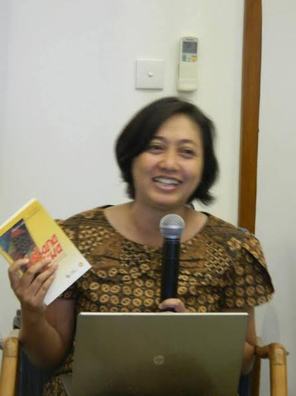 foto: Dok. Indonesia untuk Kemanusiaan foto: Dok. Indonesia untuk Kemanusiaan Ulasan Rahim dan Batin Puan Ulasan novel ini disusun pada bulan sebaik-baiknya bulan, Mei. Bulan saat teman-teman buruh mengusung rahim Marsinah dan teman-teman perempuan melawan lupa pada rahim 98. Juga saat Maria—tokoh mahasiswa pada Novel Istana Jiwa—akan merayakan hari lahir Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 23 Mei. Partai yang ia yakini jalan perubahan terbaik, yang lalu begitu cepat ditelikung dan dibumihanguskan. Bulan penuh kesakitan, kekecewaan, sekaligus penanda bahwa rahim dan batin para puan tetap lentur dan penuh semangat meraih kembali martabatnya sebagai manusia. Seperti rahim, para puan lentur menghadapi setiap perampasan harkat di dalam keluarga, partai, masyarakat dan negaranya. Seperti rahim, mereka merawat hidup sambil terus bernegosiasi dengan kekasih, suami, bapak, partai dan negara. Sebelum melahirkan Istana Jiwa (Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, 2012) Putu Oka Sukanta melahirkan novel Merajut Harkat (Elex Media Computindo, 2010) tentang pertaruhan untuk tetap menjadi manusia ketika para lelaki dipenjara, disiksa, coba dirampas seluruh martabatnya. Sedang pada Istana Jiwa kita dipertemukan dengan tokoh para perempuan di luar penjara, yang bertahan hidup baik untuk diri, keluarga, orang-orang terkasih di luar penjara maupun para lelaki yang di dalam penjara. Novel sejarah ini menggambarkan situasi menjelang, saat dan sesudah berlangsungnya kudeta 1965. Situasi itu, kemudian lebih subtil dituturkan melalui tokoh-tokoh perempuan: 1. Maria atau Ria, aktivis Consentrasi Gerakan Mahasiwa Indonesia (CGMI) dan anak dari anggota parlemen dan penulis Koran Harian Ekonomi berhaluan kiri—Bung Rampi. Ria dengan sepenuh jiwa memilih menjadi anggota PKI beberapa saat sebelum peristiwa 65 terjadi. 2. Ibu Suri, istri Bung Rampi dan ibu dari Maria. Tokoh Istri yang disibukan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan suaminya Bung Rampi—selama dipenjara. Kerja kerasnya yang dapat mengembalikan rumah mereka yang dirampas, bukannya disyukuri oleh Bung Rampi setelah pulang dari penjara. Tapi dicurigai sebagai hasil menjual diri—Bung Rampi menganggap rendah pekerja seks. 3. Asmi, istri Mulia, wartawan, yang bertahan hidup dan mengurus suaminya selama di penjara. Seperti istri-istri yang lain di novel ini, para suaminya lebih tertarik dengan politik daripada urusan keluarga. Sehingga saat dipenjara pun Mulia membatasinya “Aku nggak perlu kabar tentang keluarga, kirim kabar-kabar tentang politik saja.” 4. Kirtani, Ivone, Hwani, Istri-istri lain yang suaminya dipenjara dan setengah mati mempertahankan rumah dari okupasi militer yang melibatkan mahasiswa haluan kanan. Novel ini dapat diulas dari ragam pandangan. Bagi yang menyukai politik, ia dapat mengulasnya dari aspek geo-politik. Yang suka gerakan mahasiswa, dapat mengupasnya dari konflik-konflik yang terjadi antara lain antara Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan CGMI. Dalam tulisan ini, novel akan dibahas dari pengalaman rahim dan batin tokoh-tokoh perempuannya. Baik rahim fisik para tokohnya maupun rahim mental dan sosialnya dari perempuan sebagai ibu/istri maupun perempuan sebagai gerakan—Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Rahim dan Batin Puan Sebelum Kudeta 65 Secara umum kudeta militer 1965 menghancurkan hidup bersama antara warga yang PKI, yang sehaluan atau yang dituduh PKI dengan warga negara yang lain. Mengalihkan harta PKI dan yang diPKIkan kepada militer. Membakar buku-buku yang dianggap sehaluan dengan PKI. Menjebloskan orang pada penjara tanpa peradilan. Menghilangkan hidup dan penghidupan warga PKI dan yang dianggap sehaluan. Secara detail perubahan Orde Lama ke Orde Baru juga menghancurkan rahim dan batin perempuan, baik sebagai individu aktivis, istri, ibu maupun secara gerakan—pada Gerwani. Dari sudut pandang relasi kuasa perempuan dan laki-laki pada novel ini menunjukan belum setara bahkan dari sebelum penghancuran oleh Orde Baru. Tetapi Orde Baru memperburuk relasi kuasa itu. Sebelum kudeta 65, tokoh-tokoh perempuan di novel ini tidak dianggap sepenuhnya oleh ayah/suami mereka. Maria ditegur oleh bapaknya yang pemimpin besar karena memutuskan menjadi anggota PKI tanpa meminta izin selaku anak kepada ayahnya (hal. 37). Tokoh-tokoh laki-laki di novel ini juga digambarkan tokoh yang suka menulis, berbincang politik berlama-lama dengan orang lain. Tapi tidak banyak bicara dan tidak punya banyak waktu untuk keluarganya. Kondisi ini yang kemudian memperburuk situasi para istri pascakudeta 65 saat suami mereka ditangkap. Para istri ini menanggungjawabi hal-hal yang tak sungguh-sungguh mereka mengerti. Berikut kutipan perbincangan para istri—Asmi dan Aidah—saat kebingungan menghadapi suami mereka yang ditangkap: “Apa kamu tahu sebenarnya apa yang terjadi?” “Tidaklah. Mana pula aku tahu. Aku kan cuma sekretaris di kantor, mestinya suamimu yang tahu dan memberi tahu kita. Kok ia diam saja, kemana Mulia sekarang?” “Pergi ke kantor.” “Kantor kan sudah diduduki tentara. Semua diobrak-abrik tentara.” “Jangan-jangan ia ditangkap di kantor.” (hal. 101 – 102) Termasuk kesulitan para istri untuk mencari tahu keberadaan suami mereka ke lembaga militer, penjara yang tak pernah mereka ketahui sebelumnya. Juga kebingungan mereka terhadap pemberitaan Gerwani yang keji—organisasi perempuan yang diberitakan sehaluan dengan kegiatan suami mereka. Dengarkan pula keluhan Ibu Suri mengenang perlakuan suaminya sebelum penangkapan: “Kalau sudah begini, coba siapa yang mengurusnya? Siapa yang membesuk? Apa perempuan-perempuan yang selalu disediakan oleh-oleh kalau pulang dari luar negeri?” “Ibu cemburu?” “Bukan cemburu Nduk, tapi merasa dikesampingkan. Orang-orang luar selalu lebih penting dari kita. Di rumah bapakmu tidak punya waktu untuk kita....Ibu Baru menyadarinya, ternyata ada raja kecil di rumah.” (hal. 180) Rahim dan Batin Puan Setelah Kudeta 65 Puan sebagai Isteri Setelah menangkap para suami, rezim militer kemudian merampas rumah tinggal mereka. Yang memiliki rumah sendiri diminta untuk menyerahkan untuk digunakan pos keamanan atau dipaksa tinggal satu rumah dengan keluarga tentara. Bahkan Hwani, yang tinggal di rumah kontrakan pun, diminta pindah oleh pemilik rumah, karena ada ancaman rumah kontrakannya akan dirusak (hal. 138). Maria dan Ibu Suri pun akhirnya mengontrak rumah kopel. Sedang istri yang menolak memberi tahu keberadaan suaminya disiksa dan diancam diperkosa (hal. 156). Mengirim makanan dan menentramkan suami yang dipenjara tak dapat dielakkan dari tokoh para istri. Meskipun kasih sayang mereka tak bersambut dari orang yang diurusnya itu. Saat Asmi memberi kabar rapor anak-anak mereka yang nilainya bagus, suaminya membalas dengan lintingan kertas yang berisi: Semalam aku mimpi kamu sayang. Aku nggak perlu kabar keluarga, kirim kabar politik (hal. 200). Setelah suaminya keluar dari tahanan para istri terus berjuang menghadapi dinamika suami mereka. Dari kewalahan menghadapi gairah seks suami hingga membantunya pulih dari mimpi buruk dan membangun kembali pekerjaannya. Dan Ibu Suri yang menemukan si raja kecil Rampi yang semakin menyakitkannya dengan menganggap upaya Ibu Suri menitip foto dan surat lewat pastor tidak istimewa karena disensor. Rampi juga tidak lagi merasa bagian dari keluarganya, “Bapak sebagai kepala rumah tangga tidak mau makan dari hasil kerja istri dan anak. Tapi, Bapak belum menemukan pekerjaan yang layak dan menghasilkan uang” (hal. 273). Keluarga Ibu Suri dan Rampi berakhir ketika Rampi mencurigai rumah yang mereka miliki hasil dari jualan lendir Ibu Suri. Puan sebagai Ibu Tokoh-tokoh Ibu dalam novel ini juga berjuang untuk mengurangi penderitaan anak-anaknya akibat penangkapan suami mereka. Ibu Maruto yang meminta kepada Pak RT, agar suaminya ditangkap saat anak sedang tidur. Dan menyerahkan suaminya kepada para penangkap, untuk menghindari ancaman mereka yang akan mempertontonkan penyiksaan di tahanan kepada anaknya (hal. 106 - 107). Kirtani sebagai ibu dari Ayang, selain mengurus keperluan keluarga dan suami di penjara, ia juga harus merawat Ayang yang trauma. Ayang trauma karena mendengarkan penyiksaan dari ruang tahanan, saat Kirtani mengajaknya mencari suaminya. Kirtani menghibur Ayang bahwa ayahnya tidak disiksa, walaupun Ayang didatangi mimpi buruk terkait kondisi ayahnya. “Ayah dimana, Mama?” “Sedang sekolah, masuk asrama. Belum dapat cuti.” (hal. 93) Para ibu juga memulihkan kesedihan anak-anaknya yang di sekolah diejek “anak PKI” juga saat para ayah diasingkan ke Pulau Buru. Puan sebagai aktivis mahasiswa dan Gerwani Perempuan muda aktivis dan Gerwani/yang dituduh Gerwani ditangkap dan mengalami penyiksaan seksual. “Perasaan keibuanku mengutuk cara-cara yang digunakan pemeriksaan menyiksa mereka. Ada yang rambutnya digunting, ada yang teteknya disundut rokok, memeknya diunyel-unyel sampai kesakitan menjerit-jerit...” ( hal. 156) Novel ini juga menggambarkan bagaimana rezim militer mengawinkan patriarki dan agama untuk menghancurkan gerakan perempuan. Setelah mereka berhasil memobilisasi organisasi mahasiswa berbasis agama—HMI, PMII, GMKI, dll—menjadi kolektif yang melakukan perlawanan kepada PKI yaitu KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), hal. 55. Selanjutnya pemberitaan untuk menghasut kebencian pada Gerwani dikait-kaitkan juga dengan agama: “Perempuan-perempuan tidak dikenal mendatangi rumah-rumah para pahlawan kita dengan memakai mukena seolah-olah mereka orang Muslim. Gerak-gerik mereka menimbukan ketjurigaan karena jelas mereka ini orang-orang Gerwani...” “Tubuh para djenderal itu telah dirusak, mata dicungkil, sementara itu ada yang dipotong kemaluan mereka...Sukarelawan Gerwani telah bermain-main dengan para djendral, dengan menggosok-gosokan kemaluan mereka ke kemaluan sendiri.” (hal. 81) Selanjutnya alat patriarki dan agama ini juga dilengkapi dengan upaya-upaya pecah belah sesama perempuan: “Bahkan menurut sumber jang dipertjaya, orang-orang Gerwani menari-nari telandjang, di depan korban-korban mereka, tingkah laku mereka mengingatkan kita pada upacara kanibalisme yang dilakukan suku-suku primitif berabad-abad yang lalu. Marilah kita serahkan pada kaum wanita untuk mengadili moral kewanitaan orang-orang Gerwani yang bermoral bedjat lebih buruk dari binatang.” (hal. 83). Tidak Mungkin Menyangkal Perilaku Patriarkis Saat Mengkritisi Peristiwa 65 Dari perjuangan tokoh-tokoh perempuan pada novel ini, sedikitnya ada dua catatan yang perlu diingat-pahami saat kita memahami peristiwa 65. Pertama sumbangsih para puan dengan perannya sebagai anak perempuan, istri, ibu, aktivis dan gerakan perempuan pada penyelamatan harkat manusia Indonesia ditengah kecamuk dan deraan penghabisan hidup dan penghidupan oleh Orde Baru. Negosiasi mereka agar tak diperkosa, agar tak seluruhnya harta terampas, agar pulih luka batin dan luka batin anak-anak dan suami mereka, agar tak meninggal kelaparan lelaki-lelaki yang dipenjara. Gotong-royong diantara mereka untuk saling memberikan bantuan dan perlindungan, meskipun pemberian bantuan itu meningkatkan kerentanan mereka untuk diciduk rezim. Ketabahan dan keliatan mereka mengelola fitnah—penghabisan atas nama agama, serangan seksualitas pada Gerwani dan pecah belah sesama perempuan Indonesia. Ingatan pada sumbangsih para tokoh perempuan ini, penting menjadi guru bagi sesiapa yang akan melanjutkan pertumbuhan Indonesia sebagai bangsa dan negara hari ini. Dan semangat bagi perempuan Indonesia untuk mengelola menghadapi penguasaan dan pecah belah atas dasar seksualitas dan akibat sistem ekonomi yang rakus saat ini. Kedua, kekuatan dan keberanian novel ini dalam menunjukan relasi kuasa perempuan dan laki-laki yang belum setara. Tidak hanya relasi antara tokoh perempuan dengan rezim Orde Baru, tetapi hingga relasi mereka dengan suaminya sebagai bagian dari warga dan partai politik yang ditindas rezim. Tidak berarti bila PKI dan orang-orang sehaluan dikorbankan oleh rezim Orde Baru maka mereka lepas dari kritikan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Karena, pertempuhan pemulihan kesadaran pada keadilan ini tentunya mesti sejalan dengan keadilan antara perempuan dan laki-laki. Demikian juga dalam pengungkapan menuju kebenaran dari cara pandang, cara tutur, rahim dan batin perempuan pada peristiwa 1965 yang tertuang dalam novel ini. Bagaimana Putu Oka Sukanta, sebagai laki-laki yang bagian dari mereka yang dipenjara dapat menghidupkan tokoh para puan dalam novelnya Istana Jiwa ini? “Ketika saya dipenjara, saya diberi makan, pakaian yang dibagikan oleh kawan sepenjara yang dikirim oleh para istrinya,” demikian ungkap Penulis pada diskusi buku ini. Tak terbayangkan hidup para tahanan politik tanpa dukungan perempuan-perempuan itu. Karena itu, karya ini juga dipersembahkan untuk perempuan-perempuan hebat itu. Dan untuk kita semua, untuk tak pernah lengah merawat kerja sama dan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pertempuhan menuju keadilan apapun. [1] Disampaikan pada Diskusi Istana Jiwa, bagian dari rangkaian Terus Melangkah 75 Tahun Putu Oka Sukanta, diselenggarakan Indonesia untuk Kemanusiaan, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dan Mata Budaya, Jakarta, 20 Mei 2014.  Pengantar Setidaknya ada 81 negara yang melarang keberadaan minoritas seksual. Minoritas seksual ada sepanjang sejarah kemanusiaan, dan tidak dilahirkan secara tiba-tiba. Dimana ada manusia, keberadaan mereka telah inheren di dalamnya. Banyak reaksi atas keberadaannya, sebagai sebuah fitrah, sebagai ancaman atas prokreasi maka perlu diberangus, sebagai ketaknormalan, dan lain-lain. Eksistensi mereka bukan tanpa resiko, seringkali kematian mengancam. Stereotype dan stigma seumur hidup merupakan bagian dari kehidupan nestapanya. IDAHOT (International Day Against Homophobia & Transphobia) merupakan peringatan dunia yang diadakan untuk memberikan penghargaan hidup, karya dan prestasinya. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memberikan pidatonya pada 17 Mei lalu bahwa “Kesetaraan berawal dari kamu”, dengan penjelasan lebih jauh bahwa LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) mengalami banyak diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. “Mereka tak hidup dalam penghargaan kita, dan mereka hidup dalam ketakutan”, terang Ban Ki-moon. Sekarang ada kurang lebih 2.8 milyar manusia yang hidup di sekitar 81 negara yang mengkriminalisasi eksistensi mereka. IDAHOT dirayakan setiap tanggal 17 atau sepanjang bulan Mei setiap tahunnya. Di Indonesia aktivis minoritas seksual SUARA KITA memperjuangkan hak-haknya melalui link berikut (http://www.suarakita.org/2014/04/ayo-terlibat-aktif-dalam-peringatan-melawan-homophobia-transphobia-2014/). Tulisan ini akan menjelaskan sebagian dari mengapa minoritas seksual mengalami subordinasi dalam masyarakat modern. Seks, Seksualitas dan Kelahiran Liyan Mary Wollstonecraft dalam ulasannya menantang “kemerdekaan”, menjelaskan bahwa kemerdekaan tak sungguh-sungguh berpihak pada mereka yang Liyan—perempuan sebagai “vulnerable group” bersama minoritas seksual. Dalam A Vindication of the Rights of Woman (1792), Mary melakukan ekspansi besar-besaran pada kemerdekaan atas perempuan dalam struktur politik masyarakat—yang sebelumnya, mustahil bagi perempuan. Karena kemerdekaan yang didengungkan kali pertama, tak sungguh-sungguh mengajak perempuan dan minoritas seksual ikut serta. Perempuan dan minoritas seksual tidak terlihat (the invisible, the intangible, thus the vulnerable). Tradisi liberalisme klasik ternyata memiliki cacatnya dengan tidak memperhatikan gender Liyan dalam konstruksi keadilannya. Dengan kelahiran liberalisme, lalu lahirlah cucu-cucunya seperti sosialisme, marxisme, komunisme, di samping feminisme. Seluruh isme-isme tersebut merupakan perangkat ideologis dan gerakan yang diyakini membawa spirit kemerdekaan dan kebebasan manusia. Yang kemudian tak sungguh-sungguh dirasakan oleh Liyan (minoritas seksual dan perempuan). Dalam perjalanannya spirit kebebasan tidak akan meng-adil jika tidak beririsan dengan gender dan ras. Kesetaraan ras merupakan gelombang yang didengungkan terutama oleh orang-orang kulit hitam, yang masih digerus oleh struktur yang tidak adil. Demikian juga kesetaraan gender menjadi spirit yang terus diperkarakan sampai sekarang. Karena keduanya, tak kunjung mendapatkan tempat adilnya. Di tahun 2014 ini, masih banyak Gender Liyan, yaitu minoritas seksual, berjuang mendapatkan hak-haknya yang secara tidak adil dilibas oleh heteronormativitas a la sejarah seksualitas manusia yang Freudian. Dengan itu, kerap dijumpai bagaimana perjuangan ras minoritas berjalan beriringan dengan perjuangan perempuan dan kelompok rentan lain, seperti kelompok minoritas seksual. Okky Madasari dalam novel terbarunya, Pasung Jiwa, mengabarkan perihnya menjadi Liyan, pedihnya menjadi Liyan. Tercerai-berainya Sasana menjadi Sasa. Sebagai transgender, Sasa adalah potret mereka yang termiskin di antara yang miskin. Novel Okky Madasari ini merupakan ecriture feminine, meminjam terminologi dari Helene Cixous, bahwa pengalaman perempuan juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Istilah ini juga dikenal sebagai white-ink, bahwa perasaan perempuan dituliskan dengan tinta susu Ibu. Sasana: ”Seluruh hidupku adalah perangkap. Tubuhku adalah perangkap pertamaku. Lalu orangtuaku, lalu semua orang yang kukenal. Kemudian segala hal yang kuketahui, segala sesuatu yang kulakukan. Semua adalah jebakan-jebakan yang tertata di sepanjang hidupku”. ... Setiap hari, anggota Dark Geng menghampiriku saat aku baru keluar dari kelas. Mereka minta jatah lima ribu rupiah. Kadang mereka menggeledah tasku, mengambil apa saja yang bisa diambil. Aku menurut. Asal aku tak dipukul, lalu pulang penuh lebam, dan membuat ibuku kembali menangis. Tak ada yang bisa melawan, tak ada yang berani melaporkan. Beberapa kali ada guru yang melihat penganiayaan. Tapi tak ada yang mengambil tindakan. Tak ada yang kena hukuman. Bagi sekolah ini, keributan, perkelahian, penganiayaan, adalah urusan kecil remaja laki-laki yang bisa diselesaikan mereka sendiri. Aku pun jadi membenci laki-laki. Membenci diriku sendiri yang jadi bagian dari laki-laki. ... Setelah dua bulan jadi anak baru di Malang, aku menemukan sesuatu yang membuatku begitu bahagia. Barangkali ini hasil penantian panjangku selama bertahun-tahun. Hidupku kini hanya untuk berdendang dan bergoyang. Sudah tak terhitung berapa kali aku membolos kuliah. Ruang kuliahku sekarang ya warung Cak Man itu. Cak Jek sudah aku anggap seperti kakakku sendiri. Tiba- tiba Cak Jek datang dengan membawa sebuah bungkusan. CAK JEK: (sambil menyerahkan baju, wig, make up dan sepatu) Kita harus profesional.. Sasana berdendang kembali sambil memakai semua yang diberikan oleh Cak Jek. Hingga pada saat akhir lagu Sasana telah berubah menjadi Sasa. (Okky Madasari: Novel Pasung Jiwa). Dalam gender, dalam jenis kelamin, dalam struktur seksualitas, liberalisme memasung, mengungkung kebebasan dan keadilan terhadap liyan. Atas nama seksualitas, kemudian Liyan direndahkan derajat dan martabatnya. Keberadaan transgender, bencong, banci, lesbi, dan minoritas seksual lain, merupakan sebuah keberadaan yang dihinakan dalam pasungan Liyan. Martha Nussbaum (1947-), seorang professor dan feminis dari Universitas Chicago menulis dengan terang dalam bukunya Sex and Social Justice (1998 dengan Juha Sihvola). Dalam buku ini, Nussbaum memaparkan bagaimana seks dipakai sebagai alat kontrol untuk meliyankan kelompok rentan, menistakan derajat dan martabat pilihan liyan. Seks dan seksualitas sendiri menjadi alat yang”menjijikkan” untuk melakukan eksekusi-eksekusi tidak adil terhadap Liyan yang rentan. Seksualitas: jenis kelamin, identitas gender, dan ekspresi & orientasi seksual telah menjadi momok yang dipakai sebagai alat untuk menakut-nakuti Liyan, dipakai untuk menindas liyan, dan pada akhirnya memasung kebebasan Liyan. Nussbaum mendeskripsikan bagaimana hierarki sosial dapat terbentuk dari kelas-kelas yang meliyankan mereka yang abnormal, dalam tanda kutip. Kebebasan manusia yang fungsional, kemudian malah juga dicerca sebagai alat yang berbahaya dalam kemerdekaan sang Liyan itu. Maka sejak itulah, kebebasan mendapatkan stigmanya yang buruk. Padahal dia lahir dan dielu-elukan untuk membebaskan manusia dari pasungan. Dari perbudakan, dari kebodohan. Atas nama kejijikan, abnormalitas, sampah, Liyan diliyankan dengan sistematis dan sistemik. Penyingkiran terhadap Liyan dilakukan dengan pembuatan sekat-sekat dan kategori-kategori seperti LGBTI (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseksual). Dalam fungsi-fungsi sosialnya, bahkan, mereka yang diliyankan dalam box-box itu tak benar-benar tahu, apa label untuk mereka karena seksualitas sesungguhnya bersifat cair, bertumbuh, kontekstual, individual, dan kontinum. Tentara 4: Jadi kamu itu bencong yang mau coba-coba melawan negara? Sasa: Tidak! Sasa melotot tajam ke arahnya. Oknum-oknum Laskar yang ada di situ tertawa. Sambil terus menyebut kata bencong. Lalu Sasa yang tidak terima dengan perkataan tersebut meludahi dan menendang kemaluannya. Tapi orang tersebut membalas memukul sasa dengan pentungan sampai terkapar. Oknum laskar: Udani wae, ben kapok. Lanangan kok dadi wedok!” (Okky Madasari: Novel Pasung Jiwa, 2013). Dalam masyarakat tradisional, keberadaan mereka tak sungguh-sungguh diliyankan, dan mendirikan sebuah tempat dan situs tradisi yang tidak bisa disangkal oleh sejarah. Sebut saja periwayatan Reog dengan Warok-Gemblak. Bahkan hubungan tersebut diniscayakan sebagai sesuatu yang spiritual. Apa-apa yang diadopsi oleh negara modern (baca: state), jelas mengadopsi sejarah seksualitas Freud, yang tak mengandaikan bahwa mereka ada. Seksualitas klasik Freud yang heteronormatif, men-sida-sida penis kecil perempuan, menyunat tangis anak lelaki, membekukan peran ibu, peran ayah dengan kaku, ternyata telah melahirkan banyak ketidakadilan atas entitas-entitas seksualitas dalam struktur tradisional dan adat. Kemudian Freud mendapatkan genderang pendukungnya dari agama-agama Semit yang membabat habis keberagaman seksualitas di bumi ini. Atas nama kejijikan, tabu, dan tempelan dosa, kemudian Liyan dilahirkan dalam rahim kebebasan. Apa yang dicitakan bebas, tak sungguh-sungguh dapat dinikmati oleh Liyan yang menjijikkan dan pendosa itu. Kubah keagungan dan kesucian kemudian didominasi, dieksploitasi dan disalahgunakan oleh mereka yang menyebut diri sebagai normal dan tak menjijikkan. Martha Nussbaum: Kejijikan, Rasa Malu, & Kesetaraan Seksual Kerap, di jalanan, atau di salon-salon, kita akan menyingkirkan diri dari kejijikan melihat para bencong pemangkas rambut. Juga pandangan-pandangan remeh terhadap tukang salon banci yang dandan menor tetapi anggun sedang membedaki wajah kita, atau sekedar merapikan keris yang menancap di ekor punggung kita. Demikian. Dalam Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law (2004), Martha Nussbaum menulis bagaimana kejijikan menjadi alat yang digunakan untuk menindas keadilan dan kebebasan terhadap Liyan—empati dan penghargaan dibolehkan absen karena rasa jijik dan rasa malu. Hukum tunduk pada kejijikan dan rasa malu. Otonomi, otoritas, preferensi, kebebasan kita, yang sok normal, diletakkan dalam hierarki tertinggi, ter-agung, di atas mereka, para Liyan, Kaum yang Menjijikkan itu. Demikianlah keadilan sosial dicetak dan dipublikasikan dengan menggunakan seksualitas sebagai alat kontrol. Seksualitas yang sifatnya “given”, terberi dan asasi tersebut disamakan dengan kelakuan sundal dan tercela. Ketidakadilan dalam kebebasan dipasung dengan kategori gagap “normal versus abnormal”. Pada abnormalitas fisik, seperti difabilitas, kejijikan tak begitu menjadi alat penyerang. Tetapi terhadap seksualitas, penanda kejijikan dan laku dosa memperparah stigma, stereotype dan ketidakadilan terhadap kaum Liyan. Pada lelaki, kekuasaan diberikan; pada perempuan, properti dititipkan; pada minoritas seksual, kejijikan dan segala pelengkap dosa disematkan. Otonomi diri dan agensi diri tak sungguh-sungguh dimiliki oleh perempuan dan minoritas seksual, karena mereka sekadar barang, dan sekadar pendosa yang tak berguna. Nussbaum dalam bukunya menggambarkan bagaimana emosi dan kejijikan itu telah melahirkan penderitaan dan kejahatan atas minoritas seksual. Liberalism does think that the core of rational and moral personhood is something all human beings share, shaped though it may be in different ways by their differing social circumstances. And it does give this core a special salience in political thought, defining the public realm in terms of it, purposefully refusing the same salience in the public political conception to differences of gender and rank and class and religion. This, of course, does not mean that people may not choose to identify themselves with their religion or ethnicity or gender and to make that identification absolutely central in their lives. But for the liberal, choice is the essential issue; politics can take these features into account only in ways that respect it. (Nussbaum, Sex and Social Justice, 70) Dengan sengaja, sistem dalam negara menciptakan pemikiran politik yang mendefinisikan realitas publik dalam struktur dan hierarki seksualitas yang meliyankan perempuan dan minoritas seksual. Padahal struktur seksualitas yang adil adalah yang mengakui setiap penghuninya, baik laki-laki, perempuan dan minoritas seksual sebagai makhluk politis dan manusia utuh. Kebebasan telah diciderai dengan invisibilitas gender sebagai penanda untuk menindas Liyan. Kesetaraan antar manusia, mau tidak mau, harus dimulai dari “kesetaraan seksual” (sexual equality, meminjam Nussbaum). Dan kesetaraan seksual merupakan salah satu penanda utama dalam spirit kebebasan yang adil dan memerdekakan. Dan darinya distribusi kekuasaan, representasi, otoritas, dan otonomi, seharusnya menjadi hak kaum Liyan itu. Happy IDAHOT! Referensi: Madasari, Okky. 2013. Pasung Jiwa. Jakarta: Gramedia. Nussbaum, Martha C & Juha Sihlova. 1999. Sex and Social Justice. Oxford: Oxford UP. Nussbaum, Martha C. 2004. Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law. Princeton: Princeton UP. Oleh: Okky Madasari  Foto: Dok Okky Madasari Foto: Dok Okky Madasari Siapakah aku ini? Siapakah aku? Demikian baris penutup dalam novel Shanghai Baby (1999) karya Wei Hui. Sebuah pertanyaan eksistensialis - pertanyaan mendasar yang terus diajukan manusia sepanjang keberadaannya di dunia. Pertanyaan itu terus menggelayut dalam benak Nikki, tokoh utama dalam novel tersebut. Nikki, perempuan 25 tahun itu menatap nanar gemerlap kemajuan Shanghai sekaligus memandang enggan jejak-jejak masa lalu Shanghai. Ia berdiri di perbatasan, terombang-ambing dalam kebingungan, sembari terus bertanya: Siapakah aku? Siapakah aku adalah sebuah pertanyaan tentang esensi diri, esensi keberadaan. Nikki menjadi simbol dari jutaan perempuan yang sedang kebingungan, tersesat di antara simpang perubahan. Nikki, bagian dari perempuan Tiongkok yang sejak lahir diikat oleh nilai-nilai, dibangun dengan kebiasaan, dididik untuk menjadi seorang perempuan seperti yang kebanyakan. Ia ingin loloskan diri dari semua yang sudah ditanam. Ia ingin membebaskan diri dari ikatan-ikatan usang. Sementara zaman yang baru hanya hadir dalam kelap-kelip lampu, gedung-gedung tinggi, barang-barang dan segala kesenangan yang menjadikan generasi Nikki hanya sebagai mangsa. Nikki memandang semua yang ada di sekelilingnya dengan penuh keheranan. Masa lalu yang usang dan terus membelenggu di satu sisi, dan masa baru yang menyilaukan mata dan memasang segala sesuatu dengan harga. Nikki tidak memilih dua-duanya. Ia lari ke balik imajinasinya, ia bermain-main dengan kesadarannya. Hadirlah Nikki yang terasing dari sekelilingnya, yang tak peduli, sekaligus yang penuh keberanian dan kenekadan mengikuti kata hatinya. Ia menolak nilai-nilai leluhur yang tak sesuai lagi baginya, dan tak sudi menelan mentah-mentah nilai-nilai baru yang disodorkan padanya. Nikki dengan berani melawan tradisi sekaligus melawan modernisme Shanghai yang telah merebut jiwa perempuan-perempuan segenerasinya. Nikki telah menunjukkan pada dunia sosok perempuan yang baru: mereka yang tak larut dalam nilai lama juga tak mau tunduk pada nilai baru. Perempuan yang membebaskan diri dari ukuran-ukuran di luar dirinya, dari kekuasaan-kekuasaan yang berusaha mencengkeramnya – entah itu dari tradisi, agama atau modernisme dan kapitalisme. Sosok Nikki tak dikenal oleh perempuan-perempuan Tiongkok lainnya. Pemerintah membredel novel ini. Lagi-lagi kekuasaan mengontrol perempuan, mengatur apa yang layak dikonsumsi dan diadopsi, menentukan seperti apa sosok perempuan yang layak dan pantas jadi narasi – bahkan dalam imajinasi sastra. Imaji perempuan seperti Nikki tak mendapat kesempatan untuk bertarung dalam wacana ide. Ia diberangus dan disingkirkan bahkan sebelum sempat dikenal oleh perempuan-perempuan sebangsanya. Imajinasi Kekuasaan Bangunan imaji atas sosok perempuan senantiasa menjadi ladang pertempuran. Kekuasaan agama melahirkan teks-teks kitab suci yang menjadi pedoman bagaimana harusnya menjadi perempuan. Bahkan dalam kisah yang pertama kali hadir di dunia tentang turunnya Adam dan Hawa, perempuan dihadirkan sebagai sosok penggoda yang membawa dosa. Dari situlah lahir kisah-kisah lanjutan yang memberi perempuan seperangkat aturan, larangan, dan keharusan. Di Indonesia hari ini, kita melihat bagaimana karya-karya yang menjadi arus utama adalah karya yang hendak menjadikan dirinya sebagai representasi kekuasaan agama. Karya-karya berlabel Islami dan Religi mendominasi toko-toko buku. Karya-karya seperti ini menggambarkan perempuan sebagai sosok yang menutup aurat, penurut, berbakti pada suami, dan mau dipoligami. Melalui kisah di novel, perempuan diberi pengetahuan cara berbusana sesuai aturan agama, cara memperlakukan suami, hukum perkawinan, hukum bergaul dan sebagainya. Melalui novel, perempuan diberi pengetahuan --yang sesungguhnya hanya merupakan cara kekuasaan untuk mengontrol dan mengatur perempuan sesuai keinginan mereka. Lihat saja bagaimana Ayat-Ayat Cinta, novel yang laku keras dan mendapat perhatian besar dalam masyarakat menggambarkan perempuan. Fahri seorang laki-laki yang digilai banyak perempuan. Ia menikah dengan Aisha, perempuan cantik berjilbab dan bercadar, yang kelak mendorong suaminya untuk menikah lagi dengan Maria. Sementara ada satu sosok perempuan, yang membuat pengakuan palsu bahwa ia diperkosa Fahri. Bukankah ini semua adalah narasi yang lahir dari imajinasi patriarki? Karya ini mendorong lahirnya karya-karya lain yang sejenis. Kepentingan patriarki yang menggunakan agama untuk mengendalikan tubuh, pikiran, dan imajinasi perempuan bertemu dengan logika pasar. Karya-karya semacam ini laku keras, salah satunya karena ada yang berpikir dengan membaca novel berlabel Islami mereka melakukan hal mulia dan mendapat pahala. Terlebih jika kisah yang dihadirkan mampu membuat pembaca terbuai dan larut dalam cerita, sehingga pembaca pun merasa terhibur. Agama juga dijadikan dasar bagi negara untuk melakukan kontrolnya. Atas nama moral dan penghinaan agama, negara melakukan pemberangusan. Padahal sesungguhnya negara hanya sedang menyusun narasi sosok perempuan yang sesuai dengan kepentingannya. Karya seperti Shanghai Baby dilarang, bukan semata karena ia dianggap merusak moral masyarakat. Lebih dari itu, Shanghai Baby membisikkan keberanian dan semangat untuk melawan semua tatanan – hal yang paling ditakuti oleh kekuasaan. Di Indonesia, dalam 32 tahun kekuasaan Orde Baru, narasi utama perempuan dalam karya sastra didominasi oleh karya-karya yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah, yang sibuk dengan urusan percintaan dan rumah tangga, yang menempatkan keutuhan perkawinan di atas kebahagiaan. Tentu saja ada karya Nh. Dini yang menyajikan hal sebaliknya.Tapi Nh. Dini hanya sendiri. Ia dikepung oleh karya-karya serupa Karmila(1973)– yang menyajikan sosok perempuan sebagaimana harapan norma agama, norma masyarakat, dan kepentingan negara. Karmila dan novel-novel yang sejenis, dianggap pemerintah Orde Baru paling pas untuk menjadi narasi utama dalam kesusastraan Indonesia saat itu. Sebab novel-novel seperti ini tidak menghadirkan persoalan sosial politik dan tidak punya kecenderungan kritis untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah dan melawan tatanan dalam masyarakat. Selain itu, gambaran masyarakat urban yang hidup dalam kemakmuran menjadi cermin keberhasilan pembangunan pemerintah. Lagi-lagi, kepentingan pemerintah bertemu dengan kepentingan pasar. Novel Karmila laku keras di pasaran, yang segera menandai kelahiran novel-novel lain yang sejenis. Pembaca yang dibentuk untuk tidak kritis menyukai gambaran perempuan dalam novel-novel seperti ini. Perempuan yang seperti harapan orang kebanyakan. Perempuan yang lemah dan tunduk pada nilai agama dan adat. Perempuan yang makmur dan dipenuhi oleh segala keindahan. Perempuan yang terus dibujuk untuk membeli dan membeli, tapi tidak diajak untuk mempertanyakan dan melawan. Imaji sosok perempuan seperti inilah yang hingga sekarang masih menjadi arus utama dalam novel-novel Indonesia. Label-label baru disematkan: chicklit, metropop, atau teenlit. Tapi toh tak mengubah esensi. Tagline Being Single and Happy yang dipasang dalam sampul novel-novel chicklit hanya menjadi sekadar gimmick pemasaran. Alih-alih menyuarakan feminisme dan pembebasan, novel-novel ini hanya menjadikan perempuan sebagai objek konsumerisme dibalik citra perempuan karier yang mandiri. Jika novel berlabel Islami memberikan pengetahuan agama pada pembaca, novel-novel chicklit menghadirkan pengetahuan mode mutakhir dan sederet merek ternama pada pembaca. Tanpa memberi pemahaman kritis, ia mengantarkan perempuan pada cengkeraman kapitalisme berkedok kebebasan menikmati hidup. Dari kepentingan agama, negara, hingga kapital, imaji sosok perempuan dibangun dan ditanamkan. Perempuan dipaksa untuk menerima, menelan dan mengikuti model-model yang direstui. Dalam situasi ini, perempuan hanya bisa gamang dan kebingungan seraya bertanya: Siapakah aku? *** *) Disampaikan dalam seminar “Gambaran Perempuan Modern dalam Karya Sastra Cina”, dalam rangka Sinofest XIII 2014, di FIB UI, 7 Mei 2014  Foto: Dok Jurnal Perempuan Foto: Dok Jurnal Perempuan Perempuan Hamil Dilarang Pergi Haji Belakangan ini banyak kasus dimana perempuan hamil tidak dibolehkan pergi haji. Alasannya, perempuan hamil dianggap tidak memenuhi salah satu syarat dalam pelaksanaan ibadah haji yaitu istitha’ah (kemampuan) untuk menunaikan ibadah haji. Sejumlah pihak menyatakan keberatan dengan kebijakan ini. Bayangkan, seorang perempuan sudah mempersiapkan diri bertahun-tahun untuk pergi haji, tapi tiba-tiba pihak Kementerian Agama menolak kepergiannya. Alangkah tragisnya! Ibadah haji bukan hanya diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw dan umatnya, tapi jauh sebelumnya telah dipraktikkan oleh umat Nabi Ibrahim as (QS. al-Hajj, 27). Berbeda dengan ibadah mahdlah lainnya, seperti salat, puasa, dan zakat, pelaksanaan ibadah haji mensyaratkan satu ketentuan khusus yang disebut istitha‘ah bagi pelakunya. Persyaratan dimaksud berkenaan dengan beragamnya aktivitas, lokasi, dan waktu pelaksanaan ibadah haji, sehingga memerlukan tingkat kesehatan dan kekuatan fisik yang prima bagi pelakunya, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu keistimewaan perempuan, mereka dipercaya oleh Sang Khalik untuk mengemban fungsi-fungsi reproduksi, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua itu merupakan tugas kemanusiaan yang amat luhur demi melanjutkan keturunan umat manusia. Akan tetapi, dalam mengemban fungsi-fungsi reproduksi berkaitan dengan kehamilan, perempuan diharapkan melakukannya dengan penuh kesadaran, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Sebab, perempuan punya hak memilih secara bebas apakah ia akan hamil atau tidak, kapan akan hamil, berapa jarak kehamilan yang dikehendaki dan yang terpenting berhak mendapatkan perlindungan dari kesakitan dan penderitaan akibat kehamilannya itu. Alquran mengapresiasi fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini dengan redaksi yang sangat menyentuh seperti terbaca dalam surah al-Ahqaf, 46:15. Ayat ini secara tegas menjelaskan kepada segenap manusia tentang beratnya tugas-tugas reproduksi yang diemban perempuan, dan karenanya menuntut kita semua agar memperlakukan para ibu dengan penuh empati dan kasih sayang. Dalam kaitan dengan ibadah haji, pertanyaan muncul: “Apakah seorang perempuan yang sedang mengemban tugas reproduksi itu memenuhi syarat istitha‘ah untuk menunaikan ibadah haji?” Bagaimana rumusan dan penerapan konsep istitha‘ah oleh para fukaha? Lalu, bagaimana sebaiknya kebijakan pemerintah (Kementerian Agama) dalam memberikan pelayanan haji terhadap perempuan hamil? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam uraian berikut. Konsep Istitha‘ah dalam Pandangan Fukaha Istilah istitha‘ah dalam haji bersumber dan terkait dengan istilah istitha‘ah dalam Alquran (Ali ‘Imran, 3: 97). Kata itu digunakan Alquran dalam rangka pembicaraan mengenai kewajiban menunaikan ibadah haji. istitha‘ah yang disebut dalam ayat ini dipahami oleh para mufasir dan ulama sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Kata istitha‘ah menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata istatha‘a, yastathi‘u, yang berarti “mampu, sanggup, dan dapat”. Kata ini berakar dari kata atha’a yathi’u, yang juga berarti “tunduk, patuh, dan taat”[1]. Seseorang yang sanggup melakukan sesuatu disebut mustatha‘. al-Raghib al-Asfahani, salah seorang ulama bahasa dan pakar Alquran, ketika menguraikan pengertian kata ini, menjelaskan istitha‘ah adalah kata yang mengandung makna kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diinginkannya. istitha‘ah, menurutnya berkait dengan empat unsur penting, yaitu pelaku, aktivitas, sarana, dan produk yang dihasilkan. Apabila salah satu unsur itu hilang, maka tidak disebut lagi istitha‘ah (kemampuan), melainkan lebih tepat disebut ‘ajaz atau ketidakmampuan.[2] Dari sini dapat dipahami bahwa secara terminologi, kata istitha‘ah berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Para fukaha sepakat menyatakan istitha‘ah sebagai salah satu dari 4 (empat) syarat umum wajibnya haji. Penetapan syarat ini ditetapkan berdasarkan firman Allah yang berbunyi “man istatha‘a ilaihi sabila” (من استطاع إليه سبيلا). Ini berarti, seseorang yang tidak memiliki istitha‘ah tidak dikenai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Pada umumnya fukaha memahami pengertian istitha‘ah sebagai kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk sampai di Mekkah guna melaksanakan ibadah haji. Penjelasan istitha‘ah oleh para fukaha secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu istitha‘ah yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan istitha‘ah yang berkaitan dengan hal-hal di luar diri calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya. Karena tulisan ini memfokuskan diri pada persoalan istitha‘ah perempuan hamil, maka uraian selanjutnya hanya dikaitkan pada istitha‘ah kategori pertama, yakni istitha‘ah badaniyah. Yang dimaksud dengan istitha‘ah badaniyah dalam pandangan fukaha Mazhab Hanafi adalah kesehatan dan kemampuan fisik untuk menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang fisiknya tidak sehat, seperti orang sakit, lumpuh total, lumpuh sebagian, penderita penyakit kronis, orang buta (walaupun memiliki penuntun khusus), orang tua renta yang tidak sanggup lagi duduk sendiri di atas kendaraan, orang yang dipenjara, dan orang yang dicekal oleh penguasa yang despotik, tidak dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji.[3] Pandangan fukaha mengenai istitha‘ah di atas, khususnya istitha‘ah dalam pengertian kesehatan dan kekuatan fisik, tidak menyinggung soal kehamilan pada perempuan. Artinya, substansi istitha‘ah bagi perempuan tidak dikaitkan dengan persoalan kehamilan, melainkan difokuskan pada persoalan kesehatan dan kemampuan fisiknya. Perempuan hamil yang memiliki kesehatan dan kemampuan fisik memenuhi syarat istitha‘ah haji untuk kategori istitha‘ah badaniyah. Sebaliknya, meskipun tidak hamil tetapi memiliki kondisi kesehatan dan kemampuan fisik yang lemah berarti tidak memenuhi syarat istitha‘ah tadi. Penjelasan fukaha berkenaan dengan haji perempuan sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fikih pada umumnya lebih banyak menyinggung soal busana, mahram, keamanan dalam perjalanan, dan hal-hal yang berhubungan dengan haid dan nifas. Karena ada cukup banyak penjelasan tentang nifas dalam kitab-kitab fikih, maka bisa disimpulkan bahwa perempuan hamil dalam perspektif fikih tidak terhalang untuk menunaikan ibadah haji. Tawaran Solusi Dalam perspektif fikih, faktor kehamilan bagi seorang perempuan tidak mengurangi kadar istitha‘ah baginya untuk menunaikan ibadah haji selama kehamilan itu tidak mengganggu atau menyulitkan diri dan janinnya dalam pelaksanan aktivitas ibadah haji. Tidak disinggungnya faktor kehamilan dalam perbincangan mengenai istitha‘ah, boleh jadi karena kondisi fisik perempuan yang sedang hamil itu tidak sama, melainkan berbeda-beda satu sama lain; ada perempuan hamil yang merasa kondisi fisiknya tidak terganggu, tetap sehat dan kuat, bahkan mungkin lebih sehat daripada ketika tidak sedang hamil. Tetapi, tidak sedikit perempuan yang mengalami kondisi fisik yang lemah dan kurang sehat selama hamil. Dapat disimpulkan bahwa kadar istitha‘ah seorang perempuan untuk menunaikan ibadah haji tidak berkaitan dengan faktor kehamilan. Melainkan berkaitan dengan kemampuan dan kesehatan fisiknya. Kehamilan hanyalah salah satu faktor yang diduga kuat dapat memperlemah kondisi kesehatan dan kemampuan fisik seseorang. Pertanyaannya, siapa yang berhak menentukan sehat-tidaknya atau mampu-tidaknya fisik seseorang yang sedang hamil untuk melaksanakan ibadah haji? Menurut hemat saya, yang paling berkompeten adalah dokter kandungan yang profesional. Dokter itulah (setelah melakukan pemeriksaan dengan teliti) membuat keterangan yang benar mengenai kondisi kesehatan perempuan hamil. Jika menurut dokter, kehamilannya itu diprediksikan tidak mengurangi istitha‘ah haji, maka yang bersangkutan diizinkan untuk berangkat, demikian pula sebaliknya. Untuk itu perlu dibuat peraturan bagi calon haji perempuan hamil harus menunjukkan surat keterangan dari dokter kandungan. Dalam kaitan ini, fungsi Kementerian Agama adalah memfasilitasi dan menyediakan akses bagi mereka untuk mudah mendapatkan dokter kandungan yang profesional dengan biaya yang terjangkau. Yang penting perempuan hamil hendaknya mendapatkan akses informasi dan penjelasan yang cukup terkait seluruh aspek yang berkenaan dengan pelaksanaan haji, terutama aspek kesehatan, ibadah, akidah, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dari segi kesehatan, misalnya, perlu diberikan penjelasan yang lengkap, terutama tentang vaksinasi meningitis dengan segala dampak positif dan negatifnya, khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Dalam aspek ibadah perlu dijelaskan tentang tujuan, manfaat, dan rahasia haji dalam Islam. Tidak kurang pentingnya penjelasan yang objektif dalam aspek keamanan. Bahwa pelaksanaan haji dilakukan secara serentak oleh berjuta-juta umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam radius wilayah teritorial yang sangat terbatas dan dalam tenggang waktu yang relatif pendek sehingga sangat berpotensi menimbulkan berbagai kesemrawutan yang seringkali membahayakan jiwa jemaah. Banyaknya jumlah jemaah haji dan terbatasnya fasilitas proteksi dan pengamanan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Di samping itu, perlu juga dijelaskan bahwa kehamilan itu pada esensinya adalah amanah dari Allah swt. yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dalam fikih dikenal kaidah “la dharar wa la dhirar” yang menekankan pentingnya menghindari kesulitan dan mencegah hal-hal yang akan menimbulkan kesulitan. Berdasarkan kaidah ini, perempuan hamil yang meyakini bahwa keberangkatannya untuk menunaikan haji itu akan membawa pengaruh buruk bagi diri dan janinnya, maka sebaiknya menunda pelaksanaan ibadah hajinya itu. Berdasarkan informasi dan penjelasan yang menyeluruh itu, diharapkan seorang perempuan hamil dapat dengan sadar dan penuh tanggung jawab mengambil keputusan sendiri apakah ia akan berangkat haji atau tidak. Kalaupun ia memutuskan untuk berangkat tentunya ia sadar dengan segala risiko yang bakal dihadapinya dan dengan demikian ia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi risiko itu. Sebesar apapun suatu bahaya atau risiko jika dihadapi dengan penuh kesadaran dan kesiapan tentu tidak sefatal jika tanpa persiapan sama sekali. Mengingat terbatasnya fasilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan haji, khususnya berkenaan dengan fasilitas pemberian pertolongan medis kepada perempuan hamil yang mendadak mengalami masalah dengan kehamilannya itu, maka disarankan agar setiap calon haji perempuan hamil untuk membayar jaminan kesehatan berupa sejumlah uang kepada pemerintah sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi dengan kehamilannya itu, dengan catatan jika tidak digunakan, uang jaminan itu akan dikembalikan setelah kembali ke tanah air. Bagi calon haji yang menunda keberangkatan karena alasan kehamilan, pemerintah hendaknya memberikan jaminan prioritas untuk berangkat pada musim haji berikutnya. Perempuan hamil hendaknya diperlakukan sebagai subjek yang dimintai penjelasan dan keterangan mengenai kondisi diri dan janin yang dikandungnya. Berdasarkan penjelasan dan informasinya itulah, ahli medis melakukan diagnosa untuk menetapkan kondisi kesehatan dan kemampuan fisiknya. Sayangnya, dalam realitas tidak semua perempuan punya akses terhadap informasi dan penjelasan yang benar dan komprehensif mengenai pelaksanaan ibadah ini sehingga seringkali keputusannya untuk menunaikan ibadah haji bukan didasarkan pada pemahaman yang benar mengenai syariat, melainkan cenderung didasarkan pada pertimbangan emosional dan bahkan, sering tidak rasional. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat, terutama pemuka agama, bertanggung jawab membuka akses seluas-luasnya kepada kaum perempuan di semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji. Diharapkan dengan bekal informasi yang luas dan mendalam itu mereka terlindungi dari hal-hal yang menyesatkan, sebaliknya menjadikan mereka berdaya dan mampu mengambil keputusan sendiri secara sadar dan penuh tanggung jawab. Jadi, penekanannya adalah pada bagaimana memberdayakan perempuan melalui peningkatan ilmu dan takwa sehingga mereka menjadi muslimah yang kuat, mandiri, arif-bijaksana, dan bertanggung jawab. Bukankah al-muslim al-qawiyyu khair min al-muslim al-dha’if (muslim yang kuat lebih baik dari muslim yang lemah)?[] Catatan Belakang: [1] Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Yogyakarta, 1984, h. 934-935 [2] Ar-Raghib Al-Asfahani, Mufradat Alf±© Al-Qur’±n, h. 530-531. [3] Lihat uraian Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, Jilid 3, h. 26. |
AuthorDewan Redaksi JP, Redaksi JP, pemerhati masalah perempuan Jurnal Perempuan terindeks di:
Archives
July 2018
|



 RSS Feed
RSS Feed