 Hany Fatihah Ahmad (Mahasiswi S1 UIN Syarif Hidyatullah) Feminisme, sebuah kata dengan banyak stigma dan menimbulkan berbagai persepsi di dalam ruang dialektika masyarakat. Mengenai pengertian feminisme, tentu pembaca artikel ini dapat menelusuri langsung karya-karya tokoh feminis seperti Nawal el-Saadawi, Simone de Beauvoir, Marry Wollstonecraft dan masih banyak lagi. Pilihan lainnya, pembaca juga dapat menyimak video kuliah tokoh feminis Indonesia seperti Gadis Arivia atau Rocky Gerung di Youtube. Atau membaca ribuan jurnal penelitian mengenai gagasan ini di internet.
0 Comments
 Alfiyah Sudira ( Mahasiswi Pascasarjana, STFI Sadra) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “perempuan” berasal dari kata “empu”. Dalam Bahasa Jawa Kuno, yang kemudian diserap dalam Bahasa Melayu, yang berarti “tuan, mulia, hormat”. Kata empu tersebut mengalami pengimbuhan dengan penambahan “per-“ dan “-an” yang kemudian membentuk “perempuan”. Dalam Bahasa Jawa, perempuan disebut wadon alias wadahe adon-adon, yang memiliki arti tempat dibentuknya sesuatu. Perempuan secara biologis bermakna orang yang mengalami menstruasi, memiliki rahim, hamil dan menyusui. Dengan pembawaan alaminya, pengalaman reproduksi perempuan sudah demikian kompleks dan bermacam rupa. 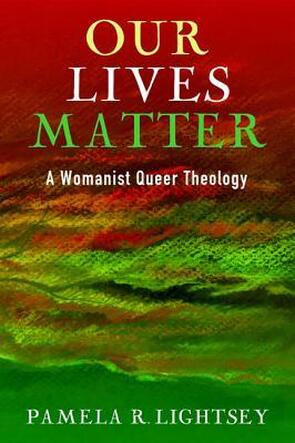 Ayom Mratita Purbandani (Mahasiswi S1 Filsafat, Universitas Gadjah Mada) “Tuhan melangkah keluar dari surga, menjelma, dan melakukan hal baru di antara orang-orang yang tertindas untuk mengubah seluruh dunia.” – Pamela R. Lightsey Pamela R. Lightsey menulis buku ringkas sepanjang 128 halaman berjudul Our Lives Matter: A Womanist Queer Theology (2015) yang terdiri atas tujuh bagian yang mengekplorasi penindasan yang terjadi pada kelompok LGBTQIA+ kulit hitam. Tak banyak buku yang membahas mengenai kelompok queer kulit hitam. Untuk alasan itulah, Lightsey membangun pemikirannya dalam buku ini. Dalam pengantar buku tersebut, kalimat pertama yang Lightsey tuliskan merupakan identifikasi atas identitas dirinya: “I am a black queer lesbian womanist scholar and Christian minister” (Lightsey, 2015: 6). Sebuah Cerpen oleh Mia Olivia
Hariman bingung saat pamannya, Lik Kung, mengatakan ia akan memberinya uang sebesar satu juta rupiah. Awalnya Hariman heran darimana Lik Kung mendapatkan uang karena setahu Hariman ia tidak punya uang dan yang lebih mengherankan lagi, bagaimana ia bersedia membagi uang yang ia dapatkan. Lik Kung terkenal sangat amat pelit bahkan untuk bersedekah dua ribu perak di masjid saja ia bisa membahasnya sampai tiga kali sholat Jumat. Mulut Hariman sudah ingin menanyakan tapi urung, entah kenapa ia merasa segan. Seakan gayung bersambut, Lik Kung membuka sendiri dari mana uang itu datang. Sebuah Cerpen oleh Mia Olivia
Sabtu, genap dua minggu Ibu mengurung diri di rumah. Sepanjang empat belas hari itu tidak ada seulas senyum-pun di wajah Ibu. Makanan yang dimasak di meja hampir-hampir tak disentuhnya kecuali barang satu dua suapan saja. Beberapa temannya menelepon menanyakan kabarnya dan dari balik pintu kamarnya aku bisa mendengar suara jawaban Ibu, sedang kurang enak badan. Satu dua orang tetangga juga datang bertandang tetapi Ibu menolak menerima dan menyuruhku mengatakan bahwa Ibu sedang sakit.  Esa Geniusa (Mahasiswi S1 Filsafat, Universitas Gadjah Mada) Seiring berjalannya zaman, saya mengamati bahwa terdapat berbagai bentuk pergerakan yang diinisiasi oleh masyarakat dunia, baik nasional maupun internasional. Secara pribadi saya menyadari bahwa kehidupan di dunia tidak dapat terlepas dari propaganda. Hidup dalam keluarga yang erat dengan isu-isu pergerakan menjadikan saya sebagai pribadi yang peduli pada bentuk pergerakan itu sendiri. Terjadinya pergerakan di Indonesia sering sekali dilandasi dengan dasar rasa persatuan dan kesetaraan yang dirasakan, hal ini salah satunya terbentuk pada model pergerakan perempuan. Bentuk dari pergerakan perempuan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Pernyataan ini didukung dengan hadirnya berbagai pergerakan yang muncul, baik dari skala kecil maupun besar serta melalui platform media hingga orasi yang didengungkan. Berdasarkan hal ini tanpa disadari membuat saya ingin melihat lebih jauh bagaimana sejatinya bentuk dari pergerakan perempuan di Indonesia, serta bentuk perkembangan dan persoalan yang hadir di dalamnya.  Nurma Yulia Lailatusyarifah (Mahasiswi Prodi Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia) Beranjak dewasa, saya belajar bahwa mengekspresikan amarah tidaklah mudah. Amarah adalah suatu bentuk emosi intens yang melambangkan ketidaknyamanan dan ketidaksenangan terhadap seseorang atau sesuatu yang dinilai salah. Akan tetapi, amarah sebagai emosi alamiah manusia kerap dilabeli sebagai emosi yang maskulin. Laki-laki dan amarah merupakan dua gagasan yang jika diposisikan berdampingan tidak perlu dipertanyakan kesesuaiannya. Berbeda halnya dengan perempuan. Sejak kecil, sebagian besar perempuan didukung untuk merawat karakter-karakter feminin, seperti kelemah lembutan, kepedulian, dan kepatuhan. Perempuan diwajibkan untuk mengendalikan dirinya dengan baik agar tidak menunjukkan emosi seperti amarah karena perempuan yang menunjukkan amarah dipandang sebagai perempuan yang tidak stabil, pembangkang, dan tidak feminin.  Sebuah Cerpen oleh Mia Olivia (Mantan Badan Pekerja Komnas Perempuan dan Pengembang Safe Circle, Komunitas Pemberdaya Jiwa untuk Perempuan dan Minoritas) Apakah seorang seperti aku diperbolehkan semesta untuk jatuh cinta? Apakah seorang pekerja seks seperti aku mampu mendapat kasih sayang alam untuk bisa bersama dengan orang yang aku cintai? Jika takdir bisa mempersatukan orang yang bahkan tidak saling cinta selama puluhan tahun, kenapa takdir tidak berkenan untuk menyatukan aku dan dia?  Retno Daru Dewi G. S. Putri (Tim Redaksi Jurnal Perempuan) Tepat pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, saya dan seorang teman menonton film berjudul Smile. Film garapan Parker Finn tersebut bercerita tentang seorang psikolog, Rose, yang mengalami delusi setelah menyaksikan pasiennya bunuh diri dengan mengenaskan. Ia dihantui oleh berbagai macam sosok yang membuatnya juga ingin menghabisi nyawanya sendiri. Setelah dicari tahu, Rose menemukan bahwa delusi tersebut dialami secara berantai oleh orang-orang yang bunuh diri sebelumnya.  Kadek Ayu Ariningsih (Mahasiswa Pascasarjana Filsafat, Universitas Gajah Mada) Sebagai perempuan asal Bali yang setahun terakhir menghabiskan lebih banyak waktu di pulau Jawa, tepatnya Yogyakarta, saya merasakan intensi keindahan budaya Jawa. Batik menjadi salah satu budaya Jawa yang menjadi favorit saya. Intensi saya terhadap batik dimulai ketika saya menonton Pagelaran Wayang Topeng Panji di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Batik sendiri sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi saya, toko-toko penjual Batik di Bali cukup mudah ditemukan. Saya sendiri memiliki sebuah atasan Batik yang sesekali saya gunakan dalam acara tertentu. Selama menyaksikan Pagelaran Wayang Topeng Panji, saya mengamati busana para penari yang berpadu padan dengan Batik. Saya melihat bahwa adanya situasi yang ‘agung’ selama pagelaran turut didukung oleh keberadaan Batik yang dikenakan oleh para penarinya. Relatif singkatnya waktu saya di Jogja dan interaksi saya yang minim dengan batik mengarahkan saya melakukan penelusuran literatur tentang Batik. Pembacaan literatur tersebut masih sangat terbatas, meski demikian, ini adalah upaya untuk memahami subjektifitas pribadi saya sendiri terhadap keindahan Batik. Penelusuran tersebut bukanlah suatu yang terkategori sebagai aktifitas ilmiah namun menjadi cukup menarik untuk sedikit menulis dan membagikannya. |
AuthorSahabat Jurnal Perempuan Archives
April 2024
Categories |
 RSS Feed
RSS Feed