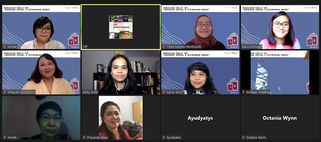 Dokumentasi Jurnal Perempuan Dokumentasi Jurnal Perempuan Kekerasan seksual bukanlah suatu peristiwa yang normal. Kekerasan seksual marak terjadi karena adanya kecacatan sistemik dan paradigma patriarki dalam masyarakat. Pemerintah, sebagai institusi sosial terbesar dalam suatu negara, wajib hadir dan mengakomodasi payung hukum yang memadai, agar kekerasan seksual tidak menjadi momok bagi masyarakat. Pengesahan RUU PKS menjadi salah satu hal yang dapat menyediakan payung hukum bagi korban—agar korban dapat mengakses keadilan dan pemulihan yang berhak diterimanya. Pada Kamis (30/9) lalu, Yayasan Jurnal Perempuan mengadakan diskusi publik peluncuran Jurnal Perempuan (JP) edisi 109 bertajuk: “Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender”. Diskusi publik ini dilaksanakan secara daring dan utamanya membahas artikel-artikel dalam JP 109. Salah satu tujuan peluncuran JP 109 adalah menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap pengesahan RUU PKS.
Diskusi publik ini menghadirkan Titiek Kartika (Dosen FISIP Universitas Bengkulu), Atnike Sigiro (Direktur Yayasan Jurnal Perempuan), Ikhaputri Widiantini (Dosen Filsafat FIB UI). Turut menanggapi paparan materi, Mariana Amiruddin (Komnas Perempuan), Baihajar Tualeka (LAPPAN Maluku), dan Rina Prasarani (HWDI). Abby Gina (Acting Director Jurnal Perempuan)—berperan sebagai moderator diskusi. Abby Gina membuka diskusi publik dengan menyampaikan data mengenai tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Selain masih tinggi, kasus kekerasan seksual juga sangat beragam dan kompleks, sehingga sulit ditangani. Diketahui bahwa Indonesia sudah memiliki beberapa perangkat hukum yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual. Namun, perangkat hukum tersebut belum mampu menyediakan pemenuhan hak dan pemulihan korban. “Undang-udang yang ada belum mengakomodasi kebutuhan korban dan hak konstitusional warga negara, maka dibutuhkan payung hukum yang membahas kekerasan seksual secara komprehensif—yaitu RUU PKS,” ujar Abby. Saras Dewi (Ketua Pengurus Kurawal Foundation) membuka diskusi publik ini dengan menyampaikan dukungan bagi penyintas kekerasan seksual. Ia juga mendorong negara turut hadir dan berperan dalam pengentasan kekerasan seksual. “Kita harus memaksa negara untuk hadir dan menghadirkan keadilan bagi para penyintas kekerasan seksual,” ujarnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber. Titiek Kartika memaparkan temuannya dalam artikel “Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses” yang juga dimuat dalam JP 109. Titiek menunjukkan bagaimana praktik maskulinitas dalam keluarga mendominasi kasus kekerasan seksual dan perkosaan sedarah atau inses. Dalam hal ini, kasus inses menjadi sulit ditangani karena banyaknya rasionalisasi terhadap perilaku tersebut. Selanjutnya, Ikhaputri Widiantini memaparkan tulisannya yang berjudul “Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis”. Berdasarkan riset pribadinya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, dengan pendekatan konseptual dari feminis Dianne Herman (1989) tentang rape culture—menurut Ikhaputri praktik kekerasan seksual kerap dilakukan oleh sesama mahasiswa maupun tenaga pengajar, tidak diakomodasinya standpoint feminis dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus membuat korban sulit mengakses keadilan. Demikian, penanganan kasus kekerasan seksual di kampus sering mengabaikan perspektif korban. Atnike Sigiro memaparkan risetnya yang bertajuk “Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman ‘Forum Pengada Layanan’ (FPL). Atnike menunjukkan berbagai tantangan dan kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan seksual dari sudut pandang FPL yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, seluruh organisasi yang tergabung dalam FPL pernah menangani lima belas jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi oleh Komnas Perempuan. Namun sayangnya sistem hukum yang ada belum mengenali kompleksitas tersebut. Riset Jurnal Perempuan menunjukkan bahwa salah satu bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh lembaga FPL adalah payung hukum, seperti Peraturan Perundang-Undangan, prosedur yang berperspektif korban, dan perubahan cara pandang hukum. Selain pentingnya payung hukum berperspektif korban, para narasumber menyatakan pentingnya revitalisasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sebab perubahan kultur kekerasan seksual tidak bisa hanya direspons lewat aturan hukum tanpa menyentuh kesadaran individu dan juga kelompok. Artinya pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kesetaraan gender dan membuka ruang dialog mengenai seksualitas secara terbuka dan juga rasional. Para narasumber dalam paparannya menyatakan bahwa aturan hukum tentang kekerasan seksual dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab dia tidak hanya melindungi hak dan kepentingan perempuan, tetapi juga melindungi anak, kelompok difabel, laki-laki—seluruh warga negara Indonesia dari tindak kekerasan seksual. Ketiadaan payung hukum yang mengatur kekerasan seksual secara komprehensif membuat banyak kasus kekerasan seksual mengalami jalan buntu. Sehingga, diperlukan pembaruan terhadap instrumen hukum tersebut. “Ketika kita mengajukan desain daripada RUU PKS, di dalamnya perlulah memasukkan definisi dan pemahaman kekerasan seksual yang komprehensif,” tutur Titiek. Sebagai penutup, Ikhaputri menegaskan pentingnya pengesahan RUU PKS tanpa adanya pemotongan substansi, sebagai pendorong adanya peraturan-peraturan penanganan kekerasan seksual di instansi lainnya. “Kalau kita berhasil menggolkan RUU PKS menjadi UU PKS—tanpa perlu ada perubahan-perubahan demi kepentingan tertentu, tetap pada substansi yang memang berpihak pada kepedulian terhadap isu-isu kekerasan seksual—ini akan sangat membantu, karena (upaya penghapusan kekerasan seksual—red) bisa dilanjutkan dengan membuat payung hukum di setiap kampus,” tutupnya. (Nada Salsabila). Comments are closed.
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
March 2024
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed