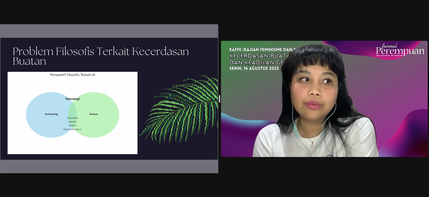 Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Kehadiran kecerdasan buatan menjadi salah satu topik besar tahun ini dengan kedatangan mesin teks generatif seperti ChatGPT dari OpenAI. Dengan cepat penggunaan teknologi kecerdasan buatan hadir di keseharian, bahkan menjadi teman mengobrol orang-orang. Namun tak butuh lama bagi masyarakat untuk menyadari persoalan-persoalan baru yang meresahkan yang dibawa oleh penggunaan kecerdasan buatan ini. Berangkat dari dilema ini, LG. Saraswati Putri, atau yang akrab dipanggil Yayas, hadir pada kelas daring KAFFE Agustus (14/8/2023) untuk membagikan pemahaman terkait teknologi kecerdasan buatan dari sudut pandang filsafat dan keadilan gender. Ketika Yayas bertanya apakah peserta familier dengan ChatGPT dan sebagainya, para peserta menjawab sudah menggunakannya untuk beragam hal seperti membantu menulis dan menyunting surel, membuat takarir media sosial, atau bahkan hal sepersonal ucapan ulang tahun. Yayas ingin memulai pemaparannya dengan menceritakan sejarah kecerdasan buatan mulai dari masa Alan Turing memikirkan bagaimana mesin bisa memecahkan kode. Yang amat menarik, Yayas menghubungkan perkembangan teknologi ini dengan hasrat manusia untuk menciptakan sesuatu yang dapat berpikir seperti manusia, yang bahkan sudah dapat ditemukan pada mitos-mitos lampau. Misalnya mitos Pygmalion yang membayangkan ingin menciptakan seorang gadis ideal dari marmer. Kemudian Yayas membahas dua pandangan dalam memahami teknologi, yaitu melihatnya sebagai enframing, bahwa “Teknologi hanya dipakai, digunakan secara permukaan saja, tidak ada pandangan yang lebih mendalam, lebih holistik tentang suatu wujud dan sistem teknologi.” Sementara itu ada cara yang lebih esensial dan substansial, yaitu melihat bahwa ada subjek dan diri di setiap ciptaan manusia. Yayas kemudian mengajak kita memikirkan berbagai pertanyaan filosofis seputar kecerdasan buatan. Misalnya, bagaimana kita bisa jadi subjek yang otentik—siapa diri sesungguhnya di era teknologi digital yang begitu deras dengan misinformasi dan disinformasi. “Bagaimana cara menjadi jujur jika dorongan untuk menulis pun diserahkan kepada mesin yang berpikir?” tanya Yayas. Sebagai dosen pun, ia mengecek ZeroGPT untuk memeriksa apakah tulisan para mahasiswa ditulis dengan AI. Pada saat yang sama, ia juga meminta mahasiwa untuk berdiskusi dengan AI karena menurutnya AI dapat memberikan referensi buku, bahkan dapat berperan sebagai tutor. Pertanyaan selanjutnya yang Yayas bahas adalah terkait alienasi. Yayas menyampaikan bahwa banyak filsuf, termasuk filsuf cyberfeminist yang mempertanyakan mengapa AI menjadi momok di daerah maju saja. “Bagaimana dengan perspektif atau tatapan orang-orang yang tidak datang dari budaya Silicon Valley, misalnya? Ada keterasingan dalam artian ketimpangan, bahwa AI hanya bisa menguntungkan orang-orang yang punya akses. Ada problem aksesibilitas di sana.” Dari menyimak kuliah-kuliah oleh Yuval Noah Harari, Yayas sendiri mulai memikirkan bagaimana AI dapat memperkokoh struktur hierarkis dan ketimpangan yang ada. Sebagai filsuf yang memerhatikan isu lingkungan, Yayas juga mengajak berpikir terkait kemungkinan bencana besar yang sangat mungkin terjadi—bukan khayalan fiksi ilmiah belaka—dari pemanfaatan AI. Lebih lanjut mengenai ketimpangan, Yayas juga membahas bias data, bahwa data tidak dimunculkan secara seimbang oleh AI, berkaitan dengan bagaimana ketidakadilan gender pun dihadirkan oleh bias data. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mesin-mesin tersebut dibuat oleh individu atau korporasi yang tidak punya semangat afirmatif terhadap berbagai macam perbedaan serta ragam pengetahuannya. Tak luput juga dibahas bagaimana mesin kecerdasan yang berkembang saat ini berada dalam lingkup korporasi, sehingga perkembangan ke depannya akan menggunakan logika korporasi. Yayas juga menyampaikan keresahannya terhadap penggunaan AI oleh negara-negara dengan ruang demokrasi sempit. Terkait hal ini, Yayas mengingatkan bahwa hak kita sebagai warga digital belum terpenuhi, sebab kita tidak mendapatkan transparansi dan akuntabilitas tentang bagaimana mesin-mesin itu dilatih, dan pertanggungjawaban bahwa mesin-mesin itu aman. Dengan posisi AI dalam korporasi, Yayas juga menyebutkan bahaya pemanfaatan AI untuk otomasi senjata militer, lalu kolonialisme baru atau kolonialisme data. Teks Feminis Seputar Kecerdasan Buatan
Yayas kemudian membagikan bacaan-bacaan menarik seputar kecerdasan buatan, yang ditulis oleh para pemikir feminis. Misalnya Nina Shick yang membahas kebencanaan informasi yang terjadi karena begitu derasnya arus berita bohong, dan kebencian yang diamplifikasi di ruang digital. Nina Shick membahas misalnya bagaimana deep fake disalahgunakan untuk meniru wajah, khususnya perempuan, dalam video-video pornografi. Kemudian, Sadie Plant yang secara spesifik mengamati irisan antara teknologi digital dan gender. Dalam, bukunya Zeros + Ones: Digital Women + New Technoculture, Sadie Plant terpengaruh oleh perempuan pemikir dan pakar matematika Ada Lovelace. Plant membaca catatan-catatan Ada Lovelace, yang sudah memiliki gagasan tentang bagaimana memaknai kehadiran mesin yang berpikir. Konsep siborg oleh Donna Haraway (A Cyborg Manifesto) juga tidak luput dari paparan dosen Departemen Filsafat Universitas Indonesia ini. Menurutnya, teknofantasi dalam pandangan maskulin terobsesi pada disembodiment, yaitu untuk meninggalkan tubuh. Manusia ingin disembodied dari tubuh manusia yang banyak kekurangan dan keterbatasan. Ia memberi contoh teknofantasi dalam Mahabharata, yaitu hasrat menciptakan senjata superampuh yang bisa membinasakan. Hal ini berbeda dengan teknofantasi dalam pendekatan feminis. Misalnya pemikiran Sadie Plant menyoal embodiment atau kembali kepada tubuh, dan tubuh sendiri banyak ragamnya; tubuh satwa, gunung, bebatuan, lautan. Sadie Plant membayangkan kebertubuhan yang saling berkaitan, berhubungan, terpaut dengan lainnya. Yayas melihat pemikiran Plant juga memberikan ruang yang sangat banyak kepada gagasan queer, sebab ia juga terpengaruh pemikiran filsuf queer Monique Wittig. “Alam itu sangat queer dalam pikiran Sadie Plant,” ucap Yayas. Bacaan selanjutnya yang disebutkan adalah The Institute of Other Intelligence karya Mashinka Firunts Hakopian. Hakopian terinspirasi juga oleh The Feminist Killjoy karya Sara Ahmed dan membayangkan apabila terdapat entitas seperti artificial killjoy. Hakopian mengajak pembaca membayangkan bagaimana jika di masa depan para kecerdasan buatan melakukan konferensi, lalu terdapat AI yang punya sensitivitas lebih terhadap keberagaman. Diskusi kemudian berlanjut dalam sesi tanya jawab. Para peserta menanggapi dengan berdiskusi soal bagaimana AI mengancam perempuan adat. Kemudian ada peserta yang menganggap teknologi membuat hidup perempuan jadi lebih baik, dan berharap mendengar pandangan optimistik mengenai AI. Ada juga yang menanggapi diskursus soal transhumanisme dan kedirian. Dari diskusi KAFFE kali ini, ada banyak PR yang perlu kita pikirkan mengenai kecerdasan buatan. Masalah-masalah yang dibawa teknologi baru ini bukan fantasi ilmiah, tetapi sudah memiliki konsekuensi-konsekuensi nyata yang perlu diatasi bersama. Sebagai feminis, kita perlu memikirkan secara kritis risiko pelanggengan ketimpangan oleh teknologi kecerdasan buatan, tetapi juga jangan sampai luput memikirkan cara-cara menjadikannya alat untuk meretas ketidakadilan. (Asri Pratiwi Wulandari) Comments are closed.
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
March 2024
Categories |
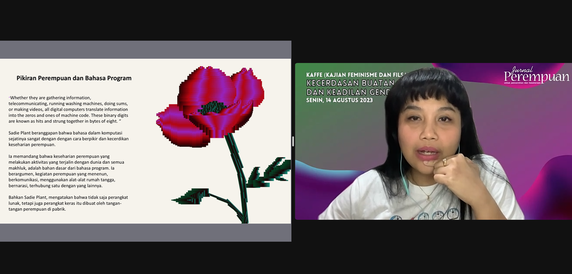

 RSS Feed
RSS Feed