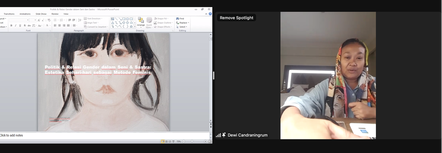 Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Pada Senin, 26 Februari 2024, Jurnal Perempuan mengundang Dewi Candraningrum, seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, aktivis perempuan, seniman, sekaligus Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan periode 2014-2016, untuk mengisi kelas Kajian Feminisme dan Filsafat (KAFFE) edisi Februari 2024. Kelas kali ini bertajuk Politik dan Relasi Gender dalam Seni dan Sastra: Estetika Sehari-hari sebagai Metode Feminis. Sebelum membicarakan relasi di dalam karya seni dan sastra, Dewi mengajak kita untuk merefleksikan ulang, apa yang disebut sebagai seni? Apa yang disebut sebagai sastra? Sekitar dua tahun lalu, Dewi dan rekan-rekan seniman menerbitkan sebuah buku yang berjudul Membisikkan Bekal untuk Perjalanan yang Sangat Jauh. Dalam buku ini, mereka mendekonstruksi seni sastra menggunakan metode feminis. Mereka mengkritik atas definisi, konsep, dan kategori seni sastra karena pada mulanya seni sastra mengacu pada sesuatu yang diciptakan untuk kenikmatan estetika belaka. Para pakar mendefinisikan seni sastra sebagai karya, individual, jenis, dan bersifat abadi.
Padahal, perempuan banyak melakukan pekerjaan seni yang sifatnya tidak abadi, seperti mendongeng sebelum tidur, menulis diary, atau membuat kerajinan tangan. Semua hal yang dilakukan perempuan itu adalah karya sastra, tetapi tidak pernah diperhitungkan sebagai sebuah karya sastra. Kita kerap bertanya-tanya, kenapa tidak ada sastrawan perempuan atau maestro perempuan yang jenius? Karena sistem terkait definisi, konsep, dan kategori seni sastra telah mendiskriminasi perempuan. Ketika berbicara tentang relasi tidak setara dalam karya sastra, Dewi juga mengajak peserta yang hadir untuk memikirkan ulang, apakah ketidaksetaraan itu hanya terjadi di dalam karakter dalam karya sastra, atau berada di luar karya sastra? Sebagaimana disebutkan di atas, perempuan telah dikeluarkan dari definisi seni sastra yang didefinisikan oleh laki-laki, maskulin, dan heteronormatif. Maka tidak heran bahwa peraih penghargaan Nobel atau Oscar seringkali adalah laki-laki dari Barat dan berkulit putih. Sebab mereka yang menciptakan definisi, konsep, dan kategori seni sastra. Maka, pertama-tama yang harus dibongkar adalah penyebutan definisi tersebut agar tidak meminggirkan komunalitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya. Lalu, bagaimana metode feminis dalam seni sastra bekerja? Pertama, melalui unsur rumahan dan sehari-hari. Dewi mencontohnya, misalnya, Faith Ringgold dan Miriam Schapiro pada tahun 1970-an memasukkan bahan kerajinan seperti serat dan kain ke dalam pajangan karya seni mereka. Karya mereka memamerkan bahan-bahan yang diasosiasikan dengan hal domestik dan feminin, yang dalam tradisi klasik seni di Barat kerap dipandang sebelah mata. Kedua, melalui tubuh melar sebagai distorsi citra ideal yang feminin. Dewi memberikan contoh lukisannya, yaitu seorang perempuan bernama Christina Sumarmiyati, yang merupakan seorang penyintas tragedi 1965. Dalam lukisannya, Dewi melakukan “pemberontakan” dengan merepresentasikan wajah perempuan yang tidak putih, terlihat traumatis, penuh kerut wajah, dan serius. Ini merupakan salah satu caranya dalam melawan citra mainstream tubuh perempuan ideal yang lembut dan cantik. Metode feminis dalam seni sastra juga mendekonstruksi analisis tatapan karena selama ini dalam karya seni sastra, posisi penonton dan pembaca ditentukan oleh pembaca laki-laki, maskulin, dan heteronormatif. Banyak karya-karya seni roman yang masih menggunakan male gaze atau tatapan laki-laki seperti kisah putri kerajaan yang jatuh cinta dengan pangeran. Tatapan laki-laki telah membantu secara teoretis memahami bahwa tidak ada tatapan yang netral dan universal. Menatap kemudian menjadi tindakan politis. Melalui hegemoni tatapan, maka ada kuasa untuk mengobjektivikasi dan menundukkan siapapun yang subordinat—perempuan dan kelompok marginal lainnya. Dewi kemudian memberikan beberapa contoh karya seni sastra “liyan” yang menggunakan metode feminis. Pertama, Soe Tjen Marching dalam naskahnya Sastra Perempuan Indonesia Tionghoa dan Mei ’98 menampilkan karya Agnes Christina yang berjudul The Lessons of Silence. Dalam karyanya, Agnes mengatakan bahwa ia hanya bisa menulis karya sastra dalam Bahasa Inggris, karena menggunakan Bahasa Indonesia sangat menyesakkan baginya, sebagai seorang etnis Tionghoa yang mengalami peminggiran pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa relasi negara yang sangat represif bisa memengaruhi cara perempuan menulis dan bertutur. Kedua, Seli Muna Ardiani juga dalam naskahnya yang berjudul Perempuan Dalam dalam Hegemoni Tradisi Pakem menemukan bahwa dalang-dalang perempuan tidak bisa membabar satu cerita yang suci untuk upacara yang suci. Mereka juga kerap mendapat stereotipe buruk karena perempuan dalang pulang malam dan lebih mementingkan urusan seni dibandingkan urusan lain. Metode feminis dalam seni sastra memiliki implikasi politis dan filosofis. Citra perempuan yang mapan telah dijungkirbalikkan dengan citra-citra perempuan lain yang “mengganggu”, yang kemudian membuat penonton mempertanyakan nilai-nilai yang dianut dan diyakininya sebagai sebuah standar yang universal. Metode feminis dalam kerja seni sastra mempertanyakan normalisasi praktik kesenian selama ini yang banyak meliyankan hal-hal di luar gagasan adiluhung. Metode ini adalah beragam cara, alat, dan sarana untuk melakukan penyelidikan gagasan kesenian yang berusaha mengatasi ketidakadilan, bias, membawa perubahan sosial, menampilkan keragaman manusia, dan mengakui posisinya sendiri, baik sebagai seorang perempuan, minoritas seksual, masyarakat adat, dan lain-lain. Dengan demikian, seni bisa menjadi jalan yang membebaskan dan memerdekakan. (Fadilla D. Putri) Comments are closed.
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
March 2024
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed