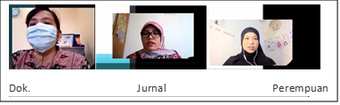 Jumat (18/12), INFID mengadakan webinar dengan topik “Women’s Rights are Human Rights: Meninjau Kembali Urgensi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. Webinar yang merupakan bagian dari Festival HAM 2020 ini menghadirkan Mariana Amiruddin (Wakil Ketua Komnas Perempuan), Tatat (INFID) dan Rika Rosvianti (pendiri perEMPUan). Salah seorang anggota DPR yang sedianya menjadi narasumber tidak kunjung hadir hingga acara usai. Pandemi yang tengah melanda saat ini bagai jebakan yang nyata-nyata meningkatkan kerentanan berlapis bagi perempuan. Penanganan pandemi yang mensyaratkan warga untuk tetap berada di rumah memerangkap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga bersama pelaku; berada di luar rumah pun tak mengurangi risiko menjadi korban karena kekerasan terhadap perempuan juga kerap terjadi di ruang publik; memindahkan aktivitas melalui daring pun berisiko menjadi korban kekerasan berbasis gender secara online (KBGO). Komnas Perempuan kembali menegaskan terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi. Mariana menyampaikan menurut data terkini sampai dengan Oktober 2020 telah terhimpun 1.458 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, terdapat 378 kekerasan fisik dan 483 kasus kekerasan seksual. Di ranah komunitas, dari data yang terhimpun sebanyak 56,8% atau 405 kasus yang dilaporkan merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara itu di ranah siber, sampai dengan Oktober 2020 telah terlapor sebanyak 659 aduan kasus kekerasan berbasis gender di ranah siber, yang meningkat 200% dibandingkan dengan jumlah aduan pada tahun sebelumnya (2019) sebanyak 281 kasus. “Sepanjang tahun 2016 hingga 2019, dari catahu yang dihimpun Komnas Perempuan, terdapat 55.273 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke lembaga layanan baik yang dikelola masyarakat, di bawah pemerintah maupun aduan ke kepolisian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.841 merupakan kasus kekerasan seksual, dimana 8.964 merupakan kasus perkosaan. Dari jumlah laporan yang diadukan tersebut, kurang dari 30% kasus yang kemudian diproses secara hukum” ujar Mariana. Minimnya proses hukum untuk kasus kekerasan seksual, menurut Mariana, menunjukkan aspek substansi hukum yang ada tidak mengenal sejumlah tindak kekerasan seksual dan hanya mencakup definisi yang terbatas. “Aturan pembuktian yang membebani korban dan budaya menyalahkan korban serta terbatasnya daya dukung pemulihan korban juga menjadi kendala utama”, Mariana menambahkan. Sejalan dengan hal tersebut, Rika menyampaikan bahwa meskipun sudah terdapat seperangkat peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi rujukan untuk kasus kekerasan seksual seperti UU PKDRT, UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak namun kesemuanya memiliki cakupan perlindungan yang terbatas. Perempuan dengan identitas berusia di atas 18 tahun yang tidak terikat dalam perkawinan tercatat dan / atau bukan korban tindak pidana perdagangan orang, yang menjadi korban kekerasan seksual masih belum terlindungi aturan hukum. KUHP yang ada menurut Rika mengandung kelemahan dan keterbatasan untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Tidak mengherankan jika kemudian bermunculan korban yang menceritakan kasus kekerasan seksual yang dialaminya melalui media sosial sebagai upaya terakhir dalam mencari keadilan. Fenomena yang dikenal dengan istilah “spill-case call out” ini menurut Rika, bukan tanpa konsekuensi. “Spill case call out ini berpotensi menimbulkan kerentanan lain seperti misalnya korban bisa terkena ancaman UU ITE karena dianggap mencemarkan nama baik pelaku”, ujar Rika. Konsekuensi lain, ungkap Rika, adalah memunculkan apa yang disebut “online redemption” dimana pelaku memohon maaf atas perbuatannya tersebut. “Online redemption dianggap cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, padahal hal tersebut tidak membantu korban dan hanya sekedar memulihkan nama baik pelaku semata”, ungkap Rika. Lebih lanjut Mariana juga memaparkan bahwa ketiadaan dan tertundanya prioritas payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual adalah suatu tindakan pengabaian dan melanggar hak konstitusi perempuan sebagai warga negara yang dijamin Undang-undang. Apabila kelalaian, pengabaian, pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak, terus dilakukan, maka negara dapat dikatakan telah bertindak inkonstitusional, tidak menjamin kemerdekaan bagi perempuan sebagai warga negara untuk jauh dari rasa takut dan diskriminasi. Di sisi lain, Rika menyesalkan bahwa kampanye mendorong pengesahan RUU PKS yang dilakukan selama ini melalui pendekatan humanis terbukti belum berhasil menggugah empati para pembuat kebijakan terhadap korban. Menurutnya, strategi lain dengan pendekatan perilaku rasional yang mengedepankan insentif dari adanya UU PKS barangkali akan lebih mengena di hati para pembuat kebijakan. “Mewujudkan UU PKS bukanlah hal yang sulit. Catahu yang diluncurkan setiap tahun merupakan bentuk peringatan tidak tertanganinya pemenuhan rasa keadilan, perlindungan dan pemulihan korban”, tegas Mariana. (Dewi Komalasari) Comments are closed.
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
March 2024
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed