 Oleh Andi Misbahul Pratiwi Prof. Mustofa merupakan seorang pakar di bidang kriminologi. Ia menyelesaikan Sarjana Kriminologi (Drs.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia pada 1977. Pada November 1981 hingga Maret 1982 ia menjadi visiting scholar untuk bidang Sosiologi Hukum di Universiteit te Utrecht Belanda dan meraih Postgraduate Diploma di bidang kriminologi dari University of Melbourne, Australia pada 1988 dan pada tahun 1990 melanjutkan studi Master by Research (MA) di bidang dan universitas yang sama. Gelar Doktor Sosiologi diperolehnya dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada 1988. Kini ia menjabat sebagai guru besar di Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Laki-laki yang memiliki motto menjadikan kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan di Indonesia sebagai gejala sosial, harus ikut memberi manfaat bagi perwujudan kesejahteraan rakyat Indonesia ini telah banyak melahirkan karya yang telah di publikasikan dalam buku maupun jurnal. Rama Sayudhia: Anak Laki-Laki yang Bicara Tentang Kesehatan Reproduksi & Melawan Perkawinan Anak23/7/2021
 Andi Misbahul Pratiwi Artikel ini pernah dimuat di Jurnal Perempuan Edisi 105 “Ingatlah bahwa keberhasilan dan kegagalan adalah dua hal yang selalu mewarnai kehidupan seseorang untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap berusaha dan terus semangat.” -Rama Sayudhia Rama Sayudhia (15 tahun) tinggal bersama orang tuanya dan keluarga besar di sebuah desa kecil di dekat pelabuhan Lombok Barat. Sejak kecil, Rama sudah melihat praktik kekerasan dan perkawinan anak di sekitarnya. Di lingkungan tempat tinggal Rama, praktik perkawinan anak, pekerja anak, penelantaran anak, dan kekerasan terhadap anak sangat umum terjadi. Realita pahit ini membuatnya tergerak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuknya dan anak-anak di Lombok Barat. Rama dinominasikan olen Plan Indonesia untuk The International Children’s Peace Prize 2020 karena keaktifannya memobilisasi anak dan kaum muda dalam isu perkawinan anak.  Arum Ratnawati Arum Ratnawati Abby Gina *Tulisan ini pernah dimuat dalam Wawancara pada JP 94 PRT Domestik dan Migran Arum Ratnawati bergabung dengan ILO (International Labour Organization) pada tahun 2002. Sejak tahun 2013 hingga sekarang ia menjabat sebagai Kepala Penasihat Teknis Proyek Promote ILO. Sesuai dengan misi ILO, program-program ILO berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Salah satunya adalah program Promote ILO, melalui program ini ILO mengadvokasi hak-hak PRT (Pekerja Rumah Tangga). Promote ILO merupakan sebuah program yang mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT. *Tulisan ini dimuat dalam Kata Makna JP edisi 107
Perempuan dan Pandemi Covid-19 di Indonesia Berbagai upaya pencegahan dan pengobatan untuk menghadang virus Covid-19 hingga saat ini masih terus dicari. Ahli kesehatan di seluruh dunia memprediksi hanya vaksin baru yang bisa mengatasi pandemi Covid-19. Prediksi tersebut didasari pada fakta bahwa vaksin telah digunakan untuk mengatasi virus telah dilakukan oleh manusia sejak awal penemuan vaksin. Perkembangan teknologi vaksin juga ditorehkan oleh kaum perempuan, namun masih sedikit mendapat perhatian dalam catatan sejarah maupun ilmu pengetahuan. 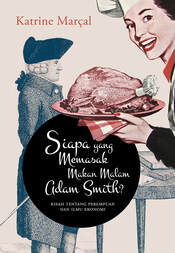 Bella Sandiata Redaksi Jurnal Perempuan 2018-2019 (bsandiata@jurnalperempuan.com) Judul Buku : Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith? Kisah tentang Perempuan dan Ilmu Ekonomi Penulis : Katrine Marçal (Diterjemahkan oleh Ninus D. Andarnuswari) Jumlah halaman : viii + 226 hlm Tahun terbit : 2015 (Ed Bahasa Inggris); 2020 (Ed Bahasa Indonesia) Penerbit : Portobello Books (Ed Bahasa Inggris); Marjin Kiri (Ed Bahasa Indonesia) Feminisme selalu tentang ekonomi. Bagaimana mungkin? Jawabannya sederhana. Saat seorang feminis terkenal, Virginia Woolf, menginginkan sebuah ruangan untuk dirinya sendiri, maka ia akan membutuhkan uang bukan? Katrine Marçal membuka buku Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith? Kisah tentang Perempuan dan Ilmu Ekonomi (Who Cooked Adam Smith’s Dinner? A Story about Women and Economics) melalui pembuktian bahwa setiap orang termasuk feminis sekalipun pasti akan berhubungan dengan ekonomi.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Gadis Arivia Pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, Pengajar filsafat di Fakultas Ilmu Budaya, UI, 1991-2017, Adjunct Professor di bidang sosiologi dan sociology of gender di Montgomery College, Maryland, USA. *Naskah dipresentasikan dalam Forum Menyalakan Lilin Masa Depan, 10 Mei 2020 (Zoom Webinar) Pendahuluan Pandemi Covid-19 bermula dari kota Wuhan, China, terdeteksi pada bulan Desember 2019. Pada pertengahan bulan Januari 2020, virus ini dengan cepat menjalar ke seluruh dunia dan dalam waktu singkat jutaan orang terinfeksi serta ratusan ribu orang meninggal dunia. Hampir di setiap negara, pemerintah setempat menerapkan aturan lockdown dan social distancing guna menghentikan penyebaran virus. Covid-19 bukan saja mengakibatkan krisis kesehatan melainkan juga krisis ekonomi dan sosial. 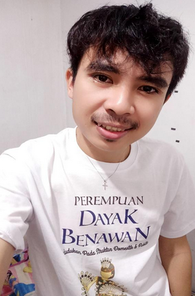 Dok. Pribadi Dok. Pribadi Nicodemus Niko Mahasiswa Doktoral Sosiologi, Universitas Padjadjaran (nicoeman7@gmail.com) Sebagian besar masyarakat Indonesia, secara umum masih menempatkan permasalahan seksual sebagai pembahasan yang tabu untuk diperbincangkan sehari- hari. Masyarakat seolah-olah menutup rapat segala perbincangan yang menyangkutpautkan tentang seks dan seksualitas. Baru-baru ini di Kalimantan Barat, pelaporan atas kejahatan seksual menguap ke permukaan. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat pada bulan Februari lalu membeberkan data kasus terkait penanganan kekerasan terhadap anak, dimana kejahatan seksual menjadi dominasi kasus yang ditangani (Antara Kalbar 2020). Sepanjang bulan Januari 2020 saja terdapat 20 kasus kejahatan seksual yang dilaporkan. Hal ini berarti bahwa ada kesadaran masyarakat untuk melapor atas segala bentuk kejahatan seksual yang dialami oleh anak-anak, ini sebuah kemajuan untuk bisa speak-up.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Nikodemus Niko Mahasiswa Doktoral Sosiologi, Pascasarjana FISIP, Universitas Padjadjaran (nicoeman7@gmail.com) Kemiskinan di negeri ini kian hari bukan semakin membaik, sebaliknya justru semakin memburuk. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi yang merajalela menjadi satu diantara sumber-sumber kemiskinan. Si miskin akan sangat sulit untuk mengubah nasib, sebab memang dimiskinkan. Perempuan adalah pihak yang paling menderita menghadapi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Tidak jarang diantaranya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, rentan terhadap pelecehan dan perkosaan, dan ada yang dinikahkan walau masih berusia muda. Mosse (2007) berpendapat bahwa ideologi yang paling kuat dalam menyokong perbedaan gender adalah pembagian dunia ke dalam wilayah publik dan privat, yang umumnya disebutkan bahwa laki-laki di ruang publik dan perempuan di ruang privat. Hal ini yang kemudian memanifestasi ketidakadilan gender terjadi di berbagai tingkatan struktur, bahwasannya ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam relasi kuasa. Ketimpangan ini yang menurut Indraswari (2009) sebagai penyebab utama terjadinya kemiskinan pada perempuan, yang mana perempuan diputus akses-aksesnya terhadap sumber daya.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) Mengapa judul tulisan ini demikian? Kata korban dalam jejak bahasa Indonesia kurang dimaknai secara dalam oleh masyarakat kita. Pemaknaan kata korban sangat jauh berbeda dengan kata victim dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korban diartikan sebagai “pemberian untuk menyatakan kebaktian, dan kesetiaan”. Ada pula kata kurban dalam kamus tersebut yang berasal dari bahasa Arab yang dicontohkan dalam kalimat “jangankan harta, jiwa sekalipun kami berikan sebagai korban”.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Safina Maulida (Sarjana Filsafat Universitas Indonesia, Aktivis, Fashion Designer) safinamaulida@gmail.com There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice –Montesquieu Metakonservatisme hari ini (masih) pada posisi menolak kondisi setara dan nondiskriminatif, di saat kegentingan isu perempuan dan kelompok minoritas yang mengalami kenaikan. Hal ini membuat kita masih harus kembali ke pertanyaan dasar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) –setahun lalu saya angkat topik ini dalam diskusi publik bersama Asfinawati dan Melanie Subono, setahun lalu saat RKUHP mencak. |
AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
September 2021
Categories |

 RSS Feed
RSS Feed