 Dok. Pribadi Dok. Pribadi Oleh: Abby Gina Boang Manalu Rubrik: Wawancara JP 111 Perempuan dan Perhutanan Sosial Ir. Erna Rosdiana merupakan salah satu perempuan pejabat tinggi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada 21 Juni 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melantik sembilan orang pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). Dari sembilan orang pejabat eselon II, terdapat tiga pimpinan perempuan dan Erna Rosdiana merupakan salah satunya. Sejak saat itu, Erna Rosdiana menempati posisi strategis sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Oleh: Retno Daru Dewi G. S. Putri Rubrik: Profil JP 110 Perempuan dan Inisiatif Keadilan Farida Haryani adalah seorang aktivis pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjabat sebagai Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat (PASKA) Aceh. PASKA didirikan untuk memberdayakan para penyintas konflik dan pelanggaran HAM, khususnya perempuan, dan penyandang disabilitas. Dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal, PASKA membimbing para dampingannya untuk mengasah kemampuan yang dapat meningkatkan kondisi finansial mereka. Perempuan penyintas konflik dan pelanggaran HAM menjadi salah satu sasaran utama pemberdayaan Farida karena mereka mengalami beban berlapis akibat masalah yang terjadi.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Oleh: Abby Gina Rubrik: Wawancara JP 110 Perempuan dan Inisiatif Keadilan Galuh Wandita adalah Direktur Asia Justice and Rights (AJAR). Galuh adalah seorang aktivis kemanusiaan. Secara konsisten ia telah mengadvokasi pemenuhan hak bagi orang-orang yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Lebih dari 30 tahun, ia bergelut pada isu ini. Pada tahun 1997, Galuh menjadi salah-satu pendiri organisasi perempuan pertama di Timor-Timur yang bekerja untuk isu kekerasan terhadap perempuan dalam konflik, Fokupers. Setelah jajak pendapat (1999), Galuh bekerja sebagai petugas HAM bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Timor-Timur. Pada tahun 2002, ia diangkat sebagai wakil direktur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sebelum terlibat dalam kerja advokasi untuk Timor-Timur, selama 10 tahun sebelumnya ia telah aktif dalam kerja kemanusiaan bersama organisasi masyarakat sipil, termasuk upaya membangun jaringan solidaritas antara perempuan Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Timor-Timur. Pengalaman advokasi yang begitu kuat, menjadi basis Galuh untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM dan memerangi segala bentuk impunitas. Galuh Wandita, mendapatkan gelar Bachelor of Art dari jurusan Antropologi, Swarthmore College dan gelar Masters in International Human Rights Law dari Universitas Oxford.  Dok. Mariana Amiruddin Dok. Mariana Amiruddin Oleh: Abby Gina Rubrik: Wawancara JP 109 Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender Mariana Amiruddin adalah seorang aktivis gerakan perempuan. Saat ini sedang menjalani periode kedua (2019-2024) sebagai Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagai Wakil Ketua. Komitmennya memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia telah tumbuh sejak menempuh studi magister program kajian gender di Universitas Indonesia. Mariana menyelesaikan studi magisternya pada tahun 2000, sejak saat itu dia mengadvokasi isu kesetaraan gender melalui aktivisme dan menghasilkan berbagai tulisan. Selama lebih dari 10 tahun ia terlibat dalam mendokumentasikan dan membangun diskursus feminis di Indonesia bersama Jurnal Perempuan. Di tahun 2008-2013 dia menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan. Mariana juga dikenal sebagai penulis baik karya fiksi, esai, maupun artikel yang terbit di berbagai surat kabar dan majalah. Isu-isu yang diangkat dalam tulisannya terkait tentang feminisme, sastra, politik dan hak asasi manusia.  Dok. Diah Pitaloka Dok. Diah Pitaloka Oleh: Atnike Nova Sigiro Rubrik: Profil pada JP 109 Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender Diah Pitaloka, perempuan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jabar 3, Kabupaten Cianjur – Kota Bogor. Diah Pitaloka saat ini mengetuai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia periode 2020 – 2024. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia merupakan forum anggota parlemen perempuan lintas partai yang memperjuangkan isu-isu perempuan dan kelompok marginal lainnya di DPR RI. Kepengurusan Keanggotaan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia juga melibatkan para perempuan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI. Menurut Diah, persoalan perempuan merupakan persoalan bersama, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan itu sendiri.  *Tulisan ini pernah dimuat dalam Wawancara pada JP 107 Perempuan dan Pandemi Covid-19 Dr. Pinky Saptandari saat ini adalah Dosen Senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unair Surabaya. Ia mengampu mata kuliah Antropologi Gender & Seksualitas, Antropologi Pembangunan, Antropologi Kesehatan & Gizi, Antropologi Psikologi & Psikiatri dan Antropologi Hukum. Pinky menempuh studi S1 bidang Sosiologi di Universitas Airlangga, lalu meneruskan pendidikan S2 bidang Antropologi di Universitas Indonesia.  Oleh Gadis Arivia “I want to live like a butterfly in the sun.” Ini bukan ungkapan Toeti Heraty tapi ungkapan Margaretha Zelle atau Mata Hari, penari perempuan di tahun 1917 yang dituduh telah membunuh 50.000 tentara Perancis. Ia memiliki pacar-pacar yang berpengaruh di berbagai negara, cerdas luar biasa serta menjadi mata-mata terkenal. Toeti Heraty tentu tidak pernah menjadi mata-mata, hanya sekali ia mencoba melakukan kegiatan mata-mata, ketika itu ia benar-benar ingin mengetahui apa yang akan dilakukan komunitas yang mencintainya untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Kegiatan mata-mata tersebut sukses. Karlina Supelli: Pemahaman Kesejarahan Gerakan Perempuan Penting dalam Memaknai Kebangsaan*16/4/2021
 *Artikel Wawancara ini dimuat dalam JP 98 Perempuan dan Kebangsaan Dr. Karlina Supelli adalah salah satu filsuf perempuan Indonesia. Saat ini Karlina merupakan dosen tetap pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara. Perempuan kelahiran Jakarta, 15 Januari 1958 ini memiliki minat yang mendalam pada kosmologi dan filsafat. Sebelum menggeluti bidang filsafat Karlina dikenal sebagai ahli astronomi, 15 tahun lamanya ia bertekun pada bidang tersebut. Pergelutannya dengan ilmu kosmologi melahirkan pertanyaan dalam diri Karlina tentang bagaimana suatu bermula. Kegelisahan inilah yang menjadi titik pijaknya untuk mengenal, memahami dan setia pada filsafat. Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan PRT*15/2/2021
 *Catatan: Tulisan ini telah diterbitkan dalam JP 89 Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (2016) Lita Anggraini dikenal sebagai aktivis perempuan yang gigih memperjuangkan isu Pekerja Rumah Tangga (PRT). Ia bersama kawan- kawan PRT dan para aktivis ada dalam proses advokasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) selama 13 tahun yang hingga kini belum juga diundangkan. Tiga kali pergantian presiden dan tiga kali pula pergantian jajaran wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyurutkan Lita yang menjabat sebagai Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) untuk mewujudkan kebijakan yang memberikan perlindungan dan situasi kerja yang layak bagi PRT. 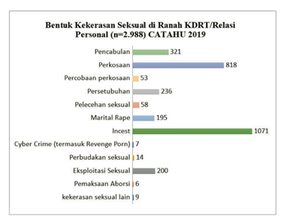 Sudah dua dekade Azriana Rambe Manalu aktif di gerakan perempuan baik sebagai pengacara probono bagi perempuan korban kekerasan maupun sebagai aktivis perempuan yang membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Pada April 2015 Azriana terpilih sebagai Ketua Komnas Perempuan, lembaga negara yang berfokus pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak perempuan, untuk periode 2015-2019. Posisinya saat ini sebagai Komisioner Komnas Perempuan bukanlah kali pertama, pada 2007 hingga 2009 ia juga tercatat sebagai Komisioner Komnas Perempuan. |
AuthorRedaksi Jurnal Perempuan Archives
November 2023
Categories |
 RSS Feed
RSS Feed