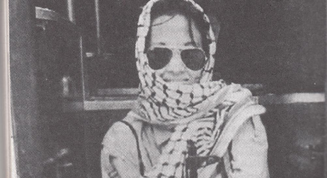 Waktu itu saya bertanya, “Apakah Anda tidak risau bahwa Anda dicari-cari oleh polisi dan sejumlah aparat dari berbagai negara?” Khun Sa waktu itu menjawab, “Saya bukan bandit, saya bukan teroris, tetapi saya juru selamat ratusan petani di daerah ini,” ujarnya. (Yuli Ismartono, 2003) Kutipan di atas adalah salah satu isi percakapan antara Yuli Ismartono dan Khun Sa seorang “Raja Opium” yang sangat disegani di wilayah Segitiga Emas (golden triangle), yaitu terletak di antara negara Burma, Laos dan Thailand. Bertemu dengan Raja Opium adalah pengalaman jurnalistiknya yang paling dikenang sekaligus sebuah prestasi tersendiri.  Lahir dari sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Mei 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melangkah menuju upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Fokus perhatian Komnas Perempuan pada saat ini adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai buruh migran, perempuan korban kekerasan seksual yang menjalankan proses peradilan, perempuan yang hidup di daerah konflik bersenjata, dan perempuan kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah pedesaan.  “Saya setuju dengan sebutan bahwa negeri kita ini adalah negeri yang maskulin. Saya dapat melihat dan merasakan maskulinitas itu dari ‘teks-teks’ sosial kita yang sarat dengan pelecehan seksual terhadap perempuan. Dan, saya kira semua itu akibat hegemoni patriarki yang telah tumbuh cukup lama dalam negeri ini. Untuk itu, saya sangat tertantang untuk menulis cerpen sebagai saksi atas ketidakadilan.” (Ratna Indraswari Ibrahim)1 Bila Ratna Indraswari Ibrahim tidak menulis, itu bisa berarti dua kemungkinan, yakni tidak ada lagi pelanggaran kemanusiaan atau kehidupan ini memang telah usai. Sejauh ini, memang tidak pernah terbayang oleh Ratna jika ia harus berhenti menulis. Baginya, menulis cerpen bisa mengungkapkan sekaligus menggambarkan suatu realitas sosial yang terjadi di masyarakat. “Cerpen adalah bagian dari sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra merupakan refleksi kejujuran atas realitas sosial di mana karya sastra itu tumbuh,” kata Ratna. Alasan itulah yang menjadikan Ratna merasa dapat membantu dan berbagi kepada sesama manusia lewat cerpen-cerpennya. Kemanusiaanlah yang menjadikan Ratna tetap menulis. Ratna adalah perempuan biasa yang luar biasa. Mengenal Ratna mengingatkan kita pada si Genius Stephen Hawking yang memberi pemahaman bahwa keterbatasan fisik bukanlah instrumen utama bagi berkurangnya kegeniusan seseorang. Ratna secara fisik tidak mungkin mengerjakan pekerjaannya seperti manusia normal. Ratna adalah orang cacat secara fisik, tetapi genius secara ide. Ratna adalah Stephen Hawking dalam dunia sastra dan perjuangan perempuan di komunitasnya. Hampir sebagian besar anggota tubuhnya, terutama tangan dan kakinya, tidak bisa difungsikan, menyuap makanan pun tidak mungkin ia kerjakan sendiri. Di atas kursi rodanya, Ratna kerap kali kecewa kepada masyarakat yang memperlakukan orang cacat dan perempuan dalam posisi yang tidak penting, terbelakang, dan bodoh. Tekad untuk mengubah pandangan masyarakat yang keliru inilah yang menjadikan Ratna selalu hidup dalam kehidupan yang tidak berperilaku adil. Ia sangat mengagumi ibu Nabi Musa A.S., karena kecerdasannya, perempuan itu menemukan jalan untuk menyelamatkan Musa kecil dari kekejaman Firaun yang siap membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir. Ratna bercita-cita agar perempuan di negerinya dapat berpikir seperti itu, berpikir alternatif, cerdas, dan mandiri dari kekuatan laki-laki yang mendominasi dan memperlakukan perempuan secara tidak adil. Itulah Ratna, ia hidup dalam cerpen-cerpennya yang kelak akan dikenal sebagai sosok yang memberi pemahaman kepada dunia bahwa nilai dan kedudukan manusia bukan dilihat dari fisik, melainkan dari tindakan, pikiran, dan sumbangsih seseorang dalam kehidupan bersama. Ratna dan Sisi Kehidupannya Dalam dunia sastra, nama Ratna Indraswari Ibrahim cukup dikenal sebagai penulis cerpen. Cerpen-cerpennya kerap dimuat di sejumlah media cetak, baik lokal maupun nasional. Selain dikenal sebagai penulis cerpen, Ratna juga dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan hak para difabel untuk memperoleh perlakuan yang sama sebagai warga negara. Kondisi fisiknya memang tidak normal karena sebagian besar anggota tubuhnya tidak berfungsi. Ia terserang penyakit polio pada usia 12 tahun dan sejak itu ia harus mengisi hari-harinya di atas kursi roda. Meskipun harus menghabiskan kehidupannya di atas kursi roda, Ratna merasa tidak mempunyai persoalan menyangkut kondisinya yang difabel. Persoalan ini baginya sudah lewat. Ia juga tidak mengalami diskriminasi dalam keluarganya. Orang tua dan saudara-saudara tidak pernah memperlakukannya secara istimewa. Inilah yang menjadikan Ratna merasa selesai dengan kondisinya. Di atas kursi roda, Ratna semakin menemukan dirinya. Kehidupannya telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang cukup berharga bagi dirinya menyangkut keberadaan difabel lainnya. Di atas kursi roda, ia dapat merasakan bagaimana perlakuan masyarakat masih belum sepenuhnya menerima orang-orang difabel. Keinginan Ratna hanya satu, yaitu perlakuan yang sama dari masyarakat kepada mereka yang difabel. Dengan sepenuh hati, Ratna kerap memaksa masyarakat yang menganggap difabel sebagai objek yang perlu dikasihani untuk mengubah pandangan bahwa difabel adalah subjek yang juga mempunyai peran penting. Ratna telah menunjukkan perannya, yaitu menumbuhkan motivasi kepada rekan-rekannya sesama difabel dan masyarakat umum bahwa mereka ini adalah manusia biasa yang juga warga negara. Kepedulian ini diwujudkan Ratna dengan mendirikan organisasi penyandang cacat di Kota Malang, yaitu Bakti Nurani yang pada tahun 1977—2000 dinakhodai oleh Ratna. Melalui Bakti Nurani, Ratna membangun jaringan keluar dengan berba- gai organisasi untuk membangun kekuatan. Tidak saja dengan sesama organisasi penyandang cacat, tetapi juga organisasi sosial lainnya. Baginya, membangun jaringan dapat menggalang kekuatan yang mempercepat proses perubahan masyarakat. Kekuatan jaringan yang dibangun Ratna tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri hingga pada tahun 1993, ia diundang untuk hadir dalam seminar Hak Asasi Manusia di Sidney, Australia sebagai delegasi dari Indonesia. Ratna Indraswari Ibrahim lahir dari keluarga besar. Ia adalah anak keenam dari sebelas bersaudara, lima laki-laki dan enam perempuan. Ratna dilahirkan di Kota Malang, Jawa Timur pada 24 April 1949. Darah keluarganya mengalirkan minat menulis yang tinggi dalam diri Ratna. Ia sendiri mengakui bahwa kelahirannya dalam keluarga Saleh Ibrahim (ayahnya) membawanya pada perasaan seperti anak ikan yang bertemu dengan air. Ayahnya, Saleh Ibrahim yang berdarah Padang adalah seorang penulis dan aktivis. Beberapa karya tulisnya menghiasi sejumlah media massa pada saat itu. Sayang, Saleh Ibrahim tak bisa menemani Ratna hingga melihat putrinya ini menunjukkan kemampuan menulisnya. Pada tahun 1967, ayah Ratna meninggal akibat kanker. Umur Ratna saat itu baru 18 tahun. Ratna sangat mengagumi ayahnya. Lelaki ini mengajarkan anak-anaknya untuk membeli dan membaca buku. Karena itulah, koleksi buku Ratna banyak sekali, mencapai 1.000 judul. Semenjak ayahnya meninggal, Ratna menapaki kehidupan bersama ibunya, Siti Bidahsari Arifin, orang Padang berdarah campuran. Tidak jauh berbeda dengan ayahnya, ibunda Ratna juga yang suka menulis dan melukis. Ibunyalah yang memperkenalkan Ratna pada kemandirian dalam hal menulis. Suatu kali, ibunya pernah mengatakan, “Perempuan itu jangan ngobrol saja, perempuan itu harus menulis, menulis apa saja. karena dengan menulis, ia dapat menemukan dirinya,” ujar Ratna mengutip kata-kata sang Ibu. Tampaknya, ucapan tersebut dipegang teguh oleh Ratna, bahkan hingga kini. Pada tahun 1975, cerpen pertama Ratna berjudul “Jam” dimuat dalam sebuah majalah remaja MIDI. Sejak saat itu, Ratna semakin memantapkan hati, jiwa, dan pikirannya untuk menulis. Dalam kesehariannya, aktivitas Ratna cukup sederhana, yakni membaca, menulis, berdiskusi, dan berorganisasi. Beberapa waktu memang Ratna harus keluar rumah untuk mendatangi sejumlah seminar, baik tentang politik, sosial, maupun budaya. Ratna aktif menghadiri seminar-seminar, baik sebagai peserta maupun pembicara. Bagi Ratna, tidak ada kerugian apa pun untuk mendatangi seminar, malah menambah wawasan. Tidak jarang pula Ratna bergabung bersama teman-temannya untuk turun ke jalan memprotes sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut isu kebudayaan, perempuan, lingkungan, dan aksesibilitas bagi difabel. Ia juga kerap hadir untuk memberi dukungan pada sejumlah aksi mahasiswa, seperti aksi mogok makan yang dilakukan mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah daerah. Ratna memang tidak bisa bergabung terus-menerus, tetapi kehadirannya mampu menambah dukungan moral. Solidaritasnya yang tinggi membuat Ratna dikenal hampir di semua kalangan. Hal ini tampaknya berpengaruh bagi kehidupan Ratna. Hidupnya tak pernah sepi. Dalam keseharian, ia terus menciptakan arus bagi setiap aktivis LSM, mahasiswa, budayawan, wartawan, para difabel, birokrat, pendidik, dan elemen masyarakat lainnya. Rumahnya di Jalan Diponegoro 3, Malang tak pernah sepi dari kehadiran seorang teman, masyarakat biasa, hingga sejumlah tokoh besar, seperti budayawan dan politisi. Ratna tidak pernah membeda-bedakan siapa saja yang datang ke rumahnya. Kehadiran rekan-rekannya merupakan spirit baru bagi Ratna untuk semakin memahami kehidupan. Mereka banyak membantu, menjadikan Ratna kuat dan percaya diri. Di rumahnya, di atas kursi roda, ia mendengar banyak cerita dan keluhan tentang ketidakadilan sosial. Cerita-cerita inilah yang kerap kali menjadi ide bagi setiap cerpen-cerpennya yang hampir selalu berangkat dari kenyataan sosial. Dengan sabar Ratna mendengarkan cerita yang kadang kala cukup menyesakkan dadanya. Setiap cerita kehidupan itu selalu melahirkan korban. Ratna sendiri menyebut teman-temannya sebagai “kunang-kunang”, penerangan bagi dirinya. Ratna senantiasa mengikat komitmen dengan setiap temannya dan menjaga komitmen itu. Inilah yang membuat setiap orang memiliki komitmennya sendiri dengan Ratna. Ratna mempunyai kegemaran membaca sejak kecil. Sewaktu SMA ia telah membaca sejumlah buku “berat” untuk dibaca anak seusianya, seperti buku karangan Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi dan bacaan-bacaan Marxis. Kebiasaan membacanya ini mengajarkan Ratnapada banyak haltentang kehidupan. Kebiasaan membaca inilah yang menjadi teman hidupnya sehari-hari. Koleksi buku Ratna banyak, hampir setiap ada buku baru ia beli. Teman- temannya selalu menginformasikan adanya buku baru atau buku bagus. Ia lalu menitip temannya untuk membelikan karena ia sadar, mobilitasnya terbatas. Ditambah pula, sejak ibunya meninggal, praktis Ratna menjalani hidupnya seorang diri. Ia hanya ditemani tiga temannya yang siap membantu Ratna menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari makan, mandi, ke toko buku, menghadiri seminar, sampai mengetikkan makalah atau naskah cerpennya. Ratna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan honor menulis cerpen, juga pembayaran sewa kamar-kamar di rumahnya yang diindekoskan. Meskipun saudara-saudaranya sedia membantu, namun bukanlah Ratna bila tidak bisa mandiri. Ia harus belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri, untungnya keluarga Ratna bisa memahami hal itu. Dengan penghasilan terbatas, ia menyuguhkan secangkir kopi dan sepiring makanan kecil untuk teman-temannya yang datang ke rumahnya yang selalu terbuka. “Silakan mau makan, berdiskusi, menginap, atau apa saja selama saya bisa membantu, saya akan bantu, asalkan mau dengan kesederhanaan,” kata Ratna yang pernah menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya ini namun mengundurkan diri. Dalam menulis cerpen, ia tidak selalu meminta bantuan temannya untuk mengetikkan. Terkadang Ratna juga menuliskan naskah cerpennya sendiri, ia hanya minta disiapkan komputer di depan kursi rodanya. Dengan sepasang sumpit sebagai “tangannya”, Ratna menekan tombol huruf pada keyboard komputer secara perlahan dan penuh kesabaran. Cukup lama waktu yang dibutuhkan Ratna untuk mengetik satu kata menjadi kalimat lalu paragraf, apalagi sebuah cerpen. Setiap tombol yang ditekan membutuhkan waktu kurang lebih setengah menit, maka ia membutuhkan waktu berjam-jam untuk sebuah cerpen. Apakah ini menjadi hambatan? Tidak, justru di situlah pergulatan batinnya terjadi hingga mampu memberikan jiwa pada setiap karyanya. Dengan kesabaran, ketekunan, dan komitmen, Ratna tidak saja produktif menghasilkan cerpen, tetapi juga menghasilkan cerpen yang tajam. Selain menjadi cerpenis lepas, Ratna juga menjadi aktivis sosial dengan menjadi salah satu pendiri Yayasan Entropic, sebuah yayasan yang peduli pada isu lingkungan hidup. Bagi Ratna, alam memberikan kehidupan bagi manusia. Sungguh suatu kebiadaban bila alam harus dirusak oleh kelompok-kelompok yang mementingkan dirinya sendiri. Dari alam pun Ratna mengahasilkan sejumlah cerpen yang membela kelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 1998, Ratna mendirikan Yayasan Pajoeng dan menjadi koordinator litbang di sana. Yayasan Pajoeng adalahsebuahyayasanyang bergerak dalam bidang pengembangan kebudayaan di Kota Malang. Kebudayaan, menurut Ratna, adalah sumber peradaban. Sebuah bangsa menjadi kurang beradab ketika kehilangan akar kebudayaannya karena setiap kehidupan merupakan refleksi kebudayaanya. Ratna juga menjadi pionir bagi perkumpulan aktivis dari berbagai elemen di Kota Malang yang tergabung dalam Forum Pelangi. Komunitas diskusi ini aktif melakukan kajian dan tukar informasi antarelemen masyarakat di Kota Malang. Ratna dan teman-temannya di Malang juga membidani lahirnya Jurnal Naraswari yang memfokuskan isinya pada isu perempuan dan kesetaraan gender. Media ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami sejumlahketidakadilan gender yang terjadi di sekitarnya. Kepedulian Ratna terhadap persoalan perempuan bukanlah hal baru. Pada tahun 1995, Ratna pernah menjadi delegasi Indonesia pada Kongres Perempuan Internasional di Beijing, China. Pada tahun 1997, Ratna juga menghadiri Kongres Perempuan Sedunia di Washington DC, USA. Pada tahun 1993, pemerintah Indonesia memberinya penghargaan sebagai Perempuan Berprestasi. Dalam soal belajar, ia tidak akan pernah berhenti, “Belajar itu tidak pandang usia dan kapan pun,” demikian tuturnya. Itulah kebanggaan Ratna ketika mengikuti pelatihan kepemimpinan MIUSA (Mobility International United States) di Eugene, Orengon, USA pada tahun 1997. Mengabarkan Kenyataan Lewat Cerpen Ratna sendiri sudah lupa sudah berapa banyak cerpen yang dilahirkannya. Yang jelas, Namanya Massa (Yogyakarta: Penerbit LKis, 2000) adalah judul buku kedua kumpulan cerpennya. Kehadiran buku tersebut menjadi tonggak ketekunannya selama 25 tahun menggeluti dunia sastra. Sebelumnya, Ratna juga pernah melahirkan kumpulan cerpen berjudul Menjelang Pagi (1995) dan yang terbaru adalah buku kumpulan cerpennya yang ketiga berjudul Lakon di Kota Kecil (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002). Ketiga buku tersebut hanya berisi reproduksi ulang cerpen-cerpen Ratna yang pernah dimuat di media massa, namun itu bukan berarti sebuah ide dan intelektualitas hanya terukur dari kuantitas karya. Ratna adalah orang yang sangat menghormati proses. Memahami proses adalah memahami persoalan secara lebih substansi dan mendalam. Ia lebih senang orang mengenalnya secara proses, bukan sebagai Ratna yang sekarang ini. Konsistensinya pada proses telah melahirkan cerpen-cerpen yang cerdas. Kompas sebagai koran nasional hampir tak pernah meluputkan nama Ratna dalam setiap penerbitan buku kumpulan cerpen pilihan Kompas. Salah satu karya Ratna adalah “Bunga Kopi” yang terdapat dalam kumpulan Cerpen Pilihan Kompas Tahun 2007. Cerpen-cerpen Ratna senantiasa mengabarkan kepada kita bahwa ada penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Cerpen adalah media yang dipilihnya untuk mengungkapkan perasaannya dalam melukiskan sebuah kisah. Cerita dalam cerpen-cerpen Ratna berangkat dari kenyataan sosial yang didapatnya dari teman-temannya. Melalui cerpen, setiap pembaca diajak untuk memahami realitas sosial tersebut untuk pada akhirnya turut merasakan, apakah dirinya menjadi penindas atau yang tertindas. “Itulah tugas cerpen, mengabarkan sebuah kenyataan dan membangunkan mimpi kita dalam sebuah kisah,” kata Ratna yang menemukan jati dirinya dalam pekerjaan menulis cerpen. Ada banyak pilihan untuk mensosialisasikan gagasan dan pengalaman, Ratna memilih menulis untuk mengekspresikan semua itu. Dengan menulis ia merasa semua orang dapat membaca, kapan pun dan dimana pun. Meskipun minat baca di Indonesia masih rendah, Ratna percaya bahwa dari hal yang kecil itulah akan tercipta sesuatu yang besar. Bila kita tengok cerpen Ratna yang berjudul “Rambutnya Juminten” yang dimuat Kompas, 18 Juli 1993, kita akan dapatkan bagaimana Ratna mengabarkan suatu realitas masyarakat yang sangat mengagungkan suami sebagai kepala rumah tangga. Juminten adalah seorang istri yang dikategorikan “setia” dan ideal dalam ukuran masyarakat yang menganut paternalisme tinggi. Sebagai seorang Istri, Juminten mau melakukan apa saja demi sang Suami, termasuk memanjangkan rambutnya, meskipun dalam hatinya sangat bertolak belakang. Cerpen itu cukup kuat memaksa kita untuk tersadar bahwa perilaku paternalistis menjadikan perempuan tak berdaya. Cerpen tersebut terpilih dalam Cerpen Pilihan Kompas Tahun 1995 dan menjadi nominasi Cerita Pendek Perempuan di tingkat ASEAN pada tahun 1996. Selain “Rambutnya Juminten”, beberapa cerpen Ratna juga mempunyai prestasi terbaik, seperti “Jerat” yang masuk dalam Cerpen Pilihan Kompas Tahun 1993; “Bajunya Bu Boni” menjadi pemenang ketiga Sayembara Cerpen Majalah Wanita Femina tahun 1996; “Perempuan itu Cantik“ termasuk dalam Cerpen Pilihan Kompas Tahun 1996 dan masuk seleksi Yayasan Lontar, Jakarta; dan “Seruni” yang menjadi salah satu pemenang Sayembara Cerber Majalah Wanita Femina tahun 1998. Cerita terakhir ini mengisahkan pemberontakan seorang mahasiswa kedokteran dalam melawan tradisi. Selanjutnya, pada tahun 2000, cerpennya kembali terpilih menjadi cerpen pilihan Kompas. Sejumlah cerpen Ratna memang tidak sekadar cerpen. Ia mewakili sepotong kenyataan sosial yang terjadi. Memahami cerpen Ratna tidak bisa hanya dengan dibaca, tetapi juga harus dirasakan karena di situlah letak kekuatan cerpennya. Ia dapat menjelaskan realitas yang selama ini dipandang keliru oleh banyak orang berkaitan dengan perspektif kemanusiaan. Cerpen Ratna mengajak kita untuk bisa memahami setiap persoalan tidak dari satu perspektif, tetapi dari banyak sisi. Perspektif yang beragam dapat membantu kita untuk memahami setiap persoalan tersebut, seperti yang dikatakan Ratna, “Bahwa kebenaran seseorang itu tidak bisa dipandang dari satu sisi. Kebenaran itu hendaknya dilihat dari sisi dan perspektif yang lebih luas. Melalui share pendapat dan berbagi pengalaman, saya kira setiap persoalan yang muncul dapat lebih jelas tingkat kebenarannya.” Memihak Perempuan Lewat Cerpen
Dalam cerpen tersebut Juminten menuruti saja apa kata suaminya yang menginginkan rambutnya agar tetap dipanjangkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Juminten harus memanjangkan rambutnya. Sementara itu, di sisi lain, tren mode rambut pendek tampaknya menjadi pilihan hampir setiap perempuan. Juminten tidak saja mewakili perasaan Ratna, tetapi Juminten juga mewakili perasaan sebagaian besar perempuan yang hidup dalam hegemoni patriarki. Perempuan tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Ia hadir untuk memenuhi selera para laki-laki. Teralienasinya perempuan oleh kekuasaan laki-laki inilah yang menurut Ratna setidaknya harus menjadi perhatian setiap insan. Sama halnya dengan komentar Budi Dharma (Guru Besar Sastra Inggris di IKIP, Surabaya), bahwa Juminten merupakan korban konstruksi sosial masyarakat. “Sebagai anggota masyarakat, ia semata komponen. Ia dibentuk oleh kehendak-kehendak dari luar, bukan dari dirinya sendiri,” kata Budi Dharma. Ratna memang bertekad untuk membongkar realitas patriarki ini melalui cerpen-cerpennya. Ratna menginginkan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk bersama-sama menggugah kesadaran perempuan yang teralienasi oleh hegemoni patriarki. Ratna sangat perhatian terhadap persoalan perempuan yang telah menikah. Menurutnya, sudah banyak contoh yang menggambarkan bagaimana perempuan yang menikah selalu menjadi objek kekerasan oleh suaminya, entah itu secara fisik, psikologis, maupun secara ekonomi. Ratna berpandangan bahwa sebagai istri, perempuan yang menikah, harus berani menunjukkan hak-haknya sebagai warga negara yang sama dalam perlakuan di mata hukum. Hal ini tampak dalam komentar Ratna yang cukup keras ketika menyikapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga, “Istri harus berani melapor ke polisi bila ia dipukul oleh suami,” tegasnya. Pernyataan ini sangat jelas memberi pemahaman bahwa suami dalam instrumen perkawinan, tidak punya hak untuk melakukan kekerasan terhadap istri atas dalih apa pun. Untuk itu, istri wajib melaporkan kepada polisi bila ia mengalami kekerasan sekecil apa pun. Sebagai cerpenis, Ratna hanya bisa mengkisahkan kegelisahannya tersebut dalam sebuah cerpen. Ia pun sering kecewa terhadap tayangan-tayangan televisi yang hampir sebagian besar mengeksploitasi perempuan. Ratna khawatir bahwa citra perempuan yang terbangun melalui televisi yang suka menangis, sebagai pekerja rumah tangga, tidak mempunyai daya kreativitas berpikir, bercitra sensual, ditangkap secara mentah-mentah oleh masyarakat. Tayangan televisi ataupun media cetak adalah agen yang efektif untuk mempengaruhi masyarakat. Bila tayangan televisi sendiri telah mengalami bias gender, maka jangan disalahkan bila masyarakat akan mencontoh perilaku seperti yang tertangkap di televisi atau media cetak selama ini. Dalam konteks tersebut, cerpen-cerpen Ratna sebenarnya tidak saja melawan hegemoni-hegemoni patriarki, tetapi juga melawan hegemoni kapitalistis yang selalu menampakkan manusia secara fisik. Dalam konteks itu pula, Ratna mau melakukan apa saja agar cerpen-cerpennya bisa dibaca. Ia memang tidak menginginkan dirinya menjadi terkenal, tetapi ia hanya ingin memberi pelajaran bahwa realitas yang terjadi tidaklah sama dengan tampilan di media massa yang sangat eksploitatatif. Mensosialisasikan cerpennya melalui sekolah-sekolah adalah upayanya untuk memberikan pemahaman dini terhadap siswa tentang persoalan ketidakadilan gender. Upaya ini ia lakukan agar siswa lebih terbiasa untuk memahami realitas yang sesungguhnya. Penutup Ratna Indraswari Ibrahim memang tidak terbiasa untuk diam tidak menulis. Menulis sudah menjadi bagian hidupnya. Namun, kebiasaanya untuk menulis telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Bila Ratna menulis, berarti ada ketidakadilan yang merajalela, ada penindasan yang kejam, ada korban yang jatuh, dan ada cinta yang tercabik. Bila Ratna menulis, berarti ada perempuan yang diperkosa, ada tanah yang digusur, ada aktivis mahasiswa yang dipukul, dan ada manusia yang terbantai. Ratna memang sosok penulis cerpen yang tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang ia tuliskan. Cerpen Ratna adalah saksi yang berbicara pada nilai-nilai kemanusiaan. Semestinya kita dapat belajar dari Ratna bahwa kesempurnaan seseorang itu tidak akan diperoleh tanpa kita berupaya untuk menyempurnakan diri kita sendiri. Tidak ada satu pun yang bisa mengubah diri kita, kecuali diri kita sendiri. Itulah yang telah dilakukan oleh Ratna untuk mencari kesempurnaan dirinya. Ratna adalah saksi di mana keterbatasan fisik bukanlah hambatan seseorang untuk berbuat untuk sesamanya. Ratna telah membuktikan, meskipun ia tidak bisa menggunakan kemampuan fisik anggota tubuhnya, tetapi ia mampu memberi pencerahan melalui pikiran-pikirannya. Ratna dapat dijadikan saksi bahwa kekuatan pikiran lebih berbahaya ketimbang kekuatan fisik. Kekuatan fisik hanya tumbuh di dalam jasmani, tetapi kekuatan pikiran tumbuh di dalam jiwa. (Eko Bambang Subiyantoro) Catatan Belakang: Tulisan ini dibuat pada tahun 2002 Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 23, 2002 Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern dengan isu pendidikan perempuan adalah Kapal Perempuan (Lingkar Pendidikan Alternatif untuk Perempuan). Metode yang dilakukan adalah memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam masyarakat melalui pendidikan alternatif. Yanti Muchtar adalah Direktur Eksekutif Kapal Perempuan yang telah menerapkan pendidikan untuk perempuan ini di masyarakat terpinggir dan para ibu rumah tangga yang hidup di sana. Selengkapnya, berikut wawancara Jurnal Perempuan dengan Yanti Muchtar. Jurnal Perempuan (JP): Apa pentingnya pendidikan alternatif bagi perempuan? Yanti Muchtar (YM): Kalau kita mau melihat isu demokratisasi, maka harus ada satu, dua, tiga atau lebih masyarakat sipil yang kuat. Maka, kalau kita bicara tentang masyarakat sipil yang kuat, berarti kita juga akan bicara kelompok- kelompok perempuan yang kuat sebagai bagian dari masyarakat sipil itu. Pada akhirnya, kebutuhan untuk mengorganisasi perempuan menjadi sangat penting agar proses demokratisasi bisa berjalan sepenuhnya dan dengan yang sebaik-baiknya menuju masyarakat adil dan pluralis, yang akhirnya manfaatnya juga bisa dirasakan oleh kaum perempuan. JP: Atas hal tersebut, bagaimana Kapal Perempuan mengorganisir sekolah perempuan? YM: Tentu saja sama dengan yang tadi saya katakan, prasyarat dalam menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan pluralis membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, yaitu masyarakat sipil yang berperspektif keadilan sosial dan keadilan gender. Karenanya, kita harus memperkuat perempuan sebagai bagian yang terpenting dari masyarakat sipil sebab untuk konteks Indonesia, kita harus mengakui bahwa 57% masyarakatnya adalah perempuan. Dari jumlah ini, artinya manakala kita bicara proses demokratisasi, maka mau tidak mau kita harus memperkuat dan memberdayakan perempuan. JP: Dari kegiatan pendidikan alternatif untuk perempuan, Kapal Perempuan memilih pendidikan yang diberikan pada ibu rumah tangga. Mengapa demikian? YM: Kapal Perempuan mencoba melawan arus dengan cara memperkuat dan mengorganisasi ibu rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai kelompok yang tidak militan dan sulit diorganisasi, padahal mereka itu, kan, mayoritas. Makanya, kami coba mengorganisasi ibu-ibu rumah tangga di dua wilayah, yaitu di Ciliwung dan di Kampung Jati, Klender. Dan, ternyata setelah satu tahun, mereka berhasil mendirikan Sekolah Perempuan di dua wilayah tersebut. JP: Apa saja program yang dimiliki di Sekolah Perempuan itu? YM: Kita mencoba mengintegrasikan tiga pendekatan sekaligus. Pendekatan pertama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran perempuan sekaligus meningkatkan cara berpikir yang kreatif dan kritis, namun di saat bersamaan kita juga tahu bahwa faktor ekonomi juga merupakan sebuah masalah yang tidak bisa kita tinggalkan. Pendekatan ekonomi saja memang tidak cukup. Artinya, perempuan sebetulnya perlu pula pengetahuan, itu mengapa kami masuk dengan pendekatan apa yang disebut pemerintah sebagai “keaksaraan fungsional”, yaitu mereka dapat membaca, menulis, dan berhitung. Nah, ketiga hal itu coba kami gabungkan dengan metodologi yang berusaha tidak memisahkan ketiga hal ini. Misalnya, ketika kami mengajar membaca, maka yang dibaca adalah persoalan mereka. Setelah itu dianalisis, kemudian bagaimana menjawab pertanyaan dan menggali jawabannya. Nah, dari situlah muncul kebutuhan pentingnya berorganisasi, bersolidaritas sehingga hasil proses itu kemudian menghasilkan organisasi yang mereka inginkan. JP: Jadi, berdasarkan pengalaman perempuan itu kemudian timbul kebutuhan akan pengetahuan-pengetahuan tersebut? YM: Persis, berdasarkan pengalaman merekasendiri lalu mereka bisa merumuskan kebutuhan mereka. JP: Adakah kendala dalam pengorganisasian Sekolah Perempuan tersebut? YM: Ada, yaitu dari masyarakat sendiri, dan sebetulnya masyarakat kita memang sudah terkotak-kotak. Maka, ketika kami datang ke dua wilayah tersebut, yang keluar adalah isu penyebaran agama. Kita sempat dianggap melakukan penyebaran agama. Dan, kendala kedua, banyak yang berpikir kami bawa bantuan karena selama ini, orang datang ke mereka untuk bawa bantuan fisik. Jadi, menurut kami, materi yang nantinya disampaikan pada kelompok ibu rumah tangga ini adalah tema pluralisme juga, yaitu bagaimana saling menghargai dan bagaimana saling menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat, dan di antaranya adalah perbedaan agama. JP: Apa perubahan yang terjadi di kelompok pendidikan alternatif bagi perempuan tersebut? YM: Mereka bisa lebih terbuka dan berani mengekspresikan pikiran mereka sendiri. Misalnya, di Ciliwung, kami terkena isu agen penyebaran agama, ternyata ibu-ibu yang sekolah di tempat kami menolak isu itu dengan mengatakan itu mengada-ada dan bohong belaka. Reaksi itu sebenarnya hasil proses penguatan bahwa mereka berani mengatakan dan bertindak atas nama diri mereka sendiri. Akhirnya, posisi tawar mereka dalam masyarakat itu pun lalu menjadi lebih baik. JP: Artinya Kapal Perempuan berhasil memfasilitasi Sekolah Perempuan di dua wilayah itu, apakah memang ada kebutuhan sekolah alternatif di sana? YM: Tentu ada, sebab kalau kita mau bicara soal Indonesia yang adil dan sejahtera serta demokratis, tentu harus ada pengawasan, monitoring, dan input dari masyarakat. Masyarakat miskin tentu saja ada di dalamnya, berikut perempuan- perempuan miskin. Mungkin sebagai salah satu contoh, inisiatif LSM untuk membantu, seperti yang dilakukan Kapal Perempuan, tetapi sebaiknya itu adalah keinginan atau diinisiatifkan oleh mereka sendiri. Dan, harapan ke depan, proses-proses pengorganisasian itu dapat didorong oleh kita semua, khususnya oleh pemerintah. Dorongan itu bukan sekadar omongan, melainkan juga terjamin di APBD dan APBN, bahwa usaha-usaha yang tersistematisasi memang pendanaannya ada dari pemerintah. Mengorganisasi ibu-ibu agar mereka kuat dan mampu mengekspresikan aspirasi dan pendapat mereka itu, kan, penting. Misalnya, saat pemilu lalu, hampir semua pihak memberikan pendidikan politik, padahal seharusnya yang diberikan adalah pendidikan kewarganegaraan dan itu harusnya memang dilakukan oleh negara. JP: Berbalik pada kelompok perempuan, dalam hal ini ibu rumah tangga yang dianggap tidak militan, pengalaman Kapal Perempuan sendiri bagaimana? YM: Ya, ternyata mereka militansinya tinggi sekali karena pada tingkatan tertentu tidak ada itu namanya riil ibu rumah tangga. Banyak di antara mereka menjadi buruh cuci dan pengusaha kecil. Pengalaman kami ternyata, mereka cukup mampu untuk membangun komunitasnya. Saya hanya ingin membandingkan ketika saya pulang dari Manila, di situ ada persatuan orang tua yang isinya ibu rumah tangga dan mereka memulai aktivitas pendidikan pre-school di setiap komunitasnya dengan konsep dari mereka untuk mereka, dan ternyata gerakan ini cukup kuat, begitu pula di daerah miskin kota. Saya langsung membayangkan bagaimana mereka bisa melakukan itu dan apakah mungkin diterapkan di negara kita. JP: Dapat digambarkan apa yang dilakukan mereka di sana? YM: Seperti di Filipina, Indonesia juga saya rasa, kadang anak tidak disekolahkan, selain faktor biaya, jarak yang jauh, mungkin juga tidak ada tempat atau ibu- ibunya menganggap tidak penting. Maka, kelompok ibu-ibu rumah tangga ini bersatu dan mengumpulkan uang, menyewa satu ruangan, dan membuat satu sekolah di situ. Di sana mereka sekaligus dididik untuk menjadi guru TK dan mereka dapat bergantian menjadi guru TK di sana. Bagi yang tidak punya biaya tidak perlu membayar. JP: Apa pendapat Anda mengenai persoalan pendidikan di Indonesia? YM: Indonesia memang sudah meratifikasi deklarasi education for all, yaitu ‘pendidikan untuk semua’ dan juga berdasarkan UUD ‘45 yang diamandemen, pendidikan dasar 9 tahun seharusnya gratis, bermutu, dan aman. Karena itu, tidak mungkin bila Indonesia tidak memikirkan persoalan pendidikan ini, apalagi persoalan perempuan yang jelas separuh lebih dari penduduk di Indonesia ini. Ya, kita harus terus menjalankan metode pendidikan alternatif ini sebelum semuanya menjadi semakin runyam dan negara ini tidak menjadi apa-apa di mata dunia. (Sofia Kartika) Catatan Belakang: Tulisan ini dibuat pada tahun 2005 Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 44, 2005 Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. |
AuthorRedaksi Jurnal Perempuan Archives
November 2023
Categories |
 RSS Feed
RSS Feed